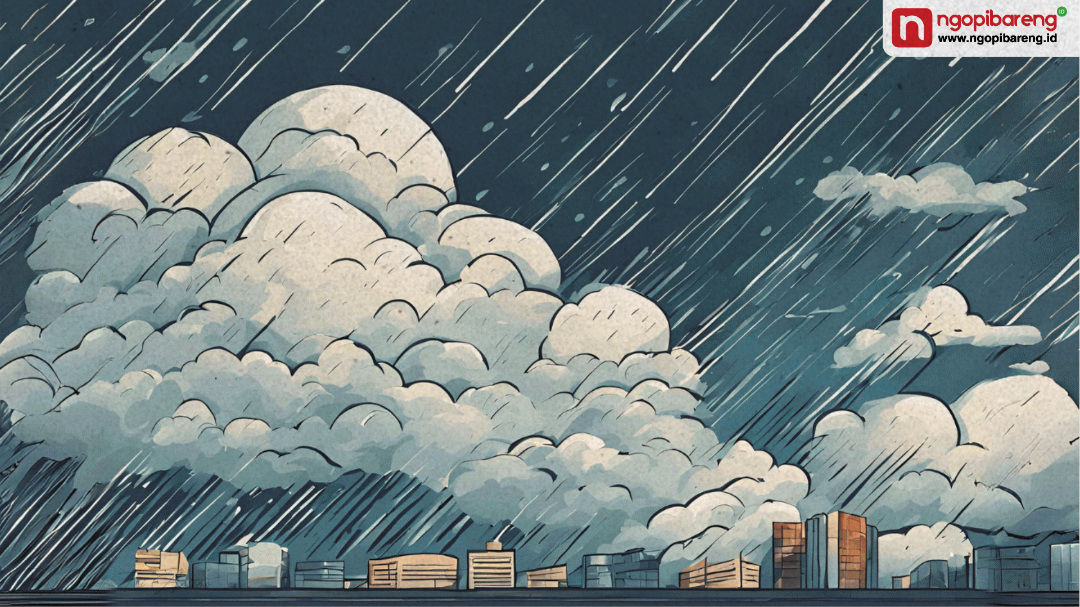UGM di Tengah Kontroversi Ilmu dan Agama

Usulan Dekan FEB UGM tentang jalur khusus untuk penghafal kitab suci menimbulkan kontroversi. Meski usul itu dimentahkan rektorat UGM, namun gagasan tersebut menyeret perdebatan soal hubungan agama dan ilmu pengetahuan. Berikut pemikiran Rizal Malarangeng yang juga alumnus kampus tersebut. (Redaksi)
RUPANYA di UGM, Jogjakarta, terjadi sebuah kontroversi yang mencerminkan dinamika baru dalam hubungan antara agama, ilmu pengetahuan dan dunia perguruan tinggi.
Hal yang sama nampaknya juga terjadi di banyak universitas lain. Ia adalah sebuah fenomena relatif baru, dan hasil akhir dari dinamika ini mungkin menentukan wajah Indonesia 10 atau 20 tahun kelak.
Saya sendiri menyadari hal itu setelah membaca sebuah respon singkat terhadap posting saya beberapa hari silam di WA group teman-teman seangkatan (Fisip Komunikasi UGM, angkatan 1984).
Posting saya adalah tentang surat dari Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang mengusulkan agar jalur penerimaan mahasiswa baru ditambah lagi dengan memasukkan kemampuan penghafalan dan seni pembacaan ayat kitab suci. Bersama posting ini saya juga menyertakan posting lainnya, yaitu Siaran Pers Humas UGM yang menolak usul tersebut, dan di bawahnya saya tambahkan komentar saya sendiri, “Aduh, UGM hampir malu-maluin banget.”
Tentu saja komentar saya memakai kalimat informal sekenanya, sebab di WA group, apalagi di antara kawan sealumni, umumnya gaya berkomunikasi memang seperti itu. Saya setuju pada isi siaran pers tersebut, dengan ungkapan yang akrab di kalangan kami.
Namun, salah seorang anggota group kami ternyata langsung merespon balik dengan cukup tajam: “Saya tidak sependapat. What’s wrong with that, Celli?” (karena kami berteman sejak mahasiswa, dia memakai nama kecil saya).
Pertanyaan ini fair untuk dilontarkan. Ia datang dari seseorang yang, setidaknya pada saat kuliah dulu, bukan tipe aktivis, apalagi pengikut radikal dari sebuah perkumpulan agama. Ia adalah perwakilan mayoritas yang ada saat ini, dan karena itu barangkali mencerminkan sebuah arus baru, bagian dari gelombang besar santrinisasi kebudayaan Indonesia kontemporer, yang kini mulai dominan.
Adapun terhadap pertanyaan tadi, jawaban saya tentu tidak memadai untuk ditulis dalam format whatsapp. Tapi kurang lebih, sikap dan argumen saya terdiri dari dua poin berikut ini.
KEMAJEMUKAN INDONESIA
Pertama, argumen yang berhubungan dengan fairness dan kemajemukan Indonesia: kalau kita anggap bahwa kemampuan menghafal ayat kitab suci memang layak dijadikan kriteria dalam pemberian preferensi masuk ke universitas negeri seperti UGM, kita harus membuka hal yang sama bagi semua umat beragama, bukan hanya buat kaum Islam.
Tapi apakah memang hal seperti itu yang kita inginkan? Calon mahasiswa penghafal Quran, Injil berbagai versi, kompilasi serat dalam kitab Wedha atau Bhagawad Gita, serta ujaran-ujaran Budha-Konfusius: semua ini harus diuji atau diseleksi. Bagaimana caranya? Siapa yang melakukannya?
Bagi saya, semua itu akan menciptakan beban tambahan yang agak kompleks bagi pihak universitas yang saat ini pun sudah kerepotan dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu mendidik mahasiswa untuk meraih ilmu pengetahuan setinggi-tingginya serta melatih mereka untuk berpikir dalam kerangka keilmuan untuk memahami berbagai aspek kehidupan.
Kalau kompleksitas tersebut disederhanakan dengan hanya menerima ketegori penghafal ayat-ayat Quran, kita tentu bersikap tidak adil terhadap umat beragama lainnya.
Dalam hal terakhir ini, perlu juga diingat bahwa selama ini pemerintah sudah membiayai pembentukan banyak universitas negeri Islam (dulu disebut IAIN). Setahu saya, pemerintah tidak melakukan hal yang sama untuk umat beragama lain. Tidak ada perguruan tinggi Katolik, Protestan, Hindu atau Budha yang secara resmi dibentuk dan dibiayai oleh negara.
Kebijakan ini diterima sebagai bagian dari konsensus bersama untuk mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam dunia pendidikan tinggi. Di Perancis, Amerika Serikat dan banyak negara demokrasi lainnya hal seperti itu tidak boleh dilakukan sebab, menurut konstitusi mereka, negara harus terpisah serta bersikap netral terhadap semua agama.
Di Indonesia kebijakan pro-Islam tersebut, kalau bisa disebut demikian, didukung luas dan merupakan sebuah kompromi produktif untuk memperkuat keutuhan Indonesia. Hasilnya pun sejauh ini patut mendapat pujian: banyak alumni perguruan tinggi Islam telah memberi sumbangan penting dalam khazanah intelektual Indonesia, dari Dr. Nurcholish Madjid, Dr. Bachtiar Effendy, hingga Dr. Saiful Mujani sekarang ini.
Singkatnya, kompromi dan akomodasi terhadap Islam sejauh ini sudah berjalan relatif baik, dan karena itu seyogyanya universitas berperan memperkuatnya, bukan justru memasukkan persoalan baru dengan akibat yang mungkin kontraproduktif. Universitas harus menjadi faktor pemersatu, sebuah tenda besar bagi pembentukan komunitas ilmiah, bukannya menjadi faktor pemicu yang mempertajam perbedaan agama di kalangan generasi muda Indonesia.
BUKAN TRADISI MENGHAFAL
Argumen saya yang kedua berhubungan dengan substansi kategori tersebut, yaitu penghafalan ayat-ayat kitab suci.
Pertanyaan yang langsung muncul di benak saya ketika membaca surat Dekan FEB UGM adalah: kenapa perguruan tinggi perlu mendorong tradisi hafal-menghafal? Bukankah cara berpikir dan metode belajar seperti itu - menghafal naskah - justru membuat pikiran jadi beku?
Kita perlu mendorong agar mahasiswa Indonesia menjadi manusia kreatif, mampu berpikir sejauh-jauhnya, membuka horizon baru dalam usia mereka yang memang perlu untuk itu. Apa hubungan semua ini dengan metode hafal-menghafal ayat kitab suci, dari agama mana pun?
Kaum pendukung kebijakan tersebut, seperti kawan seangkatan saya di WA group kami, mungkin berasumsi bahwa penghafalan ayat suci adalah tradisi panjang dalam Islam, dan karena itu perlu dihargai.
Tentu saja saya menghargai tradisi itu - waktu masih di sekolah dasar, saya juga melakukannya. Tapi di situlah soalnya: apakah tradisi harus kita terima begitu saja? Positifkah tradisi demikian bagi kemajuan Islam dalam zaman seperti sekarang? Terus terang, saya agak ragu.
Katakanlah UGM, IPB dan ITB membuat hal berbeda: mendorong atau menjadi sponsor klub sains, penulisan esai, lomba debat dan pidato di kalangan remaja pesantren. Para pemenangnya diberi beasiswa atau, kalau cukup umur, diterima langsung menjadi mahasiswa di salah satu dari tiga perguruan tinggi terhormat ini. Bagi saya, hal ini jauh lebih tepat dan pasti akan dipuji semua pihak karena ia sesuai dengan peran esensial sebuah perguruan tinggi, serta sesuai pula dengan semangat untuk membantu pengembangan pendidikan umat Islam.
Dan yang terpenting, kegiatan semacam itu mendorong dunia universitas untuk tidak terjebak pada cara yang “gampangan” dengan mendorong metode belajar yang keliru dan patut dipertanyakan.
Bung Karno, dalam masa pembuangan di Bengkulu pada zaman pra-kemerdekaan, pernah melontarkan self-criticism. Dia berkata bahwa masyarakat Islam, setelah puncak kejayaan di abad ke-11, terlanda kebekuan berpikir selama seribu tahun karena terlalu mementingkan tradisi dan hal-hal yang bersifat “kulitnya” saja. Umat Islam masih terjebak dalam “masyarakat onta,” demikian dia menyayangkan, sementara dunia sudah bergerak melahirkan “masyarakat kapal terbang.”
Kebekuan berpikir tersebut, menurut Bung Karno, adalah salah satu kunci di balik ketertinggalan umat Islam dalam mengejar ilmu pengetahuan modern.
Apa yang disampaikan Bung Karno memang terkesan jadul banget bagi anak muda sekarang - buat mereka, masyarakat sekarang adalah masyarakat iphone, algoritma, dan mungkin sebentar lagi akan berubah menjadi masyarakat intelijensia sintetis dan robotika. Namun makna di balik kata-kata Sang Proklamator tersebut tetap perlu direnungkan sekarang, terutama di kalangan pimpinan perguruan tinggi kita.
KESEIMBANGAN AGAMA DAN ILMU
Kedua argumen itulah yang dapat saya jelaskan dalam menjawab langsung pertanyaan kawan saya di WA group kami. Masalahnya memang agak sensitif, tetapi di kalangan kami seangkatan, karena sudah saling mengenal sejak lama, kami bisa berkata, our love and respect to one another are greater than anything else. Persahabatan kami cukup mendalam dan karenanya tidak akan terganggu oleh perbedaan sikap dalam memahami kehidupan.
Kalau boleh, sebagai tambahan kedua argumen tadi, saya ingin menjelaskan secara singkat apa yang telah saya singgung di bagian awal tulisan ini, yaitu bergesernya keseimbangan antara agama, universitas dan ilmu pengetahuan di Indonesia belakangan ini.
Barangkali bisa dikatakan bahwa sebenarnya, surat Dekan FEB UGM tadi hanyalah salah satu contoh dari pergeseran tersebut. We are all a bit more heavy on the side of religion now.
Karena itu, pertanyaan penting sekarang adalah, bagi generasi muda Indonesia, khususnya mereka yang belajar di perguruan tinggi, sejauh mana sebenarnya agama dan ilmu pengetahuan dapat didamaikan, disatukan dalam hubungan yang produktif?
Agama dan ilmu: dua elemen kehidupan yang masing-masing memiliki sifat dan cara pandangnya sendiri. Yang satu bermula dan berakhir dengan kepastian yang tak boleh dipertanyakan, sementara yang satunya lagi justru ingin mendobrak kepastian yang ada, mengujinya, bahkan menolaknya jika perlu. Pada agama unsur yang terpenting adalah iman dan percaya (act of believing), sementara pada ilmu kata kuncinya adalah kemampuan untuk terus-menerus bertanya serta meragukan semua hal dengan pikiran terbuka.
Jadi pada intinya, kalau kita meminjam ungkapan Richard Faynman, fisikawan terkemuka Amerika Serikat, dapat dikatakan bahwa agama adalah a culture of faith, sementara ilmu pengetahuan a culture of doubt.
Karena perbedaan mendasar itulah, hubungan antara agama dan ilmu sangat kompleks dan selalu berada dalam ketegangan terus-menerus. Di Eropa, misalnya, ketegangan itu sudah muncul praktis sejak lahirnya ilmu pengetahuan modern di abad ke-16 dan abad ke-17, dan sampai sekarang pun sisa-sisanya masih terasa - Vatikan meminta maaf secara resmi atas pengadilan Galileo Galilei baru pada tahun 1992 lalu, setelah 359 tahun!
Akankah dinamika dan ketegangan yang sama, dalam bentuk atau manifestasi berbeda, juga terjadi di negeri kita? Mudah-mudahan tidak.
Di Eropa, akhir ketegangan tersebut adalah surutnya agama dari ruang publik, beralih ke ruang pribadi yang bersifat individual, dan hanya setelah itulah ilmu pengetahuan berkembang pesat. Bagaimana dengan kita? Bisakah UGM, misalnya, mengejar ketertinggalannya dari Universitas Harvard dan Universitas Stanford jika unsur agama dan suasana keagamaan terlalu mendominasi perhatian kaum akademisi yang mengabdi di dalamnya?
Dan bagaimana pula dengan nasib kaum mahasiswa kita? The passion of learning: inilah kata kunci buat mereka agar sukses mengejar ilmu pengetahuan setinggi-tingginya. Tapi kalau pikiran mereka terbelah, atau perhatian mereka terlalu terobsesi dengan the world beyond reason, apa yang kira-kira akan terjadi?
Terus-terang, saya tidak tahu. Namun saya berharap bahwa mereka, dan kita semua, segera menemukan keseimbangan baru yang damai dan produktif antara kedua hal fundamental itu - agama dan ilmu pengetahuan.
Sebagai penutup, barangkali sebuah kutipan dari Isaiah Berlin perlu kita dengarkan: out of the crooked timber of humanity, nothing completely straight was ever made. Perjalanan Indonesia dalam mencari keseimbangan baru tersebut mungkin akan seperti itu, berkelok, naik dan turun, atau berputar-putar sebelum berjalan ke arah yang benar.
Tapi itulah kehidupan. Justru barangkali, setelah proses pencarian yang tak mudah tersebut, Indonesia akan tumbuh lebih matang dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan.
Advertisement