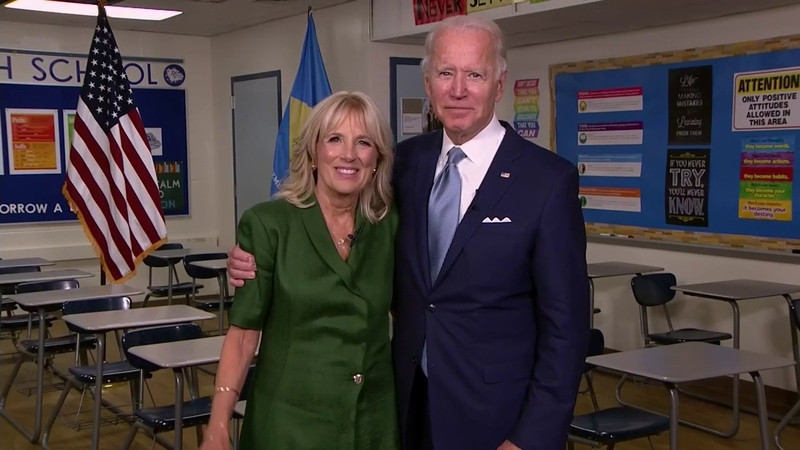Tarawih Paket Hemat

Oleh: Akhmad Zaini
“Malam tarawih pertama dimulai. Saya mendapat ‘dawuh’ untuk shalat bersama Gubernur……….Rangkaian Shalat isya’ dilanjutkan shalat tawarih ini diselenggarakan di kediaman …..Jamaah terbatas hanya keluarga dan staf. Pakai masker dan jaga jarak. Pokoknya tetap ta'at prokes.
Salatnya ‘Paket Hemat’. Durasinya tidak pakai lama. Singkat tapi hikmat. Bacaan surat-srat pendek. Doa pun pendek-pendek. Alhamdulillah. Insya Allah Berkah”
Rangkaian kalimat di atas adalah postingan di facebook senior saya, kakak angkatan ketika kuliah S1 dulu.
Saya tahu maksud dari kalimat, “Peket Hemat” di postingan itu. Yakni, shalat tawarih dengan 8 rakaat (11 dengan witir). Karena itu, dengan bercanda saya merespon postingan itu dengan berujar,” Aku paham maksude ‘Paket Hemat’. Tapi ora tak ceritakno sopo-sopo. TST. Tahu sama tahu..hehehe”
Dia mafhum kalimat saya. Dia pun merespon dengan bercanda pula. “Kwkwk..Jen ki memang benar-benar paham haliyahku.” Haliyah, secara sederhana bisa diartikan sebagai perilaku atau kebiasaan.
Saya kenal betul senior itu. Dia NU tulen. Saya yakin, dengan melaksanakan Salat Tarawih 8 rekaat, tidak otomatis dia berubah menjadi Muhammadiyah. Dan saya yakin, ketika dia menjadi imam, tidak otomatis meninggalkan ke-NU-annya. Saya yakin, se yakin-yakinnya dia tetap shalat dengan “menggunakan cara NU”. Yaitu, tetap membaca bismillah.
Ini fenoma baru yang terjadi beberapa tahun belakangan ini. Orang NU, diam-diam melakukan amalan yang selama ini menjadi “hak paten” Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya, beberapa warga Muhammadiyah juga “diam-diam” melaksanakan amaliyah yang menjadi “hak paten” NU.
Teman saya yang NU cekek (tulen) itu, tidak merasa takut memposting haliyahnya. Ini karena, sebagian warga NU paham betul bahwa soal jumlah rekaat shalat tarawih memang masuk dalam wilayah khilafiyah. Tidak terjadi kesepakatan antar ulama. Sehingga, ketika ada yang mempraktekkan 8 rekaat, tidak dihukumi salah.
Sampai saat ini, pemerintah Arab yang Wahabi, juga melaksanakan shalat tarawih di masjidil haram dengan jumlah 20 rekaat (23 dengan witir). Dalam hal ini, NU sama dengan pemerintah Arab Saudi. Sementara Muhammadiyah yang selama ini “dekat” dengan praktek keagamaan di Arab Saudi --bahkan sampai ada yang mengaitkan Muhammadiyah dengan Wahabi—malah berbeda.
Jadi, menurut saya, kecenderungan belakangan ini, mereka yang memilih shalat tarawih 8 (11 dengan witir) –khususnya warga NU perkotaan seperti senior saya tadi--, pada umumnya lebih kepada pertimbangan praktis. Cepat selesai. Bukan idiologis. Karena umumnya, mereka melaksanakan tarawih dengan pembacaan aya-ayat pendek, seperti pada shalat tarawih 20 rekaat. Harusnya, mereka yang memilih 8 rekaat, mestinya membaca ayat-ayat panjang seperti yang dulu dicontohkan oleh tokoh Muhammadiyah A.R Fachruddin.
Jumlah Rakaat
Masalah jumlah rekaat shalat tarawih, hanyalah salah satu contoh. Di lapangan, masih banyak amaliyah keagamaan yang bisa dijadikan contoh. Warga Muhammadiyah yang di era pra kemerdekaan pernah melancarkan gerakan anti TBC (Tahayul Bid’ah dan Churafat), sekarang diam-diam juga melakukan hal-hal yang dulu dikatagorikan dalam TBC. Sekarang, tidak sulit menjumpai warga Muhammadiyah menggelar acara tahlilan ketika salah satu saudaranya meninggal dunia.
Yang agak fenomenal adalah ziarah kubur. Dulu, warga Muhammadiyah terkesan anti ziarah kubur. Namun, sekarang dengan berbagai narasi yang dikembangkan, persoalan itu menjadi lebih cair. Intinya, warga Muhammadiyah boleh ziarah kubur seperti halnya warga NU. Namun, dengan catatan tidak melakukan hal-hal yang berbau pengkultusan makam dan syirik. Dan itu, mestinya juga tidak jauh beda dengan yang ditetapkan oleh para ulama NU. Cuma, mungkin bahasa dan gaya penyampaiannya saja yang beda.
Perubahan-perubahan itu, terjadi karena adanya proses dialektika yang terus terjadi. Baik antar NU-Muhammadiyah, internal NU dan juga di internal Muhammadiyah. Hal positif yang lahir dari adanya dealiketika itu, akhirnya muncul pencampuran-pencampuran. Dari sini, muncullah istilah Muhammaddinu atau MUNU (Muhammadiyah-NU). Intinya, hubungan warga Muhammadiyah dan NU menjadi lebih cair dalam masalah-masalah yang bernuansa khilafiyah.
Di lapisan masyarakat kelas menengah perkotaan, saat ini sulit membedakan antara warga NU dan Muhammadiyah. Dari sisi berpakaian tidak ada bedanya. Bila pra kemerdekaan, para aktivis NU dicirkan dengan menggenakan sarung dan peci, sekarang tidak relevan lagi. Banyak di antara warga nahdliyin yang sekarang lebih akrab dengan celana dengan sepatu, plus dasi.
Begitu juga dengan latar belakang pendidikan. Bila pra kemerdekaan, NU didominasi alumni pesantren. Sekarang, alumni perguruan tinggi bergelar akademik profesor, doktor di NU tidak terbilang jumlahnya. Mereka pun banyak yang lulusan dari perguruan-perguruan tinggi di Barat, seperti Jernam, Amerika, Belanda, Inggris dll.
NU, sekarang juga tidak hanya mengelola pesantren. Sekolah formal yang dulu menjadi ciri khas Muhammadiyah juga banyak dimiliki NU. Saat ini, setidaknya ada 21 ribu sekolah berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU. Begitu pula dengan perguruan tingginya. Saat ini, ada 258 perguruan tinggi yang terhimpun di dalam LPT NU (Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama.
Demikian juga dengan rumah sakit. Saat ini, di berbagai kota juga didirikan rumah sakit yang dikelola oleh warga NU. Dalam hal mengelola lembaga pendidikan formal dan rumah sakit ini, NU banyak mengambil inspirasi dari Muhammadiyah.
Di pihak lain, Muhammadiyah sekarang juga berupaya keras untuk memiliki pesantren. Muhammadiyah yang selama ini fokus mengelola lembaga-lembaga pendidikan formal, memang sukses mencetak jutaan kaum terpelajar dan teknokrat yang mengisi sektor-sektor industri dan pemerintahan. Namun, di balik kesuksesan itu, Muhammadiyah merasa gelisah karena semakin minim setok ahli agamanya (ulama).
Dari kegelisan itu, Muhammadiyah sejak era Dien Syamsuddin memprogramkan untuk mendirikan pesantren Muhammadiyah. Saat ini, ada sekitar 364 pesantren Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dan, dalam konteks pesantren ini, Muhammadiyah juga merasa perlu belajar banyak dari pesantren-pesantren NU. Hal itu, bisa ditankap dengan jelas ketika beberapa waktu lalu LP2 PPM (Lembaga Pengembangan Pesantren Pengurus Pusat Muhammadiyah) menggelar webinar soal kaderisasi ulama.
Dari paparan di atas, nampak sekali telah terjadi dialektika antara NU-Muhammadiyah. Ada proses untuk saling belajar. Ada proses untuk melengkapi kekurangan yang ada. Bila proses itu terus berjalan, maka sekian tahun lagi, kita akan kesulitan mencari titik perbedaan yang ekstrim antara NU-Muhammadiyah.
Dan proses itu, saya yakini akan terus berjalan secara masif. Saat ini, para elite NU dan Muhammadiyah sering terlibat dalam wacana pemikiran yang sama. Seperti soal Islam moderat, Islam rahmatan lil alamin, anti terorisme dan perlunya menjaga keutuhan NKRI. Pola pikir mereka banyak titik kesamaannya. Dan itu, dipermulus lagi dengan banyaknya tokoh Muhammadiyah yang berlatar belakang nahdliyin, seperti seketaris umum PP Muhammadiyah Prof Dr. Abdul Mu’thi, Dien Syamsuddin dan lain sebagainya.
Tentu, proses dialektika itu masih akan terus berproses. Tidak semuanya mulus. Di internal NU-Muhammadiyah, pasti ada kelompok yang masih ingin melestarikan politik identitas. Tapi, rasanya lambat laun, kelompok ini akan semakin mengecil jumlahnya. Mayoritas, akan berada di golongan yang menghendaki adanya konvergensi. NU-Muhammadiyah hanya sebatas perbedaan di organisasi. Bukan di idiologis. (bersambung)
Akhmad Zaini
Mantan Jurnalis, tinggal di Tuban.
Advertisement