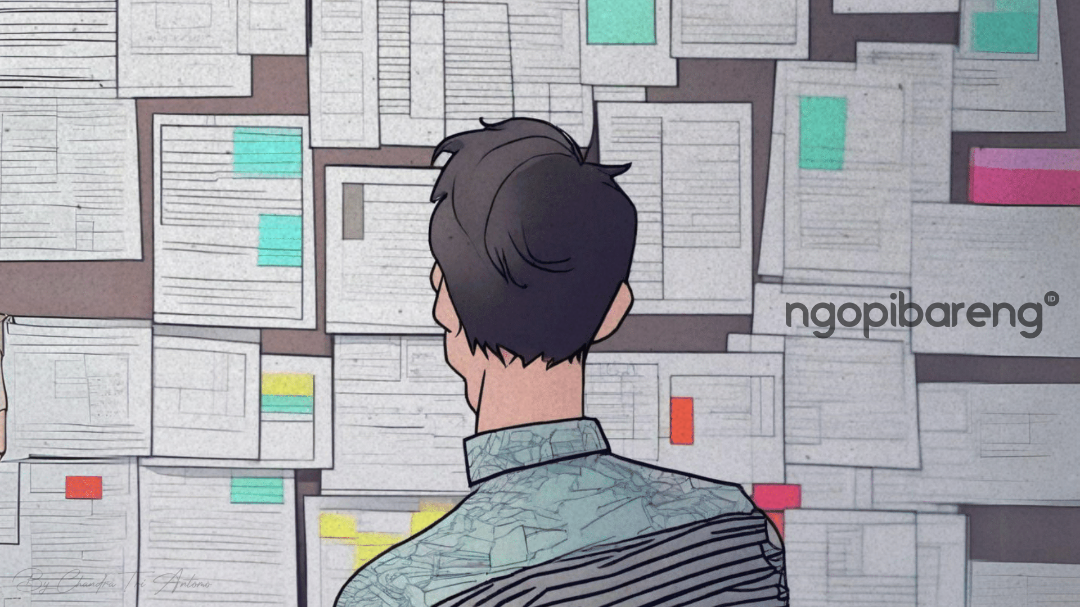Taiwan (3): Sepenggal Peradaban Dunia

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Dosen HI Universitas Jember dan Taiwan’s MOFA research fellow di Wenzao Ursuline University
SUDAH tiga kali saya berkunjung ke Kaohsiung, kota tempat saya sedang menjalani program visiting research fellow kali ini. Dalam dua kunjungan terdahulu saya tak sempat jalan-jalan. Pasalnya, dalam kunjungan pendek (short visit) tersebut waktu tersita oleh kegiatan akademis. Tak heran, jika mobilitas hanya terbatas seputar kampus. Tapi, kunjungan kali ini agak berbeda, karena waktunya relatif lama. Meski misi akademis tetap membayangi, saya masih sempat berkelana cuci mata.
Kesan perdana terhadap Kaohsiung city adalah tata ruangnya yang rapi. Mayoritas jalannya lebar dan lurus, mengapit blok-blok bangunan berbentuk persegi. Kondisi ini tak terbatas di kawasan Central Business District (CBD), tetapi juga di daerah suburb, seperti Gushan district di mana saya tinggal. Jadi teringat pada dua well-planned cities yang pernah saya kunjungi: Washington D.C.- USA dan Melbourne-Australia. Tata ruang punya dimensi ruang dan waktu. Laiknya di dua kota ini, di Kaohsiung waktu tempuh ke lokasi dekat bersandar pada berapa blok yang dilalui. Cara ini berbeda dengan kampung saya --di Batu sana-- yang waktu tempuh sering diperkirakan dengan metafora: “paling sak-rokok-an!” (sekitar hisapan sebatang rokok!). Aspek kepastian nampaknya memang ciri budaya modern, sementara relativisme selalu mewanai budaya tradisonal.
Di Kaohsiung, kepastian antara lain tercermin pada layanan publik. Dalam transportasi, misalnya, jalur Mass Rapid Transport (MRT), Light Rail Transport (LRT), dan bis kota, terintegrasi. Dengan ini orang bisa merencanakan perjalanannya dengan waktu tempuh yang diinginkan. Selain jadwalnya pasti dan tepat, fasilitasnya juga nyaman. Pasalnya, semua wahana ber-AC. Waktu operasi mulai pukul 6 pagi sampai jam 12 malam. Bahkan, dalam jam-jam sibuk (rushing hours) jeda keberangkatan diperpendek menjadi 5 menit sekali. Pembayarannya-pun tidak ribet, karena tiket elektronik berlaku untuk semua wahana. Dampaknya positif. Kemacetan lalu lintas jarang terjadi, karena mayoritas warga lebih suka pakai transportasi publik daripada mobil pribadi.
Bersih juga tak tersisih. Meskipun mungkin belum menyamai Jepang; warga Kaohsiung nampak peduli terhadap kebersihan lingkungan. Bukan hanya jalan, tetapi juga tempat yang rawan sampah, seperti sungai dan pasar. Konon, indikator paling dasar untuk mengukur kepedulian masyarakat terhadap kebersihan bisa dilihat pada dua tempat: toilet umum dan pasar. Di Kaohsiung, sejauh yang saya tahu, kedua fasilitas publik itu relatif jauh dari kesan kotor dan bau.
Kunjungan ke RRC tahun 2016 bisa dijadikan perbandingan. Kala menuju Stone Forest, sekitar dua jam perjalanan dari kota Kunming, rombongan saya singgah di rest area. Toilet menjadi target utama. Fasilitasnya modern. Bahkan, untuk ukuran Indonesia tergolong mewah. Closet-nya saja pakai automatic flush (sentoran otomatis). Sampai-sampai, yang lucu, beberapa teman sempat berteriak tanya tombol manualnya, yang memang tidak ada. Tapi, anehnya, bau pesing tetap menyengat. Saya berfikir, mesti ada yang salah dalam perilaku pemakainya. Tak heran, jika Presiden RRC-Xi Jinping-sampai perlu mencanangkan ‘revolusi toilet’ guna mengubah kebiasaan warganya di toilet umum. Perilaku sosial, dimanapun, mencerminkan peradaban masyarakatnya.
Bukan Sekadar Aliran Sungai
Sungai bukan sekedar aliran air, kondisinya juga mengundang tafsir. Kebetulan, hotel karantina di Kaohsiung persis menghadap sungai. Dari kamar di lantai lima saya bisa mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Meski banyak orang berlari sehat di kedua tepinya, terutama di sore hari, sampah hampir tak terlihat. Kalaupun ada, itu lebih karena peristiwa alam, bukan akibat tindakan manusia. Dedaunan tua dari pohon sekitar sungai sering berguguran ke permukaannya. Satu dua puntung rokok dan serpihan tissue memang sempat saya lihat, tapi itu di seputar di tempat duduk di trotoar pinggir sungai, yang lazim dijadikan tempat kongkow pejalan kaki. Sementara itu, sungai tetap bersih, bebas sampah, dan berhias ikan yang asyik berkejaran di permukaan.
Namun, Kaohsiung bukanlah kota tanpa kekurangan. Sebagai kota besar, polusi merupakan ancaman terbesar. Suatu pagi, saya mendapati sekelompok ikan mati mengambang, karena air sungai tercemar limbah industri. Oleh karena itu, tidak seperti di kota-kota maju lainnya di dunia dimana air kran (tap water) aman untuk diminum; di Kaohsiung tap water tidak dianjurkan untuk dikonsumsi, kecuali sudah melewati tangki pengolahan (treatment plants). Sampai saat ini, pemerintah kota masih terus bergulat untuk menjamin ketersediaan air sehat bagi masyarakat.
Meski ada beberapa noktah hitam di atas, Kaohsiung masih masuk kategori kota yang bersih dari sampah. Faktor utamanya adalah tatakelola (governance) yang baik. Suatu petang, saya mendengar suara musik kencang ala penjual es krim di Indonesia. Ternyata, musik berasal dari truk sampah-sebuah rolloff truck berwarna kuning-yang diikuti oleh truk sampah lain berwarna putih. Lagu-lagu populer, seperti Für Elise dari Beethoven, diputar dengan volume keras; sebagai tanda bagi warga bahwa waktu pengambilan sampah telah tiba. Truk sampah ini berkeliling mulai jam 17 sampai pukul 21 malam, beroperasi 5 hari dalam seminggu. Truk warna kuning memungut sampah rumah tangga, sementara yang putih mengambil sampah daur ulang.
Di pagi hari, ada ritual sampah yang lain lagi. Petugas berseragam dengan motor berkantong, dilengkapi dengan japit ala pemulung, menyusuri trotoar pinggir sungai. Dia memungut puntung rokok dan serpihan tissue yang terserak di sekitar tempat duduk publik. Cara ini memang belum secangggih Australia. Suatu ketika tiba di Melbourne waktu subuh, di luar stasiun kereta api saya melihat bagaimana petugas berseragam dengan motor-yang di bawah mesinnya dilengkapi dengan semprotan air-mengusir serpihan sampah kecil dari trotoar ke jalan raya. Kemudian, truk penyapu jalan yang mengiringi memungut dengan cara menyedotnya. Tapi, di Kaohsiung, pemungutan sampah dengan motor berkantong tetap efektif mendukung manajemen sampah di kota ini. Agak siang, dukungan lain datang. Dua petugas berseragam dengan menggunakan sampan bermotor aktif menjaring sampah alam yang terserak di permukaan air sungai.
Di sisi lain, mayoritas warga juga menunjukkan kommitmennya. Mereka aktif mengumpulkan sampah rumah tangga dalam kantung plastik biru, sementara sampah daur ulang pakai kantong warna lain. Kesadaran sosial ini tak lepas dari kampanye lingkungan oleh civil society sejak tahun 1990-an. Jargon “not in my backyard” (NIMBY), yaitu penolakan terhadap apapun yang tidak ramah lingkungan-seperti onggokan sampah beserta Tempat Pembuangan Akhir (TPA)-nya; ditambah kredo “yes in my backyard” (YIMBY)-seperti tuntutan ketersediaan ruang terbuka hijau; telah menyentuh nurani warga dan mendesak pemerintah untuk bersama-sama mewujudkannya.
Hasilnya luar biasa. Tahun 1990-an Taiwan sempat dijuluki “pulau sampah” (garbage island). Tapi, tahun 2020 negara ini telah bertransformasi menjadi negara dengan tingkat daur ulang sampah tertinggi di dunia. Semula negara ini hanya mampu mengelola 70% sampah, sehingga 30% sisanya tergolek menghiasi jalanan. Namun, berkat perbaikan governance, limbah rumah tangga menjadi turun 66%-salah satu tingkat produksi sampah per capita yang terendah di dunia.
Tertib Sosial
Tertib sosial adalah ciri berikutnya. Di setiap sudut kota saya melihat budaya antri yang tinggi, dilambari empati sosial yang kental. Saat naik eskalator MRT yang panjang, setiap orang berdiri rapi mepet ke handrail sebelah kanan. Tujuannya, tak menghalangi orang lain yang tergesa untuk berjalan di sebelah kiri. Selain itu, kebisingan juga dianggap sesuatu yang menganggu. Tak heran, jika di setiap transportasi publik-seperti MRT-selalu ada tulisan peringatan: “Please quiet!”.
Dua ilustrasi di bawah ini membantu memahami transformasi Taiwan dalam hal kebersihan, kebisingan, dan empati sosial. Dalam kunjungan tahun 2019, konferensi internasional “Journey of Asian Coffee” berlangsung di Hotel Ambassador, sebuah hotel bintang lima di pinggir sungai besar yang membelah kota Kaohsiung, bernama Love River. Ketika menyeberanginya, teman dari Canada berkata: “Saya takjub dengan perubahan sungai ini. Sepuluh tahun, lalu saya ke sini masih kotor penuh sampah. Kini, begitu nyaman dipandang karena kebersihannya!”.
Pagi sebelumnya, setelah sarapan, ada diskusi kecil di lobby hotel. Seorang kawan Filipina cerita bagaimana di bandara Hongkong dia dan penumpang lainnya pernah terganggu oleh kebisingan diselingi teriakan pelancong asal China daratan. Kisah perilaku pelancong asal RRC semacam ini bukan yang saya dengar pertama kali. Seorang teman Indonesia juga pernah cerita bagaimana dia ikut ditegur oleh check in officer bandara, karena kebetulan berdiri di belakang sekelompok pelancong RRC yang bising. Mendengar cerita teman Filipina, seorang pembicara dari Taiwan menyela: “Perilaku semacam itu juga dilakukan oleh pelancong asal Taiwan, tapi itu dilakukan oleh generasi kami terdahulu”! Semua yang mendengar, termasuk saya, terdiam mafhum.
Kerapian, kebersihan, keheningan, dan empati sosial; telah diakui sebagai global values. Bahkan, semua nilai-nilai ini telah dianggap sebagai bagian dari komponen peradaban dunia. Untuk mewujudkannya, antara lain, menuntut pembangunan manusia (human development). Prosesnya juga tidak bisa instant. Namun, sayangnya, belum semua orang memahaminya. Jika-pun sudah faham, ironisnya, tidak jarang yang masih enggan untuk memulainya. (bersambung)
Advertisement