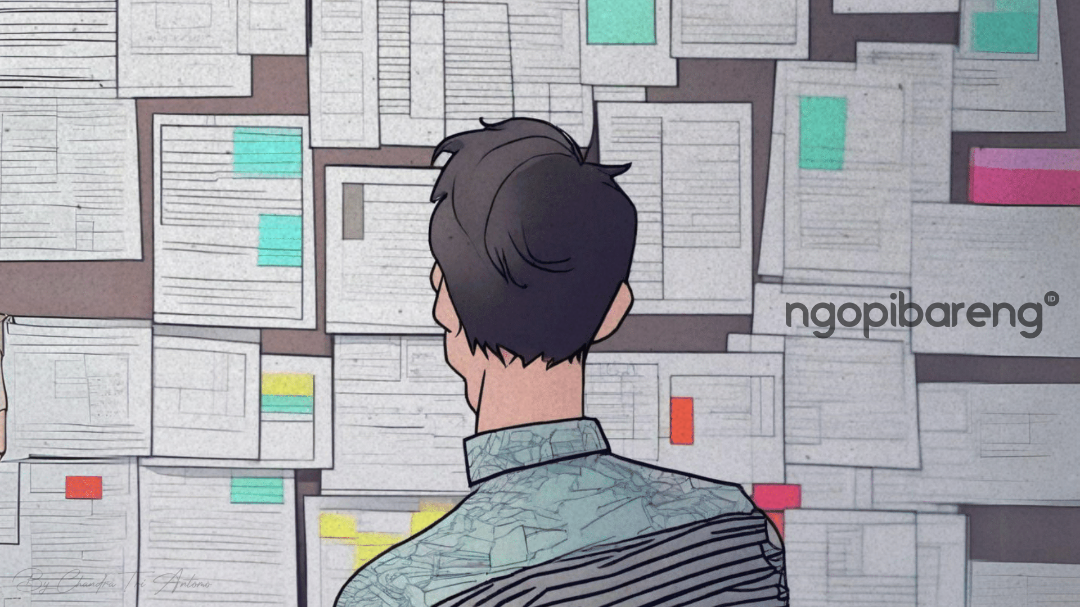Taiwan (1): Kala Pandemi Menggila

Oleh: Himawan Bayu Patriadi
Masa pandemi Covid-19 di Indonesia, memang pelahan reda. Bahkan, banyak orang tak lagi memedulikan protokol kesehatan: bermasker dan menjaga jarak. Tapi, tak demikian dengan di sejumlah negara. di Taiwan, misalnya, berbeda dengan di tanah air. Pemberlakuan saat-saat masih pandemi, tak bisa diabaikan. Apalagi bagi warga negara asing yang memasuki negeri itu, saat pandemi "menggila".
Pengalaman Himawan Bayu Patriadi, PhD, berkesempatan meraih Taiwan’s MOFA research fellow di Wenzao Ursuline University, mewajibkannya menaati aturan di Taiwan dan harus dikarantina terlebih dulu sebelum bebas beraktivitas mengajar.
"...saya harus mengunduh health certificate dari website Kementerian Kesehatan Taiwan dan menyimpannya di HP. Sertifikat ini ‘paspor’ untuk tiga keperluan: test PCR lagi, booking taksi khusus Covid-19, dan check-in hotel karantina," kisahnya.
Dosen HI Universitas Jember ini, diminta download LINE, aplikasi utama di Taiwan. Karena tak punya nomor Taiwan, ia diwajibkan membeli SIMCard setempat. "Fungsinya, untuk monitoring kesehatan selama karantina. Saya memilih paketan 4 GB untuk sebulan seharga NT$1000 (sekitar Rp500.000)," tuturnya.
Kisah lengkap Himawan Bayu Patriadi, yang disajiakn bersambung di Ngopibareng.Id. Berikut bagian awal tentang "Kala Pandemi Menggila". (Redaksi)
WAKTU KEBERANGKATAN itu akhirnya datang. Saya harus ke Taiwan dalam rangka program visiting research fellow di Wenzao Ursuline University, Kaohsiung. Sebenarnya, sejak pemberitahuan berhasil memperoleh beasiswa dari Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan pada Oktober 2021, ada notifikasi bahwa program fellowship bisa saya mulai sejak awal Januari 2022. Dengan catatan, saya sudah mendapatkan institusi yang bersedia menjadi research-host.
Tapi, saya lebih memilih menundanya sampai awal Juni 2022. Pertimbangannya, ingin menuntaskan tugas semester-an lebih dahulu. Yang tak kalah penting, juga kalkulasi Pandemi. Alasannya, prasyarat perjalanan ke mancanegara tak cukup memilki paspor dan visa; tapi juga terbebas dari Covid-19. Harapannya, pertengahan tahun pandemi telah mereda, sehingga perjalanan akan mudah tanpa harus ribet dengan protokol kesehatan (Prokes).
Namun, harapan tersebut tak sepenuhnya terwujud. Meski angka infeksi Covid-19 secara global telah melandai, Taiwan tetap enggan mengendorkan prokes. Aneh!? Padahal, negara tetangga, seperti Korea Selatan dan Singapura, telah melonggarkan aturan. Tapi, Taiwan tetap kukuh mempertahankan regulasi. Maklum, beberapa bulan terakhir penyebaran Covid-19 sempat meluas. Bahkan, tingkat kematian tergolong tinggi. Parameter ‘tinggi’ di sini, secara komparatif tentu relatif. Yang jelas, tak bisa disamakan dengan yang pernah terjadi di India atau Indonesia.
Setelah tiba di Taiwan,barulah saya mendapat info bahwa salah satu faktor penyebab tingginya kematian adalah rendahnya tingkat vaksinasi. Bagi saya fenomena ini merupakan keanehan kedua, mengingat negara ini secara ekonomi makmur, dan penduduknya hanya sekitar 23 juta orang. Berdasar observasinya, seorang teman menyodorkan analisa sosiologis-psikologis. Menurutnya, tidak sedikit warga Taiwan yang tergolong ‘Orang Kaya Lama’. Dengan karakternya yang cenderung overconfidence termasuk terhadap kualitas kesehatan mereka telah membuat mereka abai akan pentingnya proteksi kesehatan.
Alternatif Penjelasan
Namun, ada alternatif penjelasan. Tingginya tingkat kematian juga tak lepas dari karakter populasi. Seiring dengan meningkatnya kemakmuran ekonomi, Taiwan dihantui ‘populasi yang menua’ (the ageing population). Proporsi warga berusia 65 tahun ke atas terus membesar. Tahun 1960-an hanya berkisar 2%. Tapi, tahun 2020 telah meningkat pesat mencapai 16%, dan pada tahun 2060 diproyeksikan akan mencapai 40% dari total penduduk. Berkaca pada fenomena di negara maju¾seperti Italia saat merebaknya Corona varian Delta¾the ageing population memang rentan terhadap ancaman kesehatan. Meningkatnya jumlah lansia, ditambah rendahnya vaksinasi, telah meningkatkan resiko kematian akibat Covid-19. Walhasil, pemerintah Taiwan memperketat prokes. Vaksinasi digalakkan dan Covid tracing system diberlakukan. Bahkan, ada insentif uang cash bagi penduduk yang mau vaksinasi. Prokes berlaku untuk penduduk setempat maupun pendatang dari luar negeri .
Ketatnya prokes, saya alami sejak sebelum berangkat. Selain prasyarat test Polymerase Chain Reaction (PCR) maksimal 48 jam sebelum take-off, secara online saya harus mengisi formulir empat halaman untuk mendapatkan sertifikat health declaration. Sertifikat ini akan masuk dalam Covid tracing system Taiwan. Mobilitas saya akan selalu terpantau melalui handphone (HP). Fitur geolocation harus selalu on, jika tidak mau resiko didatangi polisi.
Saya juga diharuskan booking hotel karantina. Saya ingin karantina di Kaohsiung. Selain biaya hotelnya lebih murah, jika ada kesulitan saya mudah meminta bantuan Wenzao Ursuline University, sebagai research host. Tapi, keinginan saya ditolak dan disarankan untuk karantina di Taipei. Alasannya, selain kamar hotel terbatas, prioritas diberikan kepada penduduk dan pekerja migran. Tapi, Wenzao Ursuline University ikut turun tangan. Dengan meyakinkan bahwa saya adalah tamunya, saya akhirnya diijinkan untuk karantina di Kaohsiung.
Setelah landing jam 6 pagi di bandara Toyuan, Taipei satu-satunya entry airport selama pandemi, prokes bandara yang ketat mulai terasa. Inilah awal ujian kesabaran. Untungnya, para petugas—semua memakai Alat pelindung Diri (APD)—berbahasa Inggris lumayan, sehingga memudahkan saya memahami petunjuknya. Maklum, saya sama sekali tak faham bahasa Mandarin sekaligus buta huruf China. Sebagai pendatang, saya diarahkan ke jalur khusus.
Lupakan dulu masalah imigrasi dan pengambilan bagasi, karena prokes telah menanti. Pertama, saya diminta download LINE, aplikasi utama di Taiwan. Karena tak punya nomor Taiwan, saya diwajibkan membeli SIMCard setempat. Fungsinya, untuk monitoring kesehatan selama karantina. Saya memilih paketan 4 GB untuk sebulan seharga NT$1000 (sekitar Rp500.000). Toh, akhirnya saya juga perlu untuk komunikasi selama di Taiwan. Kemudian, saya harus mengunduh health certificate dari website Kementerian Kesehatan Taiwan dan menyimpannya di HP. Sertifikat ini ‘paspor’ untuk tiga keperluan: test PCR lagi, booking taksi khusus Covid-19, dan check-in hotel karantina. Sebelum melewati tahap ini, saya dibekali print-out health certiticate, tube kosong (semula saya tak tahu untuk apa), dan dua pack Antigen Self-Test merk Panbio.
Proses Melelahkan di Negero Orang
Setelah semua teratasi, barulah saya diarahkan menuju imigrasi dan pengambilan bagasi. Prokes selesai? Belum! Masalahnya, bahasa Inggris petugas di luar tak sebaik petugas di dalam terminal. Saya beberapa kali ‘terpingpong’ karena tak menangkap petunjuknya. Test PCR harus dilakukan lagi, meski sudah negatif sebelum pergi. Di sini saya sedikit merasa tersiksa. Pasalnya, metode PCR bukanlah nasal swab test di hidung, tapi saliva-based test dengan ludah. Padahal, sejak take off dari Jakarta, saya sedikit minum guna mengurangi buang air kecil. Dampaknya, mulut kering akibat minimnya ludah. Tak pelak, saya sekian kali gagal memenuhi takaran saliva minimal.
PCR test adalah ujung prokes bandara yang memakan waktu satu jam. Berbekal health certificate, saya mendatangi taxi counter. Petugas berkata: “Ongkos ke Kaohsiung NT$ 2660!” (1,33 juta rupiah). Setelah bayar saya nanya: “Bolehkah saya makan roti selama perjalanan?”. Dia jawab: “No! kamu hanya boleh minum!”. “Waduh!”, guman saya tanpa tanya mengapa. Maklum, saat studi di Australia, saya juga mendapati aturan yang sama. Kali ini, regulasi ini mungkin diperketat karena pandemi. Namun, terbayang rasa lapar selama lima jam perjalanan. Pasalnya, porsi makan malam di pesawat cuma sedikit, sementara di bandara tidak tersedia sarapan pagi.
Tak lama menunggu, sopir taksi datang. Dengan memakai APD, dia menyemprot sekujur badan sampai alas kaki dan semua bagasi. Saya duduk di jok belakang taksi dibatasi tabir plastik di belakang sang pengemudi. Saat berangkat dia menyuruh saya bicara via HP-nya sebagai laporan ke Central Epidemic Command Center (CECC).
Keluar dari bandara, ada yang tak dinyana. Ketika saya minum, sopir taksi ngasih dua potong biskuit. Terbengong sesaat, saya lalu tanya: “Bolehkah ini dimakan sekarang?”. Dengan bahasa Inggris terbata dia berkata: “Jangan kawatir, makan saja!”. Saya makan dengan ragu. Tapi, saat biskuit habis, ragu terkikis. Pasalnya, dia memberi lagi kripik gula bertabur wijen. Apalagi, kali ini dia juga ikut makan. Dia juga menawari rokok. Saya jawab: “Thanks, saya tidak merokok!” Dia balik nanya: “Boleh saya merokok?”, Saya spontan respon: “Ok, no problem!”. Dia tersenyum lega. Saya ijinkan merokok supaya dia tidak ngantuk, karena saya lirik jarum speedometer selalu di kisaran 120 km/jam. Sebenarnya ada gejolak dalam hati. Tapi, ‘simbiosis mutualisme’ dengan sopir taksi agak “mbethik” ini saya justru terhindar dari rasa lapar.
Tiba di hotel siang hari, sopir taksi ngontak CECC guna lapor lagi. Setelah check in dengan bahasa tarzan, karena resepsionis tak paham bahasa Inggris, saya mulai menjalani karantina 7 hari. Sorenya surprise terjadi. Meski kebutuhan hidup tujuh hari sudah tercukupi, masih ada bingkisan dua kantong besar berisi aneka makanan instant, teh, masker, dll. Satu kantong ternyata dikirim oleh Wenzao University, sedangkan lainnya dari Satgas Covid kota Kaohsiung. Yang menarik, lembar petunjuk di dalamnya ditulis dalam bahasa Indonesia! Kata penutupnya membesarkan hati: “[Dalam] masa karantina tidak [perlu] gelisah, [karena] perhatian terpadu menyertai anda”!
Selama karantina diilarang keras keluar kamar. Deringan tilpon pertanda makanan (3 x sehari) siap di depan pintu. Untuk membunuh jemu, rutinitas keseharian saya gunakan baca, browsing, dan menulis, meski terkadang terganggu karena wifi hotel kurang bagus. Monitoring kesehatan oleh CECC berlangsung tiap hari. Pagi pakai SMS, sore melalu phone call. Hari ke tujuh, saya harus melakukan dan melaporkan hasil antigen self-test. Jika tak melakukan ini, ancaman denda antara NT$ 10.000-150.000 (5 sampai 75 juta rupiah) telah menanti. Alhamdulillah, hasil test negatif. Namun, saya masih diharuskan melakukan self-health management. Boleh keluar pakai masker, tapi dilarang ke tempat keramaian dan naik public transport. Monitoring kesehatan tetap berlanjut. Cuma, anehnya, pada hari ke lima monitoring tidak ada. Eh, baru tahu ada regulasi baru. Karantina sudah diperpendek 3 hari, dan self-health management cukup empat hari.
Menjalani Prokes ketat Taiwan, memberikan beberapa pelajaran. Negara hadir dengan regulasi, sementara masyarakat secara umum mendukung dan mentaati. Meski negara ini mengadopsi demokrasi, tapi protes warga terhadap berbagai restriksi—seperti terjadi di Amerika dan di negara Barat lainya—tidak terjadi.
Keberhasilan Taiwan mengendalikan Covid-19, tak lepas dari baiknya sinergitas segenap komponen dalam tatakelola (governance) Covid-19. Pada 18 Maret 2022 lalu, The United Nation’s Sustainable Development Solutions Network merilis The 2022 World Happiness Report. Salah satu temuan utamanya menyoroti efek Covid-19 pada kesejahteraan masyarakat: “Negara-negara di mana warga mempercayai pemerintah mereka, dan saling mempercayai satu sama lain; mengalami angka kematian COVID-19 yang lebih rendah dan [mampu] mengatur tahapan untuk mempertahankan atau membangun kembali solidaritas dan tujuan bersama guna meraih kehidupan yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan”. Dalam hal ini, Taiwan merupakan salah satu negara yang masuk kriteria. Bahkan, negara ini mendapat pujian karena tingkat pencapaiannya merupakan yang tertinggi di antara negara-negara Asia Timur! (bersambung)
Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Dosen HI Universitas Jember dan Taiwan’s MOFA research fellow di Wenzao Ursuline University.
Advertisement