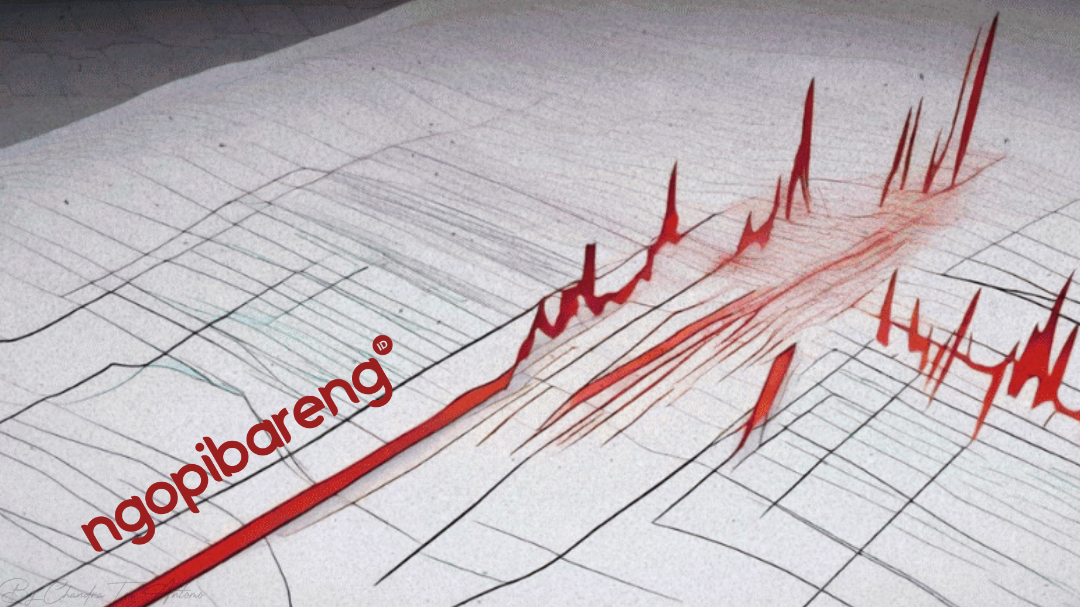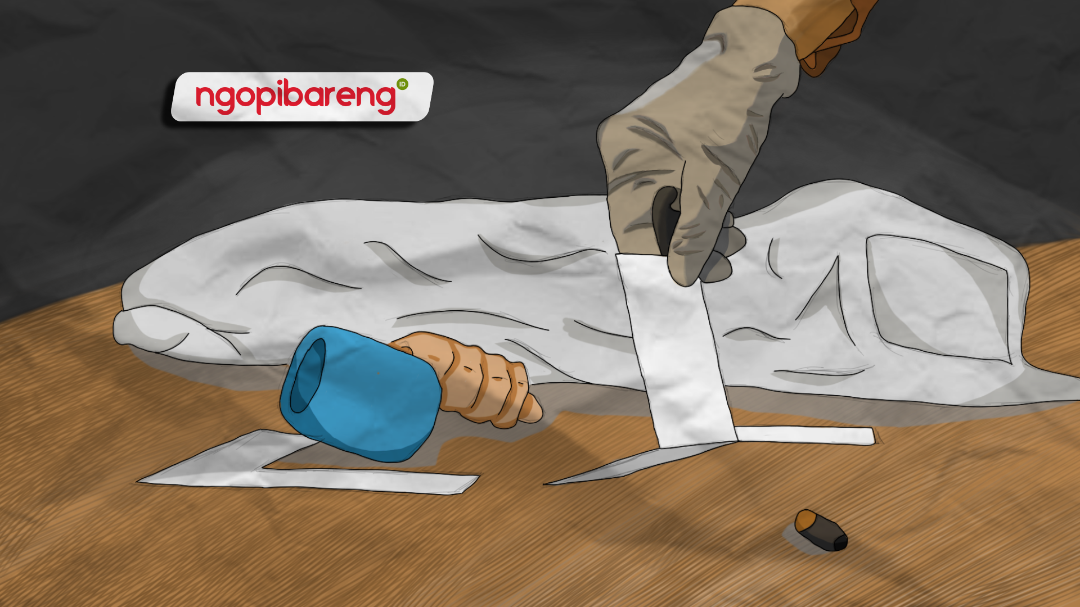Soal Polemik 'Kafir', Ini Penjelasan Perumus BM Munas NU

Polemik istilah kafir dalam pemberitaan Bahtsul Masail Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat terus menggelinding menjadi bola liar bahkan cenderung banyak disalahpahami oleh kelompok-kelompok tertentu.
Awalnya, para ulama dalam Munas NU tersebut membahas status non-Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan pertanyaannya ialah, Bagaimana dengan status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Persoalan ini dibahas dalam forum Bahtsul Masail Maudluiyah.
Diskusi yang mengemuka dari para kiai dalam forum Bahtsul Masail tersebut ialah kategori kafir merujuk pada kitab-kitab klasik para ulama fiqih, yaitu kafir harbi, kafir mu’ahad, kafir musta’man, dan kafir dzimmi.
Setelah melalui pembahasan cukup panjang, para kiai menyepakati bahwa status non-Muslim dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak termasuk dalam empat kategori kafir tersebut, tetapi mereka adalah warga negara (muwathin).
Oleh karena itu, perlu dicari kalimat lain yang lebih santun, misalnya non-Muslim. Ini tanpa harus mengubah “Qulyaa ayyuhal kaafirun” menjadi “Qul yaa ayyuhal non-Muslim”. Itu tidak boleh.
Berikut klarifikasi dan penjelasan salah seorang Perumus Bahtsul Masail Maudluiyah Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019, KH Afifuddin Muhajir Situbondo melalui sebuah video berdurasi 3 menit 40 detik:
Perlu diketahui bahwa saya merupakan bagian dari Tim Perumus Bahtsul Masail itu (Bahtsul Masail Maudluiyah yang membahas kedudukan Non-Muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara).
Dan perlu diketahui pula bahwa Bahtsul Masail di Munas itu tidak membahas tentang apakah non-Muslim di Indonesia ini kafir atau bukan. Akan tetapi yang dibahas adalah kategori mereka. Apakah mereka itu harbi, mu’ahad, musta’man, dan dzimmi?
Jawabannya, mereka (non-Muslim dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia) itu bukan harbi, bukan mu’ahad, bukan musta’man, bukan pula dzimmi.
Karena memang definisi-definisi tersebut tidak bisa diterapkan kepada non-Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, istilah yang tepat, katakan saja mereka non-Muslim.
Pertanyaan: Lalu bagaimana dengan ungkapan misalnya, “kamu kafir”, atau ungkapan dengan “yang mereka tidak sukai.”
Harus dibedakan pula antara keyakinan dan pernyataan, apa yang boleh atau bahkan wajib menjadi keyakinan belum tentu bisa dinyatakan. Misalnya, suatu kelompok yang dinyatakan dalam Al-Qur’an dinyatakan kafir, kita wajib meyakini mereka kafir.
Akan tetapi mengatakan, “kamu kafir”, “dia kafir”, “mereka kafir”, itu bisa menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat plural, yang sudah damai dan sudah diusahakan dan diciptakan dengan susah payah oleh pendahulu-pendahulu kita.
Oleh karena itu, perlu dicari kalimat lain yang lebih santun, misalnya non-Muslim. Ini tanpa harus mengubah “Qulyaa ayyuhal kaafirun” menjadi “Qul yaa ayyuhal non-Muslim”. Itu tidak boleh.
Di dalam sebuah kitab yang dinamakan Al-Qinyah atau Al-Qunyah, ini dari madzhab Hanafi, dikatakan di situ. Ibarat (tabir)-nya begini: “walau qaala li Yahudiyyin, aw Majusiyyin hiya kafiru, ya’sami insaqqa ‘alaihi. Jikalau misalnya seorang Muslim, berkata kepada penganut agama Yahudi atau agama Majusi: "wahai si kafir", maka si Muslim berdosa jikalau di Yahudi dan si Majusi itu keberatan terhadap ungkapan itu. Bahkan di dalam penjelasan selanjutnya, orang yang seperti itu berhak untuk dihukum atau di-takzir.
Pertanyaan: Harapan kiai kepada masyarakat terutama kaum santri menyikapi pemberitaan yang sudah menggelinding seperti bola liar, bagaimana?
Di dalam Islam sudah ada ajaran tabayyun, ajaran kewajiban klarifikasi. Itukan pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan.
Perlu diketahui bahwa persoalan serumit ini tidak mungkin dipahami oleh orang yang pengetahuan agamanya rendah. Orang yang ngajinya bertahun-tahun sekalipun barangkali masih sulit untuk memahami persoalan ini. Apalagi mereka yang tidak pernah ngaji. (adi/nuo)
Advertisement