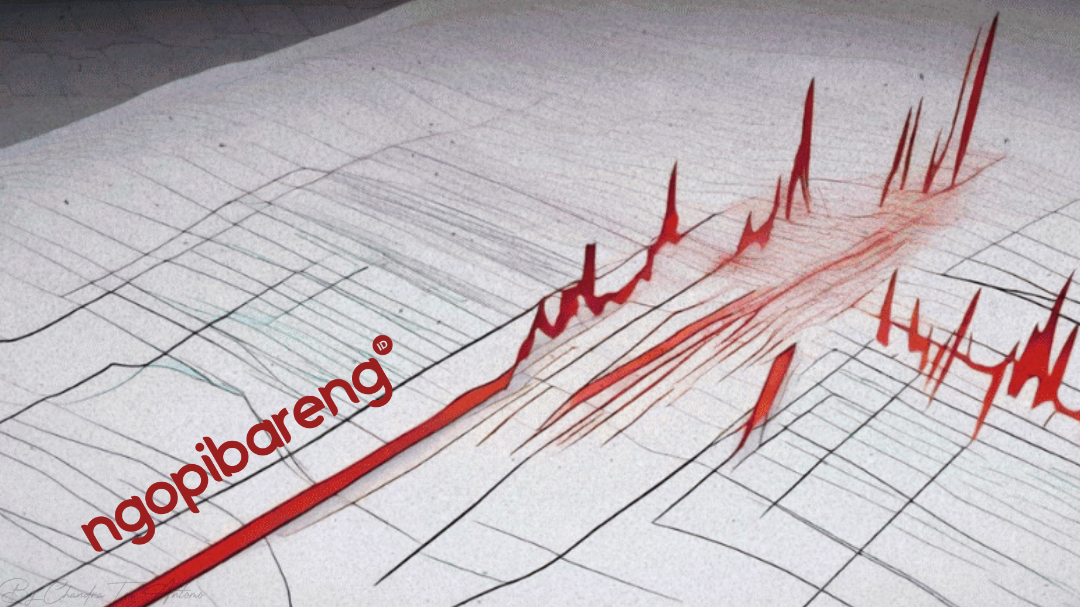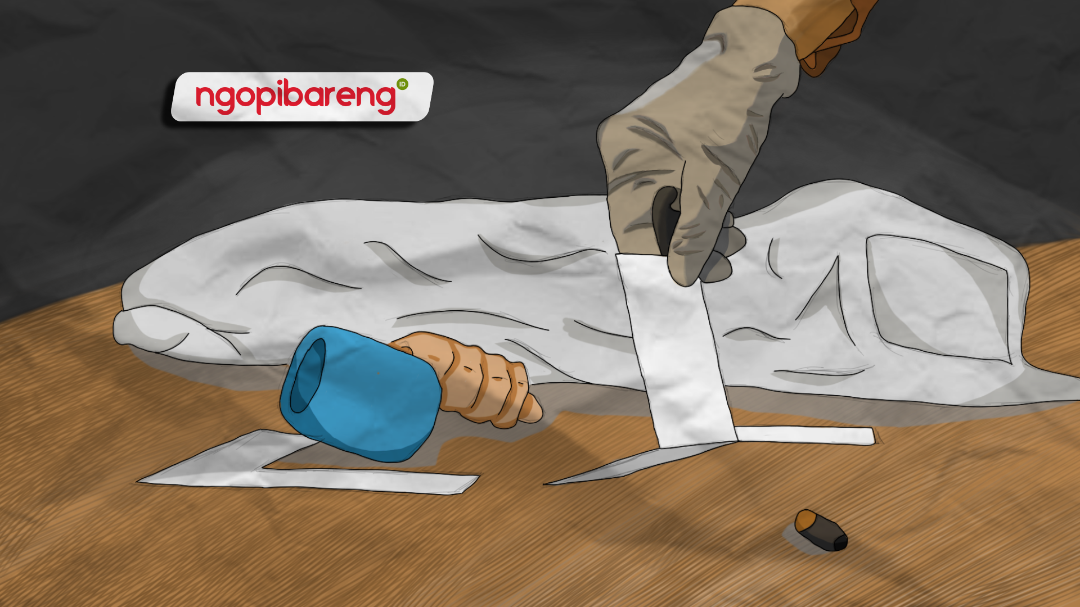Shireen

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Dosen Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Jember
=================
Masih segar dalam ingatan. Wajah sejuk itu menghiasi layar TV dengan background bangunan berkubah keemasan—Masjid Al Aqsa. Itulah sosok Shireen Abu Akleh! Jurnalis senior Al Jazeera yang ditembak mati tentara Israel saat meliput serbuan tentara Israel terhadap kamp pengungsi Palestina di Jenin, wilayah Tepi Barat (West Bank). Selama Ramadan sampai Idul Fitri kemarin, saya begitu akrab dengan wajah Shireen. Siaran live-nya tentang serbuan tentara Israel ke dalam komplek masjid Al Aqsa, menjadi menu ‘ekstra’ sehabis buka puasa. Apalagi, reportase-nya bukan sekedar kabar, tetapi juga berisi dengan bumbu investigasi.
Saya bukanlah pemirsa fanatik Al Jazeera. Channel TV yang berpusat di Doha ini adalah menu pelengkap—selain CNN, France24, dan Deutsche Welle. Alasannya, hanya ingin mendapatkan berita yang berimbang. Motivasi ini muncul, antara lain, berkat perjumpaan saya dengan seorang akademisi asal Palestina di Southern Illinois University at Carbondale (SIUC), USA. Ketika itu, saya sempat bertanya kepadanya: “Mengapa seorang ibu Palestina sampai melakukan bom bunuh diri melawan Israel? Sehingga, Israel yang mempunyai mesin propaganda handal dengan mudah melabelinya dengan stigma “teroris”?!
Dengan mimik serius kawan Palestina itu menjawab: “Kamu tidak akan bisa memahaminya jika selalu merujuk berita dari sumber media Barat, karena mereka jarang mengungkap apa yang sebenarnya terjadi! Jika ada seorang ibu Palestina sampai nekad melakukan serangan bom bunuh diri, itu tak lepas dari rasa putus-asanya atas hilangnya semua yang dimiliki akibat perampokan oleh Israel di tanah pendudukan; mulai dari perampasan sumber air, penggusuran rumah dan tanah demi pemukim Yahudi, sampai hilangnya harga diri akibat perlakuan tentara Israel yang tidak manusawi!. Sayapun mahfum, tanpa gumam apapun.
Berbekal informasi first-hand perspective ini, saya bisa menyelami, berempati, bahkan kagum terhadap keberanian Shireen dalam mengungkap tragedi Palestina; meskipun akhirnya harus dibayar dengan nyawanya. Baginya, berprofesi sebagai jurnalis bukan karena keterpaksaan, melainkan sebuah pilihan. Dengan ghiroh (passion)-nya, dia menjadi role model jurnalis mumpuni yang berdedikasi.
"Saya memilih jurnalisme untuk bisa menjadi dekat dengan orang jelata", ujarnya tegas. Misinya, yang diungkapannya tahun lalu, begitu menggetarkan kalbu: “Tidak mudah bagi saya (sebagai jurnalis) untuk mengubah kenyataan, tetapi setidaknya yang bisa saya lakukan adalah menjadikan suara kami (Palestina) didengar (masyarakat) dunia!". Tak heran, jika lawan kemudian menggangapnya sebagai ancaman.
Shireen bukanlah jurnalis Palestina pertama yang ditembak mati. The Palestinian Journalists Syndicate (PJS), mencatat bahwa sejak pendudukan Israel atas wilayah Palestina—Tepi Barat, Jerusalem Timur, dan Gaza—pada tahun 1967; 86 wartawan Palestina telah dibunuh oleh Israel. Dan, lebih dari separuhnya tewas sejak tahun 2000. Namun, dialah yang nampaknya paling kokoh bersemayam dalam relung hati warga Palestina. Salah satu alasannya; di tengah kebungkaman dunia, reportase-nya yang tajam tetap mematuk-matuk benteng kekejaman Israel.
Shireen juga bukan sosok seperti Peter Arnett, jurnalis CNN yang pertama kali melakukan live report dalam pemberitaan televisi dalam perang teluk tahun 1990-1991. Terdapat perbedaan antara keduanya. Reportase Arnett bernuansa ‘semangat akan kegagahan’ Amerika, dengan background langit Baghdad yang memerah diwarnai raungan sirine, seiring bombardemen negara adi-kuasa tersebut terhadap wilayah Iraq. Sementara reportase Shireen bernuansa ’ketabahan akan kesedihan’, dengan background lorong-lorong wilayah tepi Barat dan Gaza yang sesa dengan rintihan penderitaan akibat penindasan sekutu dekat negara adi-kuasa itu.
Tak pelak, kematian Shireen bak pentas sebuah drama multi-dimensi. Dalam dimensi politik, terkesan ada kekhawatiran politik dari pihak Israel dan pendukungnya. Sesaat setelah kematiannya, pasukan Israel segera menggerebek rumahnya, menyita bendera Palestina, dan menghalangi pemutaran lagu-lagu perjuangan. Seiring dengan bekerjanya mesin propaganda Israel, beberapa mass-media dan agen berita Barat ‘berhati-hati’ untuk tidak menyinggung Israel. Seperti secara kritis disorot dalam Twitter, mereka melakukan whitewashed reporting (reportase yang menutupi kesalahan). New York Times (NYT), misalnya, tajuk beritanya hanya memberitakan: “Shireen Abu Akleh, Trailblazing Palestinian Journalist, Dies at 51” (Shireen Abu Akleh, pelopor jurnalis Palestina, wafat di usia 51)—tanpa penjelasan penyebab kematiannya. Akun @bethavemiller menilai narasi “Dies at 51” ini sebagai sesuatu yang “unbelievable” (tak layak untuk dipercaya). Sementara @Bassam Khawaja melihatnya sebagai “a really strange way to say” (narasi yang benar-benar aneh).
Senada dengan NYT, The Associated Press (AP) juga melakukan hal sama. Agen berita yang berkedudukan di New York ini memberitakan Shireen “was killed by gunfire” (terbunuh oleh tembakan). Akun @aimrabie dengan sengit mengecam pilihan kata-kata ini dengan menudingnya sebagai bentuk “unethical journalism” (jurnalisme yang tidak etis). Argumennya, Shireen bukanlah dibunuh oleh “aliens” (orang asing), tetapi secara faktual jelas ditembak oleh tentara Israel. Dengan tidak menyebut siapa pembunuhnnya, AP dianggapnya telah menyebarkan ‘fakta alternatif’ dengan mengaburkan ‘kebenaran hakiki’.
Dalam dimensi sosial, pemakaman Shireen merupakan salah satu peristiwa yang paling dikenang dalam sejarah Palestina. Ribuan pelayat—diiringi dentang lonceng seluruh gereja yang bersahutan di se-antero Jerusalem Timur—menghantar jenasahnya ke peristirahatan terakhir. Penghormatan besar ini berjalan khitmat. Sikap represif tentara Israel yang tetap berlanjut, tak membuat para pelayat surut. Semua ini mencerminkan betapa Palestina begitu mencintainya. Salah satu penyebabnya adalah reportasenya yang selalu ‘hidup’; karena tragedi Palestina sejatinya adalah kisah tentang dirinya. Penghayatannya yang mendalam terhadap nasib Palestina tidak pernah luntur, mengingat dia dilahirkan dan dibesarkan di salah satu kolong Jerusalem Timur. Selain itu, dia merupakan sosok langka yang telah mewajibkan diri untuk membawa misi suci: “menyuarakan mereka yang tidak mampu bersuara” (giving a voice to voiceless).
Sementara itu, dimensi “langit” menyajikan kisah sebuah misteri kala maut menjemputnya. Perjalanan Shireen ke Jenin 11 Mei lalu, guna meliput serangan tentara Israel ke kamp pengungsi Palestina; seakan napak tilas penemuannya akan roh perjuangan bersama warga Palestina. Dua dasawarsa yang lalu—persisnya tahun 2002—dia juga meliput serbuan Israel yang mematikan ke kamp pengungsi yang sama. Tahun lalu, dia menulis kenangannya tentang peristiwa heroik kala itu: “Bagi saya, Jenin bukanlah satu cerita fana dalam karier saya atau bahkan dalam kehidupan pribadi saya. Ini adalah kota yang meningkatkan semangat juang saya dan membantu saya untuk terbang. Ini mengandung semangat Palestina yang kadang gemetar dan jatuh tetapi, di luar semua harapan, [tetap] bangkit untuk mengejar derajat dan mimpinya”.
Bagi sosok seperti Shireen, kematian hanyalah sekedar mengubur jasadnya. Dedikasi, komitmen, dan semangat perjuangannya akan tetap segar sebagai kenangan, bahkan inspirasi, yang indah bagi bangsa Palestina. Ini selaras dengan namanya—“Shireen”—yang dalam bahasa Arab, bermakna “keindahan yang segar” (fresh beauty). Rest in Peace, Shireen!
Advertisement