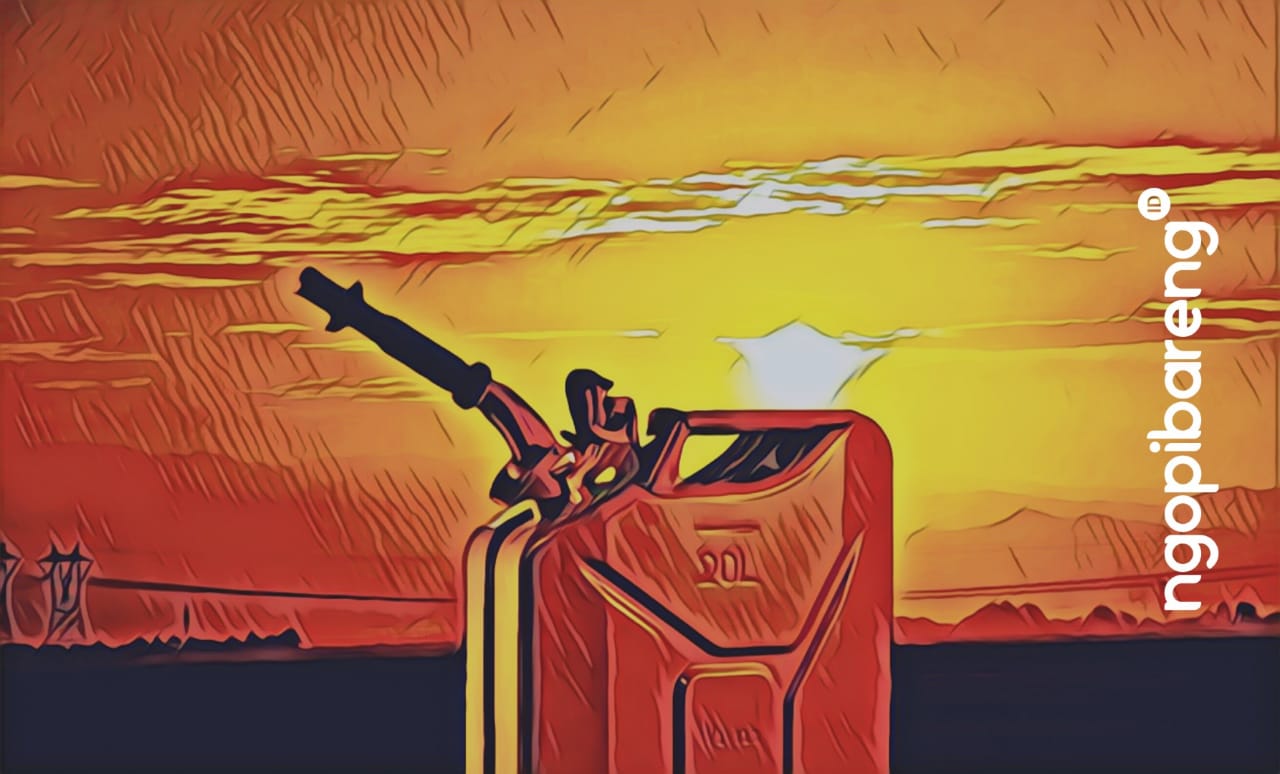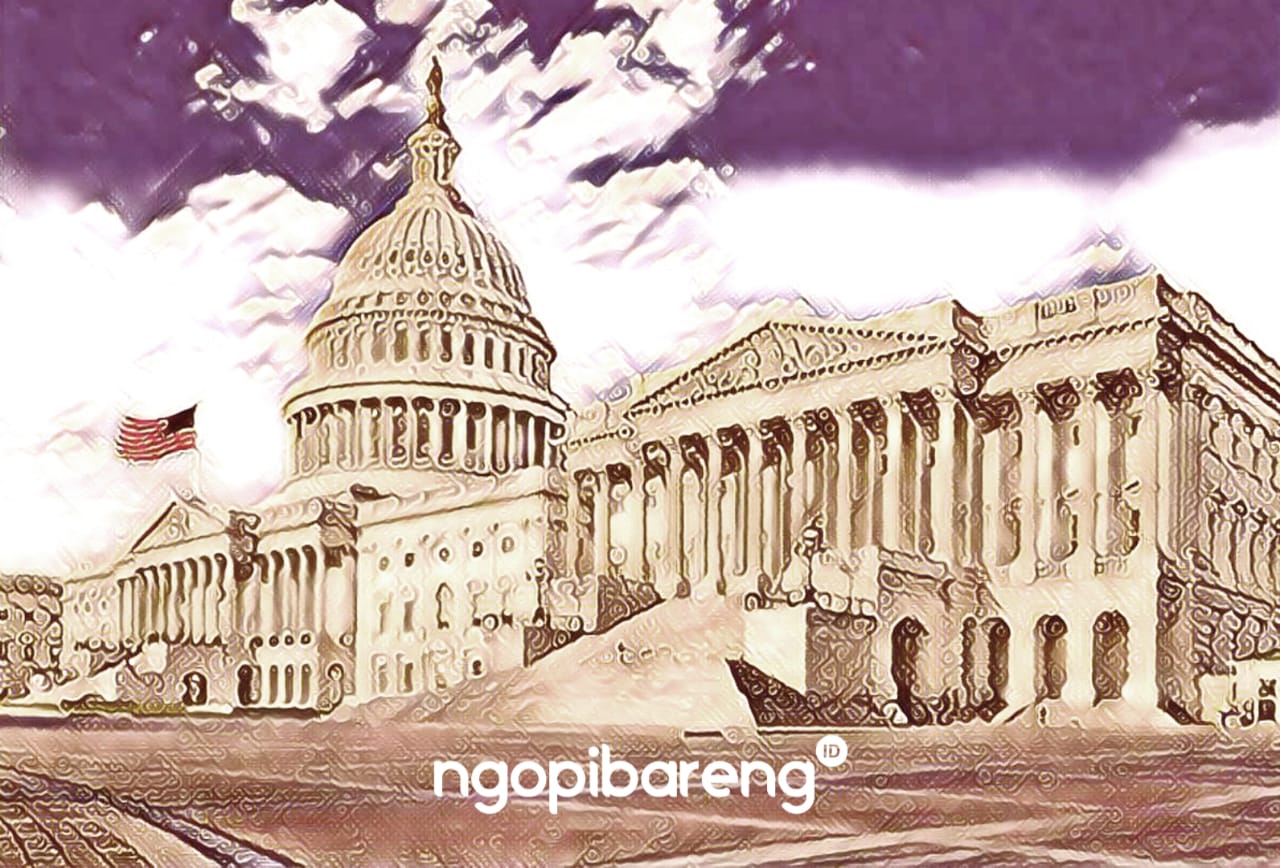Saat Jumatan dalam Senyap

Ibu Ulfah Lanto, camat cantik yang bertugas di Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel), ramai jadi perbincangan. Minggu lalu, Ibu muda ini dilaporkan ke Polisi. Alasannya, membubarkan salat Jumat di Masjid Ar Rahma di wilayahnya.
Menurut juru bicara polisi setempat, ada warga yang lapor. Ada jemaah masjid yang tidak terima salat Jumat dibubarkan. Deliknya penodaan agama. Namun, kepolisian melihat, para petugas hanya melakukan sosialisasi.
Peristiwa ini menarik perhatian saya. Hmm, apakah karena Bu Camat yang cantik itu? Bukan, bukan. Tetapi, masalah potensi konflik ini.
Yang pasti, Ibu Camat sebagai alat negara, telah menjalankan tugasnya. Sebaliknya, ada yang merasa agamanya dinista. Sebenarnya bagaimana?
Apakah masyarakat sudah berani melawan hegemoni negara? Ataukah ini lebih pada urusan komunikasi saja? Atau ada yang benci dengan Bu Camat dan memanfaatkan situasi?
Saya pun memilih untuk menjelajah. Ingin mengetahui masalah ini lebih dalam. Pemberitaan Bu Camat mulai beragam.
Ibu Camat, dalam pemberitaan, mengaku bersama aparat lainnya berkeliling. Sosialisasi agar masyarakat untuk tinggal di rumah. Termasuk salat di rumah.
Saat mendekati waktu salat Jumat, mereka sampai di masjid Ini. Sebagian jamaah sudah berkumpul di dalam masjid.
Lantas, tim berinisiatif menutup pagar masjid. Agar jemaah tidak makin membludak. Menurut Ibu Camat, ada dua tokoh agama, yang lantas masuk masjid.
Tokoh inilah yang meminta warga untuk bubar. Kembali ke rumah masing-masing. Salat di rumah saja.
Polisi menyatakan tidak ada indikasi pidana. Yang melapor, lucunya, tidak ada di lokasi kejadian. Kabar dari Polisi, dia terprofokasi aktifis LSM. Entah apa yang merasukinya.
Bisa jadi, penjelasan ini telah menjawab pertanyaan ketiga. Bahwa ada motif politik, karena ada yang tak suka Bu Camat. Itu menurut polisi.
Lantas, bagaiman pertanyaan kedua. Apakah ini lebih urusan komunikasi semata? Memang, lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya. Tiap daerah punya gaya bicara dan cara berkata.
Selama Covid-19 ini, banyak ragam yang dipilih takmir masjid, mensikapi anjuran pemerintah. Ada yang tetap membuka masjidnya. Misalnya sebuah masjid di sekitar Kebon Jeruk, Jakarta.
"Masjid kami dekat dengan kantor Polisi juga tentara. Tapi masjid buka seperti biasa," jelas seorang teman. Alasannya, bukan di daerah terhitung merah corona. Hal senada juga dikabarkan seorang teman di Lamongan.
Di dekat rumahnya, masjid dibuka seperti biasa. "Saat buka puasa, kita sediakan wedang corona," katanya. Entahlah, mungkin wedang itu terinspirasi dari jamu Presiden Joko Widodo.
Wedang corona sejatinya dari empon-empon. Dari jahe, kunyit, hingga kayu manis. Banyak yang suka, dan merasa makin fit.
Bagi keduanya, masjid bak oase. "Kondisi ekonomi sedang susah. Kalau di rumah terus bisa suntuk. Masjid bisa jadi sarana penyegaran iman dan bermasyarakat," tambahnya.
Oh ya, tentu saja, tetap ada masjid yang menutup aktifitas dan menyarankan shalat di rumah. Kabar ini saya dapat dari seorang teman, yang jadi takmir di Kudus. Saat adzan, diselipkan seruan untuk salat di rumah saja.
Namun, ada juga modus yang ketiga. Masjid tetap buka, tapi diam-diam saja. Ya, mirip, melawan perintah negara dalam senyap.
Saya akan bercerita tentang pengalaman saya. Saya sudah dua kami mengganti salat Jumat dengan salat Dhuhur. Lantas, saya pun sempat iseng, ingin mampir ke masjid di dekat rumah.
Mau lihat apakah ada yang Jumatan. Biasanya, ada pengumuman, kalau tidak dilaksanakan Jumatan. Tapi Jumat kali itu beda. Tak ada pengumuman sama sekali.
Baik pembatalan Jumatan atau akan ada Jumatan. Saat itu, adzan cuma sekali. Lantas setelah itu sunyi. Tak ada suara khutbah lewat pengeras suara.
Namun, saya melihat beberapa jamaah berjalan ke arah masjid. Saya pun bergegas ke sana. Memakai masker tentu saja.
Saat sampai di gerbang masjid, pintu digembok. Tak bisa masuk. Di pintu gerbang, juga terpampang kertas. Isi tulisannya: Pintu digembok.
Uniknya, masjid terlihat penuh. Semua dalam posisi mau memulai salat. Saya pun memilih jalan melingkar.
Menuju pintu belakang masjid. Di sana, banyak motor diparkir. Berjajar rapi.
Pintu kecilnya terbuka. Puluhan pasang sandal berserakan. Saya pun bergegas masuk. Di dekat pintu, ada sabun pencuci tangan.
Imam sudah mulai membaca Al Fatihah. Saya edarkan pandangan. Mayoritas jamaah memakai masker. Shaf salatpun berjarak.
Dalam kesenyapan, kami menunaikan ibadah. Tak ada pengeras suara yang bergelegar. Seperti biasanya, salat berlangsung dua rakaat.
Seusai salat, semua cepat pergi. Tak ada yang bersalam-salaman atau sekadar bersapa. Dalam kesunyian, semua beranjak ke rumah masing-masing.
Masjid kembali sunyi. Hanya marbot masjid sibuk membersihkan masjid. "Masih tarawih Pak. Cuma juga tidak pakai speaker," jelas sang marbot.
Seorang kawan, petinggi Ikatan Sarjana Nahdhatul Ulama, berbagi pesan pendek. "Kita harus patuh dan taat," katanya. Pesan itu merujuk pada ketaatan mengganti Jumatan dengan salat Dhuhur di rumah.
Lantas, juga mengganti teraweh yang biasa dilakukan berjemaah di masjid, dilakukan di rumah. Kabarnya, dulu Nabi Muhammad SAW memilih taraweh di rumah. Namun, para sahabat selanjutnya, memilih salat berjemaah di masjid.
Bagi teman saya itu, ulil amri adalah gabungan otoritas politik (umara) dan agama (ulama). "Niat patuh dan taat kepada Ulil Amri, insyaAllah, Allah yang akan menyempurnakan pahala ibadah kita," jelasnya panjang lebar.
Teman yang pemahamanan agamanya tinggi ini, menyitir sebuah hadis. Rasulullah bahkan menghubungkan ketaatan kepada pemimpin dengan ketaatan kepada beliau.
"Barangsiapa durhaka kepada pemimpin berarti durhaka kepada beliau," tegasnya. Di matanya, hal sederhana atas batasan yang bisa dijadikan patokan, selagi pemimpin tidak menyuruh maksiat.
Teman ini, bisa sangat kritis atas kebijakan pemerintah. Terutama soal energi yang dia geluti. Namun, dalam kondisi gahar pandemi Covid-19 ini, dia tunduk dan taat.
Menurutnya, perintah untuk tetap di rumah, termasuk beribadah dalam rangka menjaga maqâshid al-syarî’ah. Memastikan terpeliharanya jiwa rakyat Indonesia.
Terkait dengan upaya Ibu Camat cantik itu, teman yang satu ini seirama. Tidak ada kesalahannya. "Karena itu, tindakan melarang salat Jumat, tidak bisa dianggap menodai agama," yakinnya.
Nah, masih terkait perlawanan perintah Jumatan ini. Teman di Jogja, bercerita, beberapa kantong daerah yang dulu pendukung pasangan Prabowo dan Sandi, lebih taat. "Tapi kantong pendukung Pak Jokowi, malah beribadah di Masjid," ungkapnya sambil tertawa.
Nah, apakah fenomena ini bisa ditarik ke telaah sosial kritis. Maksudnya, ke pertanyaan sebelumya, bahwa ada perlawanan sebagian masyarakat lho atas hegemoni negara ini.
Waduh, kok ini jadi berat sekali pembahasannya. Kan, ini sebenarnya urusan sederhana saja. Sebagian masyarakat masih ingin beribadah di masjid.
Merasa lebih afdol, menghidupi masjid. Merasa bahagia saat beribadah bersama. Selain itu ganjaran pahalanya, lebih banyak.
Mereka tahu ada Corona-19. Mencoba membuat protokol pengamanan. Agar beribadah juga tetap tenang. Tapi, kenapa tidak ada kesadaran mutlak mendukung petuah pemerintah.
Tapi marilah kita berdiskusi sebentar. Apakah nyambung dengan telaahan kritis. Kita coba pakai dari bingkai teori hegemoni, dari pemikir Antonio Gramsci atas perilaku aparat negara.
Para aparatur negara, bekerja menyadarkan publik atas bahaya Covid-19 ini. Diharapkan publik paham atas pemaksaan untuk tidak keluar rumah. Paham menjaga jarak serta paham untuk beribadah di rumah.
Kalau sadar, sebagaimana teman saya yang sarjana itu, mereka bisa melakukan tanpa merasa dihegemoni oleh penguasa. Bahkan melaksanakan dengan sukarela. Iklas, serta bisa jadi supporter kuat.
Tapi ada jenis hegemoni lainnya melalui penindasan atau dominasi. Misalnya pelibatan aparat. Bisa jadi, pengarahan dari Bu Camat disebut bagian implementasi dominasi.
Atau mungkinkah, penempatan polisi dan tentara untuk membuat semua tak mudik, juga bagian dari dominasi. Memang, tak ada kekerasan fisik di sana. Tapi, mungkin, ucapan, tindakan bisa menyiratkan kuatnya dominasi negara.
Bila dua pendekatan itu terus dilakukan pemerintah, apa yang diharap tak akan terwujud. Maksudnya, kesadaran sikap, kesadaran moral, dan dukungan yang idealnya tercipta malah tidak ada. Yang terjadi, perlawanan dalam diam.
Takmir masjid dan pengurus tempat ibadah yang melawan, dengan menyelengarakan ibadah. Melakukan beragam tipu daya agar tetap mudik. Pembatasan skala besar yang tetap tak diindahkan.
Perlu dipahami, kesadaran tidak otomatis tersebar di masyarakat. Untuk itu, agar mereka tidak merasa dihegemoni, perlu adanya pengarahan konsep pemikiran.
Nah menariknya di sini. Hal itu tak bisa langsung dilaksanakan aparat pemerintah. Untuk peran ini, negara bisa mengandeng lembaga sosial ke tingkatan terbawah. Sehingga tidak ada resistensi publik.
Namun, sepertinya ini yang terlewat. Presiden Joko Widodo di media sosialnya berujar, "Dengan sinergi yang kuat dan erat, di antara pemerintah pusat sampai ke daerah, kita bisa melewati badai pendemo ini dengan semangat."
Jika kredo ini yang terus dibangun, mohon maaf Pak Presiden, sepertinya pemerintah akan terus sendirian berjuang menghadapi pendemi ini. Tidak ada niatan mewujudkan dukungan sukarela nan bulat dari warga. Tak heran, yang terjadi, malah kebijakan yang diralat berulang kali.
Ajar Edi, kolomnis "Ujar Ajar".
Advertisement