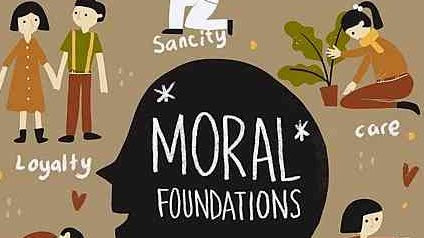Refleksi Pemilu Era Orba dan Eksistensi NU

Pada tahun ke-3 sebagai anggota Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), saya mendapat perintah menjadi personel Satuan Tugas Khusus (Satgas-Sus) untuk memenangkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Aceh.
Padahal ketika itu saya menjadi personel di Deputi IV yang menangani Intelijen Luar Negeri. Mungkin saya dipilih sebagai anggouta Satgas-Sus karena latar belakang saya sebagai santri, sehingga dianggap memahami budaya pendukung PPP yang sebagian besar terdiri kaum agamis, khususnya NU.
Konon ceritanya, Presiden Soeharto memerintahkan KA BAKIN Jenderal Yoga Soegoma agar PPP memperoleh suara mayoritas di Daerah Istimewa Aceh (awal masuknya Islam) dan DKI Jakarta ( ibu kota negara). Dengan menjadikan PPP menguasai mayoritas suara di Provinsi Aceh dan DKI Jakarta menunjukkan bahwa Pak Harto ingin memperlihatkan secara simbolis bahwa Islam tetap hadir secara mencolok dan hal ini merupakan kearifan dari Presiden kedua Indonesia tersebut.
Pemfusian Partai Politik
Segera setelah MPRS mengangkat Pak Harto sebagai Presiden kedua pada tahun 1967, beliau mendirikan Golongan Karya sebagai kekuatan politik utama yang secara formal tidak disebut “partai politik" melainkan lebih merefleksikan kelompok profesional (karya). Sedang dua partai politik lainnya sebagai sparing patner adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi atau penggabungan dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba. Sedang partai lainnya adalah PPP (Partai Persatuan Pembangunan ) yang merupakan fusi partai berhaluan Islam yaitu Partai NU, Parmusi, PSII dan PERTI.
Penggabungan partai menjadi dua partai tersebut dimaksudkan untuk membangun sistem politik baru Orde Baru yang terkenal di kalangan aktivis kampus dengan “Politik Stabil dan Dinamis". Golkar yang didukung ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, kini TNI) sebagai unsur stabilator polhukam dan sekaligus penggerak ekonomi, sedang PDI dan PPP penyeimbang agar sistem politik menjadi dinamis. Tentu saja unsur dinamis sedapat mungkin sejalan dengan derap pembangunan ekonomi.
Dalam praktik ,Golkar sebagai partai pemerintah dan PDI serta PPP sebagai sparing patner harus menyesuaikan diri dengan dinamika sosial - politik. Misalnya Golkar pada periode awal sejak berdirinya, dipimpin oleh perwira militer aktif, dalam periode selanjutnya dipimpim mantan perwira TNI dan pada periode selanjutnya dipimpin sipil. Dari 1967 sampai 1993 dipimpin oleh militer dan sejak 1993 dipimpin oleh politisi sipil diawali Harmoko, Akbar Tandjung dan seterusnya. Di tingkat pimpinan Golkar daerah juga demikian dari militer aktif, purnawirawan dan sejak 1993 mayoritas diserahkan sipil.
Dalam rangka menjalankan fungsi stabilator itulah Orde Baru melakukan kebijakan yang cenderung repressif dengan menggunakan “selubung politik tertentu", sehingga pada akhirnya tidak tampak vulgar. Misalnya dengan konsep monoloyalitas, departemen-departemen pemerintahan dijauhkan dari unsur partai politik, dimana pegawai negeri hanya loyal kepada negara c/q Golkar. Dalam Pemilu 1971 sampai pemilu 1977, langkah represif Orde Baru itu sangat terasa, namun lambat laun jauh berkurang karena Golkar kemudian diterima masyarakat ketika kemajuan ekonomi telah dirasakan oleh masyarakat.
Dalam perkembangannya kemudian, ketika terjadi krisis moneter pada 1998, yang mengakibatkan kondisi perekonomian nasional memburuk, muncul ketidakpuasan yang meluas. Rakyat aksi demo agar Presiden Soeharto yang telah berhasil memimpin Indonesia sejak 1967 agar turun. Ada tarik menarik, pro - kontra di kalangan elite; pada satu sisi menghendaki Pak Harto tetap menjabat guna mengatasi krisis ekonomi, sedang kaum elite lainnya menghendaki agar pak Harto turun. Dan secara elegan Presiden Soeharto yang saya kagumi sebagai Tokoh Pembangunan itu turun tahta dengan jiwa besar, menyerahkannya kepada Wapres Bachruddin Jusuf Habibie, bukan kepada anak turunnya.
Sebagai seorang intelijen saya juga punya pengalaman khusus yang sering saya ceritakan kepada generasi muda Nahdliyin (NU) yang kebetulan bersilaturahim. Suatu saat saya di tanya oleh atasan saya, Mayjen Soenarso Jayusman: NU itu termasuk moderat atau radikal, soalnya Pak Harto memanggil KA BAKIN Jenderal Yoga Soegama dan mengatakan dalam bahasa Jawa, "Kok saiki NU rodo genit, nakal, ana apa too?".
Pertanyaan itu dibahas dalam rapat terbatas pimpinan BIN dan sampai sekitar dua jam, tidak ada kesimpulan dengan apa yang dimaksud nakal oleh Pak Harto. Kesimpulan sementara, rapat tidak melihat gejolak di kalangan NU melawan Orde Baru. Hanya ada dua tokoh NU yang sering menyuarakan suara vokal tetapi masih dianggap wajar yaitu Pak Chalid Mawardi (ketika itu Ketua PP GP Ansor) dan H Mahbub Djunaidi, wartawan dan kolumnis.
Rapat ditunda sekitar satu jam untuk shalat zhuhur, Pak Narso Jayusman memanggil saya dan menanyakan seperti apa pandangan politik NU. Saya jawab singkat: NU selalu loyal kepada negara karena selain ikut berjuang mendirikan negara, juga tidak akan memberontak kepada pemerintah yang sah karena memberontak atau bughot hukumnya "haram".
Setelah rapat dibuka kembali dan hanya berlangsung 15 menit. Setelah mendengarkan penjelasan singkat dari Pak Narso, Jend Yoga memutuskan : begini saja, NU itu teman pemerintah, saya juga waktu muda mengaji kepada Kyai H Yasin , jadi saya ini ya NU juga. Gampang, Chalid Mawardi jadikan duta besar di negara Arab dan Mahbub Djunaidi dibantu keperluannya, biarkan tetap mengritik nggak apa-apa saya yakin tujuannya baik. Kita, ABRI lebih baik menggalang sebanyak mungkin kawan dari pada musuh.
Jadilah, Pak Chalid Mawardi menjadi Duta Besar di Syria dan pak Mahbub Djunaidi tetap meneruskan tulisan-tulisan yang bernada kritik konstruktif. Dikaitkan dengan situasi sekarang ini, mungkin politik dinasti itu muncul bukan dari pikiran Presiden Jokowi sendiri karena beliau tahu risiko politiknya, bukan hanya nasional, tetapi juga internasional. Dan memang politik dinasti dalam era perkembangan demokrasi abad ini adalah menjadi sesuatu yang dapat menimbulkan perlawanan besar.
DR KH As'ad Said Ali
Pengamat sosial politik, Mustasyar PBNU periode 2022-2027, tinggal di Jakarta.
Advertisement