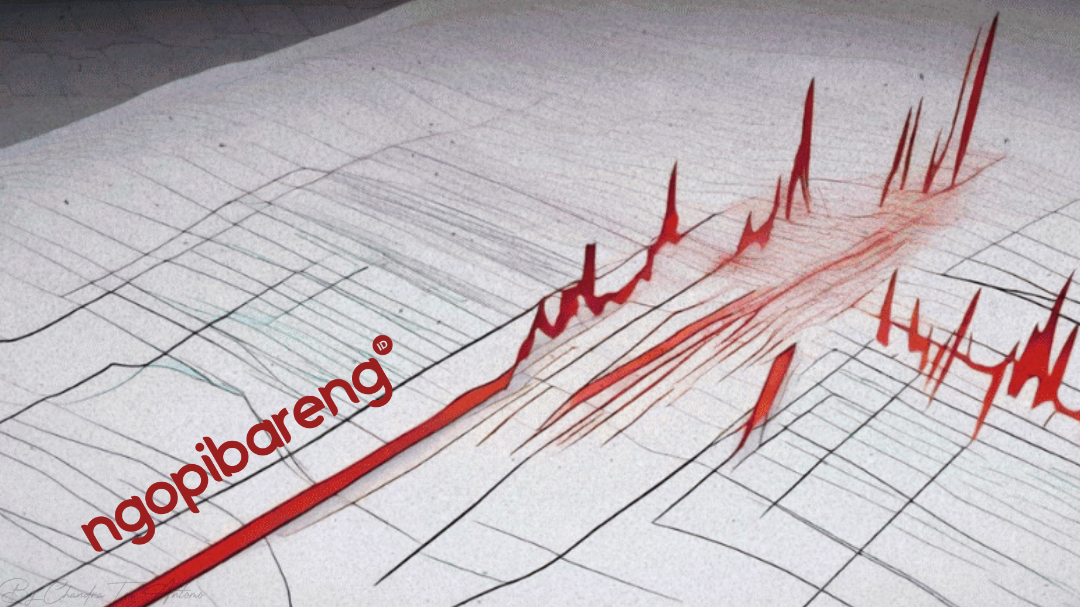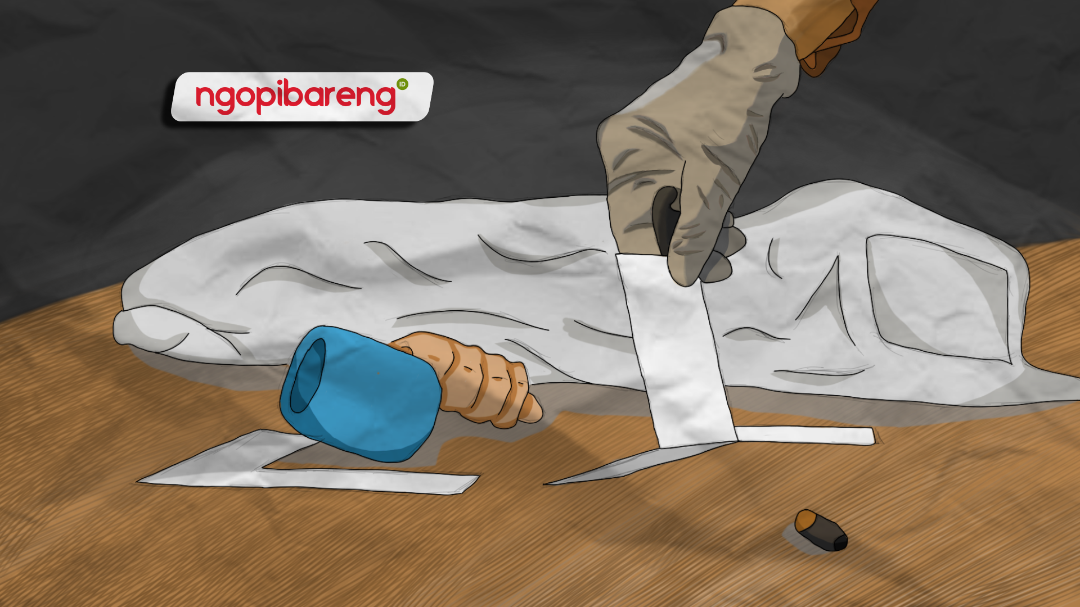Reedukasi Muslim Uighur di Xinjiang, Antara HAM dan Separatisme

Kebijakan pembangunan Kamp Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi muslim Uighur di Xinjiang oleh rezim Xi Jinping menuai reaksi dunia. Negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat dan Eropa, menyebut kebijakan tersebut dengan pembasmian etnis (genocide). Kalaupun lebih “soft” mereka menyebutnya dengan “pelanggaran HAM berat”, seperti yang dinyatakan parlemen di Selandia Baru.
Tentu, klaim sepihak ini menuai reaksi dari pemerintah Tiongkok. Beijing menyangkal semua tuduhan Barat atas isu Xinjiang. Bahwa yang terjadi di Xinjiang dengan kebijakan reedukasi tidak lebih adalah reaksi dari adanya terorisme, ekstremisme dan separatisme yang berkembang di Xinjiang.
Lalu bagaimana dengan sikap dunia Islam terhadap isu Xinjiang? karena selama ini yang diberitakan media adalah sentiment agama (Islam) dalam isu Xinjiang. Framing akan pemerintahan komunis Tiongkok yang menekan Islam, tentu menjadi menarik ketika kita melihat reaksi dunia Islam dalam menyikapinya.
Merujuk pada studi Mackerras (2010) dan Moises Naim (2009), dunia Islam terlihat diam ketika melihat penindasan muslim Uighur di Xinjiang. Turki yang secara etnis dekat dengan muslim Uighur justru mendukung Tiongkok dalam menumpas gerakan separatis di Xinjiang.
Begitu juga dengan negara-negara muslim di Timur Tengah, mereka sudah punya pengalaman dengan standar ganda HAM ala Barat pada peristiwa Arab Spring. Oleh karenanya tidak ada reaksi keras kepada Beijing ketika muncul isu dugaan pelanggaran HAM di Xinjiang. Yang ada justru sebaliknya, mendukung Tiongkok dalam menekan gerakan separatis di Xinjiang.
Branding HAM versus Separatis
LSM internasional yang concern dengan isu HAM seperti Amnesty International dan Human Rights Watch ikut menuduh Beijing telah melakukan pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Muslim Uighur dipaksa sumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan dengan batas waktu yang tidak jelas, hingga dorongan untuk menyerukan slogan-slogan Partai Komunis.
Dalam temuan terbaru Amnesty International, ditemukan visualisasi penyiksaan terhadap para tahanan di kamp reedukasi Xinjiang (Amnesty International, 2021). Negara-negara Barat beserta LSM internasional berusaha penuh membangun branding isu Xinjiang dalam perspektif HAM melalui berbagai kanal media.
Di sisi lain, otoritas Tiongkok menyangkal adanya tuduhan genosida dan pelanggaran HAM terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Kebijakan reedukasi di Xinjiang dalam kacamata Beijing tidak melanggar HAM. Dalam konferensi pers, Pemerintah Provinsi Xinjiang yang diwakili oleh Shohrat Zakir (pemimpin wilayah otonomi Xinjiang yang beretnis Uighur) menyatakan bahwa para anggota parlemen dan media Barat telah memfitnah dengan tuduhan genocida dan pelanggaran HAM di Xinjiang.
Kebijakan ini memberikan pendidikan dan pelatihan kepada etnis minoritas Uighur, sehingga tidak ada lagi gerakan separatism dan ekstremisme disana. Beijing hanya ingin memastikan wilayah Xinjiang aman, stabil, sehingga pertumbuhan ekonomi terkendali.
Branding separatis-teroris atas etnis Uighur di atas bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa argument rasional dalam melihat konteks ini.
Pertama, dilihat dari sisi sejarah, Xinjiang tercatat 2 (dua) kali ingin melepaskan diri dari Tiongkok dengan mendirikan Republik Turkestan Timur, tepatnya pada tahun 1933 dan 1944. Kebijakan reedukasi hanya bagian kecil dari rangkaian kebijakan untuk meredam separatism di Xinjiang. Dalam konteks ini terdapat beberapa kebijakan yang sudah berjalan, seperti kebijakan otonomi Xinjiang, kebijakan asimilasi antara etnis Han dan Uighur, serta kebijakan pembangunan.
Kedua, Beijing melihat isu Xinjiang dengan branding separatis-teroris, bukan branding komunis anti agama (Islam) seperti yang banyak beredar di media-media Barat. Perlu diketahui, bahwa muslim di Tiongkok itu mayoritas tersebar kedalam 3 provinsi, yakni Xinjiang, Kanshu dan Ningxia. Sementara umat Islam yang di provinsi Kanshu dan Ningxia (mayoritas etnis Hui) tidak ada tekanan dan “perhatian khusus” dari pemerintah Tiongkok.
Nah kalau tujuannya menekan Islam, seharusnya muslim Hui yang ada di Kanshu dan Ningxia mendapat perlakuan sama dengan etnis Uighur yang ada di Xinjiang. Tapi kenyataannya kebijakan reedukasi hanya ada di Xinjiang, tidak di Kanshu atau Ningxia.
Nah kembali lagi, ini menekan umat Islam atau menekan pemberontak separatis. Ini yang harus dicermati. Bahkan sekarang sudah boleh Haji berangkat langsung dari Ningxia (tidak lewat Beijing). Ini bentuk afirmasi pemerintah Tiongkok kepada muslim Hui di Ningxia yang dalam sejarahnya tidak pernah berbuat makar kepada pemerintah. Sekali lagi, apakah pemerintah komunis Tiongkok anti Islam atau anti separatis.
Berbicara isu separatis, Tiongkok tidak hanya “menekan” muslim Uighur di Xinjiang. Beijing juga tidak memberi ruang terbuka bagi masyarakat di Hong Kong dan Taiwan misalnya, ketika mereka mau melakukan makar dan pemisahan diri. Jika kita melihat pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang diberlakukan Beijing di Hongkong sangat mengikat dan berusaha mencegah perbuatan separatis, teroris, dan subversif.
Membaca Kebijakan Reedukasi di Xinjiang dalam Banyak Dimensi
Jika kita melihat isu Xinjiang dalam kacamata agama (Islam) saja, maka sangat tidak proporsional. Membaca isu Xinjiang harus multidimensi. Dari dimensi sejarah, konflik antara muslim Uighur dengan otoritas Tiongkok berlangsung sejak lama, bahkan sejak masa kedinastian.
Pada tahun 1884, Dinasti Manchu menganeksasi Kerajaan Islam Uighur dan mengganti nama wilayah Turkestan Timur menjadi Xinjiang (secara harfiah bermakna daerah baru). Pada 1933 tercatat ada pemberontakan melawan pemerintah Tiongkok. Pemberontakan tersebut sangat kental dengan intervensi Soviet yang juga berkepentingan atas wilayah Xinjiang.
Dari peristiwa tersebut kemudian berdirilah Republik Turkistan Timur yang berbasis di wilayah Kashgar dan hanya berdiri selama kurang lebih satu tahun. Berikutnya, tahun 1944 muncul Republik Turkistan Timur jilid II. Senasib dengan sebelumnya, pemerintahan Turkistan Timur II bisa ditumpas oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949. Dari sisi historis minimal kita bisa melihat bahwa sejarah gerakan separatis di Xinjiang itu berlangsung cukup lama.
Dimensi berikutnya adalah adaptasi kebijakan regional. Perjalanan panjang gerakan separatis di Xinjiang tentu membuat pemerintah Tiongkok semakin bijak dalam mengeluarkan kebijakan. Pada tahap awal penataan Xinjiang era keterbukaan pemerintahan RRT dimulai pada tahun 1995 di mana terdapat kebijakan “go western” yang menyasar daerah Xinjiang. Kebijakan “go western” bertujuan untuk pemerataan ekonomi antara Tiongkok bagian timur dan Tiongkok barat. Pada masa ini, Xinjiang dipimpin oleh Wang Lequan (1994-2010) yang memimpin industrialisasi dan modernisasi di Xinjiang.
Namun sayangnya Lequan menggunakan pendekatan militeristik ke masyarakat Uighur ketika menerapkan industrialisasi di Xinjiang. Ibarat udara dalam balon, semakin kelompok separatis Xinjiang ditekan maka semakin meledak, sehingga muncul kerusuhan tahun 2009. Lequan diganti dengan Zhang Chunxian (2010-2016) yang lebih akomodatif kepada kelompok separatis. Namun sayangnya, kebijakan akomodatif Chunxian tak membawa hasil. Kelompok separatis Xinjiang tetap melakukan aksi terorisme.
Nah pada pemimpin Xinjiang berikutnya, Chen Quanguo (2016-sekarang) berusaha melakukan adaptasi dan modifikasi antara pendekatan militeristik dan akomodatif dari rezim sebelumnya di Xinjiang. Kebijakan reedukasi adalah cerminan dari kebijakan adaptasi tersebut. Muslim Uighur yang masih simpatik dengan gerakan separatis tidak disiksa dan dibunuh seperti rezim Lequan, tidak juga terlalu diberi afirmasi seperti era Chunxian, melainkan diberi pendidikan vokasi dan diajari bahasa mandarin supaya bisa lebih sejahtera dan memiliki semangat nasionalisme.
Dimensi terakhir adalah rivalitas AS dan Tiongkok dalam ekonomi dan politik dunia. Sudah menjadi rahasia umum kalau kebangkitan ekonomi Tiongkok mengancam posisi AS sebagai hegemon dunia. AS sebagai Pemenang Perang Dunia dan Perang Dingin merasa tersaingi oleh Tiongkok. Isu Xinjiang adalah salah satu bahan utama AS untuk “menyerang” Tiongkok.
Dengan membangun opini publik lewat media, AS dan sekutunya berusaha melakukan branding HAM atas isu Xinjiang. Maka sudah tepat kiranya Indonesia bersama negara muslim lainnya mendukung Beijing dalam penumpasan gerakan separatis di Xinjiang.
Penulis:
M. Fathoni Hakim
(Staf Pengajar Hubungan Internasional FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya)
Advertisement