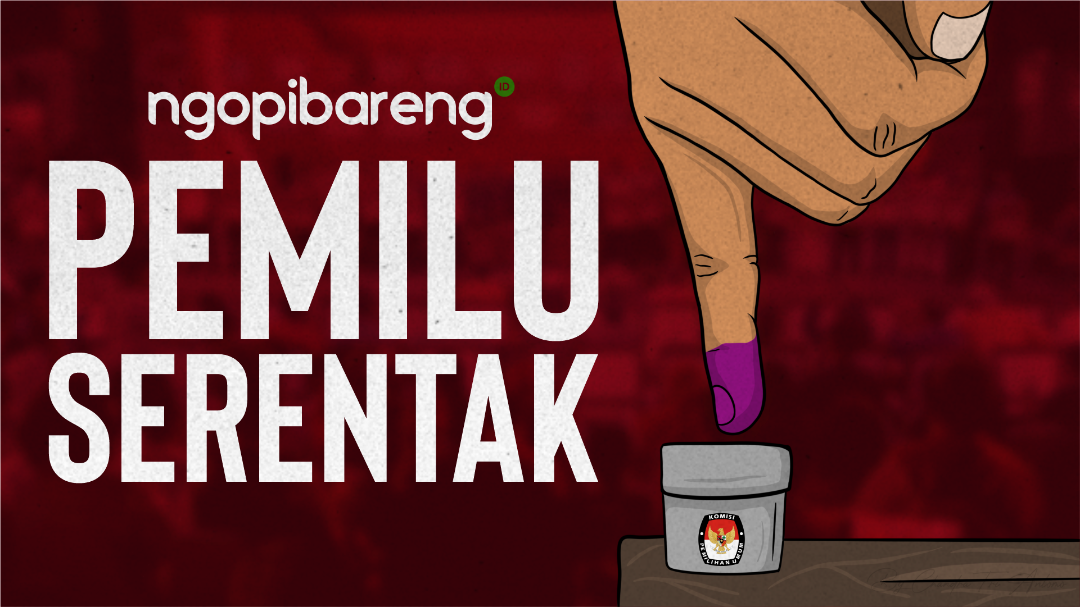Politik Kebhinekaan

PENGANTAR REDAKSI: Bagaimana kita harus menyikapi gejolak politik di Papua yang dipicu pernyataan rasisme di Surabaya? Berikut adalah renungan Anggota DPRD Jawa Timur yang dulunya aktivis literasi Diana AV Sasa untuk ngopibareng.id.
Suka atau tidak suka, Kota Surabaya harus kita sebut menjadi pelatuk (trigger) membaranya kembali Papua sejak Agustus silam hingga kini. Rasisme yang terjadi di asrama Papua di Surabaya itu menimbulkan daya rusak yang luar biasa besarnya. Tidak saja kerusakan material, tetapi juga abstraksi kita sebagai bangsa yang dijaga oleh negara ikut goyah.
Yang robek dalam peristiwa rasisme atau kekacauan yang dipicu oleh semangat merendahkan ras adalah pita "Bhinneka Tunggal Ika" yang dicengkeram dengan sangat kuat oleh Garuda. Cengkeraman itu bisa melemah dan terlepas jika kita tidak secara terus-menerus memberi nutrisi kepada Garuda secara utuh. Atau, dalam bahasa politik gizi masa Orde Baru, empat sehat lima sempurna. Kelima gizi itu ada dalam perisai yang tergantung di dada Garuda.
"Bhinneka" atau keragaman itu sesungguhnya adalah wajah kebudayaan kita. Kata itu pun ditimba dari salah satu kakawin Nusantara karya pujangga Mpu Tantular berjudul Sutasoma, terutama di pupuh 139 bait 5. Kutipan lengkapnya:
Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa
Bhineka itu adalah kebenaran faktual. Nyata. Tidak rancu. Kita memang berbeda, kok. Kita tidak sama. Bahkan, dalam ilmu pengetahuan, keragaman dalam struktur genetika Nusantara itu terumuskan secara jelas.
Bacalah pandangan-pandangan Sangkot Marzuki, presiden Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) yang berkantor di Perpustakaan Nasional RI. Peneliti bidang biogenesis dan pendiri Lembaga Eijkman ini menelaah kebhinekaan itu dari garis bayang yang dikerjakan naturalis asal Inggris, Alfred Russel Wallace selama delapan tahun pada 1854—1862.
Garis Wallace itu membagi batas-batas fauna, flora, dan bakhteria yang ada di Nusantara. Hasilnya: yang hidup di bagian barat datang dari Asia, bagian timur dari Australia, dan yang di tengah merupakan campuran.
Sangkot Marzuki yang juga pendiri Yayasan Wallace ini membuat kesimpulan bahwa yang mendiami Kepulauan Nusantara yang ada sekarang ini sebagian datang dari Asia, sebagian dari Papua, dari Australia, dan yang ada di tengah, yakni Sulawesi, campuran atau gado-gado.
Kita tidak mengenal “ras murni”. Atau, suku yang superior. Jawa tidak lebih baik dari Papua. Sumatra tidak lebih tinggi dari Kalimantan. Sulawesi tidak lebih baik dari Nusa Tenggara. Dan seterusnya. Kita ada karena perjumpaan dari banyak bangsa. Menghormati keberbedaan itu adalah sesungguhnya menghormati kemenjadian sebuah bangsa yang berbeda-beda dalam bentang Garis Wallace.
Yang diperlukan dalam fakta keberbedaan itu adalah “bhineka tunggal ika”, adalah empati. Suatu kemampuan belarasa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati atau belarasa bisa dipupuk dalam cara kita tumbuh dalam pergaulan sehari-hari.
Misal, menjaga perkataan yang merendahkan bangsa lain. Atau, melakukan perisakan berlebihan kepada rantai terlemah dalam sebuah kelompok pergaulan. Perlu diketahui, kelompok bumiputra bangkit melawan kolonialisme salah satunya terus-menerus didiskriminasi dalam pergaulan sosial, penerimaan dalam birokrasi, serta hierarki kelas dalam status kewarganegaraan.
Salah satu perisakan paling terkenal dalam sejarah kita adalah menyebut kaum bumiputra sebagai “anjing”. Dan, ini beberapa kali keluar dalam cuplikan film biopik HOS Tokroaminoto berjudul Guru Bangsa: Tjokroaminoto (Garin Nugroho, 2015), “Pribumi dan anjing dilarang masuk”.
Perkataan dan umpatan semacam verboden voor honden en inlanders itu menyumbang energi kemarahan pemuda-pemuda radikal semacam Sukarno. Jalan untuk tidak dihina adalah mempersenjatai diri dengan solidaritas, dengan persatuan.
Sejak berusia sangat muda, Sukarno terus meyakinkan dirinya dan organ yang didirikannya bahwa persatuan nasional, bahwa nasionalisme, adalah sebaik-baik siasat untuk mengorkestrasi perlawanan. Kekuatan kolonial yang didukung segalanya, baik modal maupun amunisi militer, terus-menerus digerogoti oleh pembayangan bersama tentang solidaritas sebagai bangsa yang menderita dan korban rasisme itu.
Belajar dari sejarah bangsa seperti itu, perlu merawat belarasa untuk menyingkirkan umpatan yang rasis dan perendahan suku bangsa lain lewat jalan pendidikan sejak dini.
Sudah dibiasakan sejak dini mengajarkan arti kerukunan bukan sekadar kata-kata yang dilafalkan, tetapi juga kehidupan nyata. Membangun kelompok belajar dan aktivitas, misal, dilatih dengan memberlakukan prinsip-prinsip berdasarkan pada kemampuan individu (merit), bukan semata karena kesamaan suku, agama, dan etnis.
Dalam konteks politik kenegaraan, menjaga kebhinekaan adalah memastikan semua struktur penyanggah asas bernegara berdiri tegak. Memastikan gizi dari lima bilangan sila itu, empat sehat lima sempurna itu, mengejawantah dalam setiap produk perundang-undangan, dalam setiap pembagian peruntukan anggaran, dan kebijakan-kebijakan politik yang mengayomi dan memperkuat keberagaman.
Jika "Bhinneka" adalah wajah kebangsaan kita, sekali lagi, bait "Bhinneka Tunggal Ika" dari salah satu pupuh kakawin Sutasoma yang dicengkeram Sang Garuda adalah wajah kenegaraan kita. Tupoksi negara adalah bagaimana menjalankan semua mesin kehidupan dalam sebuah sistem besar bernama Republik Indonesia bersandar pada ejawantah lima sila dalam perisai yang tergantung di dada Sang Garuda.
Nutrisi "bhinneka tunggal ika" yang dinamakan Sukarno dengan “Persatuan Indonesia” itu bisa digapai bila kita berikhtiar mengerjakan secara “gotong-royong” empat jalan pokok ini, yakni jalan religiusitas, jalan humanitas atau kemanusiaan, jalan demokrasi, dan jalan keadilan sosial.
Oleh Diana AV Sasa, Anggota DPRD Jawa Timur (2019-2024) yang juga aktivis Literasi
Advertisement