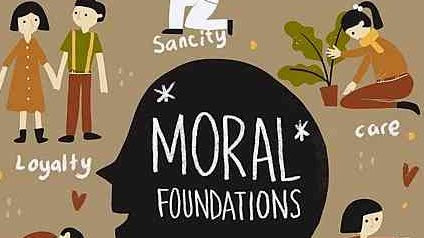Perlu Ruang Dialog dalam Polarisasi Politik

“Segera Buka Ruang Dialog". Judul tersebut tercantum pada halaman pertama, Harian Kompas edisi 4 Mei 2019. Substansinya berisi tentang urgensi dialog di antara elite politik untuk meredakan “Polarisasi Politik” pasca-pilpres dan pileg. Dialog segera diselenggarakan sehingga terbentuklah koalisi pemerintahan. Partai Gerindra dan beberapa partai lain menjadi bagian dari pemerintahan dan Capres/ Ketua Gerindra Parbowo Subianto menjadi Menhan. Kenyataannya di lapangan, polarisai politik di masyarakat masih ada hingga saat ini. Kenapa ?.
Pada dasarnya terdapat dua jenis polarisasi yang berbeda secara diametral. Pertama “polarisasi elite politik”, yaitu dua gerbong elite politik yang bebeda pilihan Capres - Cawapres. Polarisasi jenis ini selesai dengan terbentuknya koalisi kabinet yang mengakomodasi tokoh partai- partai yang saling bersaing. Kepentingan politik elite bisa diakomodir demi kebersamaan.
Polarisasi politik kedua; bersumber dari isu politik pada masa kampanye pilkada/pilpres yang mengandung substansi premordialisme atau politik identitas. Polarisasi jenis ini mengandung muatan emosionil massa yang luas. Muncul sebutan negatif untuk saling menyudutkan misalnya “sebutan kampret" dan lawannya “sebutan cebong”. Yang satu berkonotasi “muslim militan“ satunya lagi menunjuk “nasionalis sekularistik“ dan seterusnya.
Saling Mengejek, Saling Menuding
Kemudian berlangsunglah saling ejek, saling tuding-menuding, saling sudut-menyudutkan pada level akar rumput. Perdebatan premordialistik dalam ruang publik yang berlangsung dalam kurun waktu lama, sama saja dengan menebar benih perpecahan bangsa. Empat tahun lamanya kita alpa dengan membiarkan “quasi conflict" mengambang dan tidak diselesaikan secara politik-musyawarah.
Justru elit politik membawa penyelesaian ke ranah hukum formal alau solusi hitam putih. Dua tokoh yang berseberangan secara politik, masing-masing diproses hukum bergantian, mantan gubernur dan mantan ketua Ormas. Bayangkan, masing-masing pendukung menonton “drama hukum di pengadilan”. Bukannya mengurangi permusuhan, tetapi semakin mempertebal kebencian masing- masing. Solusi politik atau win-win solution atau dengan musyawarah adalah ruang yang tepat, yang merupakan warisan para pendiri bangsa.
Politik identitas yang muncul pada saat pilkada Jakarta 2016 sesungguhnya tidak perlu berlarut larut, jika diselesaikan melalui tradisi musyawarah. Dua tokoh utama yang terlibat, dua-duanya diadili, sang calon gubernur terlebih dahulu atas dasar penistaan agama dan seterunya seorang tokoh dan ketua Ormas dibawa kepengadilan dengan alasan berbeda, beberapa tahun kemudian. Drama primordialisme dipertontonkan di pengadilan, bukannya mempertontonkan seni merajut tali persaudaraan di antara dua keluarga yang bersengketa.
Konflik politik yang dilatarbelakangi oleh unsur primordialisme sebaiknya diselesaikan melalui ruang dialog. Bahkan bahasa yang digunakan oleh pendiri bangsa adalah frasa kalimat yang sangat khas Indonesia, “dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Menyikapi persoalan premordialisme dalam ranah publik, sebaiknya menjadi bagian penting politik membangun persaudaraan bangsa, bukan untuk saling salah-menyalahkan. Dengan demikian kepentingan golongan dan apalagi kepentingan bisnis harus dipinggirkan dan sebaliknya kepentingan persaudaraan bangsa yang harus didahulukan.
Dalam menyikapi “polarisasi politik“ ini kita perlu bersikap arif dan bijaksana. Polarisasi politik di antara elite, relatif lebih mudah diatasi atas dasar kompromi yang rasional dan pragmatis. Berbeda dengan polarisasi yang melibatkan masyarakat luas yang dasar polarisasinya lebih bersifat ideologis, karenanya memerlukan cara canggih berlandaskan persaudaraan. Karena polarisasnya yang bersifat ideologis maka hal demikian bisa mudah meledak menjadi konflik besar, sehingga kita tidak boleh abai.
KH As'ad Said Ali
Pengamat Sosial-Pilitik, Wa-Ka BIN 2000-2001, Mustasyar PBNU 2022-2027. Tinggal di Jakarta.
Advertisement