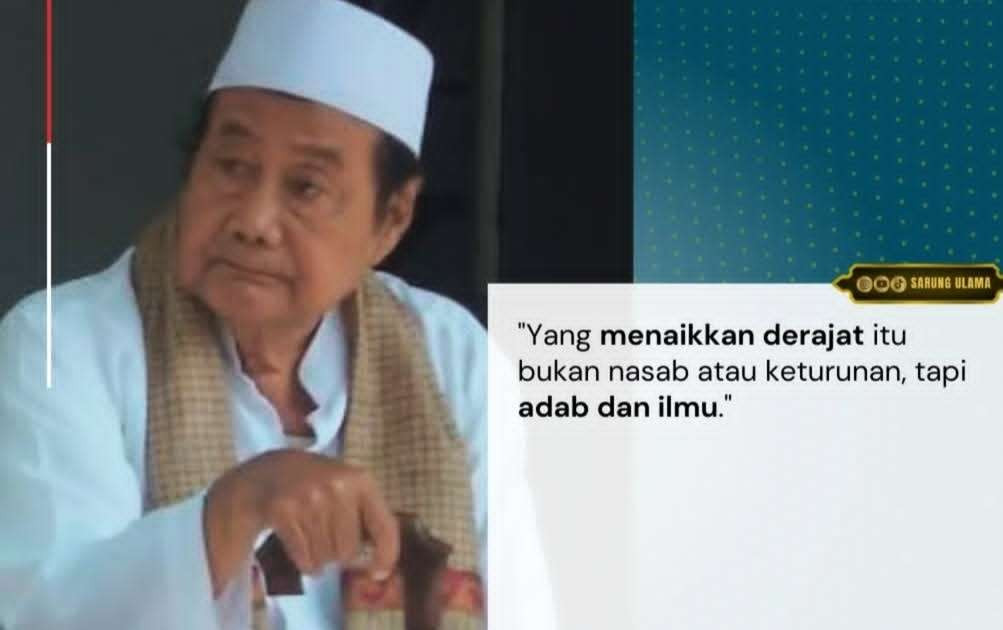Perempuan Khutbah Jumat, Bolehkah? Respon untuk Mazhab Bung Karno
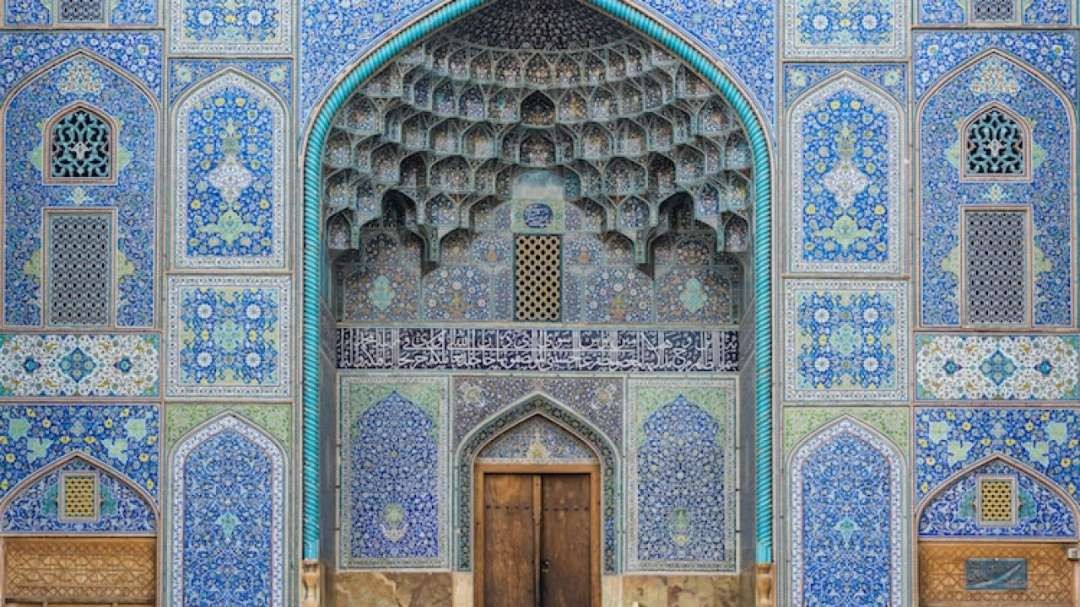
Pengantar Redaksi
Pesantren Al-Zaytun Indramayu, membikin geger umat Islam Indonesia. Pada pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1444 H tahun ini, Panji Gumirang dengan video yang aneh, viral di media sosial.
Pemimpin pesantren bernama lengkap Abdussalam R. Panji Gumilang akhirnya menjelaskan alasan mengapa jamaah wanita dan pria bercampur dalam satu shaf saat shalat Idul Fitri yang kontroversial.
Dalam ceramahnya, dia tidak menjelaskan alasannya tidak bersandarkan pada ulama mazhab yang muktabar dalam ilmu fikih, tetapi menyebutnya ‘Mazhab Bung Karno’.
Pada menit ke-7, ia mengaku terakit viralnya foto-foto kegiatan shalat Idul Fitri di PP Al Zaytun yang menampilkan seorang perempuan sejajar dengan pria di barisan depan. Secara jujur, Panji Gumilang tidak menyinggung mahzab ulama muktabar (yang diakui, red), namun dirinya mengakui mengikuti Mazhab Soekarno.
“Syeikh ingat, karena ditanya orang, ini mahzab apa yang begini-begini ini. Syekh karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, syeikh bilang, mazhabku adalah Bung Karno,” ujarnya disambut tepuk tangan.
Pria yang sempat dikaitkan sebagai Imam Negara Islam Indonesia (NII) Komandemen Wilayah (KW) 9 pada 2011 menjelaskan perbedaan antara Soekarno dengan Muhammadiyah soal tabir atau kain panjang yang menjadi pemisah antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah pertemuan dan shalat pada sekitar tahun 1930-an.
Lalu ia pun membolehkan perempuan memberikan khutbah Jumat. Bagaimana hal ini menurut ulama pesantren dan ulama di kampus perguruan tinggi Islam?
Berikut uraian Ust. Abdul Wahab Ahmad dari Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UINKHAS) Jember:

KHUTBAH Jumat bukanlah pidato atau orasi bebas sebagaimana disangka oleh beberapa orang awam. Ia adalah bagian dari ritual ibadah yang mempunyai syarat, rukun dan kesunnahan. Di antara rukun khutbah yang harus ada adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Sirajuddin al-Bulqini berikut:
وأما الخطبة فيعتبر فيها اثنا عشر أمرا :
١ - كون الخطيب بحيث تصح الجمعة خلفه.
"Adapun khutbah, maka yang dianggap sah di dalamnya adalah 12 perkara: Pertama, khatibnya adalah orang yang sah menjadi imam shalat Jumat." (at-Tadrib, I/205)
Dengan demikian, Khatib yang tidak sah untuk menjadi imam shalat jumat juga tidak sah apabila dia berkhutbah. Di antara yang tidak sah tersebut tentu saja wanita sebab wanita dilarang menjadi imam shalat bagi laki-laki sebagaimana maklum dalam semua kitab mazhab fikih. Tidak perlu baper soal ini sebab ini bukan soal emansipasi, bukan pula karena wanita dianggap "najis amat" sebagaimana disangka oleh orang yang tidak paham fikih.
Ini murni tentang ritual ibadah yang sah tidaknya hanya bergantung pada satu hal, yakni sesuai petunjuk Nabi Muhammad atau tidak. Tak ada urusannya persoalan fikih ibadah dengan emansipasi atau pemikiran Soekarno. Benar bahwa fikih memang selalu berkembang, tidak statis, tapi yang berkembang adalah objek pembahasannya di mana banyak kejadian di masa kini yang belum terjadi di masa lalu, bukan berkembang dan bisa berubah syarat-rukun ibadahnya sebagaimana disangka oleh Bapak Panji Gumilang pemimpin al-Zaitun yang mengaku bahwa dirinya mengikuti "mazhab Soekarno" dan merujuk pada buku "Di Bawah Bendera Revolusi".
Sebagaimana sampai kiamat nanti orang shalat harus berwudhu dulu tidak cukup hanya dengan mandi bersih pakai sabun, sampai kiamat juga imam shalat Jumat dan Khatib Jumat baru sah apabila dilakukan oleh lelaki, dan itupun tak sembarang lelaki tapi lelaki yang memenuhi syarat sebagaimana dibahas dalam kitab fikih. Sebab itu, ide Bapak Panji untuk menjadikan perempuan sebagai Khatib Jumat, yang diucapkan dengan nada gregetan sambil menepuk-nepuk meja, bukanlah ide yang revolusioner dan bahkan tidak ada hubungannya dengan revolusi sebagaimana sering dibicarakan oleh Bapak Soekarno di masa lalu. Ide semacam itu hanya menggambarkan ketidakpahaman terhadap fikih. Membawa-bawa isu emansipasi dalam hal ibadah ini hanyalah kebaperan yang kira-kira sama dengan kebaperan lelaki junub yang ditolak menjadi Khatib Jumat lalu marah-marah menggedor meja seolah tidak dihargai padahal dirinya adalah pejabat sukses.
Persoalan fikih ini sudah jelas dan tidak layak dibahas panjang lebar. Yang barangkali perlu diketahui masyarakat umum adalah ada perbedaan antara seorang fakih (ahli fikih yang punya kapasitas untuk menjadi rujukan dalam masalah fikih) dan seorang manajer pesantren (orang yang memimpin tata kelola pesantren). Masyarakat kita banyak yang tidak mampu memahami perbedaan antara kedua istilah ini sehingga manajer pesantren biasanya dianggap fakih, padahal dalam urusan fikih dia masih awam.
Orang yang mampu menjalankan tata kelola pesantren hanya layak dianggap sebagai manajer pesantren. Ia tidak punya kapabilitas untuk berbicara soal fikih apabila tidak mendalami persoalan fikih yang tertulis dalam kitab-kitab mazhab fikih. Apa pun gelar sosial yang diberikan masyarakat kepadanya, atau dipakai oleh dirinya sendiri, seperti gelar Syaikh, Kyai, Ustadz, Gus, atau semacamnya tak otomatis menjadikan dia sebagai ahli fikih apabila faktanya dia hanya bisa menjadi manajer saja. Cukuplah seorang manajer yang baik berbicara atau dirujuk dalam hal manajerial saja, jangan berbicara atau dirujuk dalam hal yang berada di luar kapasitasnya. (sumber: akun facebook: abdul wahab ahmad)
Advertisement