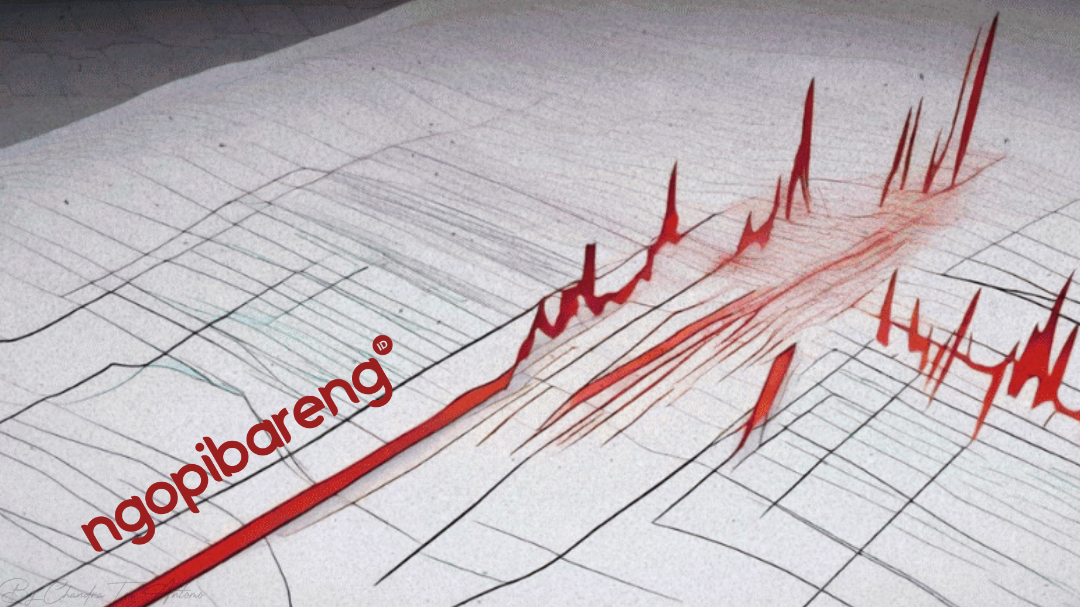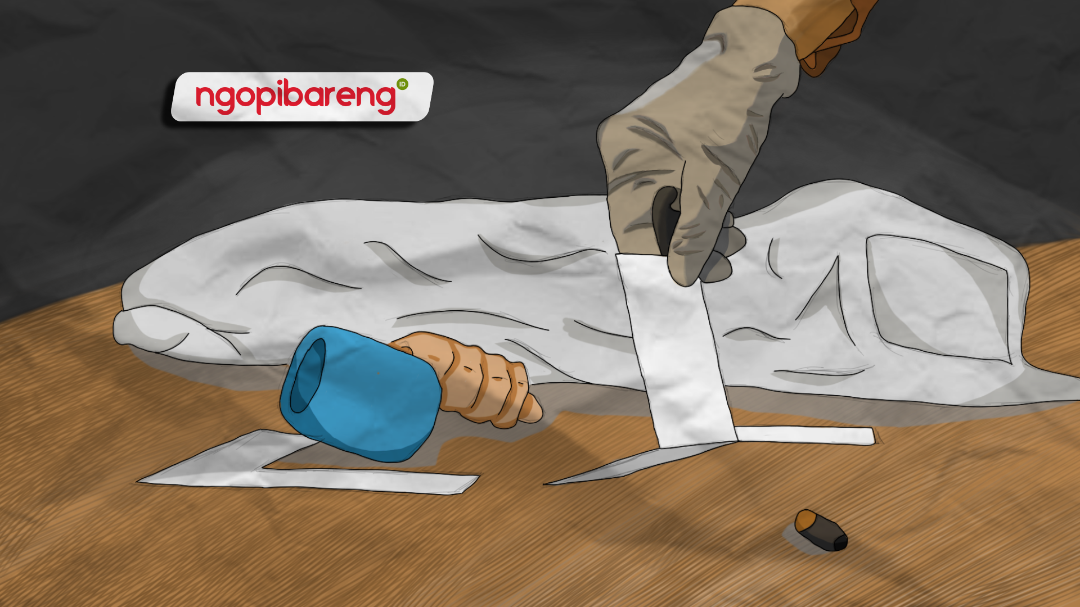Pendidikan Seks dan Konsep ‘Kafir’, Kisah Fachry Ali soal Gus Dur

Persoalan seks memang masih tabu di masyarakat. Tapi bila menyangkut soal pendidikan seks, hal itu merupakan kewajaran. Apalagi dikaitkan dengan dunia pendidikan pesantren dan masyarakat.
Pengamat sosial politik berlatar belakang Aceh, Fachry Ali ternyata mempunyai kesan khusus soal itu. Juga dalam kaitan dengan konsep 'kafir' yang sempat diperdabatkan di masyarakat. Berikut Fachry Ali bertutur terkait Kiai Abdurrahman Wahid, pendidikan seks dan konsep 'kafir':
Ketika Munas Ulama PBNU di Banjar, Jawa Barat, 2019 lalu menyinggung perlunya frasa atau konsep ‘kafir’ —dalam konteks politik dan kewarganegaraan di Indonesia— diubah menjadi ‘non-Muslim’, saya sama sekali tidak teringat pada pertanyaan apakah ‘fansurna ‘alal qaumul kaafiriin’ yang ada dalam Al-Qur’an itu berlaku universal.
Yang saya ingat justru suatu malam di Clayton, Melbourne —ketika Kiai Abdurrahman Wahid berselonjor kaki di atas karpet pertengahan 1991. Diskusi sudah selesai. Dan keisengan selalu menggoda dalam waktu-waktu seperti itu.
Maka berceritalah Kiai Abdurrahman Wahid tentang seorang kiai sepuh di sebuah pesantren antah berantah. Entah berkat apa, kiai ini meminang santriwati yang tentu saja muridnya. Pinangan tersebut disambut baik orang tua santriwati.
Maka, malam pasca-nikah, sebagai suami, kiai sepuh tersebut harus melaksanakan ‘kewajiban’-nya —ba’da isya dan, mungkin, disambung wirid seperlunya.
Ketika ‘kewajiban’ tersebut hendak dieksekusi, santriwati yang kini absah menjadi isterinya, menolak serta merta. Telah sepuh, tentu sang kiai cukup bijak dan bersabar. Walau kian larut, sang kiai dengan lembut memberikan ‘ceramah’ tentang kewajiban suami-isteri menurut pandangan agama.
Tetapi, ‘ceramah’ tersebut tidak mempan. Sedikit kehilangan kesabaran, kiai tersebut menggunakan ‘senjata pamungkas’. Kepada isterinya yang masih remaja itu, sang kiai mengatakan: ‘Kalau dinda (ce’ilee) mau melaksanakan kewajiban sebagai isteri malam ini, pahalanya sama dg membunuh 100 orang kafir.’ (Malam itu, kiai ‘menyediakan’ 300 orang kafir saja).
Mendengar itu, santriwati yang telah menjadi isterinya itu tertarik dan bergairah. Maka ia berseru: ‘Ayo kita bunuh orang kafir,’ cetusnya bersemangat. Dalam hati, kiai berkata: ‘Ini yang kutunggu.’ Maka, sang kiai berhasil melaksanakan kewajibannya.
Santriwati yang kini merasa mendapat ‘pahala’ besar dengan aksi ini, mengajak sang kiai menambah ‘pahala’ setelah kewajiban pertama usai. Kiai berkalkukasi tinggal 200 orang kafir lagi. Tak apalah. Tetapi, setelah ke-200 orang kafir tersebut terbunuh semua, hasrat berpahala santriwati ini kian meningkat. ‘Ok,’ kata kiai. Toh persediaannya masih 100 orang kafir.
Masalahnya, ketika tak ada lagi orang kafir yang tersedia untuk dibunuh, sang santriwati justru kian bergairah mencari pahala. Maka, kepad suaminya yang sudah hampir terlelap kelelahan itu, ia berkata: ‘Ayo, kita cari pahala lagi. Kita bunuh orang kafir!’
Tergeletak tak berdaya, sang kiai dari pesantren antah berantah itu menjawab sekenanya. ‘Orang kafir sudah habis. Kita tunggu mereka kumpul duluuuuu.’
Setelah itu, tak ada suara yang terdengar dari kiai ini.
Advertisement