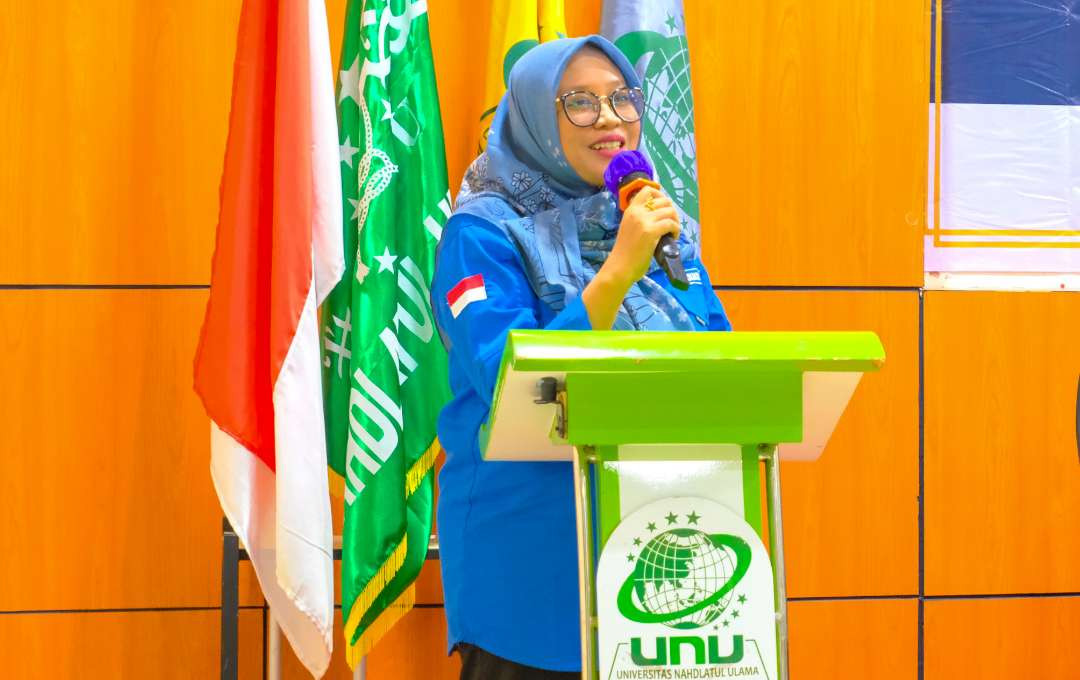Pelantikan Pimpinan DPD, Kelemahan Sistem Uji Materiil MA

KISRUH dan kontroversi sekitar pelantikan Ketua dan para Wakil Ketua DPD Selasa 4 April 2017 hingga hari ini belum mereda. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono bisa dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPD dan pengucapan sumpahnya dibimbing langsung oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA), sementara MA sendiri sudah membatalkan Peraturan DPD No 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Tata Tertib yang menjadi dasar pemilihan dan pelantikan itu?
Sebagian tokoh, pengamat hukum, bahkan termasuk mantan Ketua MA Dr Harifin Tumpa mengatakan Mahkamah Agung telah mempermain-mainkan hukum dalam kasus pelantikan Pimpinan DPD ini. Headline Koran Kompas (5 April 2014) menulis judul berita yang sama dan menuduh DPD melakukan tindakan memalukan karena terang-terangan telah mengabaikan Putusan MA yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD sebagaimana tertuang dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017. Padahal sebagai lembaga negara, DPD harusnya memberi contoh menjalankan hukum dengan benar di negara ini.
Sebagian kalangan menuding OSO dan kawan-kawan sebagai tokoh yang mendalangi kisruh pergantian Pimpinan DPD setelah pimpinan yang ada menjalankan tugasnya selama 2,5 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017. Sementara Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Prof Dr Farouk Muhammad menolak, dua Wakil Ketua DPD yang menurut Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 berakhir masa jabatan dua setengah tahunnya tanggal 1 April yang lalu, menentang pergantian pimpinan DPD itu.
Alasan GKR Hemas dan Prof Farouk menolak pergantian itu adalah karena Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPR selama 2,5 tahun telah dibatalkan MA. Dengan pembatalan itu, maka masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 tahun, sehingga tidak perlu ada pergantian pimpinan.
Upaya GKR Hemas untuk membacakan Putusan MA itu dalam rapat paripurna mendapat tantangan yang besar. Alasannya, GKR Hemas dan Prof Farouk sudah tidak berhak lagi memimpin Rapat Paripurna karena jabatannya, menurut Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017, sudah berakhir. Pimpinan DPD dianggap sudah vakum dan karena itu, sesuai undang-undang harus dipimpin sementara oleh anggota tertua dan termuda usianya. Namun anggapan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD 2,5 tahun telah berakhir itu, menurut mereka yang menentang sudah tidak berlaku lagi karena peraturanya sudah dibatalkan MA.
Kekisruhan masalah Pimpinan DPD ini kalau dilihat dari sudut perundang-undangan sebenarnya disebabkah oleh mekanisme uji materil yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Menurut UUD 45, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang. Sementara untuk menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang menjadi kewenangan Mahkamah Agung.
Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 45 bersikap tegas. Jika MK memutuskan norma undang-undang, sebagian atau seluruhnya, bertengan dengan UUD 45 maka putusan itu berlaku seketika yakni ketika palu sudah diketok oleh Ketua MK dalam sidang yg terbuka untuk umum. Putusan MK itu final dan mengikat, tak seorangpun boleh membantahnya.
Saya masih ingat ketika Ketua MK Mahfud MD mengetok palu menyatakan pasal UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang masa jabatan Jaksa Agung bertentangan dengan UUD 45 kecuali dimaknai bahwa jabatannya adalah 5 tahun sama dengan masa bhakti kabinet, maka putusan itu detik itu juga berlaku dengan serta-merta.
Sebagai reaksi atas Putusan MK tersebut, Mensesneg waktu itu, Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden SBY yang sangat masyhur, Prof Dr Denny Indrayana, segera mengadakan konfrensi pers ke istana. Mereka mencoba berkelit2 dan mencoba untuk menafsir-nafsirkan putusan MK untuk mempertahankan jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Namun Presiden SBY akhirnya tidak bisa berbuat apa2 kecuali memberhentikan Hendarman dua hari setelah MK membacakan putusannya.
Beda dengan MK yg bersifat tegas dalam menjalankan kewenangannya menguji undang-undang, Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya menguji peraturan perundan-undangan di bawah undang-undang dengan cara yang lunak. Putusan MA yang membatalkan sebuah peraturan perundang-undangan tidaklah berlaku serta-merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu untuk mencabutnya. Kalau lembaga itu tidak mencabutnya dalam waktu 90 hari, maka barulah peraturan yang dibatalkan MK dalam uji materil tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat lagi. Ketentuan ini diatur dalam beberapa peraturan MA, dan terakhir dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 yang sampai sekarang masih berlaku.
Menurut hemat saya, Peraturan Uji Materil MA yang dibuatnya sendiri itu telah menempatkan MA tidak sejajar dengan MK dalam melaksanakan kewenangan uji materi yang sama-sama diberikan oleh UUD 45. MA secara sengaja membuat dirinya sendiri menjadi kurang berwibawa dalam melakukan uji materil sebagaimana MK. Saya sudah mengingatkan Ketua MA Dr M Hatta Ali, tak lama setelah beliau diilantik menjadi Ketua, akan kelemahan Peraturan MA tentang uji materil itu dan meminta beliau untuk segera memperbaikinya demi meningkatkan kewibawaan MA. Namun sampai hari ini, perbaikan belum juga dilakukan.
Saya katakan kepada Dr Hatta Ali bahwa arsitek penyusunan peraturan MA tentang uji materil itu adalah mendiang Prof Dr Paulus Effendi Lotulung yang waktu itu menjadi Ketua Muda MA Bidang Tata Usaha Negara. Prof Lotulung memang seorang Guru Besar Hukum Administrasi Negara dan berkarir sebagai hakim Tata Usaha Negara (TUN). Karena itu, tidak heran jika Peraturan Hak Uji Materil MA nampak bergaya hukum acara peradilan TUN. Padahal, hakikat kewenangan MA dalam menguji peraturan, sangatlah berbeda dengan kewenangannya mengadili sengketa tata usaha negara. Kalau MA sudah menyatakan batal suatu peraturan perundang-undangan, maka putusan itu seharusnya berlaku serta-merta dan tidak memerlukan eksekusi dalam bentuk pencabutan oleh institusi yang membuatnya.
Kelemahan Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2012 itulah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kisruh di DPD. GKR Hemas dan Prof Farouk Muhammad mengira, Putusan MK tanggal 29 Maret 2017 yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2017 yang mengatur masa jabatan Pimpinan DPD hanya 2,5 tahun berlaku serta merta. Padahal peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dicabut oleh Pimpinan DPD atau belum lewat waktu 90 hari sejak putusan dibacakan oleh MA.
Keadaan seperti di atas dimanfaatkan Oesman Sapta Odang (OSO) dan para pendukungnya. Pimpinan DPD yang mana yang bisa mengeksekusi putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib itu, sementara pimpinan yang ada, yakni dua wakil ketua masing-masing GKR Hemas dan Prof Farouk -- sementara Ketuanya Muhammad Saleh tidak hadir karena sedang umroh -- masa jabatan 2,5 tahunnya sudah habis sejak tanggal 1 April 2017. Pendukung OSO mengatakan bahwa GKR Hemas dan Prof Farouk tdk sah memimpin sidang DPD karena jabatannya sudah kadaluarsa.
OSO juga memanfaatkan kelemahan administrasi putusan MA -- dan MA memang sering begitu -- yakni salah ketik dalan diktum putusannya yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu. Amar putusannya bukannya memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib yang dibatalkan itu, melainkan ditulis "memerintahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (DPD) untuk mencabut Peraturan Tatib DPD yang dinyatakan batal oleh MA itu.
OSO bilang, mana bisa Pimpinan DPRD mencabut Peraturan Tata Tertib DPD. Walau terdengar lucu, omongan OSO ini benar. MA telah salah dalam membuat putusan, dan kesalahan seperti itu dalam sebuah putusan yang telah dibacakan dalam sidang yg terbuka untuk umum dan telah pula dimuat dalam website MA, tidaklah dapat dikoreksi begitu saja dengan mengatakannya sebagai salah ketik belaka.
Kalau MA menulis salah nama orang yang dijatuhi pidana dalam perkara tingkat kasasi, maka untuk memperbaikinya tidak bisa diralat begitu saja, melainkan harus melalui putusan Peninjauan Kembali (PK), atau putusan itu menjadi "non executable" yakni putusan yang tidak dapat dieksekusi. Nah, masalahnya Putusan MK yang membatalkan Peraturan Tata Tertib DPD itu adalah putusan yang "final and binding" artinya putusan terakhir yang tidak ada upaya hukum lagi, termasuk Peninjauan Kembali.
Kini kembali kepada persoalan utama dalan tulisan ini, apakah sah pemilihan OSO, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai Pimpinan DPD yang baru untuk jabatan 2,5 tahun ke depan? Apakah sah sidang DPD yg memilih mereka yang dipimpin AM Fatwa sebagai anggota tertua dan apakah sah Wakil Ketua Mahkamah Agung Suwardi yang memandu pengucapan sumpah mereka sebagai Pimpinan DPD?
Jawaban saya atas pertanyaan di atas adalah semua itu adalah sah. Mengapa? Bukankah Peraturan Tata Terib DPD sebagaimana tertuang dalam Keputusan DPD Nomor 1 Tahun 2017 sudah dibatalkan MA dalam perkara uji materil tanggal 29 Maret 2017? Jawab saya, memang Peraturan Tata Tertib itu sudah dibatalkan MA, tetapi peraturan itu masih tetap berlaku sebelum dieksekusi, dalam makna belum dicabut oleh Pimpinan DPD atau belum lewat waktu 90 hari sejak putusan dibacakan.
Bahkan kalau mengikuti ucapan OSO yang lebih ekstrim lagi, Putusan MA yang membatalkan Peraturan Tatib DPD itu tergolong sebagai putusan yang "non executable" atau putusan yang tidak dapat dieksekusi karena dalam amar putusannya, MA memerintahkan Pimpinan DPRD (yang juga tidak jelas DPRD yang mana) untuk mencabut Peraturan Tata Tertib DPD yang dibatalkannya itu. Padahal semua orang tahu bahwa Pimpinan DPRD manapun di seantero republik tercinta ini tidaklah punya kewenangan untuk mencabut Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.
Walaupun kisruh DPD ini membuat sebagian orang sesak nafas dan geleng-geleng kepala menyaksikan kelucuan dan keganjilan di negara ini, namun peristiwa ini bagi saya mengandung hikmah yang besar. Negara kita sekarang ini dipimpin oleh banyak pemimpin amatiran, bahkan pemimpin dagelan, sehingga membuat saya berpikir: akan ke mana perjalanan bangsa dan negara kita ini ke depan? Indonesia dengan demokrasi model sekarang ini, nampaknya benar-benar berada di persimpangan jalan.***
*) Yusril Ihza Mahendra adalah guru besar ahli hukum tata negara. Jakarta, 6 April 2017
Advertisement