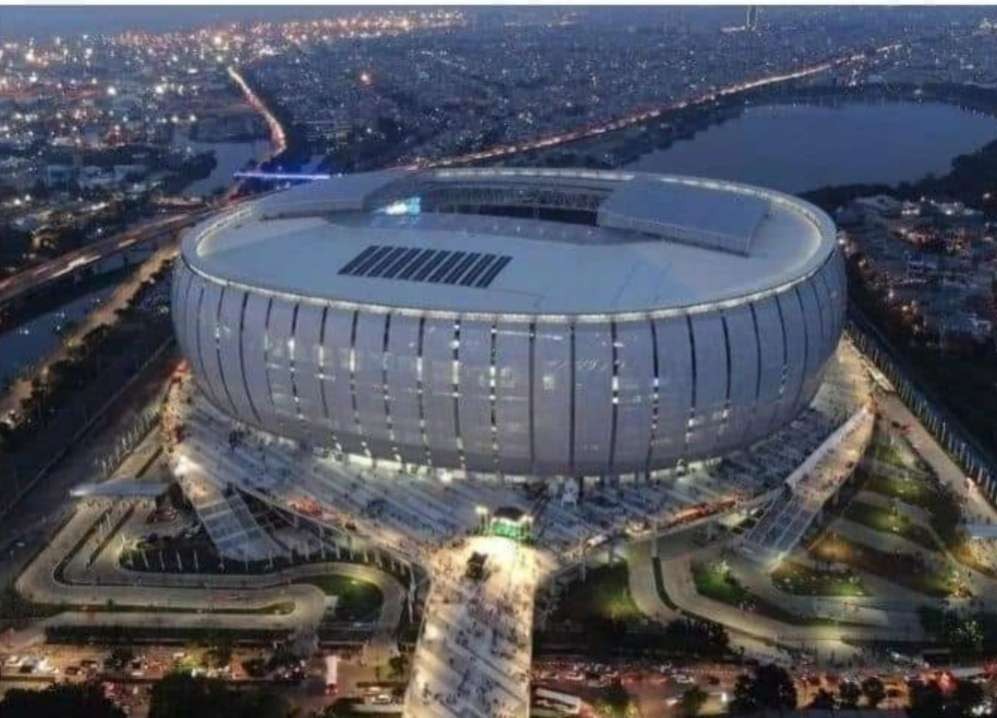Partai dan Demokrasi

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD
Dosen Perbandingan Politik - Universitas Jember
---------
Sewaktu mudik lebaran tempo hari, perhatian saya terfokus pada desa. Sepanjang jalan terdapat pemandangan yang berbeda. Banyak baliho besar bergambar politisi yang berhasrat mencalonkan diri. Sikapnya santun dengan gestur namaste, salam dengan posisi tangan di depan dada. Background-nya berhias logo, dan sering dilengkapi foto elite partai.
Pesannya jelas, memperkenalkan diri dan memohon dukungan warga. Obsesinya, terpilih sebagai wakil rakyat, dengan janji akan menyalurkan aspirasi mereka. Publik pun mafhum, itulah keajegan menjelang tahun politik.
Sehabis mudik lebaran, perhatian kembali terfokus pada berita nasional. Topik politik, khususnya dinamika menjelang pemilihan Presiden, mendominasi pemberitaan. Yang menarik, tak jarang narasi pimpinan partai politik berupaya menggapai dukungan pejabat. Tentang koalisi, misalnya, pimpinan sebuah partai mengatakan bahwa “arahnya menunggu” petunjuk presiden.
Sementara itu, menyangkut calon presiden (capres), elite partai lainnya bilang “nanti tentu ada arahan dari presiden”. Bahkan, ada pula pemimpin partai yang secara tegas menyatakan sikap partai-nya “tegak lurus” pada presiden.
Ilustrasi dua fragmen di atas menggambarkan sikap dan perilaku politik yang kontras. Politisi lokal berusaha ‘berorientasi ke bawah’ dengan meminta dukungan rakyat, sedangkan politisi di tingkat pusat ‘berorientasi ke atas’, berebut restu presiden.
Secara teoritis, gap dua kelompok politisi ini juga ironis. Dalam sistem demokrasi, secara normatif, partai seharusnya berfungsi sebagai penghubung elektorat dengan para pembuat keputusan (decision makers) di tingkat pusat.
Memang, pimpinan partai bisa saja berkilah bahwa sikap politik mereka adalah mandat hasil Musyawarah Nasional (Munas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai. Tapi, publik ternyata menilai lain. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2021, mendapati 64,7% kaum milenial menilai bahwa partai politik atau politisi di Indonesia tidak baik dalam mewakili aspirasi rakyat.
Sementara dalam surveinya pada Januari-Februari 2023, Litbang Kompas mendapatkan citra partai politik juga tak kunjung membaik. Dari 12 lembaga, citra ‘positif’ partai politik hanya bertengger di urutan ke delapan, dengan hanya menangguk 52,2% responden yang menilainya positif. Artinya, sebagai jangkar aspirasi publik, partai dinilai belum menunjukkan kinerja yang apik.
Mengapa muncul gap politis yang ironis ini? Setidaknya ada dua kemungkinan penjelasan. Yang pertama bersifat pragmatis. Dalam rejim elektoral, perolehan suara dalam pemilihan umum senantiasa menjadi prioritas utama. Salah satu caranya, partai berlomba untuk mengejar ‘efek ekor jubah’ (coat-tail effect) dari popularitas Presiden atau calon Presiden. Dalam konteks ini, narasi politik berbagai pimpinan partai yang berorentasi “ke atas” tak lepas dari upayanya untuk mendongkrak suara partai mereka dengan meraih efek elektoral dari popularitas presiden. Maklum, akseptabilitas publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi relatif tinggi, bahkan cenderung meningkat.
Litbang Kompas mencatat, survei Oktober 2022 kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 62,1%, tapi meningkat menjadi 69,3% pada Januari-Februari 2023.
Penjelasan kedua lebih bersifat teoritis. Narasi politik pimpinan partai di atas, bisa jadi cerminan dari sifat paradoksal dari partai sebagai organisasi. Lebih dari seabad yang lalu, Robert Michels meneliti perilaku organisasi Partai Sosialis Demokrat di Jerman. Persisnya, tahun 1911 sosiolog Jerman keturunan Itali ini merumuskan “Hukum Besi Oligarki” (the Iron Law of Oligarchy). Postulatnya: “Adalah organisasi yang melahirkan dominasi yang terpilih (the elected) atas pemilih (the electors), (dominasi) para mandataris (the mandataries) atas pemberi mandat (the mandators) ... Siapa membahas organisasi [akan selalu] membicarakan oligarki”. Intinya, oligarki merupakan kontrol sekelompok orang ‘atas’ terhadap organisasi dan masyarakat. Sebagai “hukum besi”, asumsi postulat ini berlaku kapan saja dan di mana saja.
Memang, terdapat definisi lain tentang oligarki. Tapi, dalam hal ini, saya mengadopsi pernyataan Humpty Dumpty: “Ketika saya menggunakan sebuah kata, hanya yang saya pilihlah yang menjadi artinya. Tidak lebih dan tidak kurang”. Saya juga realistis; memang ada pandangan pesimistis dan optimistis tentang demokratis. Postulat Robert Michels mewakili pandangan yang pertama.
Jika kedua penjelasan di atas secara substantif benar, adalah sebuah keniscayaan demokrasi akan memudar. Pasalnya, meski rasional, kedua fenomena tersebut akan menggerus esensi “suara rakyat adalah suara Tuhan” (vox populi vox dei). Padahal, kehendak rakyat seharusnya merupakan referensi utama setiap proses politik. Apalagi, kontribusi utama sistem kepartaian pada demokrasi justru ditentukan sejauh mana kedekataan hubungan partai dengan massa grassroots.
Memang, demokrasi bukanlah sistem yang sempurna. Sebagai konsep politik ia telah hidup lintas millennium. Tapi, pada saat yang sama, eksistensi-nya jua senantiasa mengundang perdebatan, khususnya antara kubu yang pesimis dan yang optimis. Bahkan, untuk menurunkan tensi perdebatan, Robert Dahl sempat menyodorkan pemilahan antara “Demokrasi ideal” dan “Demokrasi aktual”. Secara empiris, kualitas demokrasi terserak di antara dua kutub ini.
Pertanyaannya, di antara koridor dua kriteria demokrasi di atas, adakah best practice yang bisa dijadikan inspirasi? Jawabnya: “Ada!”. Ketika delegasi Fulbright visiting scholars melakukan site visit ke Capitol Hill, Washington D.C., ada agenda diskusi dengan anggota Konggres Amerika Serikat (AS).
Sebagai salah satu peserta, saya sempat bertanya: “Mengapa anggota Konggres AS yang berkunjung ke Indonesia selalu cenderung punya pandangan yang distortif, khususnya menyangkut Timor Timur (dulu) dan Papua?”. Sambil tersenyum seorang anggota Konggres menjawab: “Jangan asumsikan semua anggota Kongres punya wawasan internasional.
Pasalnya, mayoritas dari mereka lebih mencurahkan perhatian pada elektoratnya. Perkiraan saya tak lebih dari 10% dari total anggota Kongres yang benar-benar paham isu-isu internasional”. Penjelasan ini menegaskan komitmen tinggi politisi terhadap pemilihnya.
Ketika saya lanjut bertanya: “Berapa jumlah staf anda?”. Anggota Kongres yang lain menyahut: “Hampir tiga puluh orang!”. Saya menyela: “Wah, banyak juga! Apa saja yang mereka kerjakan?”. Ia menjawab lagi: “Masing-masing punya tugas. Terdapat tim pengkaji masalah yang dilontarkan elektorat untuk dirumuskan menjadi isu publik atau alternatif kebijakan, ada yang setiap hari bertugas menampung aspirasi elektorat, dan ada pula yang membalasnya melalui SMS atau email”. Informasi ini, sekali lagi, menggarisbawahi bahwa orientasi utama politisi AS adalah pemilihnya.
Lain politik di Indonesia, lain pula yang terjadi di AS. Jika di sini prakteknya cenderung event lima tahunan; di AS demokrasi justru merupakan proses day-to-day politics, karena menyapa rakyat kebanyakan adalah tugas harian. Dari satu aspek ini saja, kita sudah bisa memperkirakan kualitas demokrasi aktual di AS terserak di dekat dengan kutub demokrasi ideal. Tak mengherankan, jika prakteknya menjadi rujukan dunia. Terlepas dari kekurangan yang melekat dalam implementasinya, demokrasi masih merupakan konsep politik yang baik; setidaknya dalam kapasitasnya membentuk pemerintahan yang responsible dan akuntabel kepada rakyat.
Wallahu’alam....
Advertisement