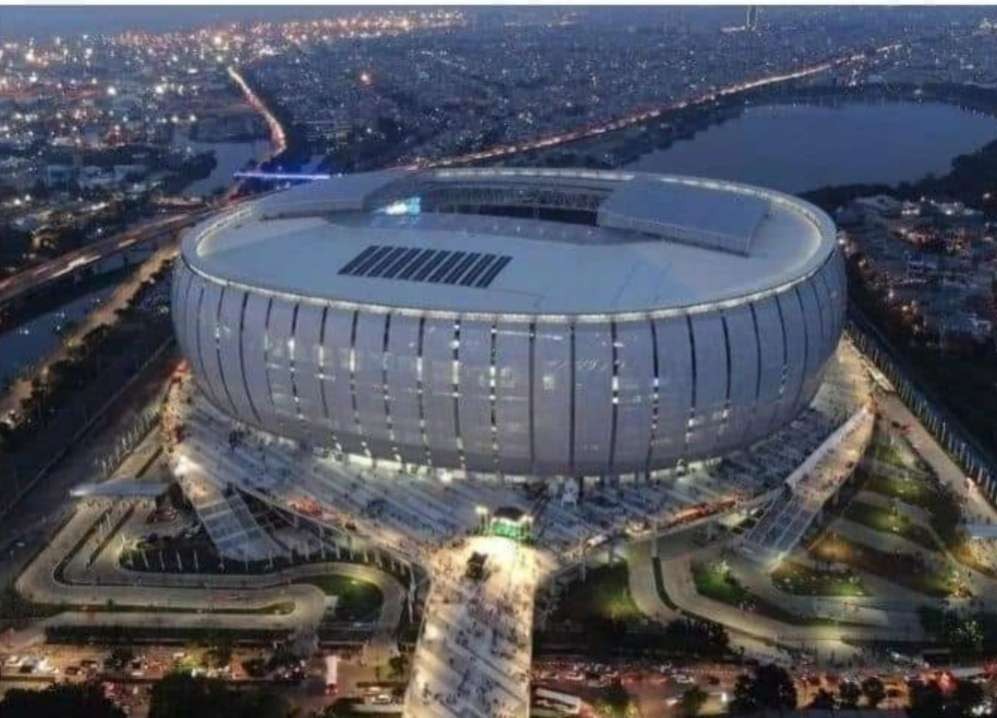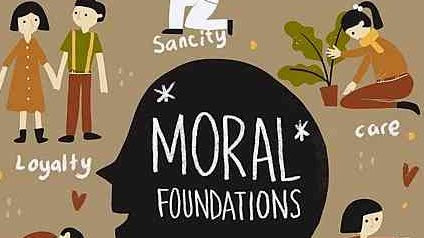Pancasila dan Penodaan Agama

Sila kesatu Pancasila, "Ketuhanan yang Mahaesa" mengandung pengertian bahwa negara menjunjung tinggi agama yang dianut oleh segenap bangsa Indonesia. Salah satu manifestasinya adalah negara menjaga dan memfasilatas peribadatan serta kegiatan sosial keagamaan umat beragama.
Negara juga melindungi agama dengan menerbitkan KUHP psl 156 (a) yang mengandung ancaman pidana kepada siapa pun yang memusuhi, menyalahgunakan dan menodai agama. Di samping itu pasal 156 b juga melarang seseorang mengajak orang lain untuk menjadi atheis.
Perlindungan terhadap agama itu sudah ada sejak era Presiden pertama RI Sukarno berupa UU PNPS tahun 1965 yang ditetapkan pada 26 Januari 1965. Bahkan di dalam UU PNPS tersebut juga memasukkan aturan yang melarang mengajak orang lain untuk menjadi atheis.
Di negara demokrasi Barat (Liberalisme), tidak ada UU tentang perlindungan agama. Kebebasan beragama dimaknai bahwa setiap orang boleh beragama atau tidak beragama serta agama dianggap sebagai masalah pribadi. Bahkan, melakukan penodaan suatu agama (blashphamy) juga tidak bisa dijerat hukum. Misalnya seseorang dengan sengaja menginjak kitab suci dianggap tidak melanggar hukum.
Di negara kita yang berdasarkan Pancasila, tidak sedikit mereka khususnya kaum intelektual yang memaknai demokrasi kita sama dengan demokrasi Barat, sehingga mempersoalkan pasal 156 KUHP. Pada intinya mereka ingin memfotokopi liberalisme dan menolak negara mengurusi agama karena dianggap “urusan individu" dan bukan urusan publik.
Lupa Esensi Demokrasi
Mereka lupa bahwa esensi demokrasi adalah sama yaitu liberty (kebebasan), fraternity (persaudaraan); equality (persamaan). Namun penerapan sistem demokrasi antara satu negara dengan negara lain tidak sama, karena nilai budaya yang berbeda. Penerapan demokrasi Indonesia tidak harus sama dengan demokrasi Amerika Serikat. Di AS semua orang bebas memiliki senjata api meniru para cowboy yang merebut tanah dari tangan suku Indian dengan senjata api. Kita sebaliknya, sedikit yang memerlukan senjata api karena kita pernah menjadi (sasaran) agressor.
Sejarah lahirnya sistem pemerintahan demokrasi pada abad pertengahan berawal dari perang agama di Eropa Barat (1618 - 1648) antara kaum reformis (Protestan ) versus kaum status quo (Katolik) yang pada akhirnya mengakhiri kekuasaan politik gereja Katolik Roma. Muncullah doktrin pemisahan agama dari politik atau lebih dikenal dengan “sekularisme".
Di Indonesia tidak pernah terjadi perang agama dan penyebaran agama sejak dahulu kala berlangsung secara damai. Dan sejak dahulu kala bangsa Indonesia terkenal bangsa yang religius. Oleh karena itulah, para pendiri Republik ini menyepakati secara bulat Pancasila sebagai dasar negara dengan Sila pertama “Ketuhanan yang Mahaesa". Artinya agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi bangsa Indonesia.
Secara umum dasar budaya kita adalah toleran khususnya toleransi dalam kehidupan beragama, Di kota saya, Kudus, Mesjid Aqsha (Mesjid Menara) berjarak hanya kurang lebih 300 atau 400 m dari kelenteng yang dibangun pada era tahun 1500 M. Bahkan, penulis Amerika terkenal Alfred Stephan menyimpulkan bahwa di negara Pancasila berlaku “twin toleration" atau “toleransi kembar". Negara menoleransi agama dengan melindungi dan mendukung kehidupan beragama, sebaliknya agama (Islam yang mayoritas ) tidak memaksakan syariat Islam sebagai hukum formal.
Para pendiri Republik Indonesia telah mewarisian ideologi negara yang visioner yang bisa berlaku universal atau model ideologi yang bisa menjadi rujukan dalam membangun hubungan antarbangsa yang damai. Dari Pancasila itulah, saya mendengar Kiai Ali Maksum (almaghfurlah) pada 1970 di gedung Sono Budoyo Yogya apa yang kemudian dengan Trilogi Persaudaraan (Ukhuwah) yaitu “Ukhuwah Islamiyah - Ukhuwah Wathaniyah - Ikhuwah Insaniyah".
DR KH As'ad Said Ali
Mantan Wakil Kepala BIN, Pengamat sosial politik, Mustasyar PBNU periode 2022-2027. Tinggal di Jakarta.

Advertisement