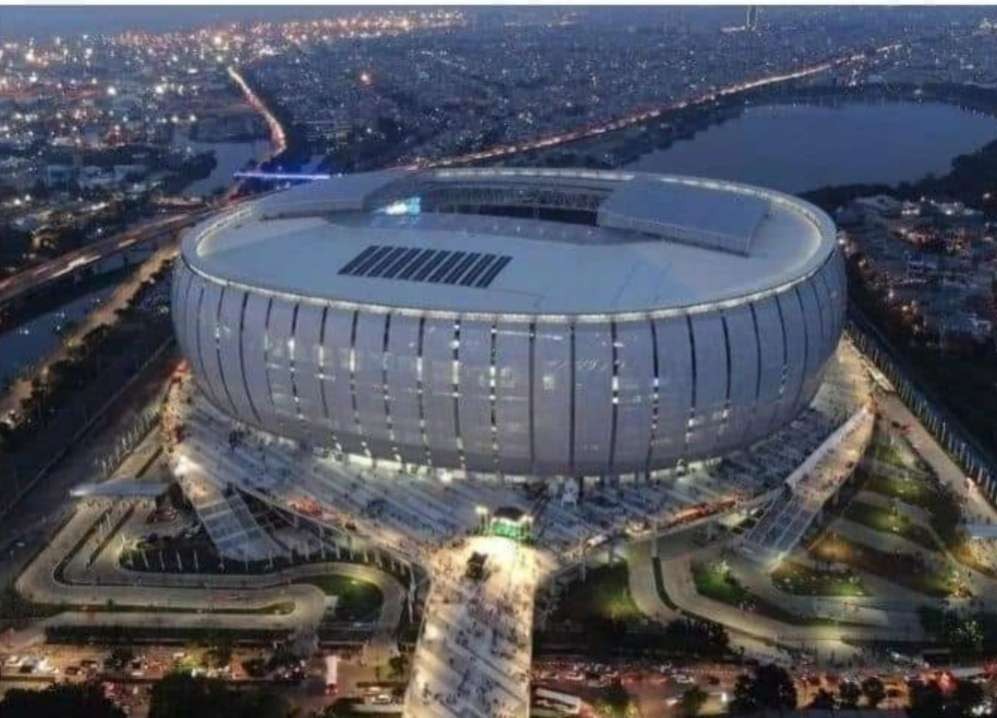Palestina: Kemanusiaan, Dukungan, dan Perdebatan Teoritis

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember
Artikel saya bertajuk “Palestina: Apa Yang Berubah?” mendapatkan banyak responsi. Di antaranya, terdapat tiga komentar yang mengandung pertanyaan. Profesor Bambang Kuswandi, seorang scientist, bertanya: “Dunia tak berdaya menghadapi kekejaman Israel, kira-kira jalan keluarnya bagaimana? Sekedar dukungan terhadap Palestina seperti yang selama ini ada nampaknya kurang terlihat dampaknya tanpa good will dari negara besar yang mendukung Israel yang selama ini seolah utopia belaka”.
Sementara itu, Dr. Aries Harianto, seorang pakar hukum, berkomentar: “Hipotesa filsafati tentang humanisme tengah diuji. Mendukung Palestina halal, membenci Israel tidak haram. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah kemanusiaan sebagai kurban dalam dua negara yang bertikai. [Apakah] kemanusiaan [merupakan] template baru peradaban dunia?”. Selain itu, Tonny Dian Effendi MA, seorang PhD Candidate ilmu Politik di Sun Yat-sen University, Taiwan; juga bertanya: “Bagaimana memisahkan ide politik dan agama dalam kasus Palestina ini. Di Indonesia tampaknya narasi agama lebih kuat daripada narasi politik”.
Memang, agak susah menjawab ketiga pertanyaan di atas. Setidaknya, tidak mudah merumuskan clear-cut answers (jawaban-jawaban yang jelas). Alasannya, permasalahan Palestina begitu kompleks. Selain melibatkan faktor internal dan eksternal Palestina, dimensi-dimensi konfliknya dengan Israel juga berjalin berkelindan. Akibatnya, tidaklah mengherankan jika berbagai komentar, penilaian, dan tawaran solusi yang muncul cukup beragam. Bahkan, mereka kadang saling bertentangan. Untuk memudahkan dalam mengurainya, saya merasa perlu meletakkannya dalam peta teoritis.
Namun, apakah berbagai pertanyaan di atas masih relevan? Pasalnya, Hamas dan Israel telah menyepakati genjatan senjata selama empat hari sejak Jum’at (24/11/23). Saya berpendapat pertanyaan tersebut masih tetap relevan, karena kesepakatan genjatan senjata bersifat sementara, terutama untuk pertukaran sandera. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, justru telah bersumpah untuk akan tetap melanjutkan perang guna mengeliminasi Hamas.
Artikel saya memang berangkat dari perspektif teoritis. Titik tolaknya, dua ‘pembelokan’ teorisasi hubungan internasional kontemporer, yakni ‘pembelokan Kritis’ (Critical turn) dan ‘pembelokan Normatif’ (Normative turn). Inti keduanya adalah kembali menambatkan diri pada validitas asumsi teori Kritis dan teori Normatif. Dalam konteks ini, ajakan saya untuk terus mendukung Palestina, apapun bentuknya, bukanlah sekedar aksi solidaritas. Tapi, sebuah langkah sadar berdasar realitas. Fondasinya, optimisme yang dilandasi transformasi atau ‘proses keberadaban’ (civilizing process) komunitas global, seiring dengan semakin meluasnya adopsi nilai-nilai kemanusiaan.
Pandangan Profesor Bambang Kuswandi tentang pentingnya “good will dari negara besar” dalam penyelesaian Palestina kurang lebih mencerminkan pandangan teori neo-Realis. Asumsinya, penjelasan isu-isu sentral politik dunia, seperti perang, konflik, perdamaian, dan kerjasama, ditentukan oleh konfigurasi kekuatan dalam sistem internasional. Ungkapannya bahwa dukungan terhadap Palestina “seolah utopia belaka” jelas merefleksikan perspektif neo-Realis. Randall L. Schweller, seorang neo-Realis, mengkritik teori Kritis dengan menggambarkannya sebagai ‘dreaming of the impossible dream” (bermimpi tentang mimpi yang tidak mungkin” menganggapnya sebagai “fantasy theory”.
Realisme varian neo-Realisme ini memang telah menunjukkan daya eksplanatif (explanatory power) yang koheren, elegan, dan kuat. Salah satu alasannya, perspektif ini mempunyai tolok ukur (measurements) yang jelas. Tapi, neo-Realis bukanlah satu-satunya teori yang mampu menjelaskan fenomena global kontemporer. Sejauh ini, untuk penyelesaian Palestina signifikansi peranan negara besar masih juga sekedar ‘utopia’. Apalagi, pertanyaan mendasar juga menyasar: Apakah mungkin perubahan radikal politik negara bisa terjadi tanpa perubahan sifat dan sikap manusianya?
Pertanyaan terakhir di atas merupakan titik keberangkatan teori Normatif, yang esensinya berbasis teori Kritis. Perspektif ini bukanlah sebuah fantasy theory. Asumsinya, sebuah teori harus bersifat ‘praksis’, sekaligus emansipatoris. Posisinya inheren dalam struktur sosial aktual dan konflik sosial faktual, berfokus pada politik perlawanan terhadap berbagai bentuk penindasan terhadap suatu komunitas, dengan senantiasa berupaya menegakkan hak-hak dasarnya. Jadi, transformasi komunitas politik global menuju terbentuknya dunia yang dicita-citakan, termasuk penyelesaian krisis Palestina, bukanlah visi yang akan terwujud tanpa aksi perjuangan. Dalam hal ini, visi dan aksi untuk meraih cita merupakan suatu proses kontinum: a process of becoming!
Penjelasan terakhir di atas, menyediakan konteks bagi komentar Dr. Aries Harianto: ”Hipotesa filsafati tentang humanisme tengah diuji”. Tapi, pandangan saya sedikit berbeda. Dalam hubungan internasional humanisme bukan “tengah diuji” diuji, melainkan relatif “telah teruji”. Norbert Elias (1998) menegaskan bahwa a civilizing proses di Eropa telah berhasil melembagakan berbagai hak-hak dasar manusia, seperti self-determination dan HAM. Sementara itu, Norman Geras juga menggarisbawahi, bahwa kini sangat sulit menghentikan berbagai gerakan perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan, seperti ketidaksetaraan gender, diskriminasi ras, penindasan etnis, dan eksklusi pengungsi.
Secara empiris, transformasi civilizing process semakin deras melanda komunitas global, termasuk sikap terhadap Palestina. Seperti dilansir Rami Khouri, jurnalis kawakan Timur Tengah, meski pelan tapi pasti, kalangan media AS mulai kritis terhadap informasi konflik Israel-Palestina. Menyadari bahwa kini mereka melayani masyarakat yang kritis, media AS tidak lagi menerima begitu saja klaim Israel tentang perangnya terhadap Palestina. Setelah melihat berbagai penindasan Israel terhadap Palestina, Black Lives Matters, sebuah gerakan yang memperjuangkan keadilan sosial; juga telah mencabut sikapnya yang semula pro-Israel dengan menegaskan sikapnya untuk mendukung Palestina.
Pada level individu, empati dan peduli berlandaskan humanisme juga merebak. Aktris Melissa Barrera, misalnya, tidak peduli disingkirkan dari proyek Scream VII setelah lantang membela Palestina. “Diam bukanlah pilihan bagiku!”, tegasnya. Begitupun Reham Hamed, seorang warganegara Mesir, tetap kekeuh berpartisipasi dalam gerakan boikot terhadap produk Israel dan para pendukungnya. Kepada Reuters ia mengatakan: “meski saya tahu [tindakan boikot] ini tidak akan berdampak besar pada perang, setidaknya sebagai warga negara [Mesir] tindakan ini yang bisa saya lakukan agar tidak merasa tangan saya berlumuran darah".
Ironisnya, di tengah maraknya kepedulian lintas negara; tanggung jawab terhadap keselamatan negara seringkali masih dianggap lebih besar dibandingkan tanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat sipil. Padahal, menurut Andrew Linklater, kekuatan negara yang luar biasa tapi diekspresikan dalam perang total dan genosida, seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina, pada dasarnya merupakan ‘sisi gelap dari modernitas’ (the dark side of modernity). Pada konteks inilah reaksi kritis gerakan masyarakat global terhadap keangkuhan negara bisa dimaklumi, termasuk angkara murka yang sedang menimpa rakyat Palestina. Dunia setidaknya perlu menyeimbangkan tanggung jawab terhadap keselamatan baik terhadap negara dan masyarakat sipil.
Fenomena kosmopolitan di atas, secara apik digambarkan Andrew Linklater dalam narasi teoritisnya. Sebagai seorang teoritisi Kritis, ia berhasil mendamaikan ketegangan konseptual antara ‘kepatuhan sebagai warga negara’ dan ‘kepedulian sebagai warga dunia’; dengan menggaungkan konsep Jurgen Habermas tentang Post-national Community. Dalam konteks inilah, pengamatan Tonny Dian Effendi, MA., menemukan tambatannya. Ia menegaskan bahwa dalam konteks Palestina: “Di Indonesia, tampaknya narasi agama lebih kuat daripada narasi politik”. Kepedulian berdasar kesamaan agama ini dapatlah dimaklumi, mengingat 99% penduduk Palestina adalah muslim. Apalagi, Islam punya konsep ‘ummat’ yang esensinya merupakan konsep transnasional yang sifat kepeduliannya juga mencerminkan konsep Post-national Community. Wallahu’alam …
Advertisement