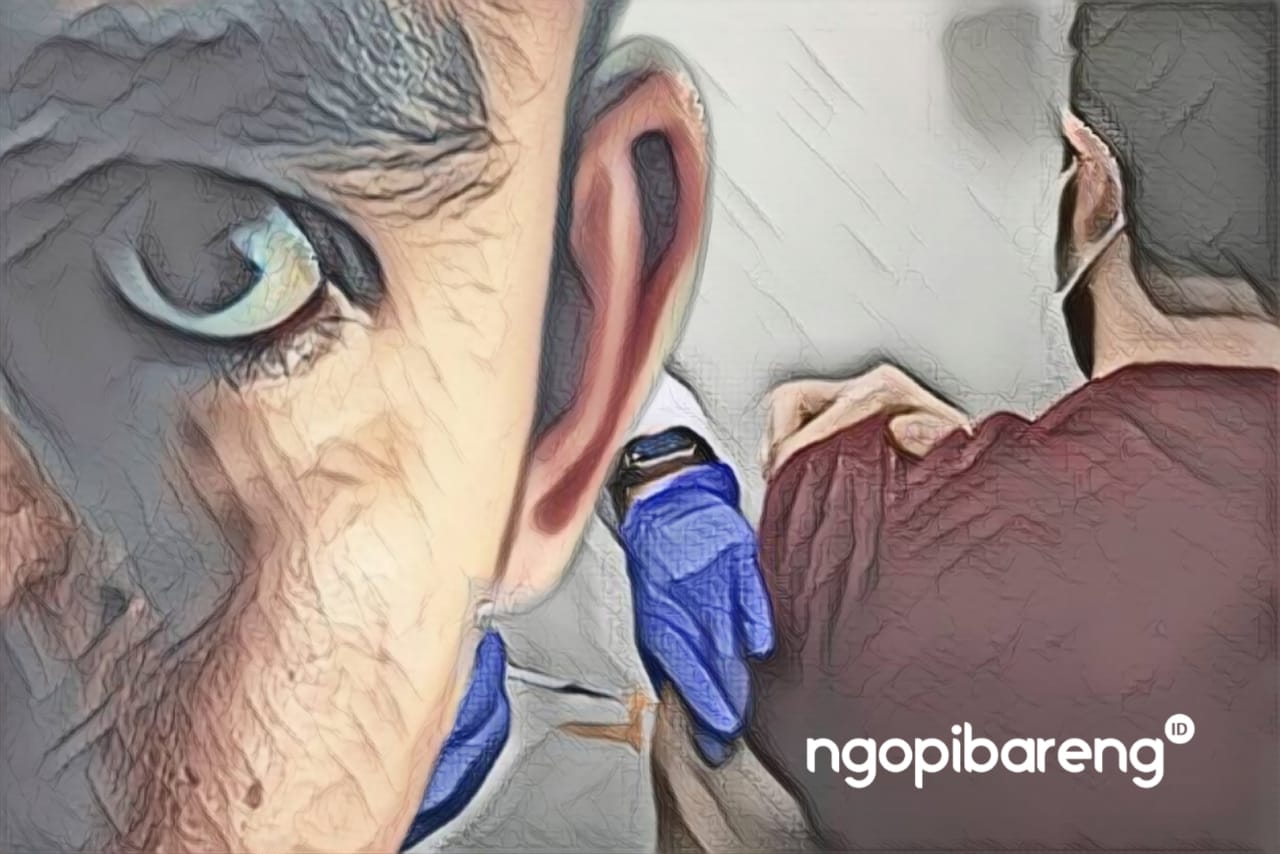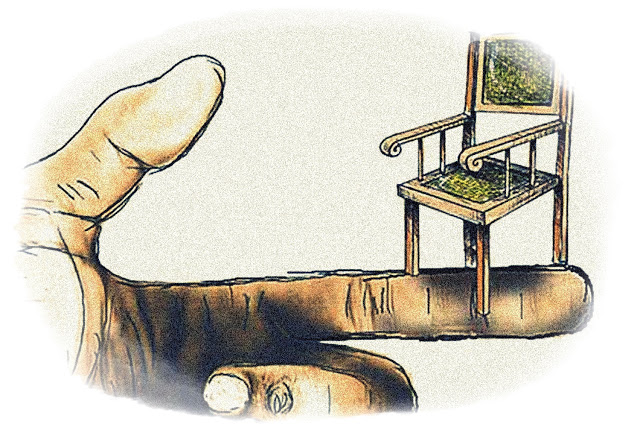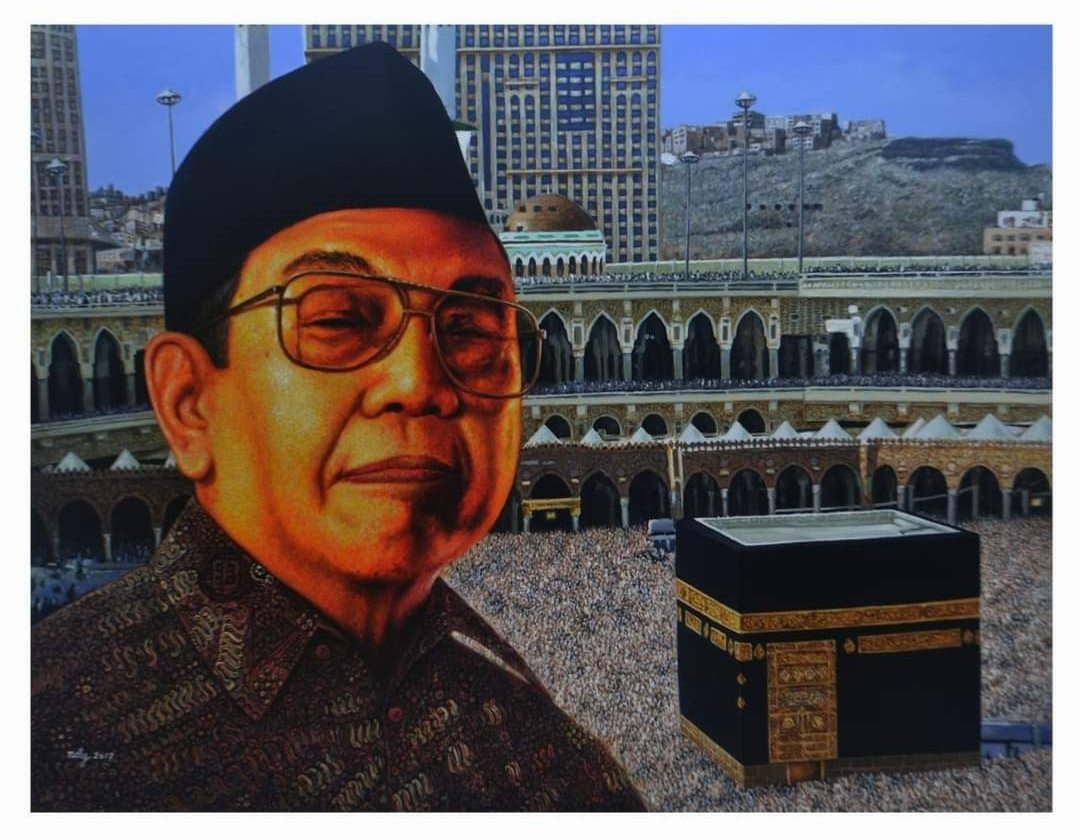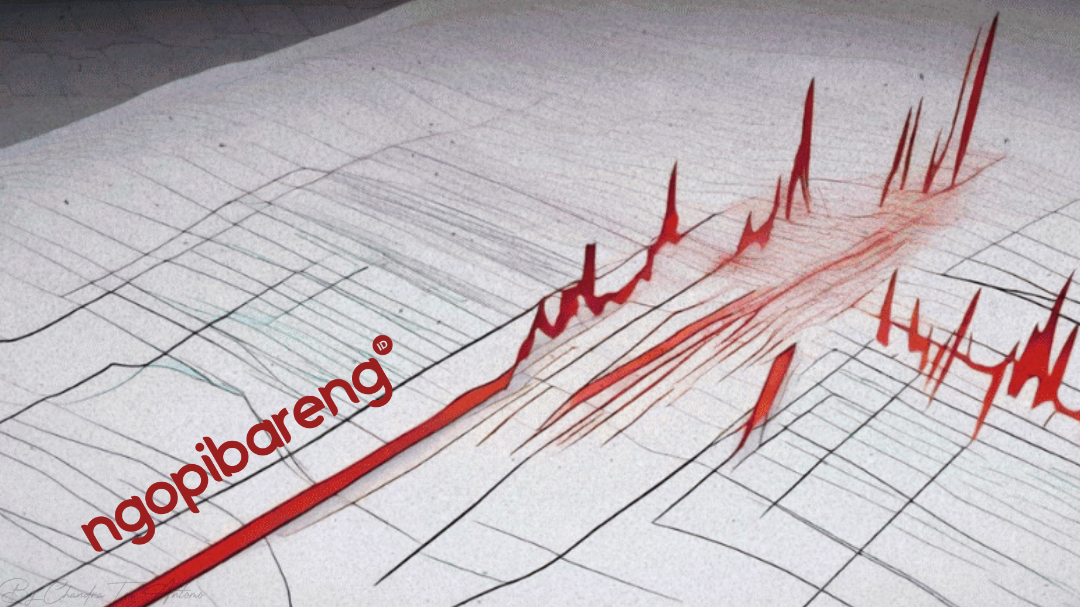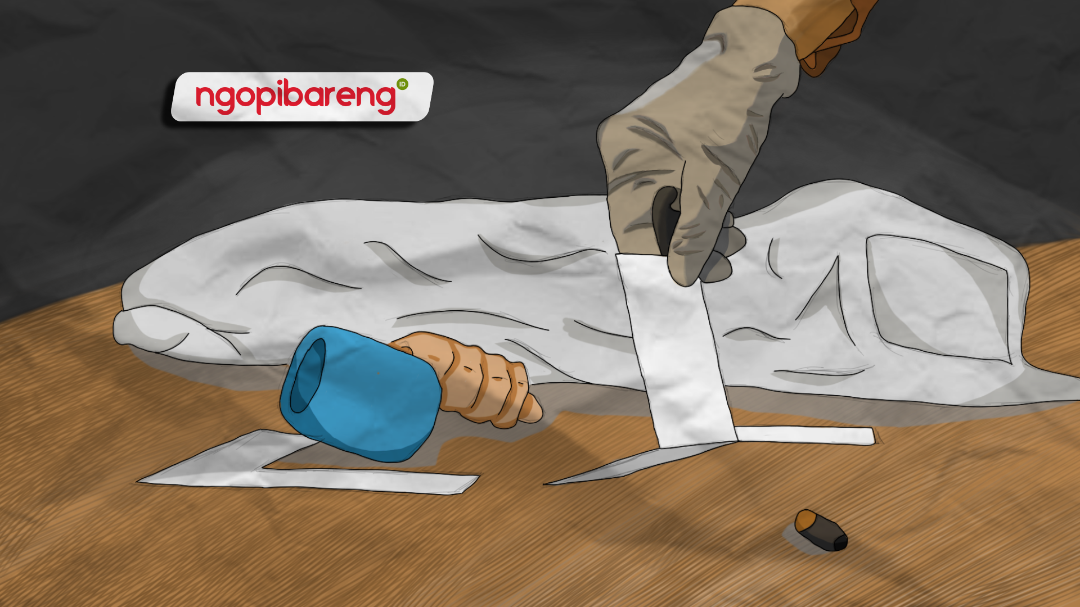Narasi Kebencian di Tengah Pendemi (3) Subur di Era Refomasi

Reformasi berkah bagi banyak orang. Juga sekaligus menjadi momentum berkembang pesatnya kelompok Islam formalis.
Kanal-kanal yang di era Pak Harto tertutup rapat, di era reformasi terbuka lebar. B.J. Habibie, presiden pertama di era ini, menampilkan gaya kepemimpinan baru yang memberikan harapan ke semua anak bangsa. Dia jauh beda dengan mentornya; Pak Harto. Habibie lebih egaliter dan demokratis.
Di era kepemimpinan Habibie ini, krisis ekonomi belum reda. Tapi lumayan membaik. Paling tidak jaman ini, kurs rupiah atas dollar AS yang sempat mencapai kurs terendah Rp17 ribu, naik menjadi Rp6.500. Ini prestasi yang luar biasa.
Naiknya nilai tukar rupiah atas dollar As, pelan-pelan menjadikan perekonomian Indonesia juga membaik. Ini menjadi berkah bagi semua. Siapa pun berpeluang untuk maju. Yang penting mau bekerja keras dan memiliki ketrampilan memadai.
Situasi itu, jelas beda jauh dengan di era Soeharto. Di mana ekonomi masih dimonopoli beberapa orang –termasuk anak-anak Pak Harto.
Kelompok Islam formalis adalah kelompok yang sangat siap dengan perubahan itu. Sebab, mereka sudah bersemai sejak era 90-an. Artinya, sudah sekitar 10 tahunan berproses. Sehingga, mereka langsung move on. Langsung bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik. Sebagian dari mereka, dengan cepat menjadi pelaku-pelaku usaha yang sukses.
Sektor-sektor pemerintahan juga bisa mereka isi. Mereka yang dulu aktif di kajian-kajian Islam di kampus, kini siap menjadi birokrat-birokrat di pemerintahan.
Demikian juga dengan peluang di perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN). Mereka pun terlihat sangat siap mengisi. Baik dalam arti ketrampilan, maupun dalam arti jumlah sumber daya manusia (SDM).
Di pihak lain, orang-orang kultural (pesantren) terlihat gagap. Mereka yang selama era Soeharto (30 tahun lebih) dibonsai, tidak memiliki kesiapan untuk menangkap peluang tersebut. Secara kuantitas, mereka tetap mayoritas. Namun, minim kemampuan. Meraka kurang terlatih untuk main di tengah gelanggang.
Yang pasti, terbukanya peluang di era reformasi ini, berimbas kepada meningkatnya jumlah kelas menengah muslim. Kelas menengah dalam arti ekonomi, juga pendidikan. Mereka yang sebelumnya berada di strata rendah, di era reformasi ini mampu memperbaiki diri menjadi kelas menengah.
Dan lagi-lagi, yang mengalami peningkatan strata itu mayoritas adalah kelompok Islam formalis. Ini tentu terkait dengan kesiapan mereka untuk move on tadi.
Sedang kelompok kultural, mayoritas stagnan di stratanya. Bila ada yang ikut arus “move on”, jumlahnya sangat sedikit. Atau mereka yang sudah ikut gelombang pemikiran dari kultural ke formalis.
Dengan cepat, kelas menengah muslim ini membangun peradaban baru yang bercirikan Islam formalis. Sekolah-sekolah Islam terpadu bermunculan bak jamur di musim penghujan. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah-sekolah ini cepat menjadi primadona masyarakat –khususnya kelas menengah—untuk menyekolahkan anaknya. Biaya mahal yang dibadrol, tidak menjadi persoalan.
Pemakaian jilbab bagi perempuan juga menjadi trend baru. Di era Soeharto, sempat ada peristiwa, gara-gara ingin mengenakan hijab saat sekolah, seorang pelajar harus menempuh jalur hukum. Namun di era reformasi ini, pemakaian hijab di kalangan pelajar malah menjadi trend. Hampir semua pelajar, baik sekolah di negeri atau swasta, mayoritas berhijab.
Imbas dari tend berbusana muslim ini, maka era reformasi ini salah satunya ditandai dengan bangkitnya perusahaan-perusahaan konveksi busana muslim. Dan lagi-lagi, kelompok Islam formalislah yang lebih siap menangkap peluang tersebut.
Positif! Perubahan itu, tentu berdampak positif bagi performa umat Islam Indonesia. Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini, menjadi terlihat hijau royo-royo. Simbul-simbul Islam, seperti masjid atau musholla tidak aneh lagi bila bertengger di depan kantor pemerintah. Stasiun televisi, juga tidak alergi lagi menayangkan program-program yang bernuansa Islam.
Itu berkah yang harus disyukuri umat Islam. Saya pun senang. Namun, seiring dengan itu, pemikiran-pemikiran formalis pun menjadi semakin menguat. Pendekatan kultural ala Walisongo yang sudah ratusan tahun dipraktekkan di nusantara, pelan-pelan terdesak. Bentuk negara NKRI yang semula dianggap final, kembali diperbicangkan. Kelompok formalis lebih condong bentuk negara Islam.
Di sinilah, titik persoalan seriusnya. Perdebatan lama yang sudah ditutup oleh para pendiri bangsa dengan sangat elegan, kini dibuka lagi. Politik identitas kembali muncul. Ketika menjelang pemilu 1999 Habibie head to head dengan Megawati, maka politik yang dikembangkan adalah politik identitas. Muslim non muslim.
Situasi ini, menjadikan eskalasi suhu politik meningkat. Sebagian pengamat sudah mendefisikan Indonesia di jurang perpecahan. Kondisi ini, semakin genting ketika pada sidang umum MPR 14 Oktober 1999, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak. Dengan begitu, Habibie kehilangan peluang untuk head to head dengan Megawati.
Ini masalah serius. Penolakan dari kelompok Islam formalis atas sosok Mega sudah mengkristal. Nah, di tengah kebuntuan ini, Gus Dur akhirnya dijadikan solusi oleh “Poros Tengah” yang dimotori Amien Rais. Gus Dur dinilai sebagai sosok yang bisa diterima kelompok Islam, juga kelompok di luar Islam.
Namun, Gus Dur tidak lama diperankan sebagai solusi. Ini karena selain adanya kepentingan-kepentingan pragmatis para politisi, pandangan keislaman Gus Dur juga tidak sejalan dengan kelompok formalis. Gus Dur yang berakar dari pesantren, tetap kukuh mengambil jalur kultural. Gus Dur menyuburkan berkembangnya nilai-nilai toleransi. Secara mengejutkan, warga Tionghoa diperbolehkan merayakan Imlek. Bahkan, hari raya ini dijadikan hari libur nasional.
Ini jelas problem serius bagi kalangan Islam formalis. Periode pemerintahan Gus Dur pun akhirnya “the end”. Gus Dur dipaksa meninggalkan istana.
Kelompok Islam formalis mendapat momentum luar biasa di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka sukses masuk dalam barisan pemerintahan. SBY yang mestinya berpeforma layaknya Soeharto –Islam abangan/bukan santri--teryata memilih berkawan dengan kelompok Islam formalis. SBY menerapkan hubungan politik mutualisme. Pilihan politik ini berbuah pada stabilitas politik pemerintahan SBY selama 10 tahun. SBY tidak benturan dengan kelompok Islam formalis.
Persoalan muncul ketika pada pilpres 2014, Jokowi menang pemilu menggantikan SBY. Jokowi adalah muslim abangan, namun memiliki kedekatan dengan kelompok Islam kultural. Jokowi memiliki rekam jejak istimewa. Dia dianggap sukses menorehkan tinta emas ketika menjadi Wali Kota Solo. Demikian juga ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun.
Lain dengan SBY, ternyata Jokowi memilih tidak berkawan dengan kelompok Islam formalis. Dengan popularitas yang tinggi dan dukungan politik yang kuat, Jokowi berani mengambil keputusan-keputusan fundamental. HTI yang aktif mengusung khilafah dibubarkan. Belakangan yang terbaru, Jokowi juga tidak menerbitkan ijin bagi FPI. Aktivitas FPI dilarang. Puluhan rekening FPI diblokir.
Nah, menurut saya, berakar dari konstelasi yang demikian itulah akhirnya narasi kebencian begitu marak menyertai perjalanan pemerintahan Jokowi. Tidak terkecuali, narasi kebencian yang berseliweran selama terjadi pandemic covid 19 ini.
Sampai detik ini, Jokowi kokoh tak tertandingi. Dia tetap terlihat tenang di tengah-tengah gempuran itu. Bahkan, dengan gayanya yang lugu dan kalem, Jokowi mampu memainkan irama politik yang smart.
Film belum tutup layar. Kelompok Islam formalis semakin keras melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi. Produksi narasi kebencian ditingkatkan. Hoak bertebaran di medsos. Masyarakat di akar rumput menjadi terombang-ambing dalam ketidakpastian. Dengan keterbatasan wawasan dan akses informasi yang akurat, masyarakat menjadi terbelah. Sebagian ikut arus pemikiran Islam formalis. Sebagian, tetap kukuh pada jalur kultural.
Inilah bahaya api dalam sekam, seperti yang saya sebut di tulisan seri 2. Sewaktu-waktu, bisa menjadi kobaran api yang membahayan. Karena itu, saya berharap semua komponen bangsa menyadari bahaya besar itu. Kemudian, berikhtiar bersama-sama mencari solusi sedini mungkin. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kehancuran yang menimpa beberapa negara di Timur Tengah, merembet ke negeri tercinta. (bersambung)
Akhmad Zaini
Mantan Jurnalis, kini menjadi pendidik di IAINU Tuban
Advertisement