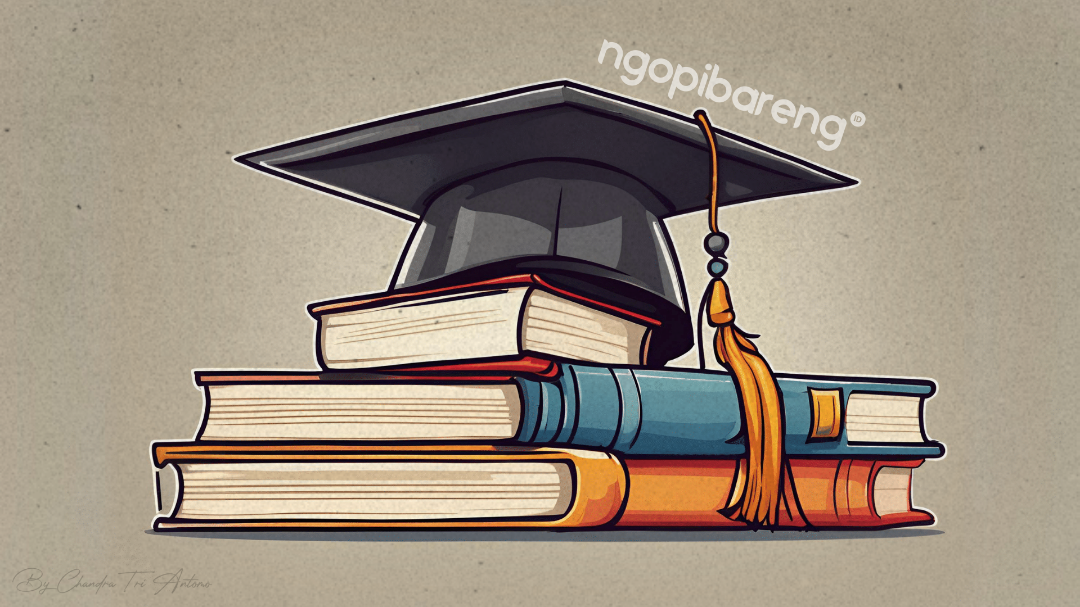Narasi Indonesia

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Sebingkai foto hitam putih menyita atensi saya. Meskipun agak kabur karena usia, guratannya masih tampak jelas. Foto itu mengabadikan sederet rumah tempo dulu di tepian sebuah sungai. “Itu potret desaku dahulu”, ujar kakak ipar yang berasal dari Kotabaru Reteh di kawasan pesisir Riau. "Tapi, kini desa itu sudah jauh berbeda”, tambahnya.
Dialog kecil ini menghardik saya untuk menyodorkan komparasi dua kisah yang berbeda berkaitan dengan meredupnya tradisi bahari di Indonesia. Sempat muncul argumen, bahwa meredupnya tradisi bahari dipicu kehancuran berbagai kerajaan maritim di Indonesia.
Tahun 2016, Mukhlis PaEni, sejarawan, mengatakan: “Sejak VOC (Kongsi Dagang Hindia Timur), dinamika kemaritiman dan tradisi besar maritim kita menghilang. Astronomi, undang-undang laut dan mitologi laut menjadi hilang”.
Misal, pasca perjanjian Bongaya tahun 1667 kehidupan bahari di Sulawesi selatan telah bergeser. Pasalnya, Belanda berhasil memaksa kesultanan Gowa dan rakyatnya menjauh dari laut dengan bertani. Bahkan, perkampungan pesisir diusir sampai 10 mil dari garis pantai dengan bangunan rumah yang membelakangi laut. “Ini rekayasa politik luar biasa. Ini memotong tradisi. Kita-pun berangsur jadi petani,” tambahnya.
Secara sosiologis, dampaknya sangat ironis. Sejak itu, dermaga dan galangan besar dibangun dan dikuasai Belanda, sedangkan rakyat hanya sebagai buruh di dalamnya.
Tapi, kisah di Sulawesi Selatan baru cerita sebagian. Kisah serupa, dengan sebab yang berbeda, juga terjadi di Sumatra. Kotabaru Reteh, hanyalah sebuah desa di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Namun, desa ini salah satu saksi penyintas zaman di tengah kegamangan Indonesia dalam mencari identitas.
Dulu, desa ini bersimpuh takzim di tepi sungai Reteh. Semua rumah menghadap sungai tersebut. Sejak kelahirannya, entah kapan, sungai Reteh merupakan halaman depan semua rumah warga. Bahkan, sungai ini merupakan wajah desa.
Selain sebagai jalur utama transportasi, sungai Reteh juga merupakan urat nadi perekonomian. Jaraknya dekat dengan muara. Tak pelak, warga lebih akrab dengan tradisi sungai dan bahari dari pada budaya darat.
Dahulu, untuk mudik, warga desa juga lebih memilih jalur laut melalui Jambi dari pada jalan darat. Alasannya, waktu tempuhnya lebih cepat. Untuk kebutuhan hidup warga sehari-hari, laut menjadi tumpuan. Budidaya darat seperti sayur-sayuran, hanya menyumbang sekitar 30 persen, selebihnya dipenuhi oleh produk sungai dan hasil laut.
Namun, orde Baru telah mengubah landscape Kotabaru Reteh. Kebijakan pembangunan memicu transformasi desa itu. Pembangunan prasarana darat membalik cara pandang warga terhadap dimensi dan urgensi ruang. Semua rumah yang sebelumnya menghadap sungai menjadi berbalik menghadap jalan raya.
Pembalikan ini mencerminkan revolusi pandangan tentang ruang: “Darat menjadi lebih bernilai dari sungai dan laut”. Sejak itu, sungai dan laut termangu sendu. Statusnya sebagai halaman muka dan wajah desa harus ditanggalkan. Sekarang, keduanya tak lebih dari sekadar halaman belakang.
Kisah rakyat Gowa dan cerita warga Kotabaru Reteh saling melengkapi, bahkan saling mengkonfirmasi, penjelasan tentang hilangnya budaya bahari di Indonesia. Yang perlu dicatat, dua fakta akibat yang sama tersebut dikarenakan sebab yang berbeda. Kisah hilangnya tradisi bahari di Gowa karena paksaan kolonial, sedangkan di Kotabaru Reteh disebabkan kealpaan negara.
Kisah Kotabaru Reteh merupakan lintas empiris perubahan orientasi pembanguan negara. Tapi, dalam prosesnya, pembangunan berjalan tanpa kompas identitas. Pasalnya, modernitas yang diusungnya bersifat parsial, sehingga menggerus identitas tradisional.
Syahdan, koreksi orientasi pembangunan dilakukan. Pada 20 Oktober 2014, Presiden Jokowi mengatakan: “Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk”. Maka, mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut pemberani”. Penegasan politik ini mengingatkan saya pada salah satu lagu kebanggaan masa kecil, “Nenek moyang kita orang pelaut”. Gubahan Ibu Sud tahun 1940 ini mencerminkan ekspresi folklore.
Keselarasan antara pernyataan politik Presiden dan lirik lagu ini bukan tanpa landasan. Salah satunya, adalah teori "Out of Taiwan". Postulatnya, nenek moyang kita adalah kaum Austronesia yang semula bermukim di kepulauan Pasifik barat. Mereka kemudian bermigrasi ke Nusantara dengan mengarungi laut.
Kelekatan dengan laut juga tercermin dalam berbagai jenis perahu tradisional, seperti terpahat dalam relief candi Borobudur. Jadi, sejak lama jiwa bahari telah menjadi bagian identitas diri Nusantara.
Dalam konteks ini, Presiden Jokowi, menegaskan: “Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus terus-menerus kita pulihkan dan kita kukuhkan, bukan melalui jargon-jargon kemaritiman semata, tetapi melalui kerja nyata di berbagai bidang”. Tak pelak, penegasan ini menghantar pada deklarasi Indonesia sebagai Poros Maritim dunia.
Walhasil, deklarasi Poros Maritim telah melahirkan visi lima pilar pemerintah. Lima pilar ini mencakup pembangunan budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas antar pulau, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim. Visi Poros Maritim ini memang telah mendorong beberapa kebijakan inovatif terhadap laut. Tapi, inkonsistensi terasa masih pekat mewarnai implementasi.
Tahun 2016, Menko Polhukam, Mahfud MD, menegaskan: “Persoalan kita sebenarnya adalah tidak adanya konsistensi dalam pelaksanaan atas haluan negara, karena selalu terjadi gangguan politik terhadap haluan yang ada”. Jadi, permasalahannya terletak pada level implementasi.
Secara empiris, sinyalemen Mahfud MD di atas mudah ditemui. Poros Maritim ternyata belum ada masterplan-nya. Pada tahun 2017, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengonfirmasi: "Tidak ada masterplan. Masterplan negara ya, bukan masterplan Kementerian. Saya kan tidak bisa suruh kementerian lain". Akibatnya, minim arahan dari kementerian lain terhadap program aksinya guna mendukung konsep Poros Maritim.
Tahun 2022, tim peneliti Gastrodiplomasi Universitas Jember, di mana saya termasuk anggotanya, mewawancarai Menparekraf, Sandiaga Uno. Kala tim bertanya mengapa sebagai negara maritim, semua ikon kuliner unggulan Indonesia justru berasal dari darat tanpa satu pun merepresentasikan laut? Menerima pertanyaan ini, Menparekraf sempat terhenyak, seakan baru menyadari ironi ini.
Selain itu, saya memandang Poros Maritim masih perlu landasan narasi yang lebih kokoh. Penguatan identitas maritim perlu mengadopsi diksi 'bahari'. Argumennya, menurut sejarawan AB Lapian, maknanya lebih kaya; karena isinya merupakan kombinasi unsur maritime (maritim) dan ancient (kuno) yang berjalan melintasi jaman hingga kini.
Tak pelak, bahari melatarbelakangi segenap aspek yang bersinggungan dengan kehidupan di laut, kisah-kisah perjuangan dan kerja sama, sebuah lakon yang mencakup pertukaran peran, representasi ragam sudut pandang, serta mencuatnya nama-nama yang tersohor (the background of all, plays of struggle and collaboration, a play of interchanging roles, points of view, and names).
Konsep bahari ini menyediakan kontekstualisasi histori yang berarti. Pasalnya, klaim “nenek moyang kita orang pelaut” menemukan tambatannya di bumi Nusantara. Di Aceh, misalnya, Laksamana Malahayati memimpin sekitar 2000 pasukan Inong Balee hasil tempaan akademi militer Kerajaan Aceh, Mahad Baitul Maqdis. Di bawah komandonya, armada laut Aceh menguasai pesisir dan Selat Malaka, serta mampu melawan armada Portugis dan Belanda. Di Ternate, Sultan Babullah (1570-1583), ditahbiskan sebagai Kapita Lao (penguasa laut), karena mampu membawahi 72 pulau.
Sementara di Tidore, terdapat Lufu Kie, ritual bahari yang lahir ratusan tahun lalu dan tetap lestari hingga kini. Dalam tradisi ini, Sultan Tidore setiap tahun berlayar keliling mengarungi wilayah laut guna menyapa rakyatnya yang tersebar di berbagai pulau. Singkatnya, diksi bahari akan memperkukuh narasi identitas sebagai negara maritim.
Namun, masih tersisa permasalahan yang lebih mendasar. Koreksi Presiden Jokowi atas orientasi pembangunan negara memicu perdebatan tentang identitas bangsa.
Penegasannya bahwa Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim mengundang pertanyaan. Mengingat fakta bahwa keunggulan Indonesia juga ada di daratan, bagaimana dengan sektor agraris? Apakah identitas Indonesia adalah negara maritim, negara agraris, atau keduanya? Dengan mengutip Antony Reid, Sri Margana, sejarawan UGM, pernah berargumen bahwa kedua identitas tersebut sama-sama penting. “Orang asing datang ke Indonesia bukan cari ikan di laut tapi mencari komoditas dari daratannya,” tegasnya.
Elaborasi ini mengingatkan kita, bahwa tanpa naungan narasi besar yang lebih komprehensif penegasan Presiden Jokowi di atas bisa mengesankan sebuah keputusan reaktif yang dapat menjebak Indonesia kembali pada parsialitas identitas.
Lantas, kita sampai pada pertanyaan pamungkas, apa naungan narasi besar identitas Indonesia yang lebih pantas? Pada hemat saya, jawaban yang pas adalah konsep Wawasan Nusantara. Dikukuhkan oleh United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada tahun 1982, konsep ini lebih komprehensif guna menaungi matra maritim dan matra darat sekaligus. AB Lapian, sekali lagi, menggarisbawahi bahwa prinsip archipelagic state di dalamnya harus dimaknai dengan pengertian bahari, dalam arti “bukan pulau yang dikelilingi laut, melainkan lautan utama yang bertaburan dengan banyak pulau”.
Pengertian ini mengandung makna bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan justru penyatu daratan. Dengan demikian, isi narasi besar identitas Indonesia tentang kesatuan laut dan daratan seharusnya bukan saja mencerminkan keterhubungan, tetapi juga mencakup keterikatan, bahkan ketergantungan, antara keduanya dengan dilandaskan pada nilai kesetaraan. Wallahu’alam …
*Penulis adalah dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember.
Advertisement