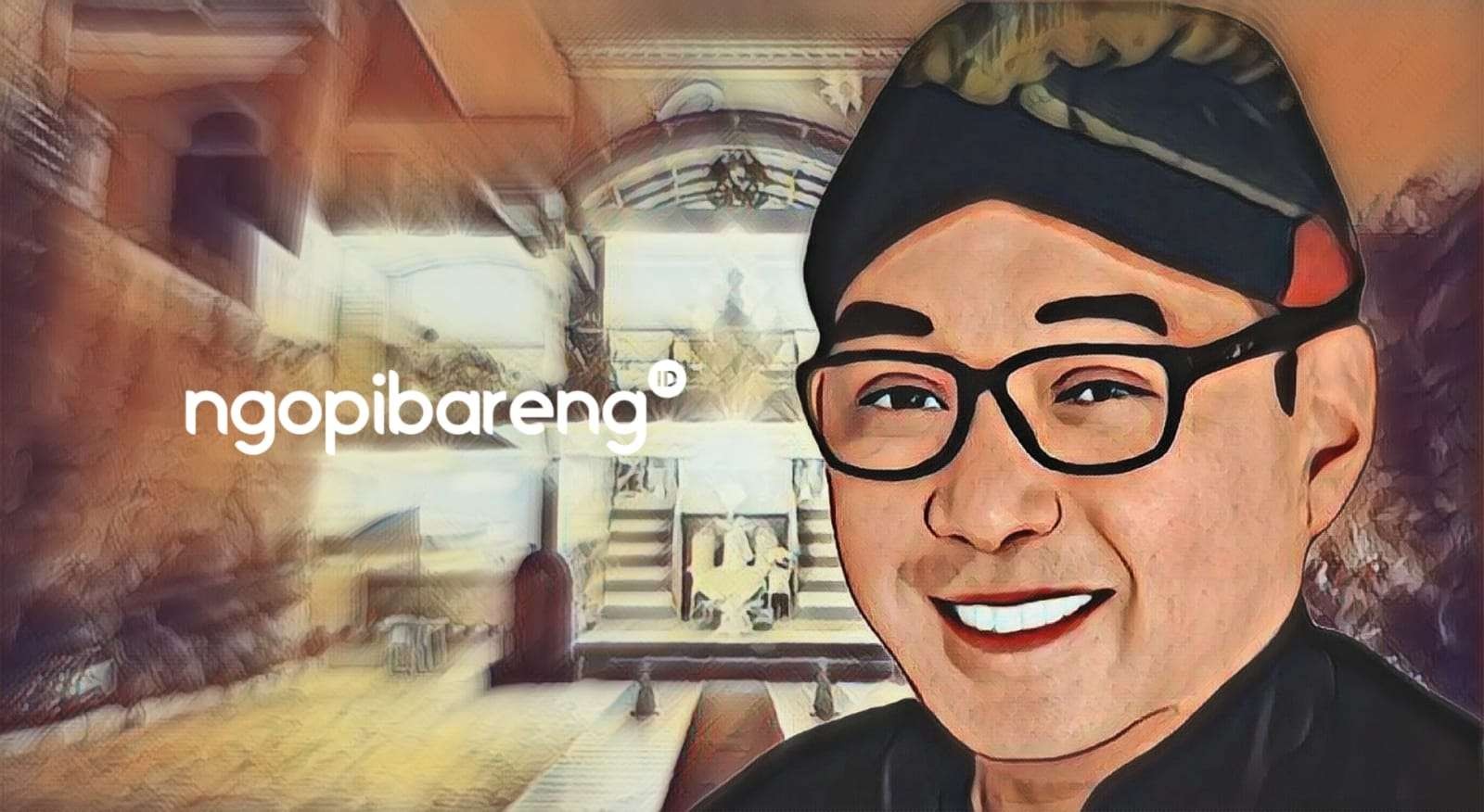Menolak Ideologisasi Riset

M. Faishal Aminuddin
Tahun 1660, John Evelyn memilih cuplikan kata “Nullius in Verba” dari puisi Horace dalam karyanya Epistles menjadi motto dari Royal Society, Inggris. Sekalipun lembaga itu milik kerajaan, namun para ilmuwan dan cendekia yang bekerja didalamnya bukanlah budak atau bawahan raja. Mereka bekerja sebagai insan yang memiliki pertanggungan jawab untuk mencari kebenaran ilmiah sekalipun harus berseberangan dengan kepentingan otoritas politik.
Lembaga riset milik negara memang sedianya diperuntukkan untuk menghadirkan berbagai temuan yang bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan. Meningkatkan kualitas peradaban dan memastikan segenap persoalan dan tantangan bagi spesies manusia bisa diberikan jawabannya. Sejarah juga mencatat, intervensi politik dalam lembaga yang berisi orang-orang bebas ini menghasilkan kerusakan. Kaiser Wilhem Institut yang didirikan oleh Kekaisaran Prussia pada tahun 1911, memaksa ahli kimia Fritz Harber untuk membuat gas sarin yang digunakan dalam perang Ypres kedua tahun 1915.
Bagi sebuah negara, memiliki lembaga riset adalah sebuah prestise yang menunjukkan sejauhmana komitmen dalam mempercayai sains sebagai pilar peradabannya. Perdebatan selanjutnya adalah, sejauhmana lembaga riset tersebut memiliki otonomi? Dimana harus meletakkan keberpihakan para cendekia atau ilmuwannya dalam konstelasi arah dan produk yang mereka hasilkan?
Komponen Kondisi Riset
Dalam laporan Global Competitivess 2019 yang dibuat oleh World Economic Forum, terdapat beberapa komponen yang bisa menggambarkan kondisi riset di Indonesia secara umum. Publikasi ilmiah berada di peringkat 56, paten 101, kontribusi lembaga riset 45 dan anggaran riset dan pengembangan berada pada urutan 116 dunia. Dari seluruh komponen, Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara yang dinilai. Kondisi ini membutuhkan respon yang sistematis dan berdasar pada persoalan riil yang dihadapi, bukan hanya oleh perguruan tinggi melainkan juga lembaga riset negara.
Riset yang bermutu membutuhkan biaya mahal meski itu bukan satu-satunya syarat. Masih ada berbagai variabel lain yang juga menentukan misalnya kesiapan dan kemampuan para ilmuwannya. Lalu dukungan untuk menunjang kinerja mereka yakni proses administrasi yang mudah dalam pemanfaatan dana riset.
Menciptakan atmosfer peer review yang kuat juga menjadi kunci bagi munculnya berbagai terobosan dan memastikan kualitas riset yang lebih baik dan diakui reputasinya.
Bagi pemerintah, riset haruslah dilihat sebagai sebuah investasi yang keuntungannya bisa diraih dalam jangka pendek atau jangka panjang. Kebijakan pemerintah yang meminta hasil riset dalam produk yang dihasilkan secara instan adalah hal yang justru tidak bijaksana. Dalam proses riset, terutama riset dasar, harus dibagi secara proporsional antara lembaga riset yang menghasilkan produk teoretik, hukum dan dalil serta formula tertentu. Tugas selanjutnya terletak pada lembaga lain atau perusahaan yang melakukan hilirisasi. Bisa untuk pengembangan bagi kepentingan strategis, militer, sampai produksi massal dalam bentuk produk siap pakai.
Dalam Science: The Endless Frontier (1945) yang ditulis oleh Vannevar Bush sebagai laporan kepada Presiden Roosevelt pasca Perang Dunia kedua, bisa diambil pelajaran penting. Sains harus menjadi perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan, standar hidup sampai keamanan. Bush menekankan bahwa investasi pada sains berorientasi pada masyarakat sebagai societal return daripada sekadar private return. Tidak mengherankan jika negara adidaya seperti Amerika Serikat, pemerintahnya sangat murah hati memberikan dana yang besar untuk riset dalam semua bidang. Riset-riset bermutu tinggi bisa dihasilkan oleh ilmuwan yang berada di kampus dan juga lembaga riset milik negara. Selain itu, dunia industrinya juga ringan tangan dalam berkolaborasi dengan universitas dan lembaga riset. Tradisi donasi dan filantropi para konglomerat dan dunia usahanya berakar kuat sampai hari ini.
Kebijakan pemerintah diperlukan untuk memastikan bahwa dengan pendanaan yang ada, muncul riset skala prioritas yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Setiap negara memiliki strategi yang berbeda-beda dalam hal ini. Cara mengukurnya bisa dilakukan dari yang sederhana sampai yang canggih. Minimal dengan melihat arah dan kecenderungan topik dan temuan publikasi ilmiah bereputasinya. Lalu seberapa efektif pendanaan yang sudah diberikan dalam mendorong lahirnya publikasi tersebut. Ini menjadi fase pertama.
Selanjutnya, melakukan identifikasi daya serap produk dan luaran dari hilirasi riset yang dilakukan tersebut memberikan dampak pada daya beli pasar. Hal ini untuk memastikan bahwa sebuah temuan atau produk benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Jepang memiliki strategi pendanaan riset yang efektif dengan mengalokasikan pendanaannya pada sektor-sektor hilirisasi yang menopang industrinya dalam bidang farmasi, kedokteran, teknologi dan manufaktur.
Bagaimanapun, riset bagus membutuhkan biaya mahal. Ketika aspek return of investment bisa dipastikan, maka terdapat perputaran uang yang bisa di reinvestasikan untuk membiayai riset lanjutan sekaligus untuk membiayai riset baru yang berorientasi pada aspek sosial atau ilmiah berjangka panjang.
Anggaran belanja riset kita tahun 2018 hanya 0.3 persen dari GDP. Negara-negara maju rata-rata diatas 2 persen. Jika dirupiahkan, belanja riset tahun 2019 hanya 35.7 Triliun yang disebar ke 45 kementerian dan lembaga riset. Dari angka tersebut hanya 43 persen yang digunakan untuk belanja riset dimana komponen yang paling besar untuk biaya operasional dan honor. Dunia industri hanya menyumbang 10 persen dimana dana pemerintah masih menyumbang 66 persen total anggaran riset nasional. Indonesia pada akhirnya tertinggal jauh.
Tiga Hal Penting Harus Dipastikan Pemerintah
Pemerintah perlu memastikan setidaknya tiga hal penting. Pertama, mempertinggi komitmen belanja riset yang bersumber dari anggaran negara dan meminta dunia industri berperan lebih besar dengan pengaturan skema keuntungan yang adil. Kedua, memberikan otonomi yang lebih besar bagi universitas dan lembaga riset dalam mengembangkan dirinya serta melakukan restrukturisasi pada aspek administrasi dan birokrasi yang membuat kerja-kerja riset lamban. Ketiga, menetapkan cetak biru arah riset ilmu dasar jangka panjang yang sepenuhnya dibiayai negara dan strategi turunan untuk riset jangka pendek yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pasar.
Akhir-akhir ini, muncul kontroversi atas pengangkatan mantan presiden Megawati sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Juga diikuti dengan reorganisasi BRIN melalui Perpres No. 33 tahun 2021 dimana BRIN menjadi satu-satunya badan penelitian nasional. Sebenarnya hal itu tidak perlu dipersoalkan terlalu jauh. Sekalipun memantik kritik seperti bagaimana mungkin lembaga riset diarahkan oleh politisi, bukan ilmuwan? Sepanjang posisi para politisi atau figur-figur nonilmuwan adalah sebatas patron yang memberikan dukungan dan jaminan atas kontribusi pemerintah dalam peningkatan anggaran riset, dan memastikan terselenggaranya proses riset yang sesuai standar, maka keberadaan mereka malah berjasa.
Pemilihan patron dalam lembaga riset adalah hal lumrah. Sebaliknya, jika figur nonilmuwan itu memaksakan ideologisasi politik yang mengintervensi lembaga riset, maka itu jadi hal buruk. Jika otoritas politik terlibat dalam mendikte bahkan menempatkan para ilmuwan didalam lembaga riset sebagai kliennya, maka tidak ada otonomi disana. Ini sama artinya menundukkan sains dibawah supremasi politik. Sains tidak bisa lagi menjadi penunjuk jalan bagi kemajuan peradaban karena dia menjadi alat untuk memenuhi selera dan kepentingan politik.
M. Faishal Aminuddin
Penulis adalah Wakil Dekan bidang Akademik FISIP Universitas Brawijaya. Doktor Ilmu Politik dari Universitas Heidelberg, Jerman.
Advertisement