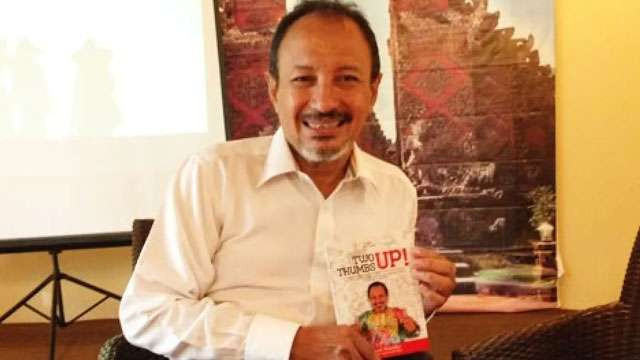Menilik Film Tilik

Di luar kelaziman saya menjumpai tagar Bu Tejo (#Bu Tejo) tengah viral di jagat Twitter. Galibnya, jagat Twitter dipenuhi oleh kegaduhan politik, skandal artis, promosi single atau album musik terbaru, perang antarfans dan seterusnya. Sontak kepala saya digelayuti pertanyaan: Siapakah gerangan Bu Tejo yang viral itu? Saya baru teringat rupanya Bu Tejo adalah salah satu karakter dalam film pendek Tilik (Menjenguk) besutan Wahyu Agung Prasetyo dan skenarionya ditulis oleh Bagus Sumartono. Diproduksi oleh Ravacana Films dan didukung oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Disbud DIY), Tilik pertama kali dipertunjukkan pada perhelatan Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2018.
Tak pelak, tagar Bu Tejo yang viral itu menggelembungkan jumlah penonton film Tilik di kanal YouTube setelah sebelumnya ditayangkan TVRI. Tercatat lebih dari 8 juta orang telah menonton Tilik di kanal YouTube sejak diunggah pada 17 Agustus lalu. Viralnya Tilik lantas memantik rasa penasaran penonton terhadap film-film pendek lokal, termasuk film pendek produksi Ravana Films lainnya. Apalagi menyusul viralnya Tilik, media daring dengan cekatan menyodorkan daftar film pendek lokal yang laik ditonton warganet.
Memilih genre ‘film perjalanan’ (road movies), Tilik mengisahkan rombongan ibu-ibu desa yang menyewa truk hendak menjenguk Bu Lurah di rumah sakit. Di sepanjang perjalanan, para ibu itu asyik menggunjingkan seorang kembang desa bernama Dian. Ada empat karakter utama yang terlibat aktif dalam pergunjingan itu: Bu Tejo, Yu Sam, Yu Ning dan Yu Tri. Di tengah perjalanan, truk yang mereka tumpangi dihentikan polisi karena melanggar aturan dan mogok hingga memaksa para ibu mendorongnya. Setelah sampai di halaman parkir rumah sakit, para ibu itu mesti menuai kekecewaan karena tak diijinkan menjenguk Bu Lurah yang masih dirawat di unit perawatan intensif (ICU).
Aspek sinematografis (mulai dari tata kamera hingga tata suara) film pendek ini menuai banjir pujian dari penonton dan bahkan sesama pembuat film seperti Joko Anwar dan Ernest Prakasa. Pilihan sudut (angle) kamera dari atas truk yang merekam dari dekat pergunjingan para ibu ikut membangun keintiman dengan penonton. Lanskap perdesaan yang diwarnai persawahan yang menghijau serta jalanan yang berkelok menyuguhkan pemandangan yang melegakan mata. Tata suara yang ciamik mampu menangkap percakapan tokoh-tokohnya dengan jernih. Seni peran dalam film pendek ini juga mengundang decak kagum penonton. Para aktor terlihat natural dalam memainkan perannya, termasuk ibu-ibu desa yang menjadi figuran.
Meski begitu, apa boleh buat, film ini juga menuai kritik yang keras. Jika boleh dirangkum, setidaknya ada tiga kritik terhadap film Tilik: (1) melanggengkan stereotipe perempuan; (2) berwatak misogynist (mengidap kebencian terhadap perempuan); dan (3) mengamini tindakan menyebarkan hoaks (kabar bohong). Menurut saya, ketiga kritik itu salah sasaran karena kekurangcermatan menonton Tilik sehingga keliru menarik simpulan. Baiklah, saya akan ulas satu demi satu kritik itu.
Pertama, apakah benar Tilik hanya melanggengkan stereotipe perempuan? Dalam film ini perempuan tak hanya menjadi karakter yang dominan, tapi juga direpresentasikan secara beragam. Sehingga tak mengesankan adanya penguatan stereotipe tertentu. Kita tahu, dalam film stereotipe bisa ditemukan dalam penggambaran karakter yang digunakan untuk membangun narasi. Richard Dyer (1977) pernah menyatakan stereotipe merupakan tipe sosial (social type) yang menarik garis batas yang tegas, jelas, baku dan muskil diubah. Begitu pula, Steve Neale (1993, hal.41) menyebut stereotipe dalam film sebagai “a stable and repetitive structure of character traits.” Dengan kata lain, pengambaran sifat-sifat karakter yang stereotipikal itu tak pernah berubah dan terus-menerus diulang. Dalam film-film Hollywood klasik era 1930-an, umpamanya, karakter perempuan berambut pirang seperti diperankan Marylin Monroe dan Jane Harlow secara setereotipikal digambarkan bodoh (dumb blonde stereotype).
Penting dicatat, Richard Dyer (1977) membedakan antara ‘typing’ dan ‘stereotyping.’ Bagi Dyer, tanpa melakukan typing mustahil seseorang bisa memahami objek, manusia dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Typing menjadi bagian penting dari proses pemaknaan karena melakukan proses klasifikasi seturut dengan kultur tertentu. Misalnya, kita menjadi ‘tahu’ seseorang karena kita ‘berpikir’ tentang peran yang dilakukannya entah sebagai orang tua, anak-anak, kekasih, teman, pekerja, atasan, dan sebagainya. Kita lantas memasukkan seseorang ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kategori ras/ etnisitas, jenis kelamin, agama, kelas dan seterusnya serta menyusun ‘tipe karakter’ (personality type) tertentu. Karena itu, gambaran tentang seseorang merupakan buah dari proses mengumpulkan informasi serta memposisikannya dalam tatanan tipifikasi tertentu. Sebaliknya, stereotyping melakukan pereduksian terhadap karakter seseorang dengan melebih-lebihkan sekaligus melakukan simplikasi. Stereotyping juga melibatkan proses memilah apa yang ‘normal’ dan ‘tak normal.’ Dalam bagian tertentu, Tilik memang melebih-lebihkan karakter Bu Tejo untuk memancing kelucuan, tapi tak lantas melakukan simplifikasi.
Sebagian warganet meluahkan kritiknya terhadap penggambaran perempuan yang stereotipikal sebagai penggemar gosip dan penyebar hoaks. Memang di sepanjang film, penonton disuguhi adegan ibu-ibu yang tampak menikmati bergunjing. Tapi, lihatlah karakter sopir truk bernama Gotrek yang notabene laki-laki itu. Gotrek tampak mencuri dengar pergunjingan ibu-ibu itu dari tempat duduknya sembari menyetir truk. Dalam salah satu adegan istri Gotrek (Yati) yang duduk di sampingnya sempat bertanya penuh selidik: “Ngopo e Mas?” (Ada apa Mas?). Gotrek hanya menjawab, “Ora popo Dik” (Tidak ada apa-apa Dik). Jawaban Gotrek tampak menyembunyikan sesuatu. Ia sesungguhnya mendengar (mungkin juga menikmati) gunjingan ibu-ibu di bak truk yang ada di belakang tempat duduknya. Dalam adegan lain, Gotrek tampak ingin tahu percakapan antara Yu Ning dan Dian lewat telepon ketika truk berhenti di depan masjid. Jadi, rupanya lelaki juga menyukai pergunjingan.
Lantas, apakah Tilik bisa dianggap berwatak misogynist? Mari kita lihat apakah representasi Tilik bernada memusuhi perempuan dan hanya mengusung representasi yang negatif belaka. Meski hanya mencuat lewat percakapan dan tak tampak di layar, penonton tahu bahwa desa—tempat tinggal ibu-ibu itu—dipimpin oleh seorang perempuan: Bu Lurah. Setelah bercerai dengan suaminya (Minto), Bu Lurah tinggal bersama anak lelakinya (Fikri). Sosok Bu Lurah agaknya sangat dicintai warganya setidaknya oleh ibu-ibu. Buktinya, begitu warga mendengar kabar ia dirawat di rumah sakit, mereka bergegas menjenguknya beramai-ramai serta rela memberi bantuan. Jelas ini bukan penggambaran perempuan yang stereotipikal dalam film Indonesia yang lazimnya memposisikan perempuan di pinggiran atau sekadar sebagai pemeran pembantu.
Selain itu, ada karakter Dian yang menjadi bahan pergunjingan ibu-ibu meski hanya muncul sepintas. Dian, seperti dituturkan Bu Tejo, bukan berasal dari keluarga berada dan ditinggalkan ayahnya sehingga ia hanya bisa bersekolah sampai SMA. Meski begitu, ia berani meninggalkan desa dan bekerja di kota. Dian boleh jadi mewakili perempuan yang mandiri dan berani membuat keputusan yang tak lazim untuk ukuran warga desanya. Ia tak buru-buru menikah sehingga mengundang ejekan sebagai ‘perawan tua.’ Inilah stigma yang melekat pada perempuan yang serius meniti karir. Alih-alih memilih menjalin hubungan asmara dengan pria yang sebaya, Dian justru memilih mantan suami Bu Lurah. Tentu, penonton hanya bisa menduga-duga motif Dian. Tapi, menganggap perempuan muda memilih pasangan yang lebih tua dan mapan itu menyembunyikan niatan buruk justru sebentuk pandangan yang stereotipikal. Stereotipe inilah yang justru digugat oleh Tilik di ujung cerita.
Tentu saja, Bu Tejo merupakan karakter perempuan yang menonjol dalam Tilik. Karakter Bu Tejo yang bersuamikan pemborong dan memiliki kedekatan dengan penjabat memiliki antusiasme mencari informasi lewat Internet dan media sosial. Ia menyindir ibu-ibu yang hanya menggunakan HP (telepon genggam) untuk bergaya ketimbang mencari informasi. Masalahnya, ia gampang percaya pada apa yang dia baca dan saksikan di Internet mapun media sosial, meski mungkin ia tidak sendirian. Karakter Bu Tejo ini dianggap warganet menguatkan stereotipe perempuan sebagai penyebar hoaks. Padahal boleh jadi ini problem literasi digital yang tak mesti berkaitan dengan identitasya sebagai perempuan. Buktinya, warga desa Bu Tejo pernah tertipu obat herbal yang diiklankan lewat Internet.
Mengingat status ekonominya yang lebih tinggi, Bu Tejo tampak disegani, sehingga mampu mempengaruhi ibu-ibu. Ia juga mampu menggerakkan ibu-ibu menggeruduk Pak Polisi yang menilang karena telah melanggar aturan lalu lintas. Tentu ini tindakan yang keliru. Tapi, bukankah film ini juga memotret absennya transportasi publik di Indonesia yang murah dan bisa diandalkan warga desa?
Tak aneh, karakter dalam film Tilik sangat kaya warna. Misalnya, karakter Bu Tejo yang tampak menonjol itu memang gampang dicap berperangai buruk karena kata-katanya penuh nada tuduhan. Ia memprovokasi ibu-ibu menggeruduk polisi dan melakukan politik uang menjelang pemilihan kepala desa. Tapi, ia mampu menawarkan jalan ke luar saat ibu-ibu terlihat kecewa karena belum diijinkan menjenguk Bu Lurah. Ucapan Bu Tejo dengan nada menyindir kini telah menjadi meme media sosial: “Dadi wong mbok solutip” (jadi orang itu sebaiknya menawarkan solusi). Sementara itu, Yu Ning yang sepintas terlihat kritis terhadap ‘fitnah’ Bu Tejo pada Dian nyatanya satu kerabat dengan Dian. Yu Ning hanya bisa menyodorkan pertanyaan, namun tak berikhtiar menyodorkan bukti tandingan. Bahkan, ketika Bu Tejo telah berhenti bergunjing, Yu Ning justru kembali memancing perselisihan pendapat hingga pecah pertengkaran sengit.
Begitu pula, sosok Yu Sam yang mula-mula memancing pergunjingan ihwal Dian, tiba-tiba berseberangan pendapat ketika Bu Tejo mendakwa Dian telah hamil hanya karena Bu Tejo pernah memergoki Dian muntah di tepi jalan. Yu Sam, menyangkal tuduhan Bu Tejo itu seraya menunjuk Yu Nah, temannya yang muntah karena mabuk di perjalanan. Sementara itu, Yu Tri hanya mengiyakan apa yang disampaikan Bu Tejo. Ia tidak cukup berani bersikap berbeda karena status ekonomi Bu Tejo yang lebih tinggi sebagaimana tampak dari pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Dalam film, hanya karakter Bu Tejo yang disapa ‘Bu’ menyiratkan status sosial yang lebih tinggi/ terhormat ketimbang panggilan ‘Yu’ (Mbakyu). Tak heran, Bu Tejo emoh mendorong truk yang mogok bersama ibu-ibu. Sebelumnya, ia mengeluh pada Yu Ning mengapa menyewa truk dan bukan mobil.
Jika menyimak komentar di jagat Twitter dan Facebook banyak warganet (penonton) yang kecewa serta kesal dengan ending (akhir cerita) sekaligus plot twist (kelokan cerita) film Tilik. Bagi warganet itu, akhir film ini justru membuyarkan niat mulia sang pembuat film: perang melawan hoaks. Selain itu, menurut warganet, akhir film itu membenarkan atau mengukuhkan ‘stereotipe’ perempuan yang lajang, cantik, bekerja dan terlihat sukses sebagai perempuan ‘nakal’ (ora nggenah) atau ‘pelakor’ (perebut lelaki orang lain).
Tapi, tunggu dulu. Akhir film ini, menurut saya, justru membalik semua gibah (gunjingan) para ibu-ibu tentang sosok Dian. Jika tak ada akhir cerita itu, barangkali penonton akan ikut termakan tuduhan Bu Tejo bahwa Dian adalah perempuan nakal. Padahal Dian justru sosok perempuan yang menghendaki hubungan yang permanen dengan mantan suami Bu Lurah. Maka, Dian jelas bukan ‘pelakor’ karena ia menjalin hubungan dengan seorang duda yang telah bercerai.
Selain itu, Dian juga sosok yang bertenggang rasa karena ia berikhtiar membujuk Fikri untuk menyetujui rencana pernikahannya dengan ayah Fikri (Pak Lurah), kendati Dian tetap bisa saja melangsungkan pernikahan tanpa persetujuan Fikri. Selain itu, akhir film ini membuktikan tuduhan Bu Sam dan Bu Tejo juga meleset karena Fikri dan Dian tidak sedang berpacaran. Pendeknya, tak seperti sangkaan warganet, akhir film pendek ini tidak membenarkan apa yang digunjingkan oleh ibu-ibu.
Jika diamati lebih jauh komentar warganet/ penonton yang berseliweran di Internet dan media sosial, menunjukkan masih campur aduknya pemaknaan hoaks atau fitnah dalam Tilik. Barangkali penonton terpengaruh oleh penuturan karakter dalam film (terutama Bu Tejo dan Yu Ning) yang menggunakan istilah hoaks secara longgar. Hoaks atau fitnah bisa diketegorikan sebagai ‘disinformasi’ yakni informasi yang keliru (sesat) dan secara sengaja dimanipulasi untuk meraih tujuan tertentu. Misalnya, dalam film Dian diinformasikan ‘hamil,’ ‘perempuan nakal’ dan ‘memakai susuk’ untuk memikat lelaki.
Harap dicatat, ‘disinformasi’ berbeda dengan ‘misinformasi’ dan ‘malinformasi.’ Misinformasi adalah informasi yang tak lengkap namun bukan karena kesengajaan. Contohnya, karena informasi yang tak lengkap (gagal menerima pesan Dian lewat HP), Yu Ning dan ibu-ibu akhirnya tak diijinkan menjenguk. Inilah sindirian Bu Tejo yang keliru pada Yu Ning karena informasi yang tak lengkap dianggap sebagai ‘fitnah.’ Sementara itu, malinformasi adalah penyebaran informasi yang bersifat personal dari seseorang (misalnya untuk tujuan balas dendam) dengan mengubah konteks dan waktu terjadinya peristiwa. Dalam film, Bu Tejo yang menemukan foto Dian bersama lelaki di media sosial dianggap menjalankan profesi sebagai perempuan penghibur.
Rupanya jari telunjuk sebagian warganet yang kecewa pada Tilik tak hanya diarahkan ke pembuat film, tapi juga penyokong dana film ini: Disbud DIY. Bagi saya, dukungan Disbud DIY terhadap film pendek ini justru patut diacungi jempol. Setidaknya, Disbud DIY sebagai penyadang dana terlihat menahan diri untuk tak menumpangkan “program-program pemerintah” pada film Tilik. Karenanya, sebagai penonton saya bersyukur. Saya tak menemukan karakter yang mengkhotbahkan program pemerintah yang lazim kita temui pada karakter Pak RT atau tokoh agama dalam film/ sinetron kita. Betapa membosankan, jika Tilik disesaki petuah dan instruksi dari pemerintah. Dalam Tilik barangkali hanya Pak Polisi yang menjelaskan peraturan lalu lintas yang dilanggar karena membawa penumpang di bak truk terbuka.
Agaknya, kepentingan Dinas terhadap film ini lebih pada dukungan pembuatan film pendek (fiksi dan dokumenter) oleh para sineas muda di Jogja. Buktinya, kita menemukan pada credit title di akhir film deretan nama yang menjadi ‘kurator’ dan melakukan ‘supervisi.’ Artinya, film itu telah melewati proses seleksi dan penilaian saat masih berbentuk proposal serta dipantau maupun diselia saat diproduksi. Tak sulit menduga ada proses dialog dan diskusi yang panjang selama pembuatan film ini. Sangat keliru menganggap Disbud DIY ‘kecolongan’ karena mendanai film yang melakukan stereotipe negatif perempuan dan bertentangan dengan kampanye melawan hoaks.
Sementara itu, ada pertanyaan klise yang kerap diajukan penonton: Apa pesan moral film ini? Setahu saya, ini jenis pertanyaan yang paling tak disukai pembuat film. Penyebabnya, pertanyaan itu seperti tonjokan pada pembuat film bahwa seakan-akan filmnya telah gagal berkomunikasi dengan penonton. Karenanya, pembuat film berkewajiban menjelas-jelaskan pesan moral pada penonton. Juga, pertanyaan itu bak memberi otoritas penonton untuk mempertanyakan tanggung jawab moral pembuat film. Ini mengingatkan saya pada jargon Orde Baru yang mewajibkan film Indonesia mengandung “nilai kultural edukatif”—nama lain bagi “propaganda pembangunanisme.”
Harus diakui, memang ada sutradara yang gemar mengusung pesan moral dalam filmya secara blak-blakan. Akibatnya, justru filmnya terjerembab ke dalam verbalisme serta menjadi rangkaian ceramah yang membosankan. Jika film hanya menyodorkan pesan moral yang dikhotbahkan, maka ia tak menggugah penonton serta membuka ruang bagi percakapan atau permenungan. Bukankah ini problem kronis yang masih menghinggapi sebagian besar film Indonesia? Beruntung Tilik tidak terperangkap ke dalam kecenderungan verbalisme pesan moral itu karena ia masih mempercayai nalar penontonnya.
Kita tahu, cukup banyak warganet/ penonton yang geregetan dengan karakter Bu Tejo. Tak aneh, muncul banyak meme karakter Bu Tejo di Internet dan media sosial. Boleh jadi karena penonton menemukan tempat berkaca. Di dunia nyata, Bu Tejo adalah karakter yang gampang ditemui di tempat terdekat mereka. Tapi, jangan-jangan kita adalah Bu Tejo itu sendiri. Sayangnya, tak banyak penonton (maupun kritikus film) yang mau mengaku. Mungkin karena gengsi atau semata-mata tak menyadarinya. Seperti Bu Tejo, tanpa kecermatan menonton, seseorang gampang menarik simpulan yang menyesatkan serta mengarah pada penghakiman yang tak adil. Akibatnya, bobot hiburan Tilik didakwa membutakan ‘problematik’ yang melekat pada film itu. Padahal justru apa yang dirumuskan sebagai ‘problematik’ film Tilik itulah yang bermasalah.
* Penulis: Dr Budi Irawanto (Dosen Ilmu Komunikasi UGM)
Advertisement