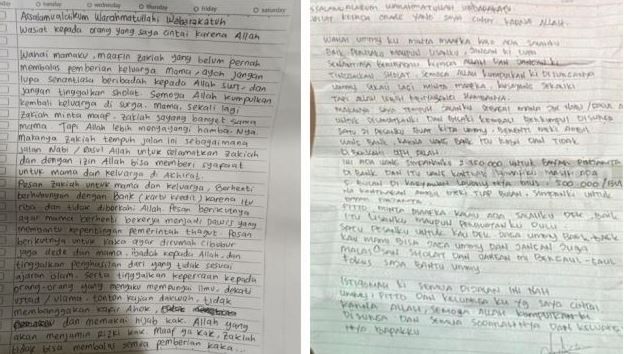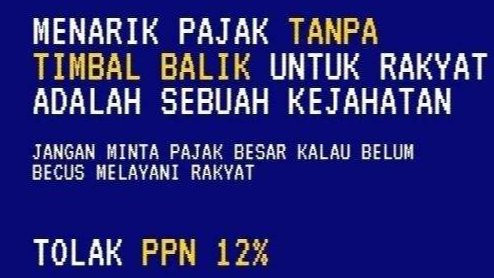Menihilkan Radikalisme Berbasis Agama: Saat Kembali ke Pesantren

Aksi teror berbasis agama kembali mengoyak-oyak rasa kemanusiaan kita. Di Makassar pada Minggu lalu dan Rabu (31 Maret 2021) di Mabes Polri Jakarta.
Keprihatinan mendalam saya rasakan ketika berita seperti itu terdengar. Keprihatinan pertama, karena peristiwa itu selalu disertai dengan tumpahnya darah seorang muslim. Dalam Islam, menghindarkan tumpahnya darah menjadi sesuatu yang sangat diutamakan. Sebisa mungkin, tidak ada darah seorang muslim yang tumpah di muka bumi.
Keprihatinan kedua, aksi teror seperti itu, selalu saja menyeret-nyeret agama untuk ditempatkan sebagai tertuduh. Dan karena pelaku aksi di Makassar dan Mabes Polri membawa simbul Islam—juga beridentitas sebagai muslim--, maka Islamlah yang menjadi pihak yang tertuduh. Seakan, Islam membenarkan aksi biadab seperti itu.
Tidak! Sama sekali hal itu tidak benar. Saya yakin, sebagian dari bangsa ini—baik muslim dan non muslim--, memiliki keyakinan bahwa Islam tidak mengajarkan seperti itu. Dan seperti saya ungkapkan di bagian awal tulisan ini, justru Islam mengajarkan agar pertumpahan darah sebisa mungkin dihindarkan.
Kedangkalan
Orang yang membawa simbul agama untuk melakukan kekerasan (teror), pada umumnya berawal dari kedangkalan dalam memahami agama. Kaum Khawarij yang dalam sejarah Islam pertama kali menumpahkan darah sesama muslim di kalangan sahabat Nabi, dipicu oleh kedangkalan mereka dalam memahami teks Al-Qur’an. Itu, imbas dari politisasi teks Al-Qur’an yang muncul sebelumnya.
Memang, dalam konteks sekarang, bisa saja pemicu dari aksi terorisme itu bermacam-mcam. Ketidakadilan, kemiskinan, ketidakberdayaan (frustasi), politik dan lain sebagainya. Namun, bila pemahaman agamanya tidak dangkal, maka orang tersebut tidak akan terjebur dalam aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama.
Di Indonesia –dan juga sebagian negara muslim di Timur Tengah--, kedangkalan pemahaman keagamaan, seakan menjadi gejala umum. Ini mengindikasikan bahwa penguasaan ilmu agama (Islam), di kalangan kaum muslimin semakin merosot. Dalam beragama, mereka terjebak ke simbul-simbul, bukan ke esensi.
Kita tentu patut bersyukur, sejak era 90-an semangat keagamaan di Indonesia semakin meningkat. Namun sayang, semangat keagamaan itu, kurang diimbangi dengan ilmu agama yang memadai. Banyak ustadz-ustadz dadakan yang bergitu pede menafsirkan teks-teks Al-Qur’an. Padahal, mereka sangat minim --untuk tidak mengatakan tidak sama sekali-- penguasaannya dalam bahasa Arab, balaghoh (santra Arab), dan perangkat-perangkat lain seperti ilmu nasakh mansukh, asbabun nuzul, yang diperlukan dalam memahami nash Al-Qur’an.
Memang, gerakan para ustadz dadakan yang marak di negeri ini, tidak langsung membawa umat ke arah gerakan terorisme. Namun, pelan-pelan telah mendekatkan ke arah terorisme. Yang kita rasakan, mereka sering bersikap radikal—khususnya dalam hal-hal yang berbasis agama--. Dan, sikap radikal ini tentu bertetanggaan dekat dengan terorisme. Paling tidak, akan ikut menyuburkan.
Berangkat dari asumsi di atas, maka saya berpendirian, memperdalam pemahaman Ilmu agama bisa menjadi salah satu ikhtiar kita untuk menihilkan atau meminimalkan aksi kekerasan (teror) yang berbasis agama. Pemuka-pemuka Islam di negeri ini, khususnya yang di NU dan Muhammadiyah harus secara sistematis untuk bergerak. Mereka harus mendidik umat Islam Indonesia, untuk beragama dengan ilmu. Tidak hanya dengan semangat dan fanatisme.
Pesantren
Berbicara soal pendalaman ilmu agama (Islam), maka pesantren –yang merupakan sistem pendidikan peninggalan nenek moyang kita—menurut saya layak diperhatikan kembali. Pemerintah, harus secara sungguh-sungguh membantu pesantren untuk tumbuh dan berkembang.
Saya bersyukur, di era pemerintahan Jokowi ini, UU Pesantren disahkan. Namun, implikasi positif dari UU itu masih perlu ditunggu. Saya yakin, pembuatan UU itu didasari oleh niat baik untuk membantu pertumbuhan pesantren. Namun, tidak menutup kemungkinan, UU itu justru menjadi jebakan batman. Kondisi konyol (negatif) yang tidak kita duga sebelumnya. Apa itu?
Pesantren kehilangan independensinya. Pesantren kehilangan ruh keikhlasannya. Pesantren, terjauhkan dari khazanah keilmuan. Pesantren terjebak dengan urusan-urusan formalitas seperti yang menimpa lembaga-lembaga pendidikan formal di negeri ini.
Terkait dengan itu, saya sangat berharap, para pengelola pesantren harus ekstra hati-hati dalam menyikapi lahirnya UU Pesantren. Pesantren harus dipertahankan menjadi lembaga tafaquh fi dien (pendalaman ilmu agama). Bukan lembaga pemberi titel atau gelar akademik.
Sejarah bangsa ini membuktikan, pesantren di negeri ini telah melahirkan ulama-ulama hebat kaliber dunia. Sebut saja, Imam Nawawi dari Banten, Syekh Khatib dari Minangkabau, dan Syekh Mahfud dari Termas, Pacitan. Bila ada keyakinan bahwa kebangkitan Islam akan muncul dari Timur, maka bangsa Indonesia perlu memiliki keyakinan bahwa Timur itu secara spesifik mengarah kepada teritorial Indonesia.
Dan, secara spesifik lagi, kebangkitan itu harus diarahkan ke pesantren. Mengapa? Karena kebangkitan semangat keislaman yang sejak era 90-an dimotori oleh para akademisi di kampus --khususnya kampus umum dan negeri--, terbukti telah membawa kepada kedangkalan pemahaman agama, seperti yang saya sebutkan di atas.
Produk dari halaqoh-halaqoh yang ada di kampus-kampus umum (negeri) adalah aktivis-aktivis Islam yang intoleran dan cenderung radikal. Kondisi ini, sudah dengan mudah kita rasakan. Baru-baru ini, Ketua Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa (FRPKB) Prof Aom Karomani menyatakan banyak kampus yang terpapar paham radikal. Hal ini, juga diperkuat dengan data dari BIN (Badan Intelijen Negara) yang mengungkapkan adanya fenomena peningkatan faham konservatif keagamaan di beberapa kampus.
Tulisan pendek ini, tidak cukup untuk menggambarkan, mengapa pendalaman Islam di pesantren tidak melahirkan faham konservatif dan radikal. Itu butuh pemaparan yang panjang dan mendalam. Ada beberapa hasil penelitian tentang pesantren, seperti “Tradisi Pesantren”, karya Zamakhsyari Dhofier, “Pesantren Madrasah Sekolah”, karya Karel A. Steenbrink, “Pergulatan Dunia Pesantren,” buku bunga rampai dengan editor M. Dawan Rahardjo, dll., yang bisa dibaca untuk memperluas wawasan tentang pesantren.
Namun yang pasti, tesis dari Kapolri Jenderal Polisi Sigit Sulistyo bahwa untuk menangkal faham radikalisme salah satunya dengan memerintahkan jajarannya untuk mendalami kitab kuning adalah salah satu jawabannya.
Kitab kuning, mestinya hanyalah simbul (istilah) dari sebuah bacaan atau refrensi keagamaan yang berbasis dari pemikiran-pemikiran para ulama salaf yang memang sangat expert dalam bidang agama. Di dalam kitab kuning itu, bertebar khazanah pemahaman keislaman yang sangat fleksibel dan mendorong kearifan dalam kehidupan sosial dan agama. (bersambung)
Akhmad Zaini
Mantan Jurnalis, kini menjadi Pendidik di IAINU Tuban
Advertisement