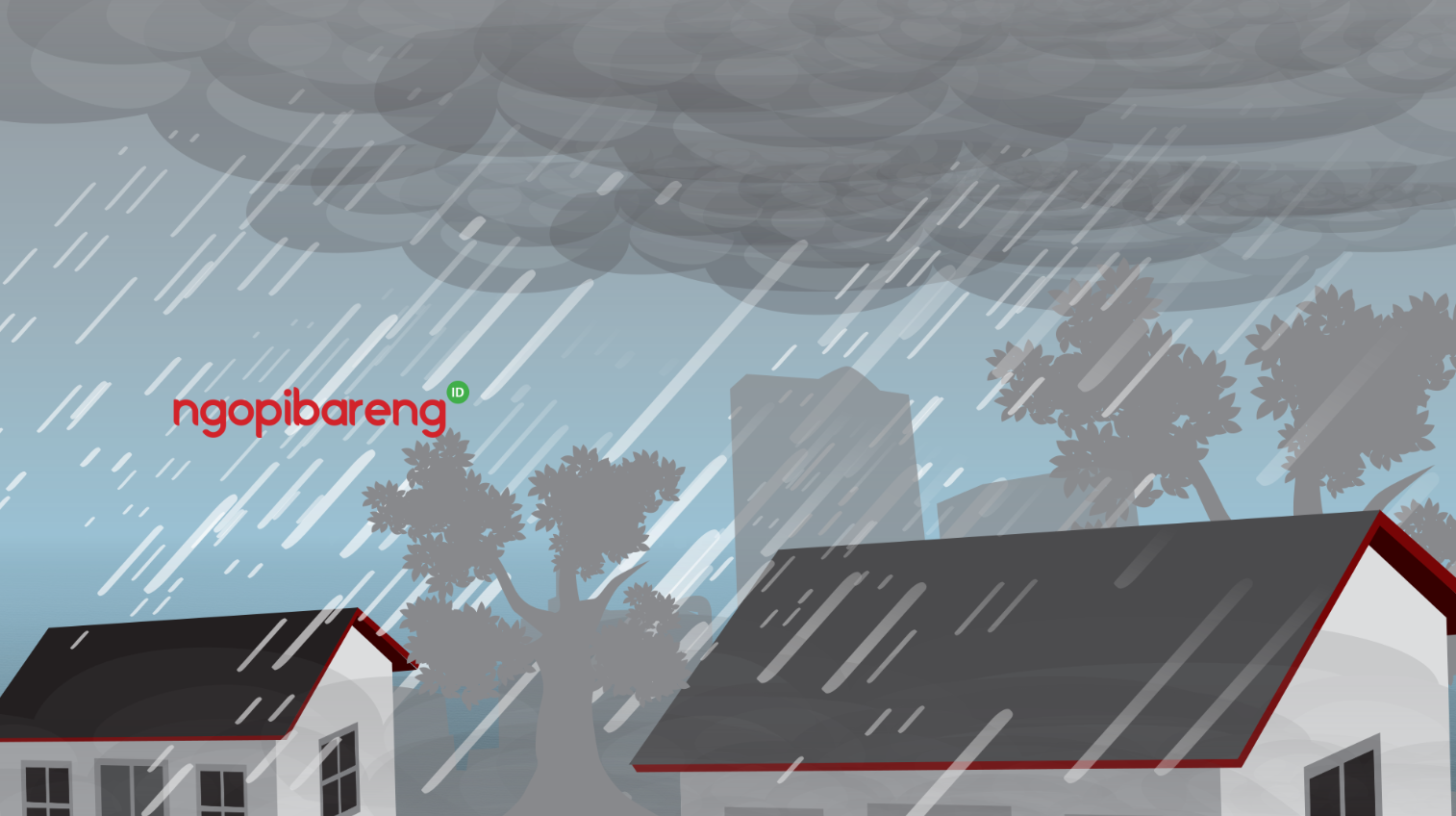Memanusiakan Riset Sosial (2)

Coretan saya berjudul “Memanusiakan Riset Sosial” (Ngopibareng.id, 04 Januari 2024) menuai ragam tanggapan. Di samping apresiasi, yang lebih penting dan substantif tulisan itu justru telah memicu diskusi. Semua ini bak kidung akademik yang mengasyikkan. Pada saat yang sama, kegamangan selalu membayangi, bahkan kegelisahan senantiasa menghantui. Pasalnya, satu pertanyaan selalu memburu: “Apakah modal riset, termasuk yang harus diajarkan pada mahasiswa doktoral, sebatas pada “methodology in a nutshell”; yaitu sekedar pemahaman prosedur dan teknik penelitian ringkas yang mekanistik, tapi minim sentuhan manusiawi?” Perjumpaan keduanya, akhirnya, mendorong eksplorasi dalam bentuk tulisan berseri ini.
Dari diskusi yang terpantik, muncul satu isu yang menarik. Apakah studi lapangan (fieldwork) memang diperlukan dalam studi sosial? Toh, dengan ketersediaan dan akses referensi yang semakin baik, penelitian bisa dilakukan dari balik meja, seperti bibliometric analysis?
Tak ada jawaban tunggal tentang isu fieldwork ini. Pandangan ilmuwan terbelah. Selain ditentukan oleh minat dan keyakinan akademik, silang pendapat tentang signifikansinya tergantung pada urgensinya. Misalnya, Samuel P. Huntington, seorang political comparatist terkemuka dari Harvard University; menganggap fieldwork tidak penting. “I don’t believe in it!”, tegasnya. Ia memandang bahwa fieldwork secara akademik bisa bermasalah. Alasannya, “melakukan fieldwork sekian waktu di suatu negara akan membuat peneliti terbelenggu, laiknya ‘tawanan dari satu pengalaman tertentu”. Dengan kata lain, fieldwork berpotensi membuat peneliti hanya berkutat pada isu yang sempit dalam area yang terbatas.
Bagi Huntington, yang lebih penting bagi peneliti justru mengasah kemampuannya membuat empirical generalizations (generalisasi empiris). Orientasinya ini telah dibuktikannya sendiri. Dari penelitiannya, ia telah menghasilkan banyak seminal books. Bahkan, dua di antaranya merupakan magnum opus. Salah satunya, Political Order in Changing Societies (1969) merupakan bukunya yang sangat berpengaruh. Pasalnya, melalui bukunya ini ia telah mendobrak ortodoksi dalam teori Pembangunan, khususnya pembangunan politik. Ia mengoreksi asumsi modernis dalam pembangunan politik, seperti yang diadopsi Seymour Martin Lipset, dalam bukunya Political Man (1961). Selain itu, bukunya The Third Wave of Democractization (1991), telah memenangkan The Grawemeyer Award for Ideas Improving World Order. Rekognisi ini berkat kerberhasilannya menawarkan perspektif yang berbeda tentang signifikansi bentuk rejim politik, baik demokrasi maupun diktator, terhadap proses demokratisasi.
Namun, pandangan Huntington, beserta pembuktian kualitas hasil penelitiannya; tidak serta merta menihilkan signifikasi fieldwork. Beberapa ilmuwan tetap mengakui, bahkan menekankan, urgensi fieldwork. Misal, James C. Scott, ilmuwan politik AS; menegaskan bahwa “tinggal di desa [fieldwork] merupakan sebuah investasi [akademis]” guna menjadi specialist. Argumen ini didasarkan pengalaman empirisnya, bahwa fieldwork telah memungkinkannya punya waktu yang cukup untuk “observe [mengamati] and cogitate [merenungkan]” fenomena secara mendalam. Walhasil, fieldwork-nya telah membuahkan penelitian yang “deeper and richer”, seperti tertuang dalam magnum opus-nya: Weapons of the Weak (1985).
Dua pandangan berseberangan, tapi kontribusi keilmuannya sama-sama meyakinkan. Lantas, bagaimana menilainya? Perlu tidaknya fieldwork, sekali lagi, ditentukan tujuan penelitian. Huntington tidak tertarik pada fieldwork, karena ia tak mau terpaku pada satu kasus. Sebagai seorang comparatist, intensinya adalah membandingkan banyak kasus, yang popular disebut studi “large-N”. Guna mendapatkan empirical generalizations, tak pelak, ia menggunakan Meta-data-analysis. Sebaliknya, Scott berhendak untuk menghasilkan analisa detail atas suatu fenomena, sehingga ia merasa perlu melakukan fieldwork.
Namun, penjelasan terasa kurang mantap jika tak ada pandangan pelengkap. Penilaian mungkin akan lebih arif, bila ada pandangan alternatif dari seseorang yang punya pengalaman penelitian variatif. Sosok itu bernama Juan J. Linz, seorang political sociologist sekaligus mantan Presiden The World Association for Public Opinion Research (1974–76). Syahdan, dalam sebuah wawancara, ia sempat cerita pengalaman penelitiannya: “Disertasi saya berfokus pada analisis sekunder data survei dan library research tentang sistem kepartaian Jerman dan sejarah sosial Jerman. [Pengalaman] fieldwork baru saya peroleh kemudian dalam karir saya, [yakni] melalui penelitian saya tentang ‘Youth and Entrepreneurs’ di Spanyol. [Untukkeperluan ini] saya melakukan fieldwork selama 1,5 tahun di Spanyol … Saya pikir Anda bisa dan harus melakukan fieldwork, apalagi jika Anda seorang akademisi. Bukan ide yang baik untuk berhenti melakukan fieldwork …”
Ungkapan di atas bukan sekedar menyangkut pilihan. Tapi, sebuah anjuran yang dilandasi sifat keilmuan. Melalui komparasi, Linz memberikan ilustrasi: “Jika Anda penelitian fisika di Chicago, hasilnya akan valid bagi siapa saja yang ingin belajar fisika di Jakarta. Tetapi, jika Anda tahu banyak tentang kepresidenan Amerika Serikat; pengetahuan ini tidak banyak membantu untuk memahami bagaimana bekerjanya [lembaga] kepresidenan di Indonesia. [Untuk memahami yang terakhir ini] Anda harus belajar konteks Indonesia dengan melakukan fieldwork di Indonesia”. Argumennya, tantangan utama dalam merumuskan proposisi teoritis adalah “to know something”. Tantangan ini menuntut pengetahuan yang komprehensif. “To know something”, tandas Linz, “seseorang harus mengetahui tentang bagaimana fenomena itu terjadi, prosesnya, apa akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan masyarakat, dan bagaimana fenomena itu berubah”. Obsesi ini jelas memerlukan fieldwork. Pasalnya, selain membawanya lebih dekat dengan konteksnya, fieldwork juga memungkinkan peneliti memperoleh kepekaan yang lebih baik terhadap fenomena.
Lalu, apa relevansinya bagi mahasiswa doktoral? Pascasarjana, khususnya jenjang S3, dipandang sebagai lahan pengembangan keilmuan. Menurut Alfred Stepan, idealnya, mahasiswa doktoral senantiasa punya kegelisahan akademik. “Mereka mempunyai kepentingan yang mendalam terhadap suatu permasalahan besar, disertai dengan wawasan awal. Mahasiswa [doktoral] terbaik hampir selalu datang ke pascasarjana setelah menginternalisasi masalah besar yang telah sering mereka amati”, tukasnya. Dalam konteks ini, baginya, fieldwork menjadi sangat berarti. Argumennya, “melakukan fieldwork guna mencari data sendiri dapat membantu peneliti muda, khususnya mahasiswa S3, menghasilkan data yang mungkin tidak tersedia ketika mereka memulai penelitiannya”. Di sinilah, titik mula investasi guna menemukan novelty dari sebuah disertasi. Secara imperatif mahasiswa S3 memang dituntut menyajikan sudut pandang yang berbeda dari thesis lain yang pernah ada. Jika tidak, mengutip Huntington: “there isn’t much point!”. Wallahu’alam …
Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember.
Advertisement