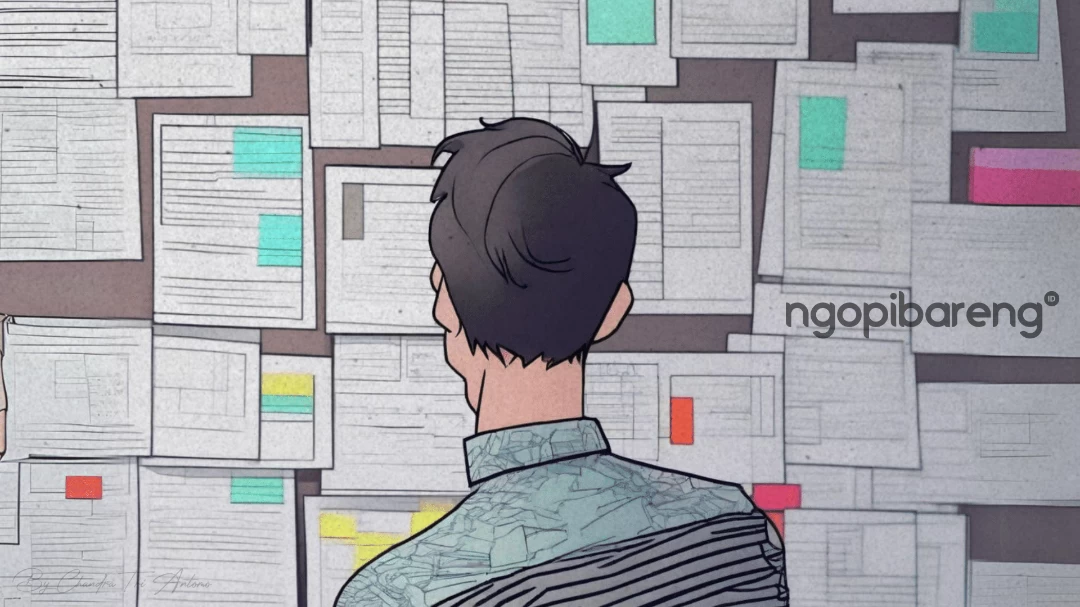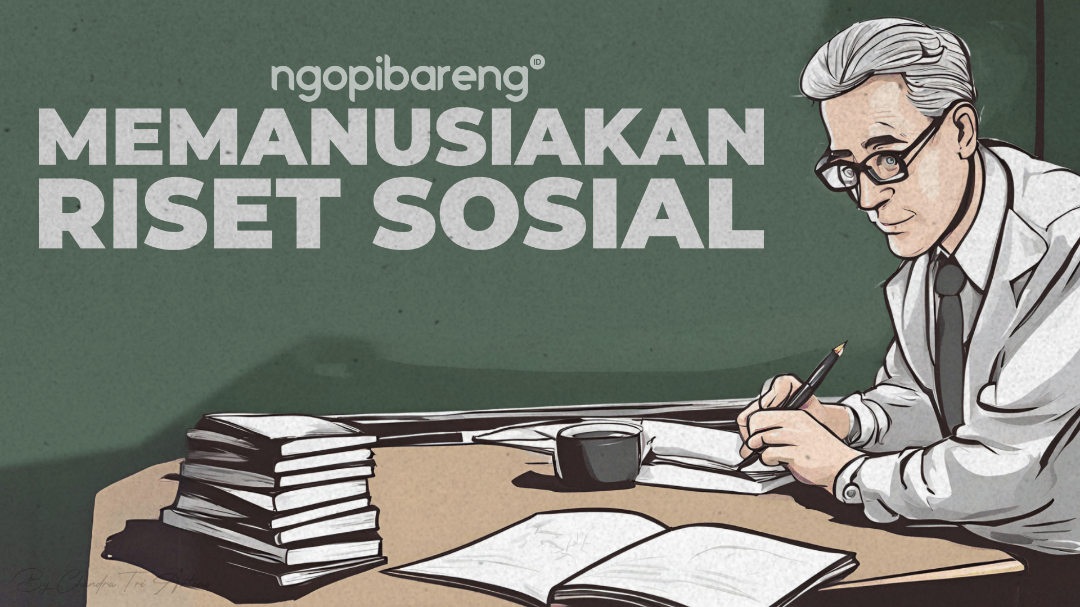Memanusiakan Riset Sosial (14)
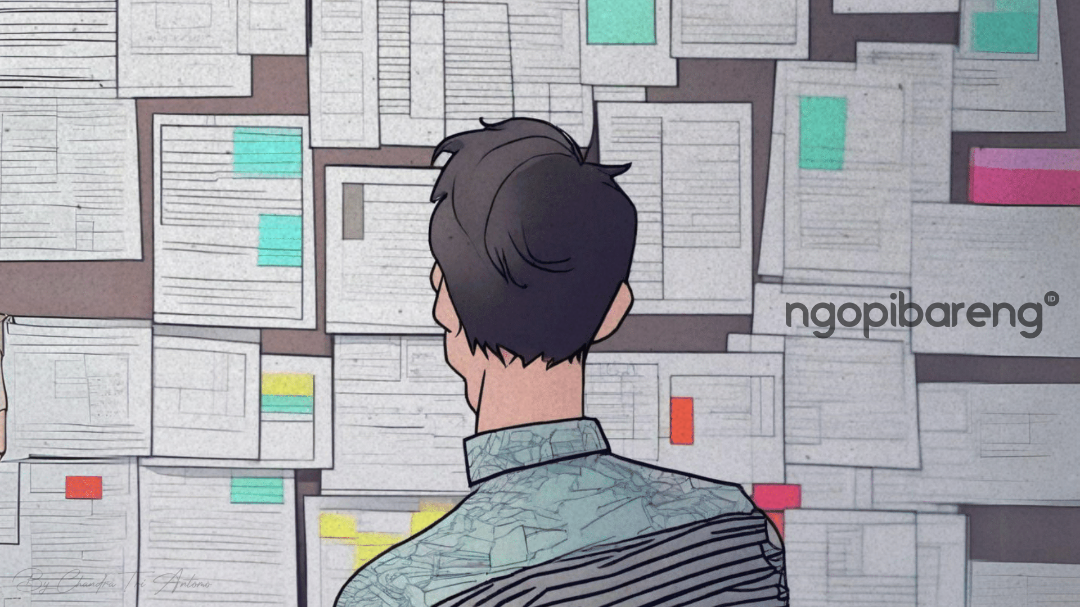
Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember
Kadang, kegemasan menyertai proses pembimbingan disertasi. Pasalnya, dari fieldwork-nya mahasiswa doktoral sering mendapatkan data yang banyak. Tapi, sayangnya, analisanya relatif sederhana, sehingga tak jarang menghambat temuan atau (novelty) dari disertasinya. Padahal, tak sedikit data yang diperolehnya itu menarik untuk diracik. Apa penyebabnya? Untuk membahasnya, saya berangkat dari satu kisah.
Sore itu, Jumat after hours, saya kembali ke kampus Flinders University, di suburb Bedford Park, Adelaide. Tujuannya, melanjutkan penulisan proposal disertasi yang hari itu sempat terinterupsi karena harus salat Jumat. Kebetulan, lokasi masjidnya agak jauh, terletak di kawasan Kota Adelaide, sekitar 10 km dari kampus. Akibatnya, saya harus meluangkan waktu agak lama untuk menunaikannya. Ketika memasuki gerbang kampus, saya berjumpa seorang kawan, kakak angkatan di program PhD, yang baru saja menyelesaikan fieldwork di Indonesia, dalam rangka penulisan disertasinya. Kami berdua-pun berjalan beriringan menuju ruang postgraduate student.
Saat akan menapak tangga Plaza Kampus, langkah kami terhenti. Pasalnya, kami berpapasan dengan Profesor Colin Brown yang tengah memakai pakaian olah raga, sembari memegang raket kecil. Dengan badan yang masih berpeluh, beliau cerita baru saja bermain squash. Perjumpaan ini terjadi, menjelang kepindahannya ke Curtin University, Perth. Perpindahan ini pula yang menyebabkan beliau tak bisa melanjutkan membimbing saya dalam menempuh program PhD. Menyadari bahwa kawan saya itu baru balik dari fieldwork di Indonesia, beliau bertanya: “How about your research fieldwork?”. Dengan percaya diri sang kawan mengatakan: “It was good and supposed to be successful; (as) I was able to collect a lot of data”, seraya membentangkan tangan guna menyimbolkan banyaknya data yang diperoleh. Dengan senyum khas-nya, Professor Colin Brown manggut-manggut. Selanjutnya, dengan nada datar dilambari senyumnya yang khas, beliau berkata: “Great! [But] collecting data is one thing, assembling them in writing is another”. Sang kawan meresponnya singkat: “Thank you!”. Entah apa yang terpendam dalam hati sang kawan ini, setelah mendengar respon Profesor Colin Brown tersebut.
Namun, saya yang ikut mendengar dialog tersebut di atas sempat tertegun. Perkataan Profesor Colin Brown, yang menegaskan bahwa ‘punya banyak data adalah satu hal, sedangkan menuangkannya dalam tulisan adalah lain hal’, membuat benak saya bergolak. Pasalnya, sebagai mantan bimbingannya selama menempuh Master degree (MA) by research, saya paham akan sosoknya. Meski berkebangsaan Australia, perasaan dan perangainya seringkali seperti orang Indonesia. Bahkan, dalam beberapa hal justru mirip dengan orang Jawa. Bagi saya, perkataannya tersebut laiknya sebuah sanepan, istilah Jawa tentang ungkapan yang mengandung arti kias dengan makna yang dalam. Tak pelak, saya merasa perlu untuk serius merenungkan maknanya.
Kala renungan mengendap, makna yang terkias mulai terkuak. Setidaknya ada tiga endapan memori dalam benak. Pertama, saat finalisasi proposal MA thesis, sebelum fieldwork di Thailand dan Indonesia; seperti lazimnya penelitian kualitatif, saya menyiapkan interview guide guna keperluan wawancara. Tapi, setelah diskusi dengan dua supervisor, Profesor Colin Brown dan Jim Schiller, PhD., saya masih didorong untuk menambah satu sub-bab lagi guna mengelaborasi some possible explanations. Walhasil, saya sempat membuat empat kemungkinan eksplanasi menyangkut permasalahan tesis yang saya ajukan. Akibatnya, pertanyaan yang tertuang dalam interview guide menjadi semakin variatif, karena melibatkan lebih banyak dimensi dan aspek sosial. Dengan pertanyaan wawancara yang lebih variatif ini, harapannya, bisa membantu upaya untuk meretas penjelasan alternatif. Kedua, teringat akan idealisasi Ballard dan Clanchy (1984) tentang outcome program doktoral, khususnya disertasi. Misi keilmuannya, adalah pengembangan ilmu pengetahuan (extending knowledge). Upayanya, adalah “deliberate search for new possibilities and explanations”, guna menghasilkan “creative originality, totally new approach/ new knowledge”. Ketiga, sekian kali saya terhenyak ketika membaca karya akademik, termasuk beberapa hasil penelitian. Bahkan, di antaranya saya sampai bergumam: “Dahsyat! Elaborasinya hebat, sampai ada aspek eksplanasinya yang tak terbersit dalam benak saya”. Gumam ini adalah sebuah pengakuan, bahwa secara komparatif analisanya lebih komprehensif dan mendalam daripada apa yang saya bayangkan dalam pikiran.
Ketiga endapan memori di atas bermuara pada catatan, betapa pentingnya imaginasi dalam penelitian. Argumentasinya, endapan memori yang pertama di atas, mencerminkan perlunya peneliti mengasah imaginasinya sejak awal. Endapan kedua, menyiratkan pentingnya imaginasi guna membantu menemukan kebaruan (novelty) penelitian. Endapan ketiga, merupakan ilustrasi hasil dari tajamnya imaginasi peneliti. Signifikansi imaginasi ini bukanlah ilusi. Pasalnya, per-definisi, imaginasi adalah “the ability of the mind to be creative or resourceful”. Dalam konteks ini, Albert Einstein pernah menegaskan: “Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world” (Imaginasi lebih lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan sifatnya terbatas [karena bersifat lokal]. [Sementara itu], [dengan] imaginasi [pikiran] kita bisa menjelajahi dunia [sosial yang luas]). Bahkan, Muhammad Ali, sang legenda tinju, sempat menggarisbawahi: “The man who has no imagination has no wings!” (orang yang tak punya imaginasi seperti seekor burung tanpa sayap [pengetahuannya terbatas karena tak kuasa menjelajah dunia sosial yang luas]).
Jika imaginasi memang penting dalam penelitian, pertanyaan pamungkasnya, bagaimana memahami dan mengasah imaginasi. Tidak mudah secara persis merumuskan definisinya, apalagi dalam konteks penelitian sosial. Tapi, berdasarkan pemahaman dan hasil eksplorasi berbagai sumber, plus pengalaman pribadi dalam meneliti; secara sederhana bisa digambarkan dengan rumus: *Imagination = stock of knowledge + exploration/comparison + connecting the dots.* Narasinya, seorang peneliti perlu selalu menambah pasokan stock of knowledge, baik berupa teori maupun pengetahuan empiris, mencakup fenomena atau data. Pada saat yang sama, guna mempertajam pemahaman terhadap suatu fenomena; perlu dibantu dengan eksplorasi, atau komparasi, fenomena serupa di lain tempat. Seiring dengan dua langkah ini, dengan berbekal penalaran logis, perlu dilengkapi upaya identifikasi kemungkinan kaitan antar pengetahuan teoritis dan empiris tersebut. Punya daya imajinasi yang baik memang tidak mudah, karena kapasitas ini tak bisa diraih secara instant. Namun, ketekunan dalam mengembangkan dan konsisten untuk senantiasa mengasahnya; insya Allah akan menghantarkan seorang peneliti pada kapasitas diri untuk mampu menghasilkan karya akademik yang resourceful dalam analisa, forceful dalam argumentasi, dan colourful dalam elaborasinya.
Wallahua’alam
Advertisement