Memanusiakan Riset Sosial (10)
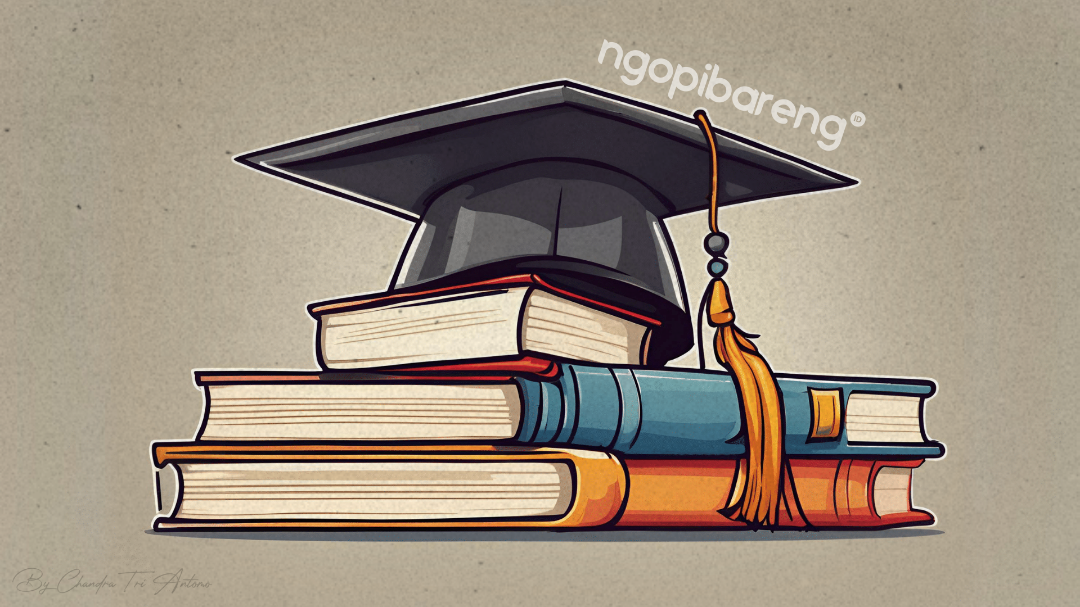
Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.,
Dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember
=====
Kupasan tentang ilmu, paradigma, dan riset sosial ternyata berlanjut. Pasalnya, tulisan berseri saya mengundang ragam tanggapan. Di antaranya, dua komentar terhadap dua tulisan yang berbeda. Yang pertama, berkaitan artikel saya bertajuk “Memanusiakan Riset Sosial (8)” (Ngopibareng, 18 Mei 2024). Seorang pakar hukum (Dr.) menyoroti kutipan saya atas pendapat Robert A. Dahl: “Identifying a [research] question is a moral and normative issues, not a scientific issue!”. Ia sepakat dengan kutipan ini. Argumennya, kutipan ini berkorelasi dengan riset hukum, karena “konsep dasar hukum untuk kepentingan manusia (moral)”.
Namun, pakar hukum tersebut tidak setuju dengan kutipan saya atas pendapat Barrington Moore, Jr. yang mengatakan: ”Anda dapat membahas isu moral tanpa harus mengambil sikap terhadap moralitas tersebut”. Ia menilai bahwa pendapat Moore, Jr. ini "kontradiktif" dengan sikap peneliti yang seharusnya subyektif, dengan output riset yang bersifat preskriptif. “So, Barrington Moore, Jr. is the barrier of ‘memanusiakan riset sosial’”, lanjutnya.
Yang kedua, tanggapan dari seorang pakar diplomasi (PhD). Setelah membaca tulisan saya “Memanusiakan Riset Sosial (9)” (Ngopibareng, 10 Juni 2024), ia bertanya: “Untuk riset Posmo [Postmodernisme] tidak boleh terasa positivis, nggih [ya]?”.
Kedua tanggapan yang berbeda ini menggelitik saya untuk memberikan tanggapan balik. Alasannya, keduanya penting dielaborasi, dengan harapan bisa membangun pemahaman bersama yang lebih baik tentang dunia keilmuan. Apalagi, keduanya berkaitan dengan riset sosial. Untuk komentar yang pertama, saya menanggapi dengan responsi, sedangkan untuk tanggapan yang kedua saya mencoba merumuskan jawaban.
Berkaitan dengan tanggapan pakar hukum di atas, perlu saya klarifikasi dahulu makna dari “memanusiakan riset sosial”. Sejak awal, saya memakai istilah itu, sebagai tajuk tulisan, karena didorong oleh pengamatan dan pengalaman, bahwa kuliah Metodologi Riset lebih terfokus membahas “schools and tools” (paradigma dan alat analisa) daripada pengalaman empiris peneliti. Pemakaian diksi “memanusiakan” sebenarnya ingin menggambarkan, sekaligus menyelami, suka duka peneliti. Argemenya, peneliti juga manusia, insan yang tak lepas dari tantangan dan hambatan dalam laku proses risetnya. Tak aneh, bila kisah-kisah yang tersaji kental dengan pengalaman penelitian empiris di lapangan dari pada sekedar merujuk pedoman riset sosial yang cenderung abstrak, kaku, dan kering. Namun, sang pakar hukum nampaknya lebih melihat diksi ‘memanusiakan’ dalam tataran paradigmatis. Tak pelak, ia mempertanyakan sikap peneliti dalam aspek “episteme”-nya (istilah yang bersangkutan) beserta output penelitiannya.
Tapi, perbedaan tafsir telah menguak tabir. Kritisme pakar hukum tersebut justru menghantarkan kita pada pembahasan perbedaan karakter ilmu. Ia mengungkapkan ketidaksepakatannya terhadap sikap ‘netral’ peneliti, seperti tercermin dalam pendapat Barrington Moore, Jr. Alasannya, sikap semacam itu kontradiktif dengan karakteristik ilmu Hukum yang harus berpihak pada “moralitas atau kepentingan manusia”. Saya memahami ketidaksetujuannya tersebut. Argumennya, berangkat dari keawaman saya, ilmu Hukum sejatinya adalah a normative science. Hans Kelsen (2005), dari University of Vienna, menegaskan bahwa ilmu Hukum “represents a normative interpretation of its objects”. Alasannya, “knowledge of law is knowledge of ‘norms’”, sedangkan “norms are series of oughts”, tandasnya. Tak pelak, secara normatif, peneliti hukum dituntut bersikap dan punya preferensi subyektif.
Sementara itu, karakter ilmu Sosial berbeda. Historiografi-nya agak buram, tapi dinamis; karena selalu diwarnai berisiknya kompetisi pandangan keilmuan yang berbeda (different voices). Margareth G. Hermann mengemasnya dengan istilah menarik: “One field, Many perspectives”. Secara faktual, karakteristik ini tercermin dalam paradigma keilmuannya yang variatif. Masing-masing paradigma ‘tidak dapat dibandingkan’ (incommensurable) satu sama lain. Pasalnya, satu paradigma tak bisa dinilai dengan kriteria paradigma lainnya. Argumennya, masing-masing paradigma memiliki asumsi dasar yang berbeda. Walhasil, mereka ‘sepakat untuk tidak sepakat’ (agree to disagree) tentang epistemologi yang dipakai.
Paradigma keilmuan erat kaitannya dengan penelitian. Pasalnya, paradigma merupakan seperangkat keyakinan dasar yang mewakili pandangan dunia (worldview) untuk mendefinisikan sifat fenomena sosial, termasuk berbagai aktor yang terlibat di dalamnya. Dalam riset sosial, aktor yang dimaksud meliputi peneliti dan obyek yang diteliti. Fungsi paradigma adalah memandu penelitian ilmiah, bukan hanya metode penelitiannya, tapi juga mencakup bagaimana peneliti mendefinisikan dan memahami realitas sosial, termasuk ‘kebenaran’ (truth).
Secara garis besar, pemilahan paradigmatis dalam ilmu Sosial menghasilkan dua kelompok utama, yakni Positivisme dan Post-Positivisme. Asumsi dasar Positivisme, dalam penelitiannya peneliti harus mengambil jarak terhadap obyek yang diinvestigasi. Tujuannya, untuk menjaga obyektivitas; sehingga perolehan ilmu tentang obyek tersebut terbebas dari bias. Intinya, kata Rebecca Campbell dan Sharon M. Wasco, “human factors must not enter the scientific process”. Sebaliknya, Post-Positivisme, yang maujud dalam Reflectivist theories beserta variannya, punya asumsi dasar yang berbeda. Post-Positivisme berpandangan semua teori Sosial mencerminkan nilai-nilai (values) tertentu. Isunya, hanyalah sekedar apakah nilai-nilai tersebut eksplisit atau implisit. Normative theory, misalnya, esensinya value-laden, sehingga dianggap unscientific. Pasalnya, teori ini selalu melibatkan dimensi moral. Dalam penerapannya, masih kata Campbell dan Wasco, peneliti tak perlu mengambil jarak dengan obyek penelitiannya. Argumennya, justru “researchers must articulate how their individual experiences shape their research findings”.
Dengan pemahaman bahwa masing-masing paradigma adalah incommensurable, dan setiap paradigma juga sepakat untuk agree to disagree; maka responsi terhadap komentar pakar hukum di atas bisa disusun. Penilaiannya bahwa pandangan Barrington Moore, Jr. “kontradiktif’" dan merupakan hambatan bagi upaya ‘memanusiakan riset sosial’ (versi yang bersangkutan), bisa dimaklumi. Penjelasannya, posisi keduanya memang berada dalam kubu paradigma yang berbeda. Sang pakar hukum berangkat dari karakteristik ilmunya yang bersifat normatif, yang mirip dengan asumsi dasar Post-positivisme,. Sementara itu, Barrington Moore, Jr. bersikap ‘netral’ terhadap posisi moral, karena bertumpu pada asumsi dasar Positivisme. Walhasil, sikap keilmuan keduanya tak bisa bertemu. Bahkan, posisi mereka berbeda secara diametral.
Hikmah dari tanggapan balik di atas, beberapa isu bisa diulas. Pertama, kita nampaknya perlu jeli terhadap ciri setiap ilmu yang sedang disoroti. Pasalnya, masing-masing disiplin ilmu punya karakteristik distingtif yang menentukan pilihan paradigmatik. Dalam riset sosial, paradigma punya peran strategis. Paradigma keilmuan merupakan titik totak keberangkatan suatu proses penelitian. Paradigma bukan hanya berfungsi memandu peneliti dalam menentukan jenis pertanyaan, tetapi juga membantu menetapkan pilihan metodologi serta kriteria kelayakan penelitian. Pemahaman terhadap paradigma akan membantu mengawal konsistensi peneliti, karena bisa memperkecil potensi ‘tersesat’ dalam proses penelitiannya.
Kedua, pentingnya konsistensi keilmuan merupakan jawaban terhadap pertanyaan pakar diplomasi di atas. Konsistensi semacam ini akan menentukan kelayakan dari sebuah riset sosial. Mengingat bahwa ilmu Sosial adalah disiplin ilmu dengan multi-paradigma, maka pemahaman yang baik terhadap setiap varian-nya akan membantu konsistensi proses penelitiannya. Kala sang pakar diplomasi menanyakan apakah penelitian Post-Modernisme tidak boleh bercita-rasa Modernisme, saya menjawab: “Sependek pemahaman saya, normatif-nya tidak bisa. Saya berpandangan bahwa pemahaman ‘tertib keilmuan’ itu penting. Apalagi di lembaga akademis, seperti program Doktoral, sebagai garda dan pengembang ilmu”.
Tapi, konsistensi keilmuan tidak hanya diperlukan dalam proses penelitian. Secara imperatif, konsistensi akademis juga dituntut dalam menilai dan menguji hasil penelitian, termasuk disertasi. Dalam konteks ini, penguji perlu menyadari, sekaligus memahami, paradigma yang dipakai mahasiswa dalam riset disertasinya. Argumennya, sekali lagi, masing-masing paradigma adalah incommensurable, di mana kriteria satu paradigma tak bisa dipakai untuk menilai paradigma yang lain. Seandainya dalam ujian tugas akhir mahasiswa masih ada yang menguji dengan menggunakan paradigma berbeda dari paradigma yang dipakai mahasiswa, maka perlu dibangun pemahaman bersama di antara para penguji. Pasalnya, jika kondisi semacam ini terus terjadi, selain tak elok dari sisi kepatutan akademis juga mengurangi fairness baik dalam ujian skripsi, tesis, maupun disertasi. Wallahu’alam....
Advertisement




















