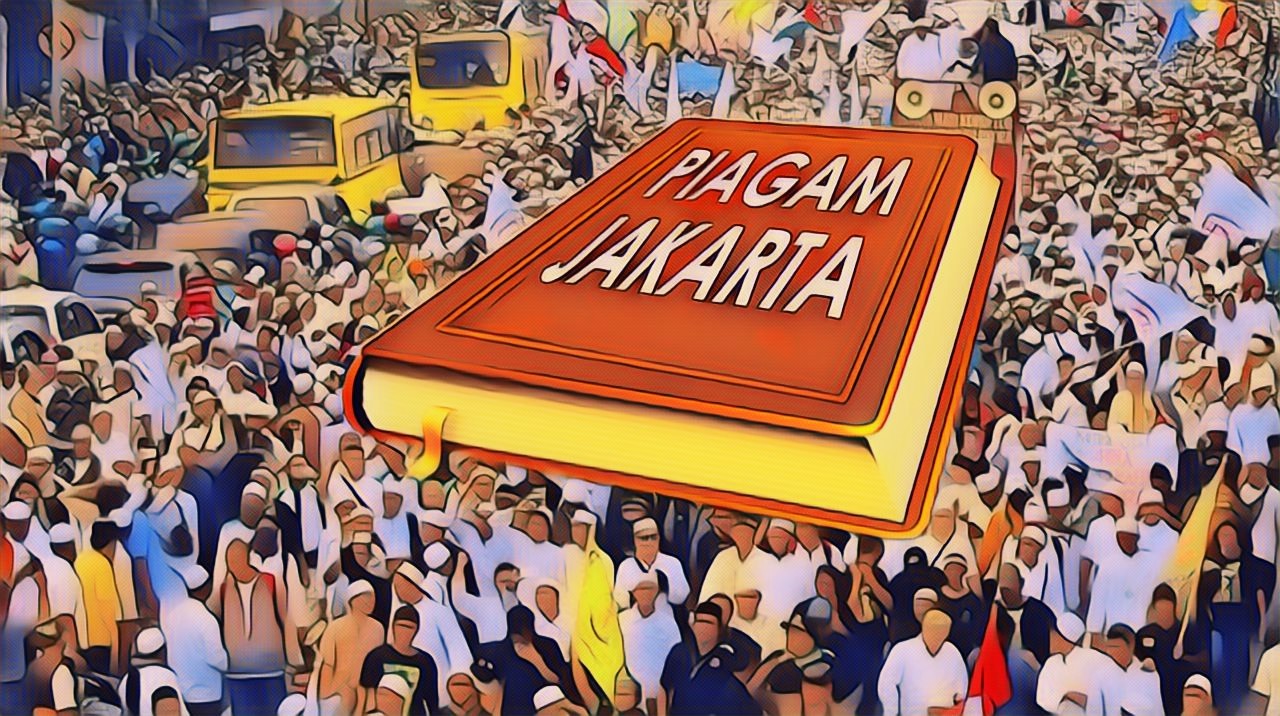Masihkah Mahasiswa Agen Perubahan, Arbi?
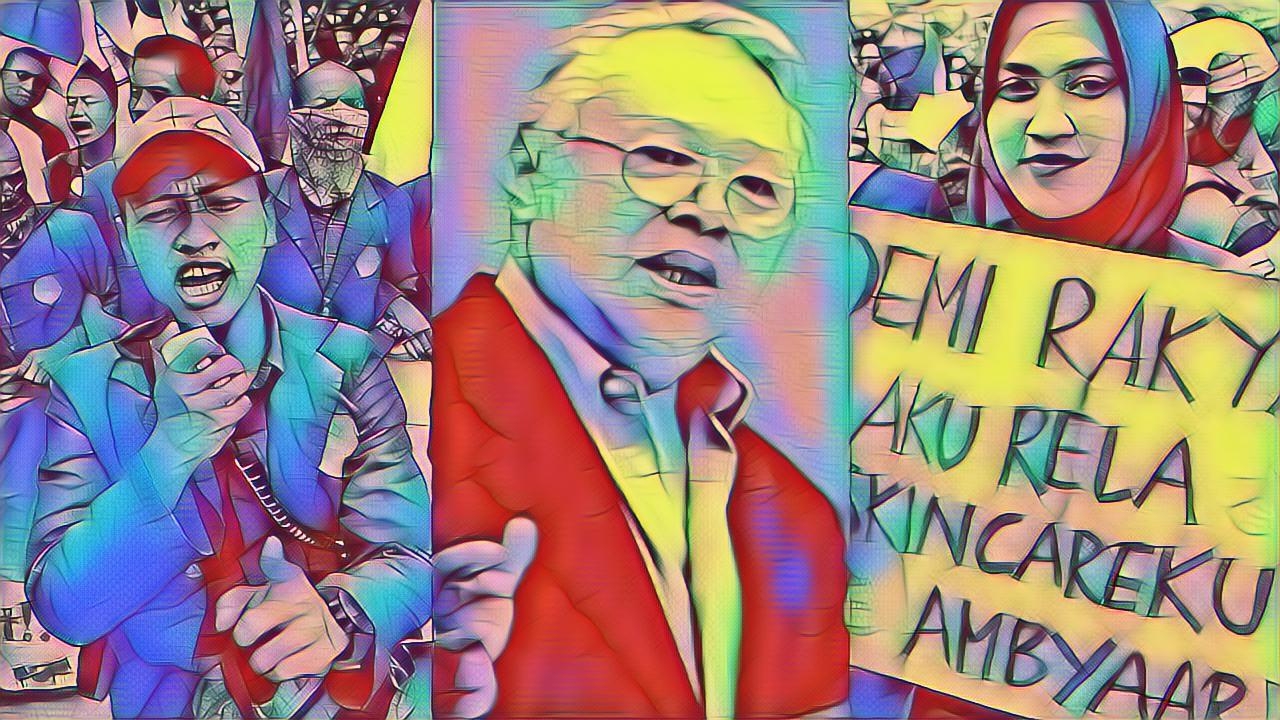
oleh: Riadi Ngasiran
Kaum muda dan mahasiswa adalah agen perubahan (agent of change). Kata-kata itu seolah menjadi doktrin yang diterima seorang anak muda di masa jauh sebelum reformasi. Ia yang belajar memahami sejarah bangsanya, memahami perubahan sosial yang terjadi di hadapannya.
Maka ketika reformasi bergulir pada 1998, ia menyaksikan perubahan-perubahan terjadi: kekuasaan pun tumbang dalam gelombang demonstrasi mahasiswa di seluruh kota di penjuru negeri.
Adakah spirit saat itu sekadar menumbangkan suatu rezim? Ataukah ada kebenaran yang ditegakkan? Siapakah yang dibela? Berebut kuasa atau hanya aktualisasi diri?
Sederet tanya pun kembali hadir, ketika sekelompok mahasiswa penuh beringas dalam kongresnya: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Surabaya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Balikpapan.
Keberingasan kaum muda, sebagaimana ditunjukkan 23 Maret 2021 malam, membanting kursi, melempar kayu dan kerusuhan dan sidang dalam Kongres HMI di Islamic Center Surabaya. Polda Jatim akhirnya mengamankan enam pesertanya sebagai pelakunya atas permintaan panitia. Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta enggan menyebutkan siapa dan berasal dari mana oknum yang menyebabkan kericuhan itu.
Soal gerakan mahasiswa, di antara akademisi-aktivis yang konsen mengiringi perubahan sosial, Arbi Sanit. Gerakan mahasiswa sejak 1966 hingga tumbangnya Orde Baru telah menunjukkan peranan mereka dalam mengukir sejarah.
Arbi Sanit memang lebih suka membahas mahasiswa. Tapi ia tak pernah bilang ulama tak berperan. Ia mempersilakan bahas ulama jika memang keahlian seseorang.
Masihkah mahasiswa sebagai Agen Perubahan, Arbi?
Tak ada perubahan yang berarti dalam kehidupan berbangsa setelah lebih 20 tahun reformasi karena memang tidak ada arah perjalanan yang jelas. Reformasi hanya berjalan sebatas amandemen konstitusi, selanjutnya relatif tak ada perubahan. Tak ada perubahan karena tak ada arah dan sudah terjebak oleh perangkap Orde Baru sejak awal.
Jebakan itu adalah tampilnya Wakil Presiden pada era Orde Baru, BJ Habibie sebagai presiden pada era reformasi. Masyarakat kala itu seharusnya menolak. Habibie merupakan bagian dari Orde Baru, seharusnya mundur bersama Soeharto. Kepemimpinan Presiden Habibie selama sekitar satu tahun membuat ada kompromi antara tuntutan reformasi dan Orde Baru, sehingga tidak ada pejabat rezim Soeharto yang diadili di pengadilan.
Setelah era reformasi realisasi dari tuntutan masyarakat yang menguat pada proses reformasi secara berangsur-angsur melemah. Tokoh-tokoh reformasi seperti Amien Rais dan KH Abrurrahman Wahid, tak berdiri pada posisi netral, tapi terjebak dalam jebakan Orde Baru: dengan mendirikan partai politik.
Bukankah pula Amien Rais ikut bergabung bersama Akbar Tandjung dan BJ Habibie pada organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang notabene adalah bagian dari Orde Baru.
Pada dekade ketiga era reformasi, hak demokrasi berpendapat dan berkumpul warga, sedang memuncak dijadikan gerakan politik, terutama oleh golongan pemolitisasi agama. Sedang memuncak politisasi aksi massa dan idelogisasi agama, terutama Islam.
Sudah barang tentu tren politik mutaakhir ini, merupakan potensialisasi saingan dan bahkan alternatif NKRI. Jika benar begitu, maka menjadi tanggung jawab pemimpin dan aparat negara untuk mengantisipasinya secara sistemik dan terukur, sehingga tidak malah menjadi ancaman pula bagi demokrasi.
Sejumlah kesaksikan menjadikan kita terngiang Arbi Sanit. Kesaksian seorang yang pernah turut serta ke kancah perubahan sosial di masa gemuruh reformasi, 1998.
Kini, telah 4 kali Pemilihan Presiden era reformasi, survei semakin mencekoki pemilih, karena menonjolkan popularitas dan atau eletabilias tinggi Capres. Di negeri maju, teknik lugu seperti itu lazim, tidak menipu pemilih yang lebih kritis atau fanatik Capres.
Tapi di Indonesia, survei independen perlu membantu pemilih supaya kritis, dengan menyertakan analisis kritis tentang calon saat peluncuran hasil survei, sehingga ada beda dengan survei oleh aparat Capres. Surveyor independen tak jadi alat Capres, secara langsung atau tidak. Gagasan ini, ada baiknya diberlakukan sama terhadap survei Kepala Daerah.
Realitas di masyarakat menunjukkan, pemimpin daerah cenderung berpolik dinasti karena berlingkup Masyarakat Primordial; pemimpin nasional yang berbasis masyarakat majemuk lebih berpoliti pluralis. Kecuali pemimpin Nasional yang berbasis keluarga. Maka, pemilih perlu cermat memilih calon kepala daerah, supaya nanti negara tidak dikuasai dinasti pemimpin nasional.
Kuasa-Raja, Kegagalan Kader Partai Politik?
Pada beberapa tahun terakhir, Arbi Sanit menyaksikan musim membangkit kerajaan, bukan saja simbolik tapi disertai istana, raja dan ratu, punggawa, dengan pakaian dan upacara resminya. Ada yang menanggapi sebagai gejala kultural, ada yang menerima sebagai hak berkumpul dan berorganisasi. Tapi perlu dilihat secara politik. Gejala itu membahayakan visi bernegara masyarakat yang gagal dimatangkan oleh penguasa dan pemerintah.
Malah kelakuan korup dan gila hormat penguasa membentuk ketidakpercayaan politik. Meski begitu, konsepsi dan institusi negara Indonesia mesti dihormati oleh warga negara. Tidak etis, tidak pantas dan lazim orang dan kelompok membentuk organisasi dengan label kerajaan yang berarti negara. Pembiarannya, memberi peluang membentuk khilafah, imperium, kemaharajaan, yang semuanya itu mengacaukan konsepsi bernegara. Maka kelompok dan organisasi pembentuk kerajaan atau negara, perlu ditertibkan istilah, atribut sampai upacara dan tempatnya.
Presiden Joko Widodo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini (ketika itu) adalah bukti otentik kegagalan partai politik Indonesia. Gagal mencetak kader handal untuk memenuhi kebutuhan negara memperoleh pemimpin pemersatu dan pembaharu. Maka, dalam orientasi mereka, tugas partai prioritas tertinggi. Lainnya tak urgen, kecuali memberi keuntungan pribadi politisi partai.
Kapan partai mulai mengabdi kepada bangsa dan negara? Jangan terus-terusan bohongi rakyat? Arbi Sanit tak sedang bergumam dengan tanya.
Bagaimana bisa, pemilik akal sehat dibuat percaya, bahwa kondisi global dan Indonesia dewasa ini mirip dengan menjelang kejatuhan rezim Orde Baru Soeharto?
Dalam kesulitan rakyat dan negara, penguasa yang sedang memusatkan kekuasaan justeru membangun besar-besaran. Lalu, bagaimana penguasa dan partai pendukungnya bisa begitu yakin bahwa pembangunan yang dipaksaka alias diakali itu tidak akan menggerus prinsip dasar demokrasi: HAM dan kebebasan serta keadilan? Itulah esensi kehadiran krisis diakhir tahun 1990-an yang sejak awal tahun 2000an muncul kembali?
Arbi Sanit, pernah menulis catatan pada 31 Desember 2019. Ketika itu, masah setelah perayaan demokrasi, pemilihan presiden dan hadirnya kabinet baru, Kabinet Indonesia Maju.
Keliru anggapan bahwa penguatan konsentrasi kekuasaan penguasa telah aman. Pertama, di dunia semakin bergolak, terutama ekonomi, politik semakin rentan.
Kedua, pemusatan kekuasaan kaum elit, adalah momentum, karena ekspressi kepentingan semakin cepat berubah.
Ketiga, elit Indonesia amat tidak kohesif, tergantung kemampuan pemimpin menyatukannya.
Keempat, massa tidak bisa dikekang, terutama saat penguasa tidak memuaskan, mereka bisa berbalik dipicu isu sederhana.
Kelima, pemilih pemenang Pilpres dengan mayoritas tipis, jauh dari mayoritas rakyat.
Pilpres dan Perayaan Demokrasi
Secara hakiki Pemilihan Presiden, penanggung jawab kondisi negara amburadul bukan presiden, melainkan survei penyaji data capres berelektabilitas dan popularitas tertinggi.
Di dunia, Sistem Presidensial berbasis multipartai tidak pernah stabil dan efektif, karena terjebak bergaya Sistem Parlementer. Aneh, partai berideologi Agama justeru terjebak oleh Sistem Multipartai, yang amat mungkin karena yakin kebenaran mazhabnya diridhai Yang Maha Kuasa, sehingga tokoh berbeda tidak percaya diri untuk menantang Tuhan, sehingga cari aman dengan bentuk partai sendiri.
Dengan begitu, berdasar spektrum ideologi untuk presidensialisme, Indonesia bisa jadi membentuk sistem Dwi Partai berdasar koalisi partai-partai berspektrum Ideologi Nasionalis dan Demokrasi. Mungkin PDIP-NasDem-Gerindra jadi koalisi Nasionalis dan Partai Demokrat-Partai Golkar ?
Jadi Koalisi Demokratik, dengan ketentuan partai agama yang ingin bergabung harus menyesusikan diri. Lebih jauh, Presidensialisme mempersyaratkan koalisi permanen demi kelanjutannya secara demokratik. Maka, presidensialisme Indonesia bergaya parlementerialisme juga memerlukan penyesuaian Sistem Pemilu Proporsional menjadi Distrik.
Pada 22 Desember 2020, Arbi Sanit menyampaikan dua saran untuk Presiden Indonesia, 1). Ketegasan Jenderal Hadi, Panglima TNI, mamberangus garakan menuju Negara Islam, dengan memerintahkan penegakan NKRI, amat tepat karena tuntutan sejarah Indonesia. Setepatnya presiden memberi bintang jasa kepada Jenderal Hadi. 2). Rakyat Indonesia sudah amat capek bertahan dari pandemi Covid-19. Setelah kembali normal lama atau baru, setepatnya Presiden berhenti melanjut megaproyek legasi ini. Selesaikan saja masa tugasnya demi kemajuan hidup rakyat dengan santai. Toh, kalau dipaksakan kemajuan cepat dan mega, hanya elit yang akan menikmati langsung.
Tiga dekade pembangunan besar-besar Orde Baru, terbukti hanya secuil dinikmati rakyat kebanyakan. Sistem yang ada belum mampu menjamin keadilan. Terima kasih bila diperhatikan. Semoga. Demikiain Arbi Sanit penuh optimistik.
Soal UUD '45 dan Realitas Politik Kini
Berdasar Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diakui dan digunakan sebagai pegangan semua rezim dan sistem politik pemerintahan menyusul Proklamasi, 3 Konsepsi Bernegara yang terlembagakan yakni Pancasila-Negara Kesatuan-Negara Republik. Maka demokrasi sebagai kedaulatan rakyat (:republik) tidak pernah dihilangkan dari cita-cita bernegara, sekalipun dalam praktiknya dikemelutkan oleh rezim demokrasi liberal dan dibengkokkan menjadi otoriter oleh rezim Orla dan Orba, sehingga dikutuk sebagai pengkhianat konstitusi, karena mengakui demokrasi lewat penerimaannya atas Pembukaan UUD 1945, sementara demokrasi diancam dan dikekang dalam praktik bernegara.
Beberapa sikap dan tindakan penguasa yang mengancam sampai menangkap pengeritik dan oposisi dibawah Presiden Joko Widodo, jika tidak segera dikoreksi secara mendasar, sudah barang tentu akan mengalami nasib sebagaimana pendahulunya dimaksudkan, yakni menghadapi kutukan sejarah politik: mengkhianati demokrasi Indonesia.
Bagaimanapun, tentu boleh dan sah mengulang sejarah kebaikan, tapi bukan sebaliknya.
Arbi Sanit kerap menegok sejarah. Peringatan bagi para pendamba dan pejuang UUD 1945 asli yang terbukti digunakan untuk mendirikan pemerintahan otoriter oleh rezim Orla (Demokrasi Terpimpin) dan Orba (Demokrasi Pancasila); pejuang negara Komunis ( :PKI) dan negara Islam (:DI/TTI) yang masing-masing memberontak di Madiun dan Aceh; para pengagum penguasa diktatur sipil-militer (Orla) dan diktator militer (Orba); para penafsir liar Pancasila; dan pencinta kerajaan budaya; serta pencinta sentralisme kekuasaan negara yang anti-demokrasi (:HAM, kebebasan); bahwa semuanya itu telah terbukti gagal dan menyisakan masalah dendam.
Bukti sejarah lebih 7 dekade merdeka, sebaliknya menunjukkan kebenaran tiga institusi atau konsepsi bernegara -- yakni Pancasila, Negara Kesatuan dan Negara Republik -- yang saling melandasi, sehingga tidak diperlukan cari-cari dalih. Republik memastikan Pancasila dan Negara Kesatuan bermakna Demokrasi.
Negara Kesatuan memastikan Pancasila dan Demokrasi tidak buyar oleh tradisi primordial dan hak individu dan kelompok. Dan Republik memastikan kedaulatan adalah milik rakyat yang berhak menentukan penafsiran dan penerapan Pancasila dan Negara Kesatuan.
Adalah menghemat energi masyarakat-bangsa-negara, bila berdasar 3 konsepsi/ institusi bernegara tersebut, segala pikiran dan langkah, difokuskan untuk memperbaiki kelemahan selama ini, sambil menciptakan pembaruan menuju masa depan yang lebih baik. Jadi, insaflah bahwa kita telah punya landasan konsepsi atau institusi bagi memoderenkan dan membesarkan negara ini. Tinggal memanfaatkannya secara inivatif dan optimal, menggunakan rasio dan akal sehat secara bijak dan cerdas.
Para penanggap, kelemahan dasar UUD 1945 asli adalah sistem Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi mandataris MPR bisa berkuasa sendiri (=mutlak) seperti Presiden Sukarno dan Soeharto, sekalipun Pembukaannya berisi NKRI yang berarti Negara Kesatuan dan Kedaulatan Rakyat (=demokrasi). Makanya direformasi oleh SU MPR hasil Pemilu 1999 via amandemen yang menghasilkan UUD RI 1945.
Maka itu tidak palsu, sekalipun sistem presidensialnya tidak sempurna, antara lain presiden berpelung memperkuat kuasanya, tapi tidak langsung presiden menjadi penguasa tuggal sebagai mandataris MPR. Tapi perlu kelicikan presiden mengakali DPR dan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat kekuasaan, seperti dilakukan Jokowi.
Akhirul kalam
Di tengah dinamika masyarakat dan negara, di masa pandemi Covid-19, ada kabar duka: Arbi Sanit meninggal dunia. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Kamis 25 Maret 2021 pagi. Ia meninggalkan jejak pemikiran yang kritis, dalam mengiringi perjalanan bangsanya.
Sebelum mengakhiri masa-masa bertugasnya, Arbi Sanit menyaksikan perubahan politik dunia, dari Donald Trump ke Joe Biden. Ternyata Pemilu Amerika Serikat (AS) mirip Indonesia: Capres bersikap dan bertindak asal menang dengan menggunakan cara apa saja, setidaknya utak-atik prinsip via praktik demokrasi. Tapi, setelah akhirnya menghadapi kegagalan berkuasa, apakah nasibnya juga akan sama: mengulang transisi demokrasi?
Memang, ada anggapan AS adalah negara yang sistemnya telah mapan, siapa pun yang berkuasa sama saja. Bagi Arbi Sanit, sistemnya sudah mapan, tapi manusia pemimpinnya yang selalu berganti; pada saat masyarakat lengah, memberi peluang kepada tokoh petualang untuk tidak selalu mengikuti alias terkontrol oleh sistem.
Arbi Sanit, betapa pun telah mengingatkan kita bahwa telah terbukti multipartai di Indonesia tidak produktif karena merentankan stabilitas akibat konflik dan jadi amat mahal. Multipartai adalah padanan sistem Politik Parlementer. Di Amerika Latin menggagalkan sistem Presidensil.
Demokrasi politik, ekonomi, sosial di Indonesia baru bisa stabil, bila kekuatan tengah, moderat-radional-akal sehat, bersatu pemimpin partai politik dan elite yang cerdas.
Bila para elite dan aktor politik melakukan politisasi dan komersialisasi agama, niscaya mendistorsi kemajuan negara-bangsa Indonesia. Nilai kolektivisme-gotong royong di masa Orde Lama dan Orde Baru melumpuhkan rasio individu kini, sehingga mudah terseret hoaks dan kekerasan massa.
Kini, kata demokrasi kekuasaan itu diperebutkan luas dipersaingkan secara jujur dan adil. Arbi Sanit akhirnya menyadari, puncak kesulitan orang Indonesia bersikap tegas dimasa hukum belum optimal tegak, adalah memilih keberpihakan, di antara 3 kekuatan: kodrat Kemanusiaan, dan kekuasaan NKRI serta gerakan sistematik mengujikan kekuasaan Negara Islam.
Arbi Sanit adalah orang yang terpikat dengan gerakan mahasiswa, hingga ia pun mempergulatkan di tengah perubahan sosial pada era reformasi. Ia tak sekadar menghadirkan diskursus. Ia pun tampil dalam mengejawantah dan memberi makna yang nyata.
Di ujung hayatnya -- barangkali tak lagi sadar karena sakit -- di tengah kongres organisasi kemahasiswaan berlabel "Islam" penuh gemuruh dan rusuh. Mereka tak sedang melakukan perubahan sosial. Tapi, menorehkan catatan tentang gejolak jiwa. Arbi Sanit tak tahu kenyataan itu.
Kekisruhan adalah jiwa kaum muda? Barangkali ada pemakluman bila pemuda dalam pengertian kaum awam. Tapi, mereka (peserta kongres itu) adalah pemuda dalam kalangan khusus, kaum terpelajar, yang akan menorehkan jejak dan bertanggung jawab atas masa depan bangsanya.
Di kejauhan, seorang yang tak pernah belajar di kelasnya, bersoloroh penuh gumam. Masihkah kaum muda dan mahasiswa sebagai agen perubahan, Arbi?
Advertisement