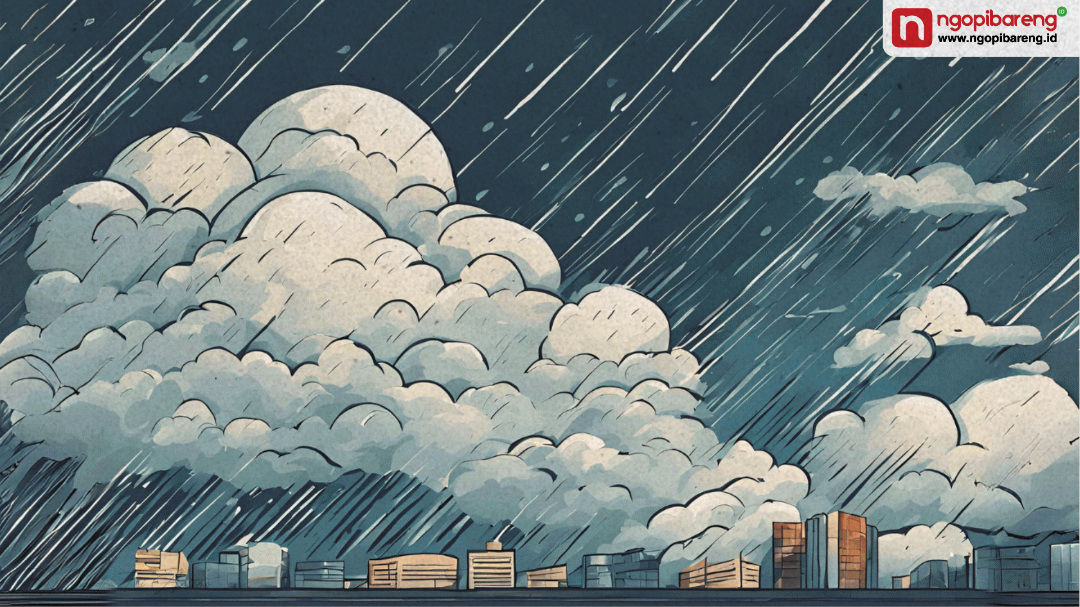Lik Man, Kang Paidi, Yu Minem apa Pensiun Membuat Kopi?

Dulu Lek Man, Kang Paidi atau Yu Minem kita percaya untuk membuat kopi. Kemana mereka sekarang?
_______________
Sekarang, ada anak muda necis, bersih dan rapi. Kita menyebutnya barista.
Di Klinik Kopi, Jogjakarta, barista bicara banyak. Waktu saya mampir dia cerita perjalanannya ke Sumatera, lengkap dengan video yang diputar di belakang.
Dia bercerita panjang lebar. Soal siapa nama petani kopinya. Lalu jenis bean-nya, juga teknik rostingnya. Persis obrolannya yang terekam dalam film AADC 2 juga hits bukan main.
Saya sampai ge er, serasa jadi Rangga. KW3. Mendengar cerita barista itu.
Di warung kopi lain, ceritanya sama. Barista bicara banyak soal kopi. Asal kopinya, kelebihannya, rasanya, efeknya, asam pahitnya.
Panjang lebar juga, padahal kita tak paham banyak yang dia bicarakan. Lalu, dia membuat kopi, memanaskan air pada suhu yang tepat, menimbang biji, menggilingnya, lalu menyeduh dengan cara yang berbeda-beda.
Ada sekian banyak jenis yang harus dipilih dari daftar. Padahal intinya sama: kopi.
Ritual ini, bagi sebagian kita kian menjadi tradisi. Ada kopi di rumah, tapi tak mantap kalau tak pergi keluar. Seolah barista dikirim Tuhan untuk menentukan rasa secangkir kopi. Dan kita tak bisa menolaknya.
Dia bahkan mengajari kita cara minum kopi yang benar. Cara minum kopi sodara-sodara, sementara cara umum yang dipraktekkan sejak baheula itu dikata tak tepat.
Dan orang-orang bilang kopi itu diminum tanpa gula.

Sementara bagi Lek Man, Kang Paidi dan Yu Minem, kopi enak itu kental dengan gula dua sendok.
Jangan bicara soal harga. Tubruk biasa bisa dibayar empat ribu segelas. Yang dibuat dengan ritual khusus oleh seseorang yang kita sebut barista itu, harganya lima sampai sepuluh kali lipat. Bahkan lebih.
Jika ini berlanjut, dan dongeng para barista itu menjadi semacam petuah yang harus dituruti. Dan ritual adalah tata cara dan tata krama yang harus diikuti demi secangkir kopi, apakah kita akan kehilangan kemampuan alami untuk membuat kopi sendiri.
Apakah akan ada masa dimana kita ragu pada tangan sendiri untuk menyendok kopi dan merasa berdosa ketika menabur gula di atas cairan hitam itu?
Padahal, dalam perbincangan dengan kawan-kawan lama, kopi adalah bahasa universal. Kopi meruntuhkan perbedaan pandangan politik. Kopi melembutkan hati cebong dan meredam emosi para kampret.
Di atas kopi, perbincangan selalu produktif. Tentang apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama penghuni kebun binatang besar bernama endonesah.

Tapi, para fakir semacam kami tentu kaya akan kata-kata dan tak cukup mampu memesan kopi ke para barista setiap hari. Padahal kopi harus ada, dalam pertemuan dan perbincangan. Jika tidak, pertemuan cebong dan kampret semacam ini akan menjadi semacam kurusetra.
Jadi, kita harus melestarikan pilihan untuk menikmati kopi tanpa barista. Tanpa ritual dan cerita-cerita dengan kosa kata seperti bean, roasting, latte, vietnam dip, cappucino, dan antah berantah lain.
Kita harus tetap diijinkan untuk tetap merebus air dalam ceret tembaga, menyendok kopi dan gula sesuka hati, lalu menikmatinya dengan merdeka.
Kopi adalah kopi. Kepadanya kita menyerahkan diri dan masa depan bangsa ini. Kepada kopi pula, kita bisa berharap pendukung Jokowi dan Prabowo bisa menikmati kehangatan obrolan di atas uapnya.
Seduhlah kopi di seluruh Nusantara. Separuh persoalan bangsa ini akan selesai dengan sendirinya. nurhadisucahyo/idi
Advertisement