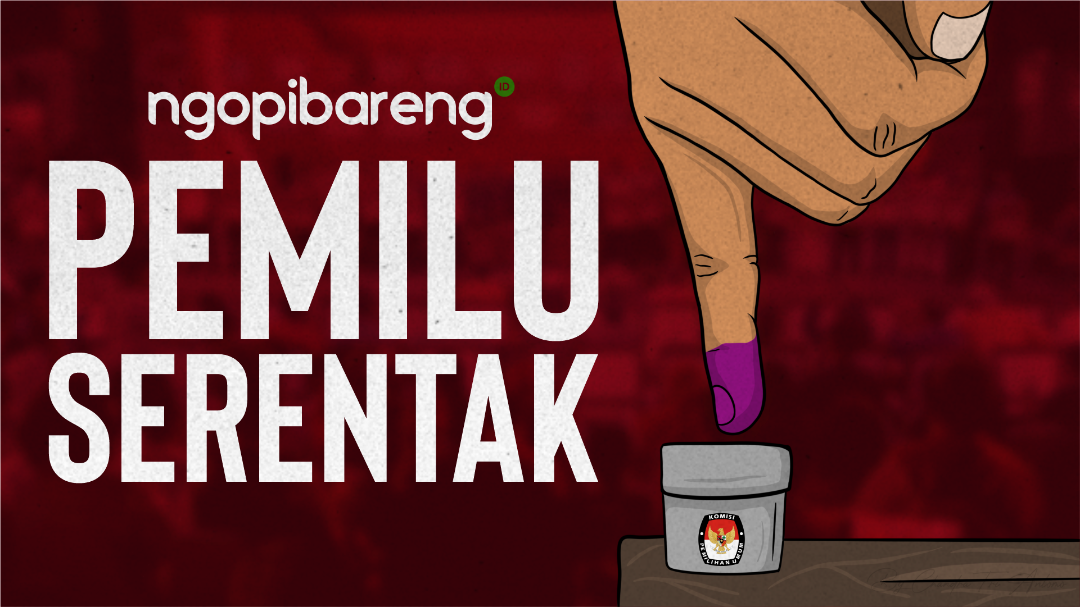Kotak Pandora Perang Ukraina

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Sudah lebih dari sebulan perang Ukraina masih tetap berlanjut. Memang telah ada upaya perundingan untuk perdamaian antara Ukraina dan Rusia di Istambul, Turki. Namun, masih terlalu prematur untuk mengharapkan hasil konkritnya. Yang semakin tersingkap justru rekam jejak dalam perang tersebut. Kedua belah pihak yang berperang —beserta pendukungnya— berhadapan di dua front: medan tempur dan medan opini. Seiring dengan semakin canggihnya media komunikasi, pertempuran opini bukan hanya wajar tetapi sudah menjadi bagian dari perang itu sendiri.
Perkembangan mutakhir, opini sudah menyerang pribadi. Presiden Joe Biden menyebut Presiden Vladimir Putin sebagai seorang “jagal” (butcher). Ungkapan ini adalah sebuah ekspresi yang lebih keras dari penyebutan sebelumnya, seperti “penjahat perang” (war criminal) dan “dikator pembunuh” (murderous dictator). Sulit untuk tidak mengatakan bahwa ungkapan Biden ini adalah bagian dari ‘strategi pembingkaian’ (framing strategy). Apalagi, di tengah kekawatiran dunia akan statemen Biden tersebut—bahwa penilaian yang mengarah pada penghinaan pribadi akan membuat eskalasi perang, dengan enteng Biden menjawab: “saya tidak akan mencabut pernyataan tersebut, karena itu bagian dari ‘kemarahan moral’ (moral outrage) saya!”.
Dengan pernyataannya di atas, Presiden Biden mungkin punya standar moral tersendiri. Permasalahannya, framing strategy senantiasa berdiri di tubir jurang distorsi. Tapi, media Barat justru sering bermain framing strategy dengan berselimut bias opini. Misal, di jagad maya Human Rights Watch Watcher menguak framing strategy yang dilakukan oleh The Economist—sebuah majalah mingguan Inggris. Pada edisinya tahun 2003, sesaat setelah invasi Amerika Serikat ke Iraq; dengan sampul bergambar foto George Bush yang ‘anggun’, The Economist menayangkan topik utama: “Sekarang [waktunya], untuk mengobarkan perdamaian (Now, the waging of peace)”. Sebaliknya, tak lama pasca invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 ini, edisi majalah tersebut secara kontras menampilkan gambar sampul sosok hitam Vladimir Putin yang ‘menakutkan’—dengan simbolisasi otaknya yang dipenuhi tank Rusia, disertai mata tajamnya yang dilambangkan dengan moncong pesawat Sukhoi—dengan topik utama: “Dimana dia [Putin] akan menghentikan [invasinya]? (Where will he stop?)”. Simbolisasi gambar sampul dan tajuk utama yang kontras ini bukan sekedar bias, tapi menunjukkan pemihakan the Economist pada langkah Barat yang dipimpin Amerika Serikat.
Yang menarik—tapi sekaligus memprihatinkan—bias nampaknya juga telah merambah kebijakan kemanusiaan. Perdana Menteri Kanada—Justin Trudeau—dengan mudah menyambut hangat kedatangan banyak korban luka perang Ukraina akibat hantaman peluru dan bom Rusia. Sangat mungkin, keputusan ini dilandasi pertimbangan relatif besarnya jumlah keturunan Ukrania di Kanada, yang konon mencapai jumlah 1,3 juta orang. Tetapi, sebaliknya, Trudeau—entah apa alasannya—enggan menerima 100 orang anak Palestina yang terluka oleh peluru dan bom Israel untuk mendapatkan bantuan medis di negaranya. Memang, jumlah keturunan Palestina di Canada hanya sekitar 44.000 orang. Sebuah jumlah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan komunitas keturunan Ukraina. Tak heran, jika kemudian Andrew Mitrovica—seorang kolumnis—menyatakan penilaiannya: “Jelas, bagi Trudeau, anak-anak Palestina yang menderita luka akibat perang tidak layak untuk dilindungi, tetapi anak-anak Ukraina yang luka akibat perang layak untuk dilindungi!”.
Apakah kalkulasi politik mendasari perbedaan perlakuan Trudeau tersebut, mengingat potensi dividen politik yang tidak setara seiring dengan proporsi jumlah dua komunitas yang tak berimbang? Apakah perbedaan perlakuan tersebut dipicu oleh persepsi dan stigma yang berbeda terhadap warga Palestina dan Ukraina? Pertanyaan semacam ini jelas tidak bisa dihindari. Apalagi, Canada merupakan salah satu konseptor ‘keamanan insani’ (human security), khususnya dalam menjamin manusia untuk ‘bebas dari rasa takut’ (freedom from fear). Dalam catatan sejarah, Lester Bowles Pearson—Perdana Menteri Canada (1963-1968)—pernah menegaskan: “komitmen dan tugas internasional ini adalah bagian dari identitas nasional Canada”. Sementara itu, Lloyd Axworthy—Menteri Luar Negeri Canada (1996-2000)—juga menandaskan bahwa Canada mempunyai kapasitas sekaligus kredibilitas sebagai pemimpin dunia dalam mendukung penjaminan human security.
Jika jawaban dari pertanyaan di atas adalah “ya”, maka itu merupakan signal stagnasi jaminan human security. Jika bias dalam kebijakan kemanusiaan semacam itu juga merupakan fenomena umum di negara-negara Barat, maka hal itu merupakan disrupsi proses keberadaban (civilizing process) politik dunia. Argumennya, berbagai perang di dunia, seperti Afghanistan, Libya, dan Syria—yang notabene dipicu oleh intervensi militer Barat di bawah komando Amerika Serikat—telah menyebabkan rantai tragedi kemanusiaan. Banyak pengungsi yang eksodus dari negaranya untuk menjadi imigran di negara-negara Barat guna membebaskan diri dari rasa takut (freedom from fear). Namun, yang memilukan, bias kebijakan kemanusiaan dari negara-negara Barat telah menjadi salah satu sebab banyaknya pengungsi yang terdampar di berbagai negara penampung sementara—termasuk Indonesia—tanpa kejelasan masa depan nasib mereka.
Perang dan berbagai bentuk kekerasan yang menyertainya—meminjam istilah Anthony Gidden—merupakan refleksi ‘sisi kelam dari modernitas’ (dark side of modernity). Tapi, ironisnya, perang Ukraina telah membuka kotak pandora problema kemanusiaan dalam politik dunia. Fenomena ini jelas menyesakkan dada, khususnya bagi Jürgen Habermas—seorang teoritisi Kritis—yang berkeyakinan bahwa gagasan tentang kemanusiaan bukan lagi sebuah utopia tapi sudah menjadi sebuah kebutuhan praktis. Sayangnya, negara yang seharusnya menjadi aktor pelopor gagasan kemanusiaan ternyata perilakunya justru sering menjadi bagian dari persoalan dalam penegakkan moralitas universal tersebut. Pada saat yang sama, Andrew Linklater—penulis Critical Theory and World Politics (CTWP)—harus juga bersabar dan tidak putus asa dalam menganjurkan transformasi masyarakat internasional untuk memiliki sensitivitas dan konmitmen kemanusiaan. Toh, seperti kata Michel Foucault; dalam setiap upaya pencerahan (enlightenment) isu utamanya bukanlah terletak pada pilihan antara bersikap baik terhadap negara atau melawannya, melainkan bagaimana melakukan transformasi orientasi dan komitmennya terhadap kemanusiaan. Wallahu’alam!
*) Himawan Bayu Patriadi, PhD. adalah dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember
Advertisement