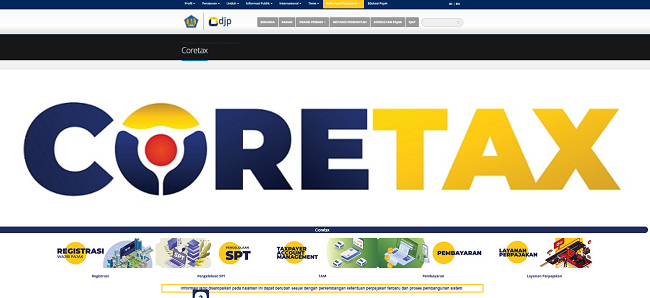Kopi Walik, Tradisi dan Modernitas

Surabaya “mendem” kopi. Demikian news Ngopibareng.id yang rilis kemarin (17/7). Ahaiii ini berita yang asyik. Kabar yang menggembirakan bagi dunia kopi yang memang sedang hits. Festival kopi bejibun. Susun-susun seperti anak tangga. Jarang-jarang di Kota Surabaya ada acara kopi sesemarak ini.
Semua acara festival kopi itu, selain memamerkan beragam jenis kopi, kedai-kedai kopi, dll, dihangatkan juga dengan kompetisi membuat kopi. Ada membuat kopi ala latte art, aeropress, V60, hingga membuat kopi dengan saring pring bambu yang sarat dengan nilai lokalitas.
Mumpung ada yang mendem kopi, mumpung juga ada yang mengusung tema lokalitas dalam kompetisinya, rasanya, asyik juga bicara kopi di luar teknik seduh kopi yang bakal dikompetisikan di atas.
Dunia seduh kopi, diluar gaya latte art, aeropress, V60, siphon, ibrik, french press, dll, yang bersinergi dengan fenomena gaya ngopi masyarakat urban, ranah tradisional mengenal gaya ngopi walik (semoga pernah mendengar dan pernah menyaksikan).
Gaya ngopi ini kesannya sederhana, hanya membuat kopi dengan teknik kopi tubruk lalu cara sajinya dengan membalik gelas. Gelas berisi kopi panas yang harusnya mendongak ke atas dengan sengaja dijungkirkan untuk langsung menempel pada lepek di bawahnya.
Sederhana. Sensasional. Eksentrik. Nyleneh. Nganeh-anehi. Kurang kerjaan. Tampil beda. Cari perhatian. Marketing. Cara dodolan. Gaya jualan. Ndeso. Tradisional. Hingga seabrek muatan yang berpusar di dalamnya.
Dari sederet kata ini muatan tradisional yang paling kuat berada di dalamnya. Sayangnya, dunia masa kini, tradisional identik dengan pinggiran. Pinggiran kerap dipersepsikan sebagai marjinal. Lalu, tradisional, pinggiran, marjinal melekat dengan persepsi rakyat jelata.
Kopi walik dengan gaya ngopinya memang menemukan "rumah"nya disana. Malah, sangat nyaman berada di rumah itu. Enggan berpindah bahkan menjadi malas untuk bergeser. Padahal dunia kopi tak pernah berhenti dan memiliki kemampuan untuk bergeser seiring dengan panggilan zaman.
Hingga hari ini, hingga media sosial begitu cetar membahana mempengaruhi semua lini kehidupan, rakyat jelata memahami biji kopi itu mahal. Maka cara sajinya adalah kopi dicampur dengan material lain di luar kopi seperti: beras, jagung, karak, kacang hijau, hingga kulit kopi. Maka di kalangan pencinta kopi rakyat jelata itu sangat familier dengan kosa kata gaya bebas seperti kopi jitu, kopi gempo, hingga kopi silit. Kopi Jitu sinonim kopi siji jagungnya pitu. Kopi Gempo, kopi siji jagunge sak tompo. Kopi silit adalah kopine siji kulite sak kranji.
Sungguh atraktif, tradisional, dan local wisdom. Sing penting mambu kopi dan pahit. Ra masalah bukan kopi asli sing penting ngopi.
Mari kita berandai-andai. Andaikan, kopi walik, ditarik sedikit keluar dari ranah local wisdom yang memahami biji kopi itu mahal, apakah kopi dengan gaya saji gelas dibalik masih jadi kopi tradisional kelas pinggiran?
Misalkan begini, material kopi walik bukan lagi kopi jitu atau kopi silit, melainkan kopi beneran seperti robusta Dampit, robusta Tirtoyudo, robusta Sumbermanjing, arabika ijen raung, arabika semeru, arabika arjuna, arabika Tango Karlo, arabika Bali , arabika Kintamani, arabika Gayo, arabika Toraja, Madheling, Wemena, Manggarai, Sunda Gulali, Sunda Mekar Wangi, dll, yang cita rasanya begitu menggugah dunia, apakah kesannya masih jadi kopi dan gaya ngopi pinggiran? Jawabnya, tergantung!
Mungkin itu yang disebut bangunan konstruksi sosial seperti yang pernah dibedah Michel Foucault dalam serangkaian buku-bukunya. Dibalik tradisi kopi walik yang eksentrik itu, boleh jadi masyakat tradisional jauh-jauh hari sebenarnya sudah bergelut dengan teknik seduh kopi dan bagaimana membuat kopi dengan sentuhan maksimal. Bahwa, teknik membalik gelas penuh kopi sejatinya mirip dengan laku infusi, atau bahasa lain yang kekinian adalah immerse dan kadang dibaca immersion. Sebuah ekstraksi kopi yang maksimal meski tanpa proses pengadukan.Jadi, siapa sangka, ternyata Kopi Walik yang tradisional itu menyimpan rahasia modernitas. widikamidi
Advertisement