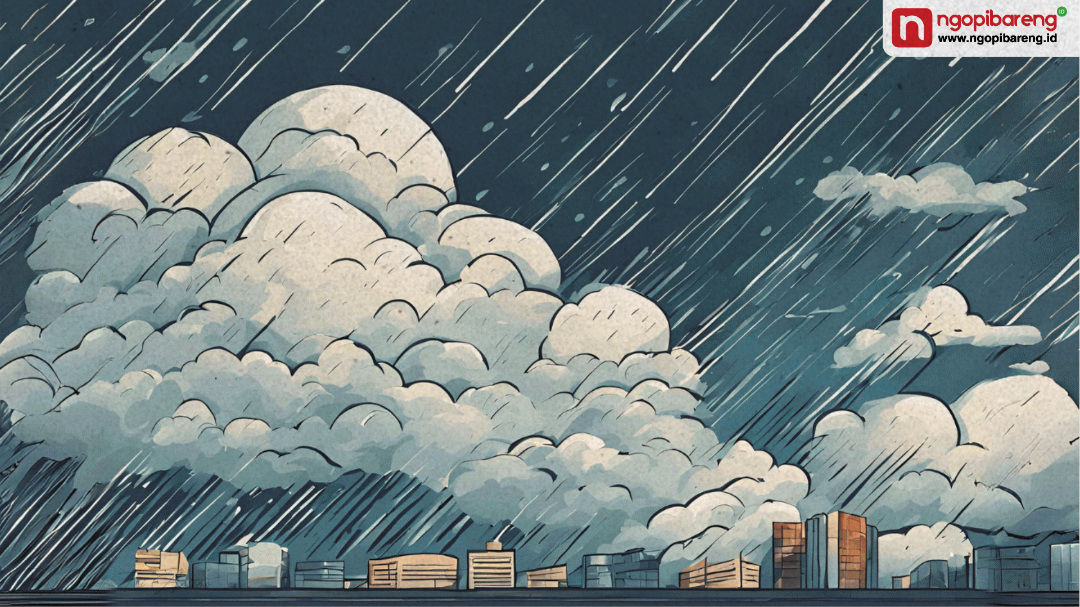Kopi Dispenser dengan Aroma Bukan Main

Kopi. Kopi instan. Pernah dengar? Tentu pernah-lah. Dengar lewat apa saja tentunya. Di radio sering berdengung iklannya soal itu. Di televisi, tayangan iklannya selalu menggoda dan selalu berhasil membikin lapar mata dan lapar hidung. Bintang-bintang iklannya juga selalu cool. Keren. Cantik. Ayu-ayu. Ganteng. Wis pokoke top-lah.
Saat ini kopi lagi naik daun. Topnya bukan main. Pamornya terkerek hingga ujung genting. Kopi menjadi macam-macam jenisnya. Tak hanya kopi instan yang iklannya begitu banyak berseliweran di media - setidaknya kopi model begini yang diketahui secara umum oleh masyarakat.
Dengan naik daunnya pamor kopi (baca: pamor kopi nusantara), apakah kopi instan masih cetar membahana di tengah isu kopi yang begini gemerlap? Gemerlap dalam arti: banyak orang merasa euforia dengan kopi, meninggalkan yang instan dan kembali ke kopi asli dari biji kopi.
Jawabnya adalah: masih. Masih cetar membahana. Masih seksi seperti Incess Syahrini.
Instanisme kopi itu identik dengan cepat dapat, cepat saji, sobek atau gunting, lalu currr air nanas. Eh panas! Cukup dengan air dari dispenser. Dan, segeralah tercium aroma kopi yang wanginya membahana ke seluruh ruangan. Menyerbu ke setiap cuping hidung dalam sesuatu jarak. Menggoda. Menarik hati untuk sekadar mengetahui ada orang sedang bikin kopi. Dan seterusnya.
Ah itu pasti kopi mahal. Aromanya kok begitu rupa ya. Itu pasti kopi Ethiopia. Atau kopi Panama. Atau Columbia. Atau mungkin dari varietas langka yang disebut Gesha yang harganya selangit itu. Bisa 700 ribu rupiah untuk per 100 gram-nya. Atau mungkin yang lainnya.
Salah. Rabaan yang salah. Itu dari kopi instan yang biasa saja. Murah pula. Tak sampai harga 2000 rupiah dalah satu kemasan saset.
Lalu? Ya. Itulah hebatnya instan. Bukan Panama Gesha, atau Gesha-Gesha lain dari wilayah yang berbeda.

Dahsyatnya kapitalisasi kopi, juga bermacam temuan teknologi pengolah kopi, membuat produk kopi dengan harga murah sangat terjangau mengalir ke pasaran seperti banjir bandang.
Saking bandangnya banjir itu, orang mengenal kopi atau sekadar beli kopi hanya perlu melihat kemasannya doang. Jadi, kemasan paling bagus, packaging paling indah, bisa dipastikan produknya akan terserap pasar dengan mudah.
Naif bukan? Sepertinya bukan! Sebab, kemasan, dipersepsikan sebagai pembawa pesan terhadap kualitas isi di dalam kemasan.
Tapi benarkah kopi instan menggerus semua segmen pasar kopi? Mungkin iya, namun sebagian kecil sepertinya tidak. Namun, perlahan-lahan yang kecil ini boleh jadi akan habis jua.
Coba jalanlah di beberapa pasar. Pasar beneran lho ya. Bukan pasar jadi-jadian. Pasar beneran itu pasar yang ada plang tulisan nama pasarnya. Sementara pasar jadi-jadian adalah pasar yang setiap saat selalu menderita ancaman diobrak Satpol PP.
Tapi sebenarnya pasar yang kategori jadi-jadian ini biasanya malah selalu ramai dan sedap oleh pengunjung. Kenapa ramai? Sederhana jawabnya, sudah pasti dia bisa menampung aspirasi pengunjungnya. Pertama: tidak jauh dari pemukiman, tidak jauh dari blok perumahan, bisa jalan kaki, bisa methangkring di atas sadel motor sembari transaksi, komplit plit dagangannya, tumpah ruah aksennya, termasuk barang-barang yang sudah berbau formalin dan seterusnya. Paling penting, bisa selisih harga

Kembali soal jalan-jalan muteri pasar tadi, singgahlah di Pasar Asem, di Surabaya. Ini wilayah perbatasan antara wilayah Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.
Di sudut nyempil di pasar itu bisa ditemui pedagang kopi bubuk. Kopi itu dia tumbuk sendiri. Kulak kopi mentahnya di pasar Pabean Surabaya. Disangrai sendiri. Kemudian ditumbuk sesuai selera pelanggannya yang makin kusut.
Nama penjual kopi ini Nurali namanya. Usianya sepertinya lebih banyak dari 60 tahun. Kering kurus dengan kulit coklat karena kepanasan. Kelahiran dan asalnya Pekalongan.
“Pekalongan itu juauhhh mas, Jawa Tengah sana. Naik bus perlu oper ping empat. Dua ratus ribu habis kalau harus pulang kampung. Di Pekalongan saya ini ndak bisa membatik mas, jadi saya kabur saja trus jualan kopi seperti ini," katanya.
Pekalongan memang terkenal daerah batik. Reputasi Nurali jualan kopi bubuk ini tak kurang dari 42 tahun. Setia betul dia jualan kopi bubuk meski pasarnya kusut seperti kumis kelinci yang sedang rontok bulunya.
Dia juga enggan pindah profesi. Cinta katanya. Meski penghasilan tak lebih dari 40 ribu (kotor) dalam sehari. Dia cukup senang kalau ada orang minum kopi beli bubuknya sama dia. Itu sudah cukup.
"Kadang sehari hanya dapat tujuh belas ribu mas. Tapi itu juga harus disujudsyukuri,” kata dia.
Coba saya pun membeli setengah kilo kopi bubukan. Kopi paling enak buatan dia. Katanya tiada campuran jagung kalau yang paling enak ini. Kopi Robusta. Harganya 60 ribu sekilo. Jadi saya cukup membayar 30 ribu untuk setengah kilo.
Di Pasar Asem, kata Nurali, setidaknya sudah lebih 15 tahun kopi buatannya menjadi penghuni pasar ini. Sekian lama dan sekian hari dia bertempur market dengan bermacam kopi pabrikan dengan beragam wajah. Hingga bertempur melawan kopi limaratusan alias mangatusan dengan kemasan sachet yang luar biasa keren. Kata para pembelinya: Yang mangatusan enaknya sudah bukan main. Kopinya Pak Nur terlalu mahal.
Di jagat penjual kopi dalam pasar itu, tak banyak orang seperti Pak Nurali ini. Tahun 90an masih banyak yang seperti dia. Namun, ekpansi besar-besaran pabrikan kopi menyasar segmen bawah membuat pedagang kopi bubuk sangrai tradisional minggir teratur. Bagaimana tidak minggir teratur wong harus bertarung dengan kopi kemasan buagus dan harganya hanya mangatus rupiah. Siapa mampu bertahan. Siapa bisa mengelus dada saban hari.
Nurali, juga "Nur-Nur" yang lain, yang masih dagang kopi bubuk di dalam pasar, harusnya tak perlu mengelus dada saban hari. Asal mereka mau. Asal mereka mau ikut arus menjualkan saja kopi saset atau kopi kemasan buatan pabrikan yang super murah itu. Bagi Nur, mungkin kendalanya hanya satu. Yaitu soal hati. Maukah mereka menjual kopi bikinan orang lain, bikinan pabrik, sementara mereka juga bisa bikin kopi yang tak kalah enaknya.
Mereka ini adalah "pendekar kopi" yang reputasinya rata-rata hampir setengah abad berjualan kopi. Apakah mereka mau? Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan instan bukan? widikamidi
Advertisement