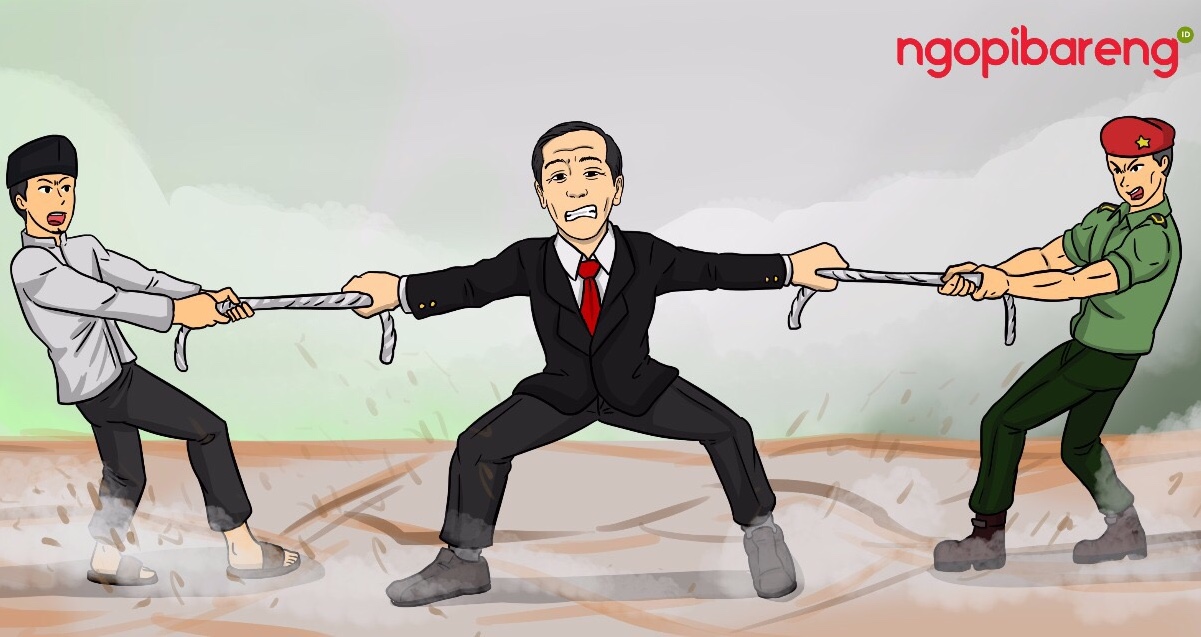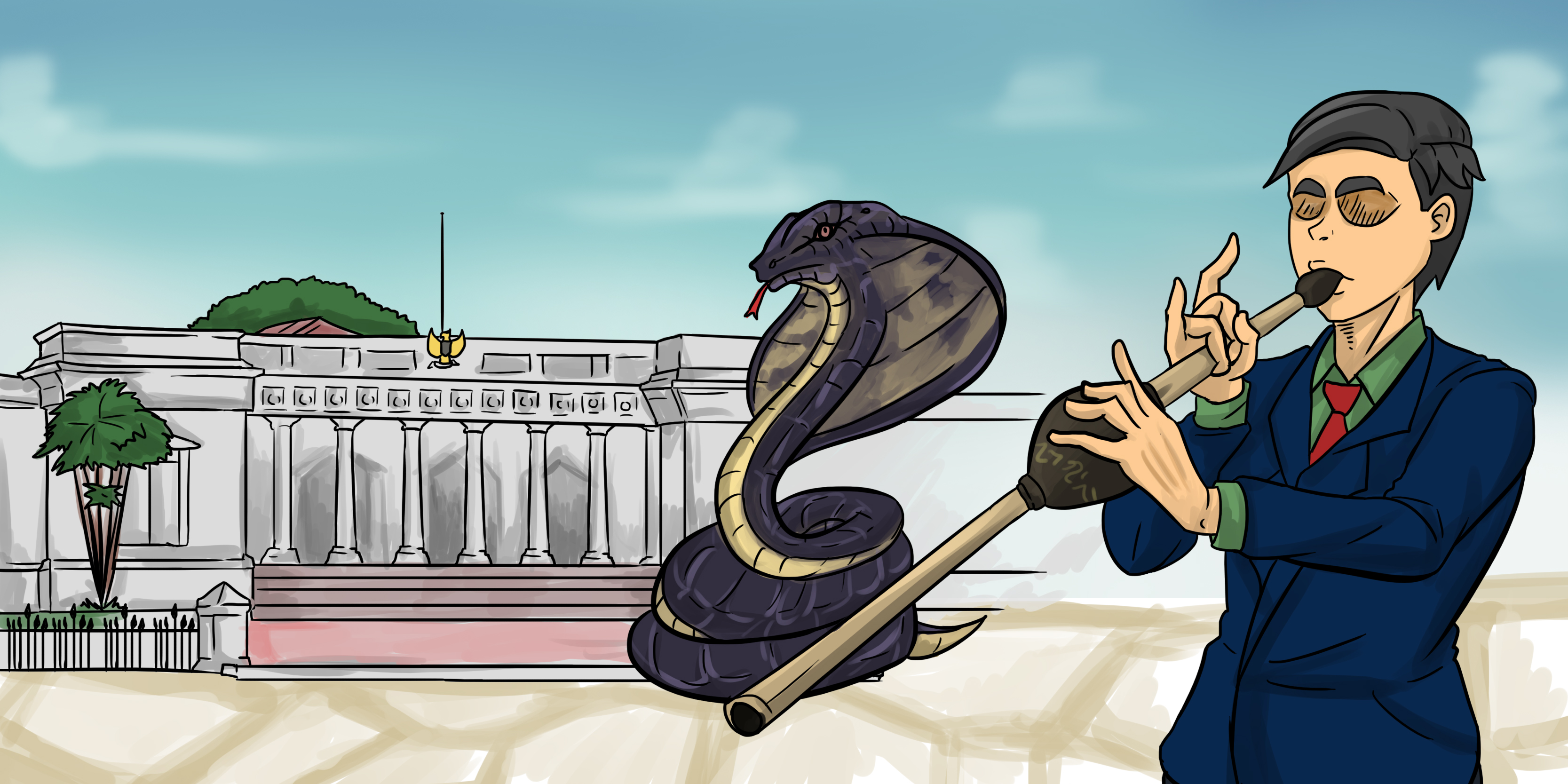Kejar Terus ''Cicak'', Hindari ''Buaya, Ada Apa KPK?

DALAM satu bulan terakhir ini, KPK mengumumkan keberhasilannya menangkap pejabat daerah koruptor melalui apa yang disebut Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ketiganya adalah Bupati Batubara, Bupati Pamekasan dan Walikota Tegal.
Keberhasilan KPK ini tentu saja patut diapresiasi. Namun keberhasilan ini juga sekaligus memberi peringatan bahwa OTT yang dilakukan berkali-kali dan sifatnya makin massif, tidak membuat pejabat bermental koruptif, takut menjadi pasien KPK.
Menjadi pasien KPK, lama kelamaan menjadi sebuah “kebanggaan”. Ingat, bagaimana Masinton Pasaribu, politisi PDIP sampai-sampai aecara demonstratif membawa koper berisi baju ke kantor KPK dan menawarkan diri untuk ditahan.
Jangan lihat cara Masinton dengan kaca mata normal. Tapi bedahlan secara kritis. Itu adalah sindiran yang hanya bisa dimengerti oleh yang peka atas kegundahan yang tak bisa diungkap secara eksplisit.
Sekalipun kasusnya berbeda dengan kasus korupsi – lebih bersifat politis, tapi reaksi Masinton seperti itu, perlu dianalisa dari perspektif – bahwa ketakutan menjadi pasien KPK, sudah berkurang.
Kewibawan KPK sedang dalam pertaruhan.
Ketakutan melakukan korupsi, bukannya berkurang.
Boleh jadi para pejabat daerah berani melakukan korupsi “kecil-kecilan” sebab mereka menyaksikan, KPK tidak berani menyentuh korupsi “besar-besaran”.
Bahkan muncul sebuah kecenderungan baru. Yang menjadi OTT, tidak merasa perlu, wajahnya ditutupi oleh kertas koran manakala disorot kamera wartawan.
Sekalipun mereka sudah diberi label koruptor oleh KPK, kecenderungan baru memperlihatkan mereka tidak merasa malu diperkenalkan sebagai ‘pejabat penjahat’.
Para korban OTT, masih bisa tersenyum sambil membela diri. Sebuah bukti yang menunjukkan, kerja keras KPK yang berusaha membangun rasa takut orang melakukan korupsi, tak menimbulkan efek jera.
Melihat hasil OTT terbaru, kasus Bupati Batu, Malang, Jawa Timur – dimana jumlah uang yang dikorupsi sebagai barang bukti ‘hanya’ Rp. 300,- juta, muncul pertanyaan: patutkah OTT itu disebut sebagai sebuah prestasi – sehingga perlu diapresiasi ?
Sebab kalau dibuat hitung-hitungan secara logika, biaya yang digunakan KPK yang berkantor pusat di Jakarta untuk melakukan OTT di Malang, Jawa Timur, cukup besar dan justru menjadi sebuah pemborosan dan inefesensi. Tidak sepadan.
Dua bulan terakhir ini saya bolak-balik Jakarta-Surabaya. Untuk perjalanan dua hari satu malam, biaya yang dikeluarkan hampir mencapai Rp. 10,- juta. Malang, letaknya, di luar Surabaya. Lebih jauh dari kantor pusat KPK.
Angka ini saya gunakan untuk perbandingan petugas KPK dari Jakarta ke Batu, Malang, Jawa Timur.
Untuk biaya personalia KPK selama di lokasi OTT, plus ke Malang dan kembali ke Jakarta dengan membawa Bupati dan dua tersangka lainnya, dengan pesawat udara, biayanya mungkin sudah hampir seratus jutaan.
Di tayangan televisi petugas KPK yang melakkan OTT di Malang lebih dari tiga orang. Dan entah berapa lama waktu yang mereka butuhkan menginap dan memantau keadaan di Batu, kota kecil di luar kota Malang.
Belum lagi waktu yang digunakan untuk operasi itu, sudah menyita waktu dan menggerogoti jumlah penyidik yang sangat dibutuhkan oleh KPK.
Sementara uang sitaan dari OTT, hanya Rp. 300,- juta.
Sehingga untuk kasus OTT Bupati Batu, secara rasional, kalau boleh diumpamakan dengan bisnis yang menggunakan logika sehat, operasi ini secara bisnis “tidak fisibel”.
Lantas apakah KPK akan mampu mengawasi 550 orang Bupati dan Walikota se-Indonesia ?
Mikir Kawan !
Ringkasnya, jika KPK terus melakukan OTT dengan penjahat seperti ini, keberhasilan ini, ibarat modus memberantas perdagangan narkoba.
Yang ditangkap dan dieksekusi, hanyalah para pengedar ketengan. Sementara bandar yang sesungguhnya, dengan omzet triliunan rupiah, tidak pernah tersentuh.
Ini sebuah ironi dan tragedi.
Karena operasi pemberantasan narkoba sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Untuk itu pemerintah membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional), setara dengan KPK dan menyisihkan anggaran lewat APBN.
Semua data tentang siapa yang menjadi bandar semestinya sudah ada semuanya. Tetapi seolah-olah sang bandar tengah bersembunyi di Laut Artik, Kutub Utara, daerah beku yang dijaga oleh para beruang lapar, pemangsa mahluk hidup. Sehingga mereka sulit ditaklukkan. Berapapun biaya yang disediakan, tidak mencukupi.
Sehingga atas keberhasilan OTT Bupati Batu, operasi itu lebih patut disebut sebagai hasil yang tidak seimbang. Hasil operasi yang tidak memenuhi harapan masyarakat anti korupsi.
Kepercayaan masyarakat yang merindukan keadilan dalam pemberantasan korupsi, seakan dibuat pupus. Keinginan masyarakat melihat kehadiran KPK dan para Komisionirnya, punya wibawa dan bermanfaat bagi bangsa, menjadi sia-sia.
Bukan itu saja.
Agenda KPK patut dicurigai. Mengapa untuk koruptor yang masuk kategori “cicak”, yang mudah ditangkap dan dilumpuhkan, keberhasilan itu dengan cepat diumumkan oleh KPK ?
Sebaliknya untuk kasus korupsi yang masuk kategori “buaya”, KPK seperti terlalu berhati-hati, tidak berani terbuka atau transparan. KPK terlalu banyak berdiplomasi. Atau seperti mengajak masyarakat main “umpet-umpetan”.
Kecurigaan patut disampaikan, bukan dalam rangka memberi “stigma” dan melemahkan kredibilitas serta akuntabilitas KPK.
Kecurigaan patut disuarakan, justru untuk mengingatkan KPK, benar-benar dibutuhkan tapi harus dengan pola kerja yang meyakinkan.
Sebab kasus korupsi “berkekuatan buaya” itu, justru yang mengumumkannnya lembaga KPK sendiri. Namun setelah menunggu lama, KPK pula yang mem-peti-es-kannya. Penanganan kasus besar sebagaimana dimaksud, seperti ditelan oleh angin di kegelapan malam.
Sebut saja kasus Bank Century, Hambalang dan Garuda. Semuanya terjadi di era pemerintahan sebelumnya – SBY.
Masyarakat perlu diberi “update”. Sudah sampai dimana penanganan mega korupsi yang melibatkan “buaya-buaya” yang hidup di air yang bening ?
Apakah para komisioner KPK takut membuat bekas Presiden RI yang juga jenderal purnawirawan itu tersinggung – sehingga tak berani melakukan “move on” ?
Sesungguhnya dengan KPK membiarkan kasus-kasus mega-korupsi di era SBY, memgambang seperti kotoran di sungai keruh, sama saja dengan memberikan stigma terhadap pemerintahan jenderal ganteng tersebut.
Nama SBY bisa tercemar, hanya karena ulah KPK yang tidak berani menyelesaikan kasus “buaya” di era SBY.
Stigma bisa menimbulkan penafsiran, bahwa KPK tidak berani mengusut kasus-kasus mega korupsi di era SBY, karena adanya tekanan dari orang-orang SBY. Atau KPK hanya menjadi perpanjangan tangan rezim SBY.
Padahal sesungguhnya, bukan begitu.
Yang dimaui oleh SBY justru mungkin agar KPK memenjarakan semua koruptor yang bercokol di eranya. Terbukti misalnya, tidak kurang dari lima menteri di era SBY yang saat ini menjad pasien KPK.
Rasa curiga terhadap KPK yang hanya menyasar koruptor berkekuatan “cicak” tercermin dari kasus e-KTP. Kesan yang muncul, KPK hanya menyasar koruptor yang dikesankan, bukan aktor utama.
Adalah KPK sendiri yang mengumumkan bahwa Setya Novanto, Ketua DPR-RI dan Ketua Umum Partai Golkar sebagai tersangka. Namun yang disaksikan masyarakat, menghadapi Setya Novanto, seolah-olah KPK bisa diajak “toleran” terhadap politisi kaya raya ini.
KPK bisa “dikadalin”.
Dengan mudahnya Setnov menghindar panggilan KPK untuk pemeriksaaan lanjutan. Dengan alasan sakit dan sakit serta kurang enak badann, mulai dari sakit vertigo dan jantung – semua jurus menghindar dilakukan Setnov menghadapi KPK.
Saat memimpin Rapat Paripurna DPR 16 Agustus 2017, dimana Presiden dan seluruh petinggi negara hadir dan acara itu disiarkan oleh jaringan TV, Setnov kelihatan segar bugar.
Namun begitu acara tanpa siaran TV, Setnov tiba-tiba jatuh sakit. Dan yang memberi tahu KPK bahwa Setnov sedang teserang penyakit, bukan dia sendiri. Tetapi melalui pihak ketiga atau perantara.
Apa iya gaya menghindar seperti ini, tidak bisa dimengerti oleh Komisonir KPK ?
Nenek-nenek yang tidak lulus sekolah dasar saja bisa paham.
Dua ratus kritikus yang ber-IQ- 200 dan menyatu di sebuah kolam renang, pun bisa menebak apa yang dimaui Setnov.
Maka semakin lengkaplah kercurigaran terahadap KPK. Yang tidak melakukan tugasnya secara tegas dan berwibawa.
Pertanyaan demi pertanyaan selalu mengemuka. Sebab untuk kasus-kasus yang merugikan negara hingga mencapai triliunan rupiah, KPK seperti menghadapi “Tembok Berlin”.
Kasus “buaya” atau Mega Korupsi ini diibaratkan dengan “Tembok Berlin”, tembok yang membela Jerman menjadi Jerman Barat (non-komunis) dan Jerman Timur (komunis) di era Perang Dingin (Détente).
KPK tidak bisa menngani kasus korupsi berskala “buaya” sebab terhalang oleh tembok tinggi yang berkawat duri yang dialiri listrik.
Dibutuhkan sebuah tekad berani mati dan revolusi baru serta waktu hampir 50 tahun, baru tembok tersebut bisa diruntuhkan lalu Jerman menyatu kembali.
Semua tokoh utama komunis yang menginspirasi perpecahan Jerman, harus meninggal dulu, baru Tembok Berlin bisa dijebol oleh generasi baru – generasi yang tidak paham akan sejarah terjadinya Perang Dingin.
Apakah bangsa Indonesia harus melakukan “potong generasi” baru kasus-kasus korupsi yang berskala “buaya” dengan uang triliunan rupiah bisa ditangani oleh KPK ?
Atau apakah kita harus menunggu NKRI terpecah belah karena krisis akibat korupsi, baru KPK bertindak?
Sebuah pertanyaan yang akan terus mengemuka, selama para Komisioner KPK tidak merubah ruh semangat mereka.
Sebagai pejabat negara yang dipercaya tapi tidak bisa men-deliver apa yang dibutuhkan masyarakat, seharusnya para Komisioner ingat, akan apa saja jawaban dan janji mereka ketika mengikuti tes uji kepatutan dan kelayakan.
Untuk Ketua KPK Agus Rahardjo dan kawan-kawan Komisionir, bertanyalah pada diri sendiri, masih layakkah rakyat Indonesia memberi kepercayaan kepada kalian ?
Masih nyamankah menerima semuan fasilitas dan atribut sebagai Komisioner KPK, sementara kecurigaan di masyarakat berjalan terus ?
Atau haruskah kepercayaan itu dimatikan saja ? *
*) Derek Manangka adalah wartawan senior yang tinggal di Jakarta
Advertisement