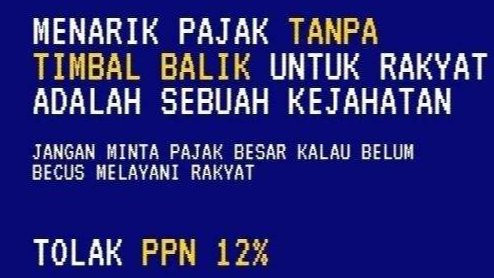Kedigdayaan NU dan Muhammadiyah

Ini dinamika politik yang ciamik. Presiden Joko Widodo mencabut atau membatalkan lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal yang di dalamnya berisikan investasi industri minuman keras (miras).
Di balik pembatalan itu, saya melihat kedigdayaan NU-Muhammadiyah. Keduanya mempunyai peran vital untuk mengubah arah “jarum jam”. Dua ormas Islam itu, terbukti menjadi kekuatan kekuatan civil society yang efektif.
Memang, begitu Perpres itu diteken, ada sekelompok kekuatan yang langsung melakukan gerakan super cepat dan sistimatis. Seperti biasa, mereka sangat reaktif. Langsung dengan gesit menviralkannya. Meme, berita yang dibumbui hoax, serta narasi kebencian pun disebarkan secara masif.
Serangan sengit diarahkan ke mana-mana. Target utama tentu Jokowi. Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang kebetulan juga ulama, menjadi bulan-bulan. Tudingan keji disemayamkan ke mantan Rais Aam PB NU itu.
Namun, menurut keyakinan saya, gerakan ini tidak terlalu ngefeks. Jika NU-Muhammadiyah tidak bersikap, (bahkan mendukung, misalnya), maka kafilah akan tetap berlalu. Perpres jalan terus! Jarum jam tidak berubah arah.
Saya tidak bermaksud menafikan ormas-ormas Islam lain atau komponen-komponen masyarakat lain yang juga menyatakan penolakannya. Termasuk MUI.
Khusus MUI, saya tetap melihatnya sebagai kepanjangan tangan NU-Muhammadiyah. Ingat, ketua umum MUI adalah Rais Aam PBNU. Tim-tim yang ada di MUI, juga mayoritas didominasi tokoh-tokoh yang berlatar belakang NU-Muhammadiyah.
Bagi saya, semua ini adalah dinamika politik yang ciamik. Cantik dan indah! Perlu dicatat sebagai salah satu prestasi sejarah politik di negeri ini. Menyelesaikan masalah dengan cara elegan. Dengan komunikasi yang dibingkai kesopan-santunan. Tidak ada pihak yang dipermalukan atau direndahkan kehormatannya.
Juga, tidak perlu dengan membuang-buang energi melakukan demo yang berjilid-jilid. Cukup dengan berargumentasi dalil dan ilmu agama.
Menurut saya, ada beberapa catatan penting yang layak jadi kajian. Pertama, keberadaan KH Ma’ruf Amin. Seorang ulama yang kebetulan menjabat sebagai wakil presiden. Di mana, keberadaan beliau, ternyata terbukti memiliki makna yang cukup strategis.
Seperti dituturkan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi, sebelum akhirnya Jokowi mengumumkan pembatalan, Kiai Ma’ruf menggelar rapat terbatas bersama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam lainnya. Rapat itu, intinya membahas tentang keberatan atau protes ormas-ormas Islam terhadap perpres yang baru diteken presiden. Juga merumuskan cara efektif menyampaikan protes itu kepada presiden.
Setelah itu, Kiai Ma’ruf pun mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden. Di mana, setelah pertemuan presiden-wapres itu berlangsung, keputusan besar pun diambil. Jarum jam berubah 180 derajat. Perpres yang sudah diteken dibatalkan.
Menurut saya, peran strategis Kiai Ma’ruf ini, sangat patut dijadikan catatan politik. Sebab, beliau sempat dibully oleh para nyinyiris yang selama ini hobby menyebar fitnah dan narasi kebencian.
Dari sini, bisa ditarik kesimpulan bahwa keberadaan seorang ulama dalam struktur pemerintahan terbukti efektif untuk menjaga aspirasi umat. Ini otomatis meruntuhkan asumsi yang mengatakan bahwa ulama yang masuk ke pemerintahan akan terkooptasi oleh kepentingan politik penguasa.
Kedua, eksistensi NU-Muhammadiyah. Selama ini, sama halnya dengan cendikiawan muslim (alm) Nurcholish Madjid, saya berprinsip bahwa NU-Muhammadiyah adalah dua sayap yang bisa menjaga keseimbangan Indonesia.
Dalam konteks masalah ini, seperti yang saya singgung di awal tulisan, NU-Muhammadiyah telah membuktikan peran strategisnya. Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial, dengan elegan mereka selesaikan. Tidak perlu otot-ototan, ribut di jalanan.
Saya berharap, pengurus serta jamaah NU-Muhammadiyah menyadari dengan baik peran strategi itu. Mereka harus dengan penuh kesadaran menjaganya. Ibarat pisau yang tajam, jangan sampai jatuh ke tangan anak kecil atau orang yang berkarakter tidak baik.
NU-Muhammadiyah, harapan saya, tetap di bawah kendali orang-orang sholeh. Sehingga umat tetap memiliki harapan soal kebaikan. Mereka memiliki tempat untuk mengadu bila kesalahan atau kelalaian terjadi di negeri ini.
Kondisi ini sangat penting. Karena dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi menggantungkan atau menitipkan aspirasinya kepada orang-orang yang punya hobby mempolitisasi agama. Mereka membungkus kepentingan politiknya, dengan menjual isu-isu agama.
Soal fenomena politisasi agama ini, saya rasa kita semua sudah mafhum. Sejak era reformasi bergulir, fenomena itu bagai jamur di musim penghujan. Masyarakat pun, banyak yang terbuai dengan gerakan ini. Mereka terkelabui dengan narasi-narasi politik yang dibungkus agama.
Yang lebih ironis lagi, kelompok ini menyeret umat (masyarakat) dalam jurang fitnah dan kebencian. Media sosial dijadikan alat menframing kebencian terhadap kelompok di luar mereka. Berbagai isu, hoax dan narasi kebencian selalu disebarkan di media sosial.
Gerakan ini, menurut saya, sangat keji. Sangat jauh dari spirit agama. Juga dengan nilai-nilai ketimuran bangsa kita. Bila terus terjadi, akan mengancam bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Membawa bangsa Indonesia –khususnya umat Islam--kepada konflik horizontal yang tidak berkesudahan. Seperti yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah.
Kemasan agama yang selalu disuguhkan pada hakikatnya adalah tipuan. Target utama yang hendak dicapai tetaplah kemenangan politik dan kekuasaan.
NU-Muhammadiyah harus bisa membendung gerakan ini. Nah, kesuksesan NU-Muhammadiyah mendialogkan masalah miras ini, harus menjadi momentum untuk lebih memaksimalkan peran tersebut.
Dijadikan model ketika persoalan serupa terjadi. Ke depan, peran-peran seperti itu harus terus dirawat.
Dan, masyarakat –khususnya umat Islam Indonesia--pun, tidak perlu berpaling ke lain hati. Tidak perlu kepincut dengan kelompok-kelompok yang belum teruji dedikasinya.
Ketiga, sikap negarawan Jokowi. Sikap presiden itu patut diapresiasi. Langkah itu, sama sekali tidak mengurangi marwahnya sebagai presiden. Sebaliknya, justru menaikkannya.
Bangsa ini harus fair memberikan penilaian. Jangan terjebur kepada kebiasaan hanya mencermati—bahkan sengaja mencari-cari—kekurangan orang, tanpa mau melihat sisi positifnya. Janganlah kepentingan politik, menutup mata dari kebenaran.
Ini juga sekaligus mematahkan anggapan bahwa Jokowi orang yang anti kritik dan anti oposisi. Sungguh saya miris, ketika Rocky Gerung dengan kasar dan tanpa beretika mengatakan kalau otak presiden harus direvisi atau diperbaiki. Gara-gara dia menuduh presiden anti kritik dan anti oposisi.
Saya tidak ingin bermaksud membela Jokowi. Saya hanya mengajak bangsa ini terbiasa dengan budaya yang jujur, fair dan adil dalam bersikap. Termasuk ketika memberikan penilaian kepada para pemimpinnya, termasuk presidennya. Kalau baik diapresiasi.
Kalau khilaf diingatkan dengan cara bijak. Tidak perlu mencaci maki. Apalagi sampai menyebar fitnah.
Keempat, soal adanya kelompok kiri di sekitar Jokowi. Hal ini, saya harap juga tidak luput dari perhatian kita. Asumsi saya, lahirnya Perpres itu, tidak lepas dari adanya peran sekelompok orang yang berpikir kiri. Mereka abai dengan norma-norma agama. Mereka hendak membawa bangsa ini jauh dari ruh agama.
Coba putar kembali rekaman-rekaman seputar lahirnya Perpres itu. Banyak sekali kelompok yang membabi buta mendukung kebijakan itu. Berbagai argumentasi disodorkan. Nilai-nilai agama, nampak sekali dinafikan.
Inilah “kelompok kiri” yang saya maksud. Mereka sekarang ini ada. Eksis di tengah-tengah belantara politik Indonesia. Sama dengan eksisnya “kelompok kanan” (Islam politik). Dua-duanya hobby membuat kegaduhan. Hobby menebar fitnah dan kebencian.
Indonesia tidak boleh oleng ke kanan atau ke kiri. Indonesia harus tetap terbang seimbang. NU-Muhammadiyah harus tetap menjadi dua sayap yang menjaga keseimbangan itu. (*)
*). Akhmad Zaini, mantan jurnalis, kini menjadi pendidik di IAINU Tuban.
Advertisement