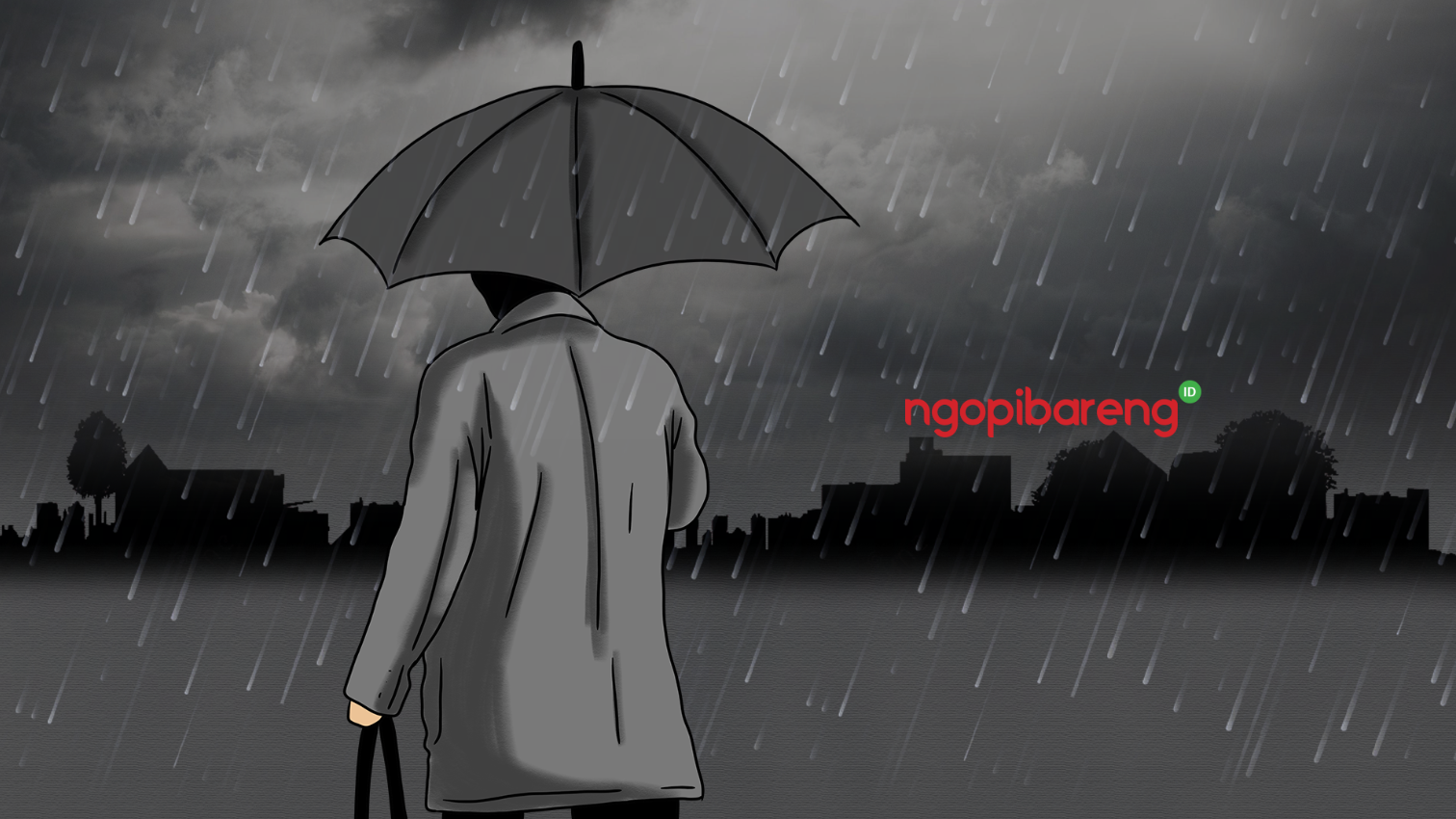Kecewa dengan Nadiem (Dua)

Senior saya di Jawa Pos, Arief Afandi pernah berkata, “saya tidak ingin anak saya sekolah di luar negeri. Kalau ke luar negeri harus sudah dewasa, kuliah.’’ Anak yang masih belia dan karakternya sebagai orang Islam dan Indonesia belum terbentuk, lanjut Arief, jika sekolah ke luar negeri bahaya. “Iso ora Njawani. Kalau sudah dewasa, relatif lebih aman,’’ jelas mantan wakil walikota Surabaya ini.
Pernyataan itu disampaikan sekitar 2004 lalu. Mungkin yang bersangkutan lupa. Seingat saya, pernyataan itu terlontar saat kami bercakap soal fenomena orang-orang yang menuntut ilmu di luar negeri sejak kecil. Dalam banyak kasus, akhirnya begitu pulang ke Indonesia, perilakunya tidak Njawai. Kepribadian sebagai orang Indonesia dan muslim, hilang.
Nadiem, lahir di Singapura. Sekolah di Indonesia hanya sampai tingkat SMP. SMA-nya dia tempuh di Singapura. Setelah itu, dia kuliah di Amerika. Pernah juga mengikuti pertukaran pelajar di Inggris (kompas.com, 23 Oktober 2019). Artinya dia mengenal Indonesia hanya sampai usia SMP. Itu pun hanya di kota (baca: Jakarta). Sepertinya dia tidak pernah mengalami hidup layaknya anak Indonesia yang tinggal di Indonesia. Dari sisi ekonomi, rasanya dia juga tidak pernah merasakan hidup kekurangan. Ayahnya, Nono Anwar Makarim adalah aktivis, tokoh nasional dan pengacara kondang.
Saya tidak buru-buru menyimpulkan Nadiem termasuk fenomena yang dikhawatirkan Arief tadi. Ini hanya soal asumsi saja. Bisa jadi toh? Asumsi itu, saya rasa tidak berlebihan. Sebab faktanya, Nadiem banyak tumbuh dan berkembang di luar negeri. Lulus kuliah, pulang menawarkan konsep bisnis online dan sukses. Dia sibuk di dunia online itu. Dia tidak sempat ikut organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang memungkinkan dia lebih mengenal problematika bangsa Indonesia.
Nadiem adalah anak muda hebat! Dia aset bagi bangsa ini. Kita harus bangga dengannya. Dan tidak ada salahnya kalau perjalanan hidupnya dijadikan cerita inspiratif untuk anak-anak muda di negeri ini. Itu sudah saya lakukan jauh-jauh hari, sebelum si Mas diangkat oleh Presiden Jokowi sebagai menteri pendidikan. Cuma persoalannya, ketika dia dibebani menjadi menteri, ketika dia “mendadak” harus memikirkan pendidikan jutaan anak di negeri ini, ketika dia harus mendesain pendidikan yang cocok untuk bangsanya, maka masalah itu muncul. Referensi ke-Indonesia-an yang dimiliki masih minim. Jam terbang mengenal seluruh problematika negeri ini masih kurang. Akhirnya, dia mendesain pendidikan Indonesia di bawah bayang-bayang masa lalunya yang serba luar negeri dan perkotaan.
Tulisan ini saya buat tidak dalam tendensi ketidaksukaan. Sebaliknya malah kasihan. Sungguh beratnya dia harus mendesain pendidikan sebuah negara, tanpa dia kenal dengan baik negara itu. Mendesain pendidikan, jelas sangat beda jauh dengan ketika dia mendesain bisnis Gojek. Sebab, pendidikan akan terkait erat dengan budaya masyarakat, agama dan juga fasilitas yang ada. Bukti kegagapan pemahaman dia adalah, ketika dalam merancang POP (Program Organisasi Penggerak) dia berbenturan dengan NU dan Muhammadiyah. Dia kelihatannya tidak punya referensi sejarah yang cukup atas dua organisasi tersebut. Dia baru tersentak kaget ketika 2 ormas besar itu menyatakan mundur dari keikutsertaannya di POP karena kecewa. Dan, publik ramai-ramai mendukung langkah NU-Muhammadiyah itu. Setelah “ontran-ontran” itu, dia baru menyadari kalau NU-Muhammadiyah itu penting. Akhirnya minta maaf. Program akan dikaji ulang.
Jadi, dalam hal ini Nadiem layak dikasihani. Beban dia sebagai Menteri Pendidikan terlalu berat. Kecerdasan dia yang selama ini dikagumi banyak pihak, seperti kurang berfungsi gara-gara kurang referensi. Itu manusiawi. ’’Anak yang lahir di Inggris sejak kecil tentu sudah mahir Bahasa Inggris. Dibawa ke Indonesia, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Sementara anak yang lahir di Indonesia, kecil-kecil lancar bahasa Indonesia. Ini bukan soal pinter bodoh. Hanya soal lingkungan dan kebiasaan.’’ Hehehe….Itu perumpamaannya.
Karena itu, menurut saya, Presiden Jokowi harus segera mengkaji secara mendalam masalah ini. Saya yakin, ketika Jokowi menunjuk Nadiem sebagai menteri, maka asumsinya itu akan mempercepat anak-anak Indonesia memasuki gerbang revolusi industri 4.0.
Tentu niat Presiden Jokowi itu baik. Itu terobosan yang berani. Perlu diapresiasi. Cuma, mendesain anak manusia tidak sama dengan mendesain aplikasi online. Karena mendesain manusia harus melibatkan latar belakang sosial, budaya dan memahami psikologinya. Tidak hanya cukup logis apa tidak.
Menurut saya, kemajuan yang dirancang bangsa ini, tetap harus berangkat dari budaya dan jati diri bangsa. Dan itu, hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengenal dengan baik budaya dan jati diri bangsanya. Kita tentu tidak ingin, anak-anak kita maju, hebat bisa menaklukkan dunia, tapi mereka sudah kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Intinya, pembangunan karakter harus diutamakan daripada pengetahuan dan skill. Pembentukan karakter ini, sudah dirancang oleh menteri-menteri pendidikan sebelumnya.
Dulu, ketika pemerintah Hindia Belanda ingin melestarikan kekuasaannya di Indonesia dan juga ingin menjauhkan umat Islam dari agamnya, maka pada awal abad 20, Belanda melancarkan politik asosiasi. Dengan politik asosiasi ini, Belanda ingin agar anak-anak muda bumi putra (baca: Indonesia) lebih mengenal budaya barat daripada budaya Indonesia. Caranya, sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Belanda di Indonesia tidak diajarkan budaya Indonesia. Sebaliknya yang diajarkan ada budaya dan tata cara kehidupan orang Barat (Belanda). Di sekolah-sekolah itu, anak juga tidak diberi pelajaran agama.
Menyadari adanya gerakan perusakan karakter anak bangsa secara sistematis ini, akhirnya para pejuang Indonesia menggagas pendidikan untuk anak Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa, Muhammadiyah mendirikan sekolah umum yang di dalamnya ada pelajaran agamanya. Sedang NU yang sudah punya banyak pesantren, tetap istiqomah dengan pendidikan pesantrennya.
Hasilnya? Politik Asosiasi tidak sukses. Anak-anak Indonesia masih terjaga ke-Indonesia-annya. Muslim Indonesia masih mayoritas. Heroisme anti penjajah masih berkobar. Dari sinilah Indonesia merdeka. NU-Muhammadiyah telah sukses berperan sebagai orang tua yang melahirkan bayi munggil nan elok: INDONESIA. Semoga sejarah itu dimengerti oleh semua anak bangsa. Wallahu a’lam bisshiwab.
*) Akhmad Zaini, mantan jurnalis Jawa Pos, kini jadi khadam pendidikan.
Advertisement