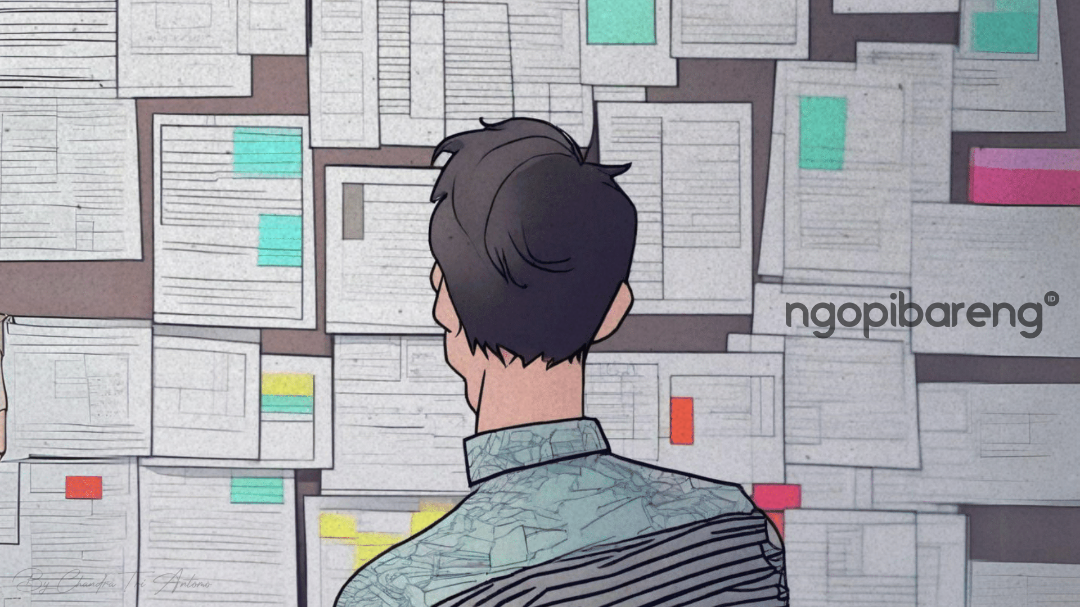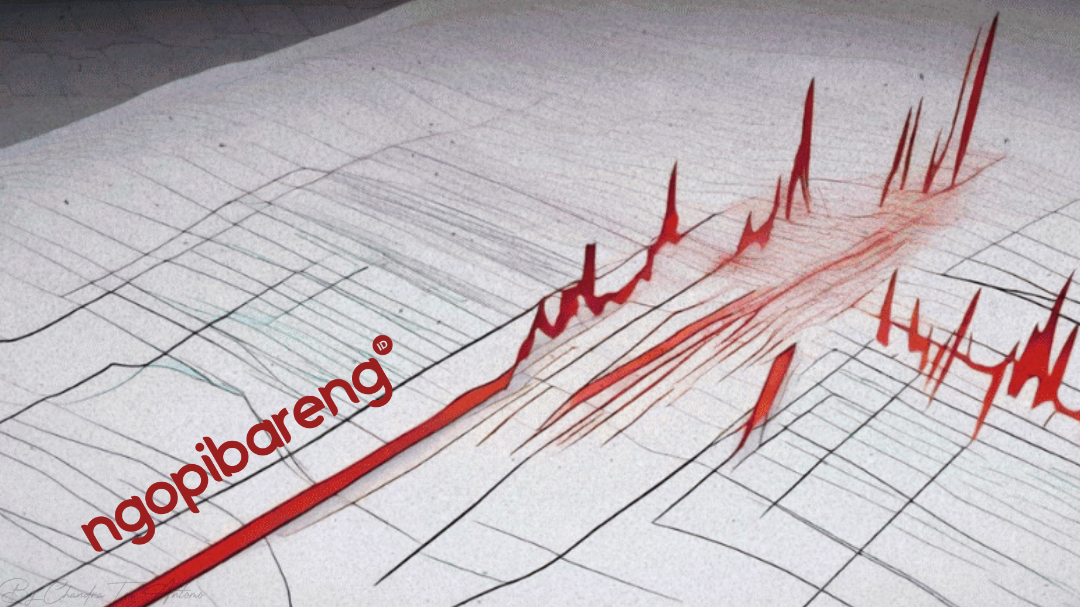Jejak Kelam Hubungan Internasional

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Tahun 2002, ketika 18 peserta Fulbright Visiting Scholars dari berbagai negara mengunjungi Holocaust memorial museum di Washington D.C., Amerika Serikat (AS); sebuah insiden membetot perhatian saya. Seorang kawan dari Palestina—seorang dosen Al-Quds University, Jerusalem—sempat menghilang dari rombongan. Tanpa teriak, dia menolak masuk ke museum. Saya-pun maklum. Tapi, kesenyapan langkahnya tak mengurangi ketegasan sikapnya. Walaupun demikian, dia bukanlah sosok yang anti-semitism (anti-Yahudi). Penilaian saya ini merujuk pada diskusi dengannya menyangkut kemanusiaan—di sela-sela program Fulbright—hampir selama 6 bulan. Penolakannya tersebut lebih merupakan simbol atas protesnya terhadap sikap tidak adil dunia—khususnya dunia Barat—terhadap perlakuan Israel pada warga Palestina, baik di Gaza maupun di wilayah Tepi Barat (West Bank).
Holocaust merupakan sebuah noktah hitam dalam kemanusiaan. Dalam peristiwa itu, dilaporkan bahwa sekitar 6 juta warga Yahudi Eropa telah menjadi korban genosida dari rejim Nazi-Jerman selama selama Perang Dunia II. Tapi, Zygmunt Bauman (1989) sempat merasa aneh ketika sosiologi ‘bungkam’ tanpa eksplanasi yang memadai. Kalaupun ada, fenomena holocaust hanya dipandang sebagai ‘penyimpangan’ yang tak dapat dijelaskan; atau sekedar sebuah ekspresi dari sisa-sisa barbarisme pra-modern. Padahal, pada esensinya, holacaust merupakan produk peradaban modern yang bersumber pada ‘akal budi’ (reason) Barat—sebuah produk pencerahan (enlightenment). Ia berargumen, bahwa peristiwa yang mengakibatkan tragedi kemanusiaan tersebut terjadi justru karena berkelindannya prinsip pentingnya solusi rasional, pelaksanakan secara sistematis melalui mesin birokrasi negara, dan eksekusi dilakukan dengan menggunakan tehnologi modern.
Berangkat dari argumen Bauman tersebut, sikap protes kawan Palestina di atas terhadap ketidakadilan dunia menjadi masuk akal. Alasannya, penindasan Israel yang terus berlanjut terhadap Palestina juga menunjukkan sisi kelam peradaban modern. Yang menarik, setelah dua dasawarsa kemudian; sentimen negatif terhadap sikap dunia tetap mendominasi persepsi publik Palestina. Seperti dilansir oleh Newsweek, pada bulan Maret 2022 sebuah think tank yang berbasis di Ramallah—Pusat Penelitian Penelitian Kebijakan dan Survei Palestina—menerbitkan hasil jajak pendapat mengenai persepsi dan sikap warga Palestina terhadap perang Ukraina. Perbedaan proporsi antara yang pro dan kontra terhadap invasi Rusia ke Ukraina tak begitu signifikan. Hasilnya, 43 persen warga Palestina menyalahkan Rusia karena memulai perang dengan Ukraina; dan 40 persen yang menyalahkan Ukraina. Namun, yang menarik, 57 persen dari mereka percaya bahwa perang Ukraina justru menunjukkan "standar ganda AS dan Eropa ketika konflik yang terjadi adalah konflik yang berkaitan dengan pendudukan Israel atas wilayah Palestina". Persepsi ini mengingatkan pada ungkapan Presiden Perancis—Emmanuel Macron—bahwa arus globalisasi telah memantik globalisasi emosi, kebencian, bahkan juga kekerasan.
Tapi, yang menyedihkan, protes terhadap jejak kebijakan anti-kemanusiaan juga menimpa orang yang sudah meninggal. Kematian Madeleine Albright pada 23 Maret 2022 lalu, sempat mengundang puja-puji pejabat Amerika Serikat. Tak aneh, mengingat Albright adalah wanita pertama yang memegang jabatan Menteri Luar Negeri AS. Apalagi, dia juga penerima Presidential Medal of Freedom, penghargaan tertinggi bagi warga sipil Amerika. Mantan Presiden Bill Clinton—yang mempromosikannya menjadi Menteri Luar Negeri—menyebutnya sebagai tokoh dengan "kekuatan yang bersemangat untuk kebebasan (freedom), demokrasi, dan hak asasi manusia". Bahkan, Presiden Joe Biden menilai Albright sebagai sosok yang "selalu menjadi [inspirasi] kekuatan untuk kebaikan, keberkahan, moralitas, dan kebebasan (freedom)".
Namun, yang memilukan, pujian terhadap Albright dibayangi oleh jejak hitam pernyataannya. Ahmed Twaij—jurnalis asal Iraq—menggugatnya dengan mengingatkan publik dunia pada pernyataan mantan Menteri Luar Negeri AS tersebut. Pada tahun 1996, acara “60 Minutes” televisi Columbia Broadcasting System (CBS) menampilkan wawancara dengan Madeleine Albright—yang saat itu menjabat Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu isu yang ditanyakan adalah dampak sanksi AS terhadap penduduk Iraq, menyusul invasi Saddam Hussein ke Kuwait. Data UNICEF menunjukkan bahwa sanksi tersebut telah menyebabkan lebih dari 4000 anak-anak balita Iraq meninggal setiap bulan, karena kekurangan makanan dan obat-obatan. Berangkat dari data ini, sang pewancara—Lesley Stahl—melontarkan pertanyaan tajam: “Kami mendengar bahwa setengah juta anak-anak [Iraq] telah meninggal. [Jumlah] itu lebih banyak daripada anak-anak [yang tewas akibat bom atom] di Hiroshima. Apakah [kematian anak-anak Iraq] tersebut merupakan harga yang sepadan?". Jawaban Albright cukup mengejutkan. Tanpa ragu dia menegaskan: “Itu merupakan pilihan [kebijakan] yang sulit … tapi, menurut saya, [kematian anak-anak itu] merupakan harga yang sepadan!”.
Pernyataan Albright di atas jelas anti-humanitas, sekaligus ironis dengan pujian terhadap sosoknya sebagai ‘kekuatan untuk kebaikan, keberkahan, dan moralitas’. Memang, sanksi merupakan bagian dari perang. Tapi, pemantik utama perang perlu dibedakan antara yang dipicu perebutan sumber daya langka (scarcity) dan yang disebabkan oleh perbedaan nilai. Sanksi AS terhadap Iraq bukanlah menyangkut survivalitas AS menyangkut perebutan sumberdaya langka; melainkan lebih dimotivasi oleh perbedaan nilai—khususnya berkaitan dengan ambisi ekspor demokrasi. Meskipun pada tahun 2020 Albright meminta maaf atas pernyataaannya—dengan mengatakannya sebagai ungkapan yang ‘benar-benar bodoh’—nampaknya hal itu tak termaafkan. Alasannya, antara lain, nyawa setengah juta anak-anak Iraq tak bisa lagi dikembalikan. Ahmed Twaij tetap meradang dan berteriak lantang memperingatkan dunia: “Sebelum Anda menulis atau memposting ulang artikel tentang Albright, luangkan waktu sejenak untuk mempelajari [kebijakan] apa yang dia pilih untuk dijalankan dengan kekuatan yang dia miliki–[dan] bagaimana [dengan semua itu] dia telah membuat kehancuran dan penderitaan bangsaku!”.
Apakah suara kawan Palestina dan Ahmed Twaij akan didengar publik dunia? Sulit untuk menerka. Alasan utamanya, misi yang diusung keduanya adalah isu yang ‘melampaui negara’ (beyond state). Padahal, sejauh ini, hubungan internasional lebih diwarnai oleh hegemoni ‘international society’ (society of states) daripada ‘world society’ (society of individual). Sangat logis jika suara pemimpin yang bertindak atas nama negara—seperti pernyataan Madeleine Albright di atas—lebih menguasai wacana dunia dibandingkan bisikan nurani individu sebagai sosok manusia (human being). Akibatnya bisa diduga, komitmen humanitas hampir selalu tenggelam di tengah hiruk pikuk logika survivalitas.
Tak beda jauh dengan sikap sosiologi menyangkut holocaust, ilmu hubungan internasional (IHI) juga gagap—setidaknya pada awalnya—dalam merespon tuntutan moralitas dan tanggung kemanusiaan. Teori yang terfragmentasi, dengan diwarnai sengitnya kontestasi, merupakan salah satu indikasi. IHI mungkin perlu sekali lagi merenungkan jatidiri. Tawaran Ken Booth cukup menarik, meskipun perlu dikaji. Terinspirasi oleh kredo Immanuel Kant tentang pencerahan, ia menawarkan metode “Dare not to know” (berani mengosongkan pemahaman) terhadap teori-teori yang sudah mapan. Metode ini, antara lain, mencakup upaya “perlunya untuk memanusiakan kembali apa yang telah mengalami dehumanisasi, membayangkan kembali kemanusiaan yang pernah terwujud, dan—yang tak kalah pentingnya—mendengarkan ‘jeritan kesunyian’ dari si lemah dan yang tertindas!”.
Memang, gamang kadang menyelimuti masa datang. Tapi, optimisme tetap siap untuk menyingkap. Meskipun rintihan kemanusiaan terdengar sayup di tepi kesunyian, spiritnya tengah bergerak di jalan keniscayaan. Toh, sebelum menjadi pemimpin negara ataupun sebagai warganegara, kita semua dilahirkan dahulu sebagai sosok manusia. Wallahu’alam!
*) Himawan Bayu Patriadi adalah dosen Hubungan Internasional Universitas Jember
Advertisement