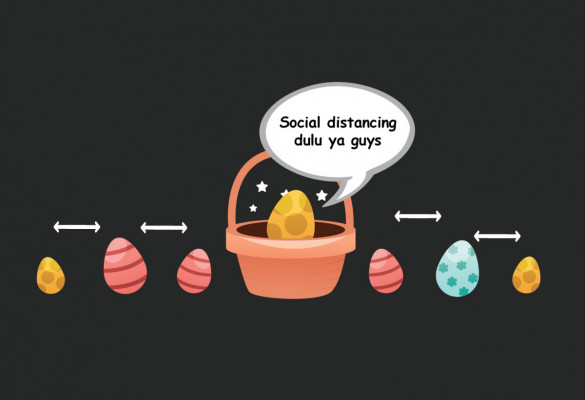Jawa dan Wabah


Dari Jawa di sebelah barat, wabah melanda. Seisi negeri pun panik di awal Maret 2020. Pembesarnya panik. Rakyatnya panik. Kita seperti bangsa yang baru pertama kali mengalami wabah, mengalami pandemi.
Padahal, ini pandemi, ini wabah, ini pageblug sudah pernah memukul kita sampai babak belur lebih kurang 109 tahun silam. Sepanjang tiga tahun, dari 1911 sampai 1914, satu per satu rakyat di Jawa tumbang. Terutama, Jawa bagian timur.
Anda hanya membuka koran Bintang Soerabaia, dan melihat betapa memilukannya wabah yang disebut pes itu. Kalau Covid-19 menjadikan kelelawar sebagai ikonnya, pes di Jawa melahirkan tikus sebagai biang ketakutan luar biasa. Eropa binasa oleh sampar, Jawa ikut menangis oleh pes. Sama saja.
Sidoarjo, Surabaya, Kediri, Tulungagung, Madiun, Purbolinggo, Lumajang, Malang disapu pandemi yang menyebar sangat luas. Satu-satu rakyat secara bergiliran tumbang. Pemerintah kolonial tidak berdaya.
Bayangkan, koran Bintang Soerabaia edisi 6 September 1911 melaporkan angka-angka seperti ini. Dan ini nyaris berlangsung tiap hari: Terkena pes di Karanglo ada 5 orang, sakit demam di Malang 1 orang, Penanggoengan 2 orang, Ngantang 3 orang, Karanglo 1 orang, Senggoeroeh 3 orang dan Toerea 1 orang. Meninggal karena terkena penyakit pes 3 orang, akibat sakit panas 9 orang. Jumlah tikus yang tertangkap hari ini 31.122 ekor, dan 1 tikus mati.
Pandemi pes Jawa itulah yang membuka mata para priyayi yang berkesempatan bersekolah di Stovia untuk turun tangan. Dokter-dokter muda bahu-membahu di lapangan. Salah dua nama dokter yang lahir dari pageblug Jawa itu bernama Tjipto Mangunkusumo dan Soetomo.
Anda tidak keliru. Nama Tjipto dan Soetomo itu dikekalkan menjadi nama rumah sakit utama negeri di DKI dan Surabaya. Memilih nama itu menjadi nama rumah sakit pemerintah adalah peringatan tentang kesiapsiagaan negeri ini berhadapan dengan wabah. Itu bukan nama asal ditempelkan. Itu monumen peringatan dari rasa sakit sebuah bangsa.
Keduanya, Tjipto dan Soetomo, lahir dan tumbuh dalam gelombang wabah yang mematikan di Jawa. Solidaritas dokter dan rakyat yang sakit itu melahirkan gelombang baru: bibit pergerakan pembebasan. Solidaritas karena sakit itu menjadikan Jawa postur politik Jawa berubah sama sekali. Di situ, para dokter yang digembleng oleh pandemi tikus itu mewujud menjadi pemimpin-pemimpin pergerakan.
Lihatlah, tahun saat wabah itu melanda. Tahun 1911 hingga 1914 itu bersamaan dengan kelahiran, antara lain Sarekat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah. Semuanya muncul justru Jawa dikabuti rasa sakit yang amat dalam. Pastilah, yang dikerjakan organ-organ itu adalah pertolongan kesehatan oemmat.
Wabah itu tapal ujian yang sangat berat bagi pengelola negeri. Dalam segala hal. Perkataan langsung diuji kenyataan di lapangan. Ketika kita bilang kita siap menghadapi wabah, orang-orang dengan benderang melihat bagaimana kesiapan infrastruktur rumah sakit, kesiapan sumber daya tenaga kesahatan, data sebaran, prosedur, dan sebagainya.
Pada wabah 109 tahun silam, segala macam cara dilakukan pembesar, yang memang sudah kehabisan akal. Termasuk memberikan penghargaan kepada para pembesar daerah yang sukses. Seremoni konyol pemberian gelar seperti ini langsung dijawab oleh tikus-tikus pandemi sepulangnya sang pejabat teras itu dari daerah tersebut. Kota tersebut ditemukan lagi kematian.
Bukan seremoni-seremoni semacam itu yang dibutuhkan, melainkan solidaritas dengan tugas masing-masing. Wabah ini menyentakkan kita untuk tidak boleh lagi main-main dengan pertahanan kesehatan. Bayangkan, virus bisa membikin ambruk semua perhitungan dan segala macam catatan kegemilangan ekonomi yang bakal dicapai. Oleh benda mahakecil ini, tiba-tiba kita melihat wajah pariwisata kita seperti mayat.
Ayo, berdirilah di hadapan RSUD Soetomo Surabaya dan lihat rumah sakit ini adalah monumen wabah. Nama yang tercetak di tembok halamannya itu adalah jihadis wabah. Ayo, berdiri di hadapan RSUP Tjipto Mangoenkoesoemo Jakarta dan saksikan bagaimana si empu yang namanya tercetak itu membuka baju turun ke gelanggang pandemi di Jawa.
Sebagai monumen wabah, dua rumah sakit ini mesti menjadi teladan bagaimana fasilitas kedua rumah sakit ini betul-betul tercanggih berhadapan dengan wabah apa saja. Ia menjadi contoh rumah-rumah sakit yang lain. Bukan saja kesiapan peralatan medis, tetapi juga sumber daya manusianya dan mental-mental pelayan kesehatannya.
Berdiri dan bergeraklah sebagai bangsa yang tidak culun berhadapan dengan wabah. Dengarkan ilmuwan, jadikan dokter sebagai rujukan suara untuk solidaritas. Lalu, wabah mestinya segera menyadarkan kita untuk berpikir yang jauh dan tidak sesaat.
Mendengarkan ilmuwan, misalnya, bukan sekadar perkataan, melainkan perbuatan. Dorong dan sokong dengan dana besar kembalinya riset-riset dasar tentang dunia molekul, biologi, genetika, dan ilmu-ilmu dasar lainnya sebagai pondasi dasar pertahanan pengetahuan bangsa ini di tengah suasana kebatinan pendidikan yang menjadi sekutu korporasi. Sudah lama riset dan keilmuan dasar seperti ini terpojok, tidak direken.
Betul, pendidikan dengan riset dasar butuh dana besar yang tentu saja hasilnya tidak bisa kita cecap dalam satu atau dua tahun, melainkan tiga dekade kemudian. Namun, kelompok ini adalah akar dari mana kita memahami dan melakukan inovasi. Terutama sekali, benteng kita kala berhadapan dengan wabah.
Mestilah pemerintah hadir memberikan dukungan total sebagai bagian dari pertahanan pengetahuan kita. Lembaga-lembaga keilmuan dasar semacam Eijkman Institute mesti diberi tempat terhormat dan ditambah lagi. Dengan begitu, anak-anak negeri yang memilih ilmu basis atau dasar seperti ini tidak sesak dada bahwa ke depan bakti-ilmu mereka hanya berakhir menjadi “gelandangan”.
Saat dunia panik seperti ini, barulah kita linglung. Kita harus mendengar siapa. Kita meraba-raba, di mana ilmuwan-ilmuwan molekul, genetika, ahli virus kita. Suara-suara mereka, voice mereka, diganti oleh dengungan ribut, dari noise mereka yang syok dan sok.
“Apakah Indonesia sudah siap bila virus corona jenis baru akhirnya masuk ke Tanah Air? Apakah sudah punya antivirusnya?” tanya jurnalis IDN Times, Dini Suciatiningrum, kepada Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio. Pertanyaan itu dipublikasikan pada 1 Februari atau satu purnama sebelum negeri diguncang kepanikan. Jawaban ilmuwan Eijkman itu membikin kita trenyuh: kita tidak punya antivirus itu.
“Jika nanti kita temukan (ada yang terjangkit), maka kita akan urutkan dulu genetiknya virus yang mana,” kata Amin. Kerja ilmuwan memang rantai kerja yang panjang, tidak instan. Pemerintah memastikan mereka bekerja dengan bahagia sepanjang waktu dengan cara satu-satunya: dukung dan sokong mereka dengan sumber daya keuangan dan infrastruktur nomor satu.*
*)Diana AV Sasa, Pegiat Literasi. Tinggal di Surabaya
Advertisement