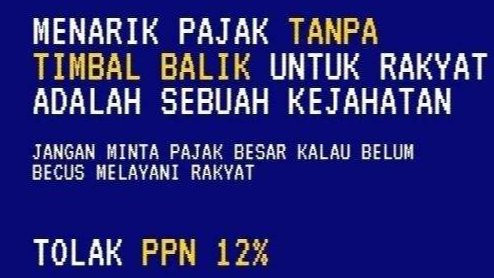Ikhtiar Kembalikan UAS ke NU
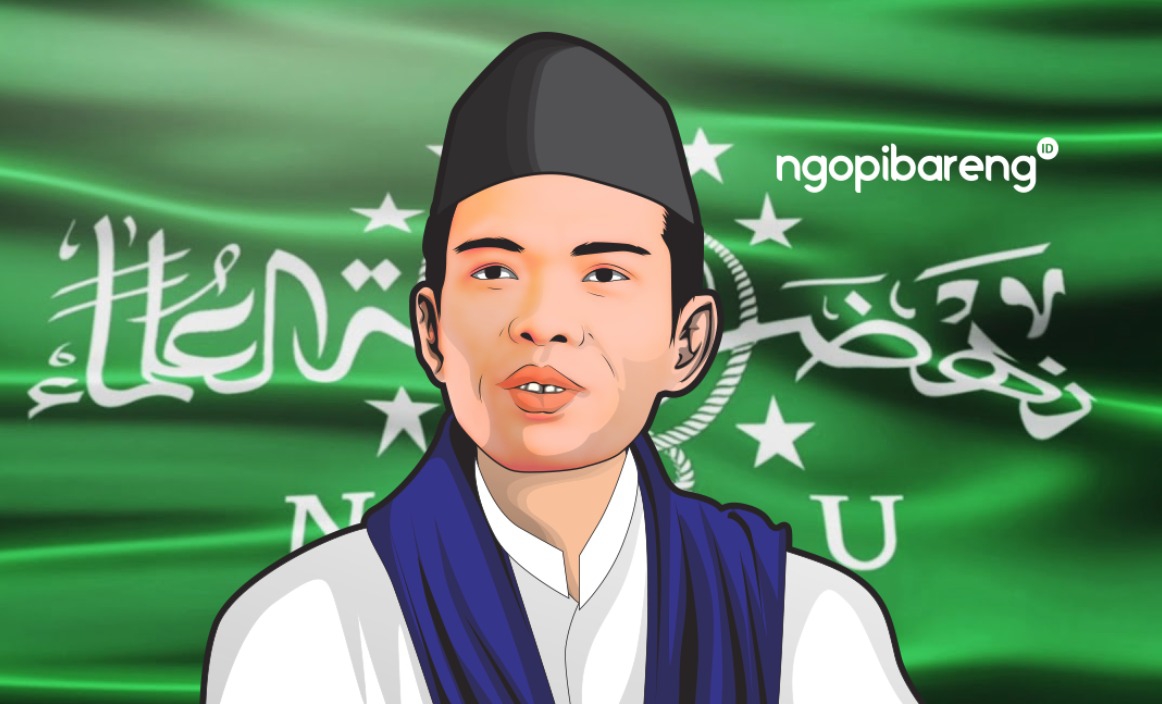
Bagi saya, ini kabar menarik. Selasa kemarin (23 Februari 2021) Ustaz Abdul Somad (UAS) mampir ke Kantor Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Timur. Di sini, UAS bertemu dengan kiai-kiai sepuh NU Jawa Timur; Rais Syuriah PWNU Jatim KH Anwar Manshur, Wakil Rais Syuriah KH Agoes, KH Anwar Iskandar, Ketua Tanfidziyah KH Marzuqi Mustamar dan juga beberapa kiai lainnya yang sedang mengikuti vaksinasi Covid-19.
Beberapa media memberitakan peristiwa itu dengan istilah “sowan”. Saya memilih istilah “mampir”. Menurut saya, istilah itu lebih tepat. Karena memang kedatangan UAS itu, tidak direncanakan sebelumnya. Para kiai yang menemui, juga kebetulan saja kumpul di PWNU untuk mengikuti program vaksinasi. Bukan berkumpul untuk menyambut UAS.
Seperti diberitakan Radar Madura, semula UAS diajak sahabatnya untuk bersilaturrahim ke Gus Ali. Namun, ketika mereka tiba di Pondok Pesantren Bumi Sholawat, ternyata Gus Ali tidak ada di tempat. Beliau sedang mengikuti vaksinasi di PWNU. UAS ditemui putra Gus Ali yang kebetulan juga sama-sama alumni Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir.
Rupanya, Gus Ali dikabari kalau UAS sowan ke rumahnya. Gus Ali pun mengontak dan minta agar UAS menyusul ke PWNU. UAS mengiyakannya dan meluncur ke PWNU.
Kalau melihat kronologis itu, tentu kedatangan UAS ke PWNU tidaklah istimewa. Maka saya cukup menyebutnya “mampir”. Begitu pun ketika ke ndalem Gus Ali. Itu, juga karena ajakan seorang sahabat. Bukan, atas inisiatif yang bersangkutan.
Setali tiga uang dengan ketika UAS sowan ke Habib Luthfi (Pekalongan) dan Mbah Moen (KH Maimoen Zubair) dua tahun lalu (Februari 2019). Itu pun atas ajakan beberapa sahabatnya sesama alumni Universitas Al Azhar. Satu di antaranya, Gus Awis (KH Afifudin Dimyathi, Darul Ulum Jombang).
UAS memang punya banyak sahabat di NU. Ketika masih kuliah di Al Azhar, dia satu kontrakan dengan Gus Awis. Sepulang ke Indonesia, UAS pun sempat aktif di NU Riau. Hanya, beberapa tahun belakangan, setelah UAS populer, ada sedikit kerenggangan.
Meski “sekedar mampir”, saya tetaplah memandang peristiwa itu “istimewa”. Berita menarik. Enak dibaca dan perlu!
Di mana letak enak dan perlunya?
Saya melihat, para sahabat UAS dari kalangan nahdliyin masih punya rasa ngeman. UAS yang punya akar pertautan dengan NU –bahkan pernah menjadi pengurus Batsul Masail PWNU Riau—diharapkan kembali mendekat ke NU. Karena seperti saya singgung tadi, beberapa tahun belakangan ini, ada gap antara UAS dengan warga Nahdliyin.
Persoalan intinya, beda pandangan politik.
Sejatinya, UAS bukan anti NKRI. Tapi, dia ada kecenderungan berpikir formalis. UAS sejalan sebarisan dengan kelompok-kelompok yang menginginkan adanya formalisasi Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini beda dengan sikap ulama NU pada umumnya yang cenderung menghindari formalisasi Islam.
Perbedaan ini, dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok formalis plus anti NKRI yang memang sejak era reformasi marak di Indonesia. UAS ditokohkan. Diidolakan. Diulamakan. Mereka (baca: kelompok fomalis pun anti NKRI) menjadikan UAS sebagai ikon perjuangan. Foto-foto UAS selalu dipasang sebarisan dengan tokoh mereka dan diviralkan di media sosial.
Strategi itu, mereka lakukan untuk menguatkan citra Islam di hadapan umat Islam. Terutama ketika harus head to head dengan NU. Mereka sangat memerlukan tokoh sepopuler UAS. Stok ulama atau ustdaz mereka, tidak cukup popluler untuk “dijual” di hadapan umat. Khususnya kalangan kebanyakan yang berkultur Nahdliyin.
Harus diakui, UAS saat ini memang menjadi salah satu dai top nasional. Dia oleh Alvara Research Center pada pertengahan 2020 dinobatkan sebagai dai paling populer. Meski, pada akhir 2020 Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia (ADDI) menganugrahkan kepada Gus Baha (KH Bahaunddin Nursalim) sebagai Dai of the Year 2020.
Intinya, ketokohan UAS itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik.
***
Sejatinya, ada perbedaan mendasar antara UAS dengan kelompok yang memanfaatkannya itu. Pertama, meski condong formalisasi agama, tapi UAS tidak anti NKRI. Sepanjang yang saya amati dari ceramah-ceramahnya, UAS memahami keberagaman Indonesia. Dia melihat NKRI sebagai solusi.
Ini beda dengan kelompok yang menyanjungnya selama ini. Sebagian dari mereka, memang anti NKRI. Target mereka mendirikan negara Islam dan mengganti Pancasila.
Kedua, dalam amaliyah keislaman. Menurut saya UAS masih nahdliyin. Secara fiqih, UAS syafi’iyah (pengikut Mazhab Imam Syafi’i). Begitu juga dalam aqidah. UAS masih sama dengan NU. Dia juga mengamalkan thariqat (tasawuf) seperti halnya para ulama NU.
Adab atau etika UAS ketika bertemu ulama, juga sama persis dengan para santri NU. Dia menunduk, mencium tangan dan minta barakah doa. Bahkan, UAS punya kebiasaan khusus. Ketika barakah doa dibaca, UAS melepas songkoknya. Setelah pembacaan doa selesai, dia minta agak ditiupkan ke kepalanya.
Ini tradisi NU. Tradisi Islam Nusantara. Sementara, mereka yang saat ini mengelu-elukan UAS, umumnya anti Islam Nusantara. Mereka tidak punya amaliyah dan tradisi seperti halnya UAS. Mereka juga memandang NU sebagai penghalang terbesar bagi terwujudnya cita-cita mereka mendirikan negara Islam.
Ketika dialog dengan para ustadz di Pesantren Sidogiri bebarapa tahun lalu, UAS mengakui hal itu. Dia mengatakan bahwa dengan kelompok formalis –khususnya HTI saat sebelum dibubarkan—dia mengaku memiliki kesamaan perjuangan. Yakni, memperjuangkan agar Indonesia lebih “Islam”. Namun, ketika perjalanan semakin jauh, mengarah pendirian negara Islam, UAS tidak sepaham. “Sudah beda jalur,” katanya.
Lewat tulisan ini, saya mendukung upaya para sahabat UAS untuk “mengembalikan” UAS ke pangkuan NU. Meski saya prediksi itu tidak mudah. Namun demikian, harapan itu tetap ada. Paling tidak, masing ada beberapa simpul kesamaan –seperti yang saya tuturkan di atas-- yang bisa dikencangkan kembali.
Sikap UAS yang mau “dimakjomblangi” (dipertemukan) dan menunjukkan sikap yang tawadhu kepada para kiai NU, saya anggap juga sebagai hal yang positif. Artinya, UAS masih menaruh rasa hormat atas otoritas keilmuan agama para kiai NU.
Saya menangkap, UAS juga tidak nyaman betul ketika dielu-elukan dan disanjung setinggi langit oleh kelompok formalis anti NKRI. Ketika seorang tokoh dari mereka menyanjung dia sebagai ulama ahli hadist dan tafsir, maka dengan cepat UAS mengelak. Dia menyebut Gus Baha sebagai orang yang layak disebut sebagai ahli tafsir dan hadist. Tidak hanya itu. UAS juga menyabut Gus Baha juga ahli fiqih, sejarah Islam dan juga tasawuf.
Bagi saya, apa yang dilakukan UAS itu memiliki makna mendalam. Paling tidak, UAS masih berani menunjukkan jati dirinya. Dengan halus, dia ingin meluruskan atau mengoreksi. UAS tidak larut dengan kebiasaan mereka yang gampang memberikan sebutan ulama kepada orang-orang yang tidak benar-benar mendalami ilmu agama.
Kalau cari selamat, menikmati ditokohkan dari mereka dan ingin melanggengkannya, UAS tentu tidak akan melakukan itu. Karena hampir mustahil, mereka akan mau dipalingkan rujukannya ke Gus Baha. Mereka itu, sejatinya sudah punya rujukan-rujukan baku. Sanjungannya ke UAS dan kedekatan yang dibangun selama ini, hanyalah untuk kepentingan sesaat. Untuk mendapat dukungan. Membangun kekuatan politik. Jika mereka sudah mencapai maksud, saya yakin mereka akan segera mencampakkannya.
Upaya mengembalikan UAS ke pangkuan NU, tentu tidaklah mudah.
UAS yang kebetulan berasal dari Riau memiliki banyak perbedaan budaya dengan warga NU di Jawa pada umumnya. Di internal NU sendiri, sudah terlalu banyak orang yang “terlukai” oleh UAS. Namun, demikian, tidak ada salahnya bila upaya itu tetap dilakukan.
Saya berharap, kepentingan besar, keutuhan NKRI menjadi energi bagi para sahabat UAS untuk tetap mengupayakan agar UAS tidak terlalu jauh dari kultur dan cara berpikir NU. Jangan sampai dia dimanfaatkan oleh para pemain politisi aliran yang punya agenda merubah bentuk negara. Harapan lain, semoga dengan upaya terus menerus itu, bisa dihindarkan kesalahpamahan yang mungkin muncul dan semakin melebarkan gap.
Lewat tulisan ini pula, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada para ulama NU yang menerima kedatangan UAS di PWNU dengan baik. Khususnya Gus Ali yang berinisiatif untuk menelpon dan “memaksanya” untuk ke PWNU. Menurut dugaan saya, para kiai itu, sejatinya tidak memiliki harapan besar atas kedatangan UAS di Kantor PWNU.
Beliau-beliau itu tahu koronologisnya. Itu hanya kebetulan. Itu hanya mampir. Namun, kebesaran hati mereka sebagai ulama-lah menjadikan beliau-beliau itu dengan lapang dada menerima kedatangan UAS. Diminta barakah doa dan meniupkannya ke kepala UAS pun, beliau-beliau itu mau melakukannya.
Mengapa saya menduga para kiai itu tidak memiliki harapan besar? Karena pertemuan UAS dengan Habib Luthfi dan Mbah Moen 2 tahun lalu, juga tidak menggoreskan atsar (jejak) yang jelas. Bahkan, gelar syech yang sempat diberikan Habib Luthfi pun, ditolak halus oleh UAS. Dia lebih nyaman tetap menggunakan gelas “ustadz” yang oleh Habib Luthfi dipandang kurang familiar di kalangan warga Nahdliyin.
Tapi, tidaklah ada yang abadi di dunia ini. Semua serba mungkin. Dan, di balik peristiwa apa pun pasti ada hikmahnya. Ada sisi positifnya. Semoga!
*) Akhmad Zaini, mantan Jurnalis, kini menjadi pendidik di IAINU Tuban.
Advertisement