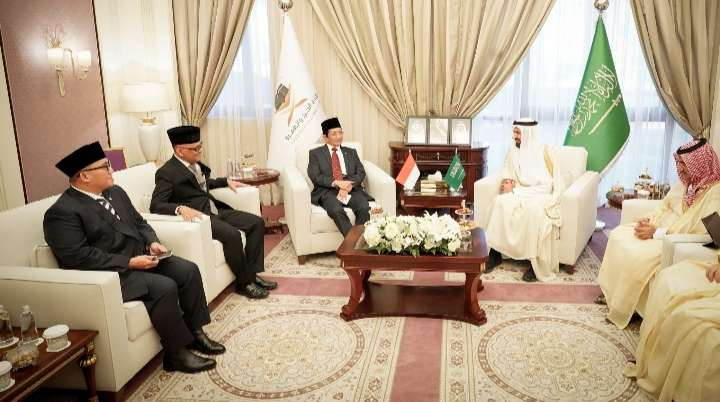Hubungan Internasional dari Pojok Sejarah

Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Perang Rusia versus Ukraina telah memasuki minggu ke tiga. Arus kuat opini dan reaksi dunia tetap selaras dengan sikap Amerika Serikat dan sekutunya. Mulai dari mengutuk sampai memberikan sanksi terhadap Rusia. Tindakan ini bukan hanya dilakukan oleh aktor negara, tetapi juga elemen swasta— baik yang terekspresi dalam media massa maupun melalui protes gerakan massa.
Tapi, yang menarik, dalam jagad media sosial terdapat pula arus lemah opini. Michael McFaul, misalnya, nge-tweet sebuah pertanyaan ‘ujian’ elementer dalam hubungan internasional (HI): “Jika sebuah negara X mengirimkan pasukan ke negara Y tanpa diundang, dinamakan tindakan apa?”. Wesley G. Hughes secara lugas menjawab: “Tergantung pada negaranya. Jika yang melakukan Rusia, maka sudah tentu itu disebut sebuah invasi, seperti kasus Georgia dan Ukrania; jika pelakunya USA tindakan itu dijuluki upaya pembebasan, seperti kasus Iraq, Syria, Libya, Panama, Cuba, Vietnam, Laos, Cambodia”.
Subtansi dialog tweeter di atas terkesan sarkastis. Tapi, bagi saya, ungkapan tersebut menarik perhatian, bahkan memantik pemikiran. Dalam tingkat mikro-empiris keduanya memang hanya mewakili ekspresi opini pinggiran. Namun, pada tataran makro-teoritis, ungkapan itu menyingkap ketimpangan pemahaman. Guna memperoleh kritisisme pemahaman terhadap HI, salah satu caranya adalah meminjam pandangan Antonio Gramsci.
Berangkat dari perspektif Gramscian, fenomena ketimpangan pemahaman di atas —langsung atau tidak langsung— merupakan refleksi dari sebuah hegemoni. Konsep ini, setidaknya menegaskan dua asumsi. Pertama, berbeda dengan Karl Marx yang hanya terpaku pada aspek kekerasan, Gramsci justru melihat hegemoni dibangun dengan dua komponen: ‘kekerasan’ (coercion) dan ‘penerimaan’ (consent).
Penerimaan yang luas akan sebuah opini tidaklah selalu bersifat alami. Tapi, sangat mungkin hasil dari sebuah konstruksi. Publik, tanpa sadar, akhirnya menerimanya bak sebuah ideologi. Bahkan, sikap ini kadang disertai kefanatikan yang dilambari sikap partisan. Opini laiknya sebuah lapisan sedimen yang kuat bercokol dalam benak orang. Akibatnya, keganjilan rekayasa menjadi tak terasa. Semua diterima sebagai pandangan utama dunia tanpa mengundang tanya.
Kedua, lazimnya pendekatan Marxian, perspektif Gramscian tak pernah abai pada sejarah. Teori justru dipandang sebagai bagian dari sejarah. Robert W. Cox —teoritisi Kritis yang berjasa membawa perspektif Gramscian dalam analisa hubungan internasional— menegaskan bahwa teori Kritis (critical theory) adalah teori tentang sejarah (a theory of history). Namun, substansinya bukan sekedar gambaran masa lalu, tteapi juga mencakup proses perubahan sejarah itu sendiri. Sejarah bukanlah navigasi linier menuju kepastian, tetapi keniscayaan akan perubahan.
Walhasil, teori Kritis tidak menerima tata dunia (world order) apa adanya, tapi secara kritis mempertanyakan asal-usulnya dan terbuka terhadap setiap kemungkinan perubahannya. Lebih dari itu, teori Kritis melihat fakta bukan hanya berdasarkan pengamatan (outside view), tetapi juga melihatnya berlandaskan pada pengalaman (inside view).
Menyangkut perang Rusia-Ukraina, teori Kritis menawarkan penjelasan alternatif. Dalam konteks kritisisme sejarah, misalnya, Vladimir Putin bukan hanya dilihat sebagai saksi, tetapi juga sosok sejarah itu sendiri. Pengalamannya memimpin Rusia selama 23 tahun sejak tahun 1999, merupakan bahan yang lebih dari cukup untuk membentuk persepsinya terhadap Rusia, Amerika, dan Dunia. Pidatonya pada tanggal 24 Februari 2022 —kala menginisisasi invasi ke Ukraina— merupakan dokumen sahih, refleksi insider perspective baik dalam kata maupun tindakan.
Bagi Putin, kehancuran Uni-Soviet adalah petaka yang harus disesali. Sejarah gemilang kekaisaran Rusia harus berakhir dengan tragis. Seperti diungkapkannya dalam sebuah wawancara: “Apa yang telah dibangun selama 1.000 tahun, sebagian besar hilang. Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang besar". Tragisnya, tragedi ini bahkan juga berimbas pada kehidupan pribadinya. Walaupun telah lima belas tahun berkarier menjadi agen Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB), pada akhirnya dia juga harus nyambi menjadi sopir taksi untuk menopang hidupnya.
Penurunan relatif kekuatan Rusia pasca Uni-Soviet, sempat memaksa Putin berpikir realistis. Dalam pidatonya, secara rasional dia menyatakan bahwa “dalam hubungan internasional, perlu mempertimbangkan perubahan keadaan dunia dan perimbangan kekuatan (balance of power)”. Baginya, ancaman strategis utama yang dihadapi Rusia adalah ambisi geopolitik Barat. Tak pelak, sejak akhir 1990-an dia mengajak Amerika untuk mengelola bersama dengan mengkoordinasikan reformasi demokrasi di Eropa Timur.
Namun, apa yang didapat Putin justru ketidakpedulian, bahkan dipermalukan. Amerika —beserta sekutunya yang tergabung dalam NATO— menginginkan Rusia tetap lemah dan selalu dalam pengendaliannya. Bersamaan dengan itu, ekspansi pengaruh NATO terus berlanjut ke Eropa Timur.
Pengalaman getir ini sempat dikeluhkannya: “selama 30 tahun kami dengan gigih dan sabar berusaha mencapai kesepakatan dengan negara-negara NATO tentang prinsip-prinsip keamanan yang setara, [tapi] kami terus-menerus menghadapi penipuan dan kebohongan yang sinis, atau upaya untuk menekan dan memeras”. Pengamatan dan pengalaman historis ini bermuara pada kesimpulannya bahwa selama ini Rusia menghadapi sebuah “Imperium Kebohongan” (an empire of lies).
Secara empiris, Putin menunjuk pada retorika Amerika yang dianggapnya bersifat hipokrit dan penuh tipu daya. Atas nama demokrasi dan kemanusiaan, negara adidaya ini semakin memperkokoh hegemoninya. Invasi AS ke Iraq —atas perintah Presiden George Bush— dianggapnya illegal, karena dilandasi konstruksi diskursif bahwa Iraq memiliki senjata pemusnah massal. Langkah serupa juga diterapkan pada Libya. Amanat PBB untuk intervensi kemanusiaan yang berlandaskan prinsip ‘responsibility of protect’ (R2P) telah direkayasa guna memperluas wilayah pengaruhnya, tanpa peduli resiko yang dihadapi.
Putin sekali lagi menegaskan: “Penggunaan kekuatan militer yang tidak sah terhadap Libya, telah memutarbalikkan semua keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB tentang masalah Libya, dan menyebabkan kehancuran total negara, menjadikannya sarang utama terorisme internasional, bencana kemanusiaan, dan perang saudara”.
Apakah pernyataan Putin diatas merupakan klaim sepihak? Ternyata tidak! Penilaian serupa —bahwa politik luar negeri AS merupakan problema politik dunia— juga dilansir oleh teoritisi Amerika. John Mearsheimer, misalnya, pada tahun 2012 dengan tegas mengatakan bahwa permasalahan politik riil yang dihadapi dunia adalah kebijakan luar negeri ‘liberal imperialist’ Amerika, yang dilaksanakan dengan konstruksi diskursif demokrasi dan kemanusiaan.
Parahnya, konstruksi ini sering disertai dengan pendekatan militeristik. Data menunjukkan bahwa pasca Perang Dingin —sejak tahun 1989— Amerika telah melancarkan perang sebanyak 7 kali, mulai dari invasinya ke Iraq (1991) sampai dengan intervensinya di Syria (2015).
Keberhasilan Putin memulihkan krisis ekonomi Rusia pasca Uni-Soviet dalam dua periode pertama jabatan Presiden (2000-2008), membuat negara ini kembali asertif secara politik-militer. Berkaca pada kasus Libya, Putin tidak mau lagi ‘diperdaya’ pada konflik Syria. Ketika Amerika membentuk koalisi internasional untuk mengintervensi Syria —dengan dalih memerangi gerakan the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL)—Rusia justru mengambil langkah yang berseberangan dengan mendukung rejim Bashar al-Assad. Jadi, keterlibatan Rusia dalam konflik di Syria sebenarnya merupakan titik balik relasi kekuatan (power relation) antara AS dan Rusia semenjak runtuhnya Uni-Soviet.
Yang menarik, langkah politik-militer Rusia untuk mengimbangi Amerika justru meniru model ‘tipu daya’ rivalnya tersebut. Dalam invasinya ke Krimea tahun 2014 —yang berujung pada aneksi— Rusia juga menggunakan dalih kemanusiaan. Alasannya, mencegah ‘genosida’ terhadap warga keturunan Rusia yang tinggal di semenanjung itu. Terakhir, pengakuan Putin terhadap dua wilayah Ukraina timur yang memisahkan diri —Donetsk dan Luhansk— mengingatkan pada tindakan illegal Presiden Trump mengakui penguasaan Israel terhadap Yerusalem Timur yang milik Palestina, dan pencaplokan dataran tinggi Golan kepunyaan Syria.
Benar kata Bishara: “Old habits die hard!” (kebiasaan lama susah hilang!)
Memahami langkah perang Putin bukan berarti menyetujuinya. Toh, filsuf Inggris—Bertrand Russell—pernah menggarisbawahi: “Perang tidaklah menentukan siapa yang benar!”. Simpati akan, bahkan harus, tertuju pada korban invasi, termasuk pengungsi yang telah mencapai 2 juta orang. Pencarian penjelasan alternatif merupakan bentuk kritisisme terhadap opini dunia yang hegemonik. Analisa tentang asal usul dan karakternya sekedar untuk menyajikan sudut pandang yang lebih fair dan seimbang.
Di balik itu, beberapa proposisi akademik mungkin bisa dipetik. Bagi negara adidaya, keputusan untuk berperang bukan hanya dipicu masalah kedaulatan dan keutuhan territorial semata. Ancaman keamanan strategis dihadapinya bisa jadi mendorong langkah yang serupa. Selain itu, perubahan relasi kekuatan antara Rusia dan Amerika —akibat kebangkitan ekonomi dan asertivitas politik Rusia— telah mengubah kepastian arah sejarah. Dengan konstelasi politik dunia mutakhir, Perang Dingin jilid II sangat mungkin akan lahir. Jika siklus sejarah ini benar-benar terjadi, maka postulat Fukuyama tentang the end of history mungkin perlu direvisi, karena yang terjadi justru “the sustainability of history”.
Yang terakhir, pola hubungan internasional relatif tak berubah. Determinan politik luar negeri juga tetap lestari. Fukuyama, sekali lagi, nampaknya perlu juga untuk mengoreksi argumennya tentang Neo-liberal internationalism, bahwa sistem demokrasi cenderung mendorong perilaku negara yang damai. Alasan empiriknya, sistem politik —apakah demokrasi ala Amerika ataukah otoriter seperti model Rusia— ternyata bukanlah penentu dominan corak politik luar negeri negara adidaya. Secara historis, perilaku negara-negara besar di panggung politik dunia ternyata justru lebih didominasi oleh sifat geopolitik, ambisi, dan kepentingan strategisnya.
Wallahu a’lam!
*) Himawan Bayu Patriadi adalah Dosen Hubungan Internasional
Universitas Jember.
Advertisement