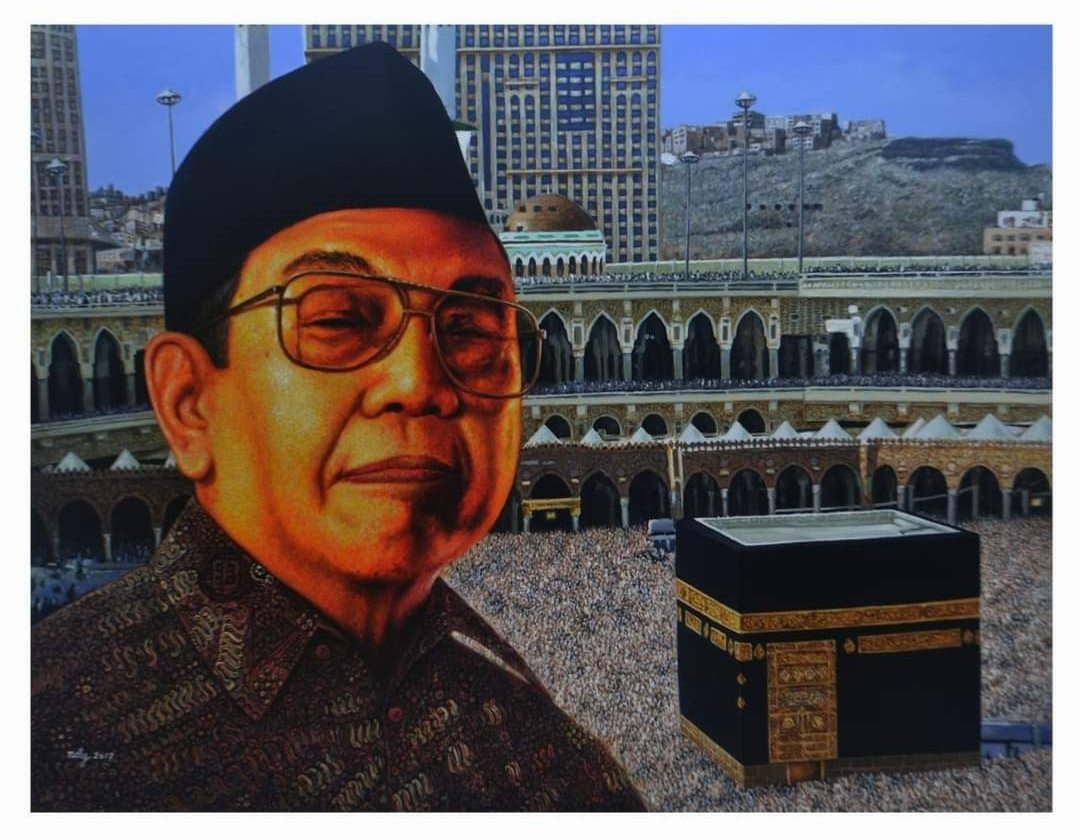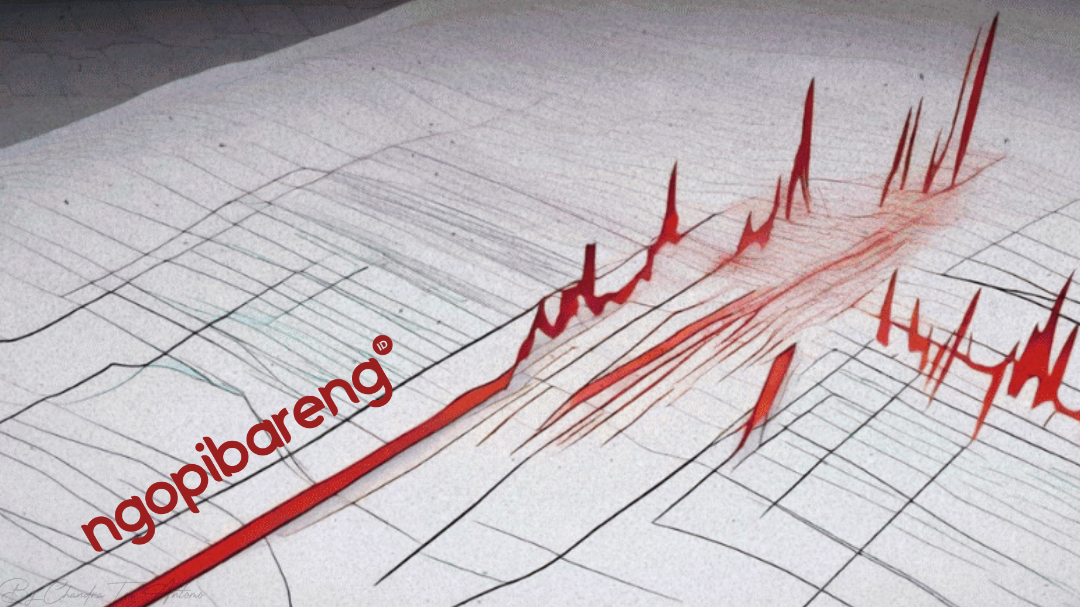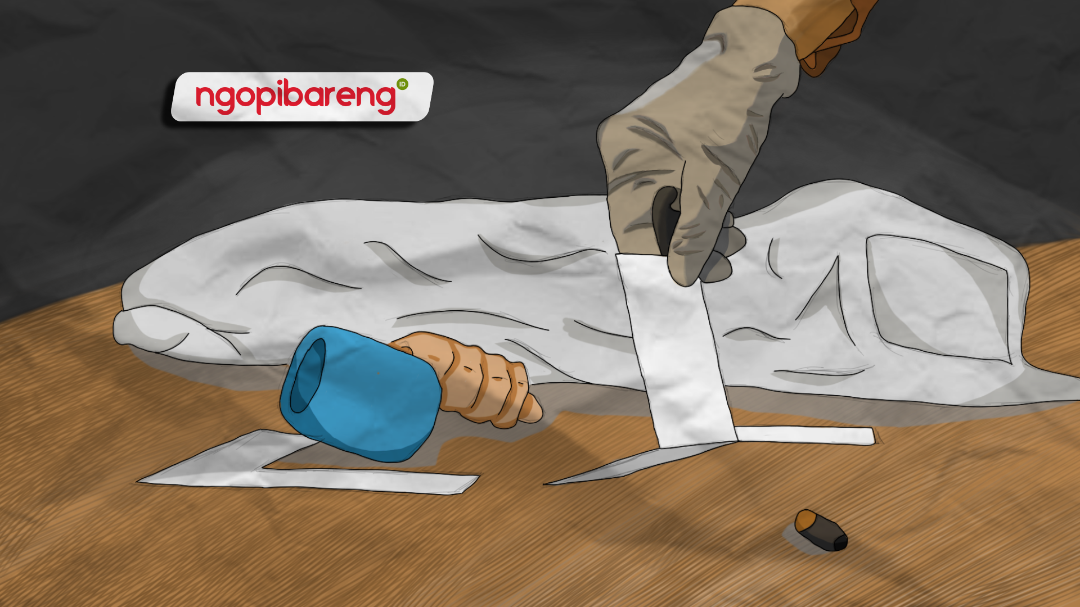Harlah ke-95 NU: ''Keramatnya'' Nahdlatul Ulama

Ini hanya bingkisan kecil. Tidak pantas disebut kado. Tujuannya, untuk ikut memeriahkan. Saya tidak berani “sok semugih” memberi kado. Atau “sok kuminter” memberikan saran pemikiran. Di Nahdlatul Ulama (NU), banyak orang yang lebih pantas memberi kado ulang tahun. Juga berjejal orang cendik pandai yang layak memberikan sumbang saran pemikiran.
Januari ini, ditetapkan sebagai hari ulang tahun (harlah) NU. Harlah versi kalender Masehi. Tepatnya pada 31 Januari. Bila merunut hitungan masehi, tahun ini NU “baru” bersusia 95 tahun. Sedang kalau menggunakan hitungan kalender Hijriyah, usianya lebih dari itu; 97 jalan, hampir 98.
Secara organisasi (jam’iyah), benar usia NU “baru 95 atau 97 jalan”. Namun, secara jamaah (sosial budaya), saya rasa lebih tua dari itu. Islam yang masuk ke Indonesia, karakteristiknya adalah karakteristik Islam yang diamalkan dan dilestarikan warga NU hingga saat ini.
Sebelum secara jam’iyah NU terbentuk, karakteristik sosial budaya itu diajarkan, diamalkan dan dilestarikan lewat pesantren. Di awal-awal Islam masuk Indonesia, karakteristik keislaman di Indonesia secara garis besar sama. Tidak multi corak seperti sekarang.
Secara fiqih mengikuti Madzhab Imam Syafii. Secara aqidah mengikuti pemikiran Imam Abdul Hasan Al-Asy’ari dan Abu Manshur Al-Maturidi. Amalan tasawufnya mengacu kepada amalan yang diajarkan oleh Imam al-Ghozali dan Imam Junaid al-Baghdadi.
Sejarah mencatat, dengan berkarakteristik seperti itu, para pendakwah Islam bisa membawa Islam ke Indonesia dengan damai. Kedatangan Islam tidak dianggap problem. Tidak dimaknai ancaman bagi budaya lokal. Nilai-nilai Islam, tanpa terasa menyatu dengan budaya yang ada di Indonesia dengan smart.
Perkawinan budaya lokal dan Islam, melahirkan tatanan budaya baru yang unik. Tidak sama dengan budaya lama karena sudah terisi oleh muatan-muatan tauhid. Juga tidak sama dengan budaya Islam yang ada di negara lain, khususnya di Makkah dan Madinah, karena memang sudah berbaur dengan budaya Nusantara.
Inilah Islam Nusantara. Secara subtansi, tidak beda dengan Islam pada umumnya. Namun, secara ekspresi budaya, Islam yang berkembang di Indonesia memiliki karateristik khusus. Yakni, karakteristik budaya nusantara yang islami.
Islam di negara lain, saya rasa juga memiliki pola seperti itu. Karena pada dasarnya, perkawinan Islam dengan budaya lokal seperti itu adalah sebuah keniscayaan. Itu sesuai dengan naluri kemanusiaan. Yakni, memadukan yang sudah ada dengan nilai-nilai baru yang dianggap baik.
Rasanya, sulit ditemukan, bila ada “Islam murni” yang benar-benar tidak berinteraksi dengan budaya lokal. Islam di Arab Saudi pun, merupakan perkawinan antara ajaran (nilai-nilai) Islam dengan budaya lokal masyarakat di sana.
Itu logika yang sangat sederhana. Harusnya mudah dipahami. Bila pada kenyataannya muncul kontroversi, ya...karena memang ada yang sengaja memunculkan. Motifnya macam-macam. Tapi biarlah. Gawe rame-rame ndoyo. Biar dunia ini menjadi samarak. Warna-warni!
Kodrat manusia memang berbeda. Masing-masing punya subyektifitas. Punya sudut pandang yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Ada ruang dan waktu yang mempengaruhi sudut pandang itu. Juga ada kepentingan pribadi (ego) yang ikut andil di dalamnya.
Kesimpulan yang perlu saya sampaikan, Islam Nusantara pada hakikatnya sudah wujud ratusan tahun lalu, sebelum NU terbentuk. Jadi, istilah “Islam Nusantara” dijadikan hasil muktamar NU apa tidak, pada dasarnya tidak penting. Itu hanya istilah. Alergi dengan istilah itu, mau pakai istilah lain pun tidak jadi soal.
Yang lebih penting dari sekadar memperdebatkan istilah, menurut saya, adalah memahami realitas sosial yang ada. Di mana, karakter keislaman yang seperti itu (perkawinan Islam dan budaya lokal), terbukti menjadikan Islam diterima oleh mayoritas penduduk di kepulauan nusantara ini. Tidak menimbulkan gesekan dengan agama Hindu-Budha yang sudah ada sebelumnya.
Fakta berikutnya, Indonesia sampai sejauh ini masih terjauhkan dari konflik internal yang berbasis idiologi seperti yang terjadi di kawasan lain, khususnya kawasan Timur Tengah. Hubungan Islam dan negara sudah terumuskan dengan baik. Pancasila menjadi persenyawaan nilai-nilai Islam dan budaya nusantara.
Karena kepentingan tertentu, sekolompok anak bangsa memang sempat menyalahpahaminya. Bahkan dengan bantuan penguasa pemerintahan (rezim), kelompok itu sempat berniat memusnahkan model keislmanan seperti itu. Dengan dalih dipenuhi praktik syirik, bid’ah dan khurafat. Kemudian, ingin menggantinya dengan model keislaman yang dianggap lebih murni.
Namun nyatanya, upaya itu tidak mendapat dukungan penduduk mayoritas di negeri ini. Mereka tetap pada posisi minoritas. Begitu rezim penyokongnya tumbang, maka gerakan itu menjadi mati kutu. Layu sebelum berkembang.
Warga NU mendefinisikan fenomena itu dengan bahasa: NU itu Keramat. Yang memusuhi NU bakal kuwalat.
Di berbagai medsos sempat beredar, deretan daftar kelompok-kelompok yang pernah berbenturan dengan NU. Satu per satu kelompok-kelompok itu tumbang. Sementara, NU sebagai Jam’iyah tetap utuh sampai sekarang.
Secara jam’iyah, para ulama di internal NU mengakui NU masih lemah. KH Mustofa Bisri (Gus Mus) pernah menyampaikan, problem NU yang masih sulit dipecahkan adalah menjam’iyahkan jamaah NU. Yakni mengorganisir kaum muslimin yang berbudaya ala Islam Nusantara itu untuk dihimpun dalam satu wadah. Satu pimpinan. Satu komando.
Kebenaran dari narasi yang dimunculkan Gus Mus itu, mudah dibuktikan. Survei-survei yang sering dilakukan lembaga-lembaga kredibel menunjukkan bahwa warga NU sebanyak 40 persen dari jumlah umat Islam Indonesia. Itu artinya akan ketemu angka sekitar 90 jutaan lebih. Namun, kalau dilakukan pendataan resmi (dibuatkan Kartanu, misalnya), bisa dipastikan, angka 90 juta itu sulit dicapai.
Begitu juga dengan pesantren, madrasah, sekolah dan perguruan tinggi. Jika diidentikkan dengan NU, banyak sekali yang identik dan mengaku NU. Jumlahnya bisa puluhan ribu. Namun, bila melihat data resmi yang terdaftar sebagai milik NU, jumlahnya jauh di bawah itu.
Itulah gambarannya. Saya yang sejak lahir sudah hidup di tengah-tengah budaya NU, juga merasakan itu. Namun uniknya, meski sulit diorganisir, sulit dijam’iyahkan, nyatanya NU tetap eksis sampai sekarang.
Mengapa demikian? Jawabannya bisa beragam. Mayoritas warga NU menyakini, ini karena para pendiri organisasi ini adalah orang-orang mukhlis. Mereka mendirikan jam’iyah dengan niat tulus. Ada proses-proses spiritual yang menyertainya. Bahkan untuk membuat lambang NU saja, KH Ridlwan Abdullah, Kawatan Surabaya, harus melakukan laku spriritual.
Orang di luar NU, mungkin sulit memahami hal itu. Boleh-boleh saja. Kalau saya sendiri punya asumsi, selain faktor “X” tadi, faktor pendukung lainnya adalah karena kesesuaian antara Islam yang diamalkan NU dengan budaya lokal Indonesia. Jadi, pada hakikatnya warga NU adalah orang Indonesia yang beragama Islam. Bukan orang Islam yang kebetulan tinggal di Indonesia. (bersambung)
Advertisement