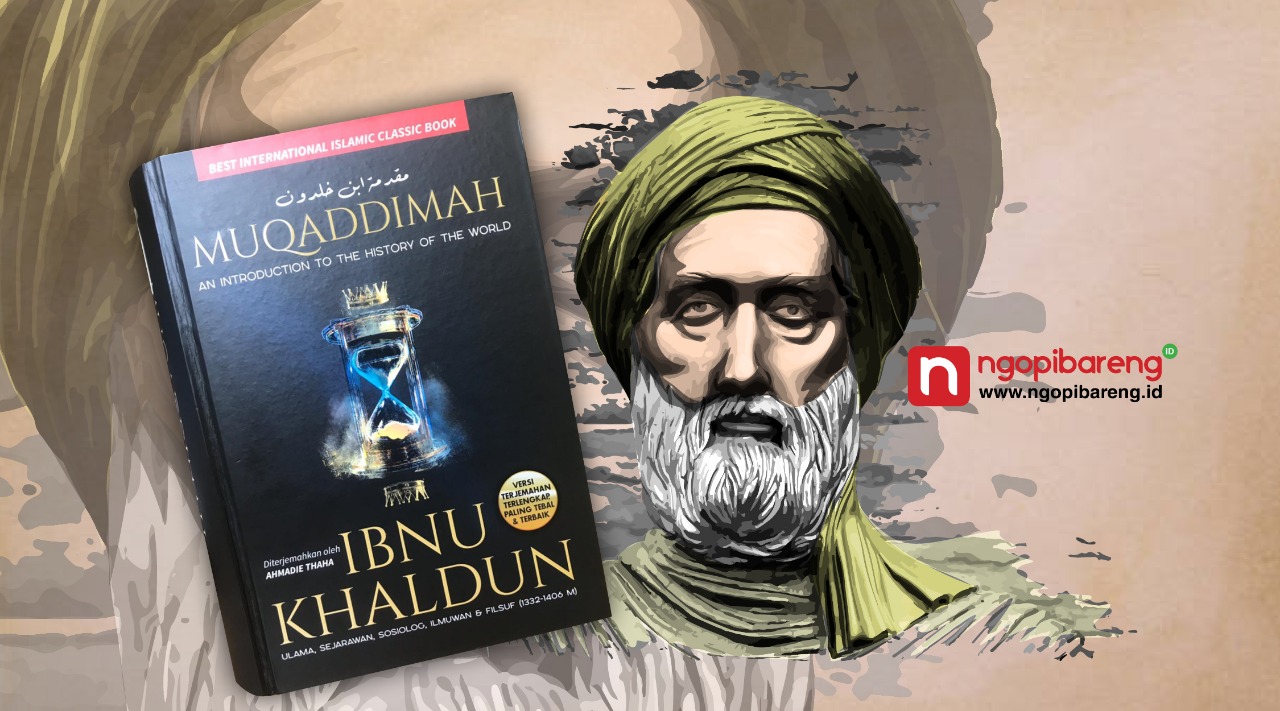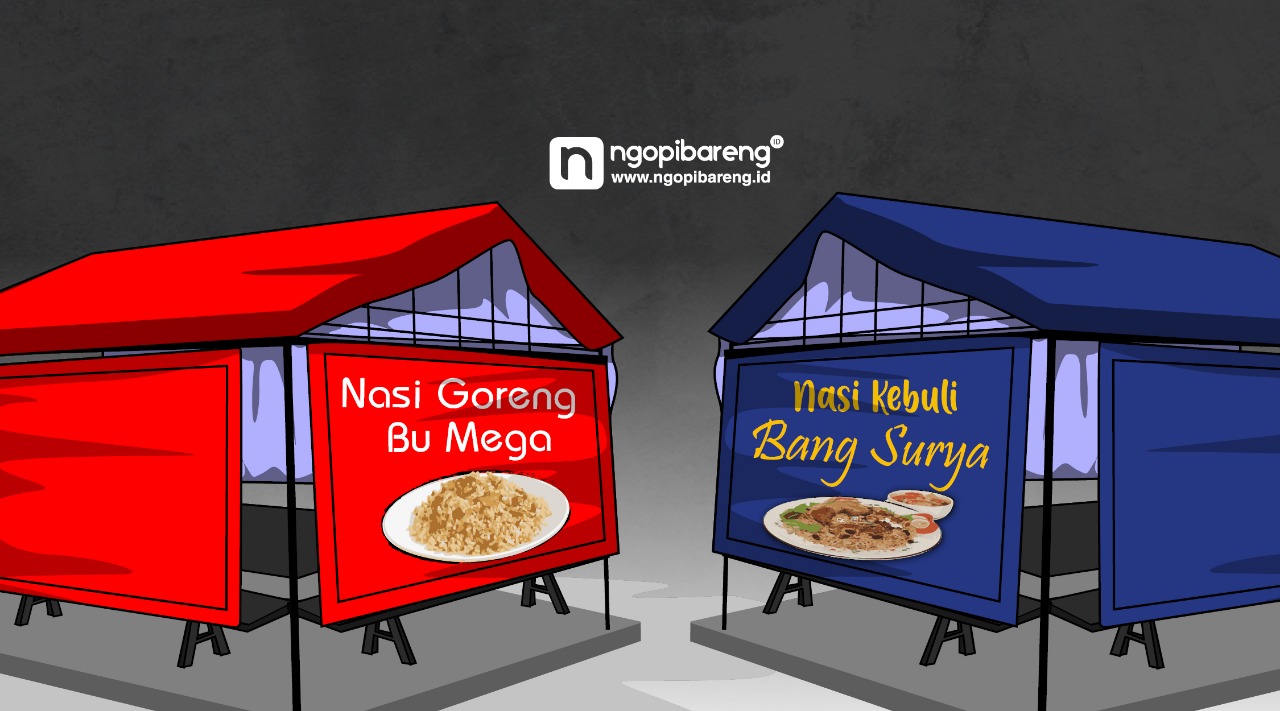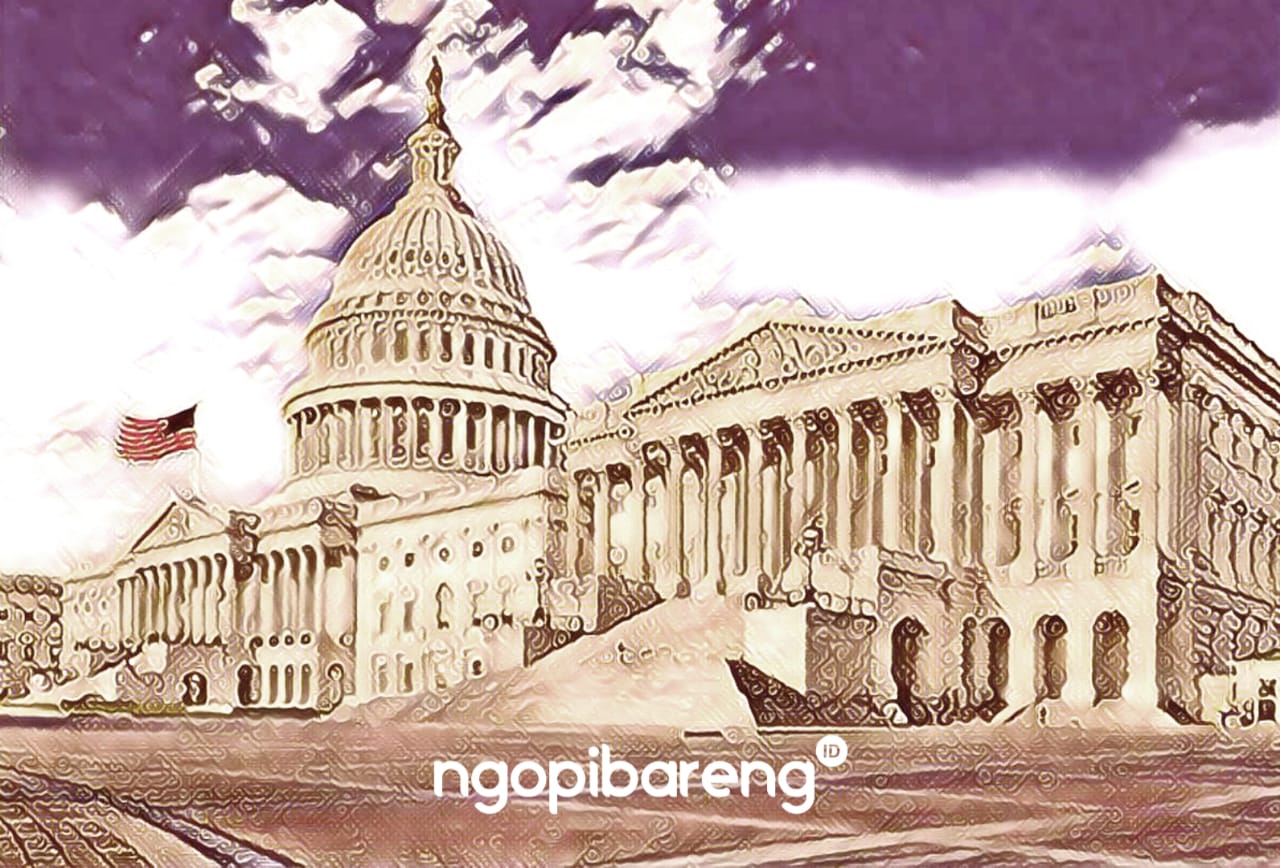Haji yang Membebaskan

Sabtu lalu, 11 Agustus 2019, kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Di jaziarah Arab, tepatnya di Padang Arafah, ada kegiatan yang lebih mengetarkan dada. Karena ada 2.489.406 jemaah haji yang melakukan wukuf.
Semua jamaah dari penjuru dunia, dengan beribu bahasa, warna kulit, disatukan. Wukuf bisa dikatakan, jadi inti dari ibadah haji. Di sinilah, pengalaman paling berkesan.
Seluruh jaamah berkumpul bersama. Tugasnya cuma satu. Merenung, merenung, dan merenung. Mengingat seluruh perilaku yang sudah dilakukan selama hidup.
Ya, kebaikan atau keburukan. Saat lebih banyak keburukan terlintas, di sinilah seluruh doa tobat harus dipanjatkan. Meminta rida Allah, agar semua dosa dihapuskan.
Memang secara maknawi, wukuf berarti mendiamkan akal. Agar batin mengingat diri, ruh suci yang ditiupkan Allah SWT. Sedangkan Arafah bermakna ma'rifah, yaitu mengenal.
Jadi, jika kita merenung di Arafah, seharusnya, inilah jalan tercepat untuk kembali mengenal Allah. Dia pemilik sekalian alam. Karena tak ada yang lebih hakiki selain ketertundukan secara tulus kepada Allah.
Karena kalau sedikit menenggok ke belakang, sebelum fase wukuf, para jamaah haji mengenakan ihram. Saat itu, banyak hal halal pun berubah menjadi haram. Tentu saja sebagaimana aturan berihram.
Di sini, tingkat kesetiaan dan ketulusan ibadah diuji makin tinggi. Banyak yang meyakini, pelarangan saat berihram jadi simbolisasi pencapaian kesucian diri. Ketulusan dan ketaatan atas janji kepada Allah.
Bila lulus, maka level spritual kita naik lebih tinggi. Seharusnya, ini lebih pada status keimanan. Namun, bagi masyarakat nusantara, status haji juga menaikkan status sosial di depan khalayak.
Jangan heran, ini alasan mengapa warga Indonesia lebih mengenal frasa “naik haji” ketimbang berangkat haji. Tentu, ini juga akibat sejarah kita. Dulu, status haji mulai dilekati kepada warga nusantara oleh VOC.
Penyebabnya, jelas. Mereka yang baru pulang dari Mekah, membawa spirit baru anti penindasan. Semangat melawan penjajahan dengan landasan perjuangan agama. Atau bisa disebut sebagai jihad. Dan surga adalah ganjarannya.
Bahaya politik para haji diendus oleh Gubernur Jenderal pada awal abad 19, yakni Thomas Stamford Raffles. Awalnya, pegawai VOC melihat perjalanan ini hanya urusan uang semata. Karena VOC mendapatkan keuntungan dengan menyediakan kapal-kapal.
Namun mereka mulai menemukan, sulitnya memadamkan gejolak perlawanan karena disulut faktor agama. Tak heran, Pemerintah Hindia Belanda menelurkan Ordonansi Haji tahun 1825. Isinya jelas. Membatasi jumlah jamaah yang akan berangkat haji.
Gubernur Raffles, menuliskan temuan atas perilaku para haji ini, dalam buku The History of Java. Menurutnya, orang Arab dari Mekah atau setiap orang Jawa yang kembali dari ibadah haji, mereka berubah. Tampil seperti orang suci.
Para haji ini begitu dihormati masyarakat. Tentu saja, karena perjuangannya untuk ke Mekah dan pulang, membutuhkan perjuangan. Bak hidup dan mati.
Selain itu, secara tak langsung mereka dilekati status terpelajar. Karena telah belajar ilmu agama dari sumbernya. Selain itu, jumlah mereka yang sedikit, membuatnya jadi spesial.
Status sosial baru ini yang memang menakutkan. “Maka tidak sulit bagi mereka untuk menghasut rakyat agar berontak. Mereka menjadi alat paling berbahaya di tangan penguasa-penguasa pribumi,” tulis Raffles.
Tapi itu dulu. Kini, dengan perkembangan jaman, hanya ada satu masalah terkait haji ini. Yakni, masa tunggu.
Jatah kuota haji untuk Indonesia sebanyak 221.000 jemaah. Komposisinya, 204.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji khusus. Nah, kuota ini dibagi ke 34 provinsi.
Masa tunggu keberangkatan haji tercepat ada di dua provinsi. Yakni Gorontalo dan Bengkulu. Rata-rata waktu tunggu 9-10 tahun.
Masa tunggu terlama adalah 41 tahun. Ini ada di Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk Bekasi, masa tunggu mencapai 18 tahun.
Lamanya masa tunggu memang bervariasi. Tergantung perbandingan antara kuota dengan jumlah pendaftar. Menunggu dengan selama itu tentu butuh semangat serta ketulusan.
Namun, banyak juga yang bisa berhaji berkali-kali. Salah satunya, Haji Nordin Hidayat. Dia alumnus PP Gontor.
Tapi, harap maklum. Haji Nordin ini punya usaha terkait umrah dan haji. Kantornya ada di Jakarta dan di Mekah. Hidupnya, bolak-balik antar dua kota itu.
Pekerjaannya, juga sangat mulia. Membantu para tamu Allah dalam beribadah. Untuk mencari berkah Illahi.
Tahun ini, adalah hajinya yang ke-17. Kadang, hati kecil ini bertanya, bagaimana rasanya wukuf tiap tahun? Seperti apa kadar nikmatnya getaran Illahi itu? Apakah kadarnya tiap tahun meningkat?
Di sela-sela melayani tamu Allah tahun ini, Haji Nordin pun berkirim pesan suara. Terutama, tentang wukuf selama 17 kali itu. “17 kali wukuf, tentu 17 kali pengalaman yang berbeda,” ungkapnya.
Setiap wukuf itu, dia mengaku hanya pasrah. “Berserah diri, Allah yang maha segalanya,” tegasnya. Karena tidak ada kekuatan selain Allah, hanya kepada Allah kita bergantung.
Memang, terkait pelaksanaan ibadah haji, tempatnya sama setiap tahun. Tapi yang berbeda dinamikanya. “Itu salah satu pembuktian, Allah maha besar dengan segala kehendaknya,” tambahnya.
Haji Nordin mengaku, ibadah haji akan membuka watak seseorang yang sebenarnya. Yang paling terasa, tentu saat di Arafah dan Mina. Dengan fasilitas terbatas tapi untuk jutaan jamaah.
Semua harus antre. Dari ke kamar mandi, makan, juga tempat tidur terbatas. “Apakah dia penyabar? Kuat Menghadapi kondisi ini,” katanya.
Saat mereka mendapatkan kenikmatan, cobaan, atau kondisi yang tak ideal. Semua akan dinilai, apakah dia hamba yang bersyukur atau tidak. Tentu, semua berharap berpredikat haji mabrur.
Karena balasan berhaji adalah surga. Sebab, haji ini tak cuma perjalanan. Ada pengorbanan di sana. “Untuk penguatan tauhid kita kepada Allah,” tegasnya.
Seharusnya, saat kembali ke tanah air, perilaku ideal muslim harus terus dijalani. “Kalau tidak, ibadah haji hanya berakhir sekadar status saja atau hawa nafsu,” paparnya.
Ajar Edi, kolumnis “Ujar Ajar” di ngopibareng.id
Advertisement