Gorbachev dalam Panggung Politik Dunia
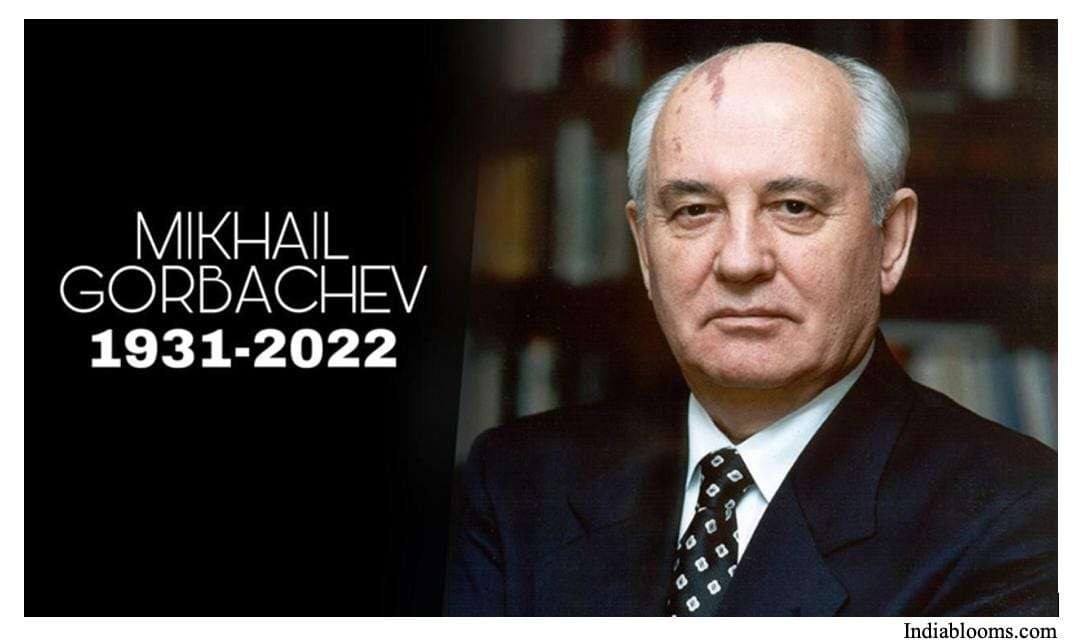
Oleh: Himawan Bayu Patriadi, PhD.
Dosen HI Universitas Jember dan Taiwan’s MoFA research fellow di Wenzao Ursuline University
Nama lengkapnya Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Populer dipanggil Gorbachev. Sosok yang mengandung kontroversi. Di Barat dia dipuji, di negeri sendiri sempat dibenci. Ironi ini bisa dideteksi dari julukannya. Barat memanggilnya “Gorby”, ekspresi sebuah keakraban. Tapi, di negerinya pernah dipanggil “Gorbach” (si bungkuk); sebuah julukan pejoratif, manifestasi sikap kebencian.
Dua sisi pandangan yang paradoksal di atas tak lepas dari keberaniannya mngambil langkah di tingkat nasional, tapi berdampak global. Di mata Barat, Gorbachev dipandang sebagai sosok yang mengubah dunia. Berkat kebijakannya, Perang Dingin antara Timur-Barat berakhir, sekaligus membebaskan Eropa Timur dari cengkeraman Uni-Soviet. Banyak yang menganggapnya sebagai ‘pahlawan’, karena telah mencegah Perang Dunia ke tiga, sehingga membuat dunia lebih aman.
Tapi, bagi negerinya, jalan reformasinya terasa menyakitkan. Banyak warganya terkejut dengan bubarnya Uni-Soviet, negara yang dicintainya. Mereka juga tertegun karena dalam waktu singkat mendapati diri mereka telah terpisah dalam 15 negara baru. Gundah-pun datang beruntun seiring petaka yang datang hampir tanpa jeda. Transisi yang tak menentu membuat puluhan juta orang kehilangan karier dan pendapatan, putusnya kontak dengan kerabat yang terpisah di berbagai negara-negara baru mantan anggota Uni-Soviet, menghadapi konflik kekerasan antar-etnis, dan mendapati pemerintahan yang korup. Bahkan, Vladimir Putin telah menilainya sebagai bencana geopolitik terbesar dalam sejarah.
Apakah misi Gorbachev gagal? Jawabannya pasti: “iya!”. Namun, apakah dia salah? Jawabannya ragu: “mungkin!” Dengan akibat yang berlipat, memang tak mudah memahami argumen di balik reformasi ala Gorbachev. Bahkan, diperlukan waktu yang lama untuk memetik hikmah dari langlahnya. Seorang jurnalis asal Uzbekistan, Mansur Mirovalev, bersaksi: “Butuh waktu berpuluh tahun bagi saya untuk menyadari bahwa Gorbachev memberi saya dan hampir 300 juta warga Soviet kebebasan–untuk mengatakan, menulis, menonton, membaca, dan percaya pada apa yang kami inginkan; untuk memilih karier atau tempat tinggal, bepergian ke luar negeri–dan tidak [lagi] dicuci otak oleh propaganda [Komunis] yang membosankan dan mematikan pikiran”.
Sejumlah catatan penting
Sebagai pemimpin tertinggi Soviet, Gorbachev menorehkan beberapa catatan. Tahun 1985, dia menggantikan Konstantin Chernenko yang meninggal dalam usia 73 tahun. Naiknya ke tampuk kekuasaan tertinggi Kremlin mengakhiri gerontokrasi-kekuasaan yang didominasi oligarki kaum tua-di negerinya. Saat terpilih menjadi Sekretaris Jenderal partai Komunis Uni-Soviet, dia baru berumur 54 tahun, jauh di bawah umur rata-rata pendahulunya, seperti Leonid Brezhnev, Yuri Andropov, dan Konstantin Chernenko.
Sosoknya sebagai generasi baru dalam kepemimpinan Soviet, merupakan penjelas utama dari kebijakannya yang berbeda dari para pendahulunya. “Setiap orang ingin melakukan sesuatu dengan caranya sendiri” tegasnya. Sebuah justifikasi terhadap “jalan lain” yang ditempuhnya. Gorbachev merupakan pemimpin Komunis tertinggi Soviet yang lahir setelah revolusi Bolshevik Oktober tahun 1917. Dilahirkan tahun 1931, ia terlalu muda untuk terjerembab dalam lorong sejarah yang membentuk pola pikir pendahulunya. Selain terhindar dari jebakan role model kepemimpinan Joseph Stalin yang brutal, ia juga terbebas dari tawanan sejarah Perang Dunia II yang cenderung membentuk sikap paranoid. Secara ideologis, Gorbachev justru lebih dekat dengan pemikiran Vladimir Ilyich Lenin, yang dianggapnya lebih manusiawi.
Pengalamannya sebagai kader partai Komunis yang ditugasi sebagai administrator pertanian membuatnya akrab dengan spirit inovasi. Gorbachev mendapati sistem Komunis yang rapuh. Ekonomi stagnan karena terbelenggu berbagai restriksi. Di Leningrad, ia pernah secara tegas mengingatkan seorang petinggi Komunis: "[Perekonomian] anda tertinggal di belakang negara lainnya”, dan ketertinggalan itu merupakan "barang jelek yang memalukan!”. Tak aneh, jika ia kemudian berpandangan bahwa "perestroika" (restrukturisasi ekonomi) mendesak untuk dilakukan, dengan “glasnost” (keterbukaan) sebagai prasarananya.
Namun, kita akan offside apabila menganggap reformasi Gorbachev adalah langkah pragmatis yang meninggalkan nilai-nilai ideologis. Reformasinya lebih merupakan langkah inovatif, tanpa dimaksudkan untuk menjadi radikal dengan mengubah ideologi. Langkahnya itu justru ingin merevitalisasi sosialisme Soviet, dilandasi keyakinannya terhadap pemikiran Lenin. Tahun 1985, sesaat setelah menjadi pemimpin Soviet dengan tegas dia mengingatkan delegasi yang hadir di forum partai Komunis: “beberapa dari anda melihat bahwa [mekanisme] pasar sebagai penyelamat ekonomi kita. Tapi, kawan-kawan, anda seharusnya tidak [terfokus] memikirkan penyelamat tetapi lebih [berfikir serius] tentang kapal [kita], dan kapal itu adalah sosialisme!".
Dalam hubungan internasional, reformasi Gorbachev beserta dampaknya juga membawa disrupsi teoritis. Dia tampil pada di masa kejayaan Realisme (the heyday of realism). Ironisnya, kebijakannya bak langkah bidak catur yang tak terduga. Kaum Realis tertegun, karena teorinya mendadak kehilangan lantun. Realisme semula, dan senantiasa, berasumsi bahwa power merupakan determinan utama perilaku negara. Proposisi teoritiknya, dalam konteks persaingan super-power, kekhawatiran akan meletusnya perang selalu mencegah keinginan negara untuk melakukan kerjasama. Tapi, yang terjadi justru sebuah anomali. Kemauan Gorbachev memberi konsesi pada Barat guna membangun hubungan berdasarkan “common security” (keamanan bersama) tak pernah ada dalam leksikon teori Realis.
Pada saat yang sama, argumen teoritis Realis juga mengalami krisis. Dengan keyakinannya akan pentingnya peran power dalam politik internasional, maka prediksi hasil akhir persaingan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni-Soviet akan ditentukan oleh power game yang dilakukan. Yang menarik, runtuhnya Uni-Soviet-yang menandai akhir Perang Dingin-bukanlah akibat tekanan eksternal, khususnya dari AS; melainkan justru akibat persolaan domestik. Tahun 2014, dalam wawancara dengan BBC, Gorbachev meyakinkan bahwa hancurnya Uni-Soviet bukan akibat faktor luar, tetapi murni karena “faktor dan proses internal di dalam negeri!”. Berlandaskan semua ini, Richard Ned Lebow melihat ‘kegagalan’ Realisme sebagai teori (a “failure” of realist theory), karena tak bisa dipakai untuk menjelaskan permusuhan antara AS- dan Uni Soviet.
Realisme yang berkelit
Memang ada eksponen Realisme yang mencoba ‘berkelit’ dalam penjelasannya, Jack Snyder, misalnya, meracik argumen prediktif dengan mengatakan bahwa proses demokratisasi, seiring reformasi yang dilakukan Gorbachev di Uni Soviet, bisa memunculkan ultra-nasionalisme yang akan berujung pada perilaku internasional yang agresif. Apalagi jika proses demokratisasi tersebut tidak berjalan tuntas. Sayangnya, prediksi ini sekali lagi tak terbukti. Argumennya tertebas karena Uni Soviet keburu tewas. Namun, rekomendasi yang diajukan layak untuk direnungkan. Menurutnya, dengan drama Perang Dingin (Cold War) yang berakhir secara tak terduga, perlu bagi para teoritisi hubungan internasional untuk menyimak pandangan dari studi perbandingan politik guna memperkaya pendekatan terotisnya.
Fenomena Gorbachev juga sempat mengundang keraguan di kubu teoritisi lain. Kegagalan eksplanatif Realisme tak serta merta membuat paradigma saingannya-Liberalisme-optimis. Michael Doyle, misalnya, secara elegan mengingatkan optimisme yang ditebarkan oleh Liberalisme. Dikatakannya, ide-ide liberalisme yang telah mengerakkan Gorbachev untuk melakukan reformasi tidaklah otomatis melahirkan hubungan harmonis antara dua negara adidaya, karena secara empiris justru secara tragis telah membuat runtuh salah satunya.
Pada saat yang sama, muncul penjelasan alternatif teoritis. Konstruktivisme sempat membuat penjelasan yang persuasif. Koslowski dan Kratochwil, misalnya, berargumen bahwa sistem internasional setiap kali akan bertransformasi jika “keyakinan dan identitas aktor domestik berubah, sehingga akan mengubah [pula] aturan dan norma yang membentuk langkah politik mereka”. Merujuk pada fenomena Gorbachev, argumen ini mempunyai pijakan empiris. Michael McFaul, seorang analis politik dan mantan duta besar AS di Moskow, pernah bersaksi bahwa “Gorbachev adalah seorang idealis yang percaya pada kekuatan gagasan dari seorang individu”. Namun, Stephen Walt segera memberi catatan dengan sebuah pertanyaan: “jika memang kebijakan negara bisa mengubah sistem internasional, sejauh mana cakupan perubahannya?” Jawabannya tak pasti. Alasannya, esksekusi kebijakan negara hampir selalu berubah. Akibatnya,, identifikasi sebuah sistem internasional baru selalu terjerembab oleh indikator yang nisbi.
Review kritis di atas bukan berarti tidak realistis. Semua paradigma teori memang punya limitasi. Namun, yang luput dari kontestasi argumen teoritis di atas adalah eksplanasi yang berangkat dari sisi humanis seorang Gorbachev. Dalam wawancara di awal tampuk kekuasaannya, Gorbachev berkata: "Ketika saya menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis Soviet, saya melakukan perjalanan ke kota-kota di seantero negeri guna bertemu rakyat jelata”. Ada satu hal yang sarat makna disampaikan warga terhadapnya. Ia melanjutkan cerita: “Mereka berkata kepada saya, Mikhail Sergeyevich, jangan kawatir, [terhadap] apa pun masalah yang kita hadapi, termasuk kekurangan pangan. Kita akan punya cukup makanan. Kita akan menanamnya. Kita akan mengelolanya. [Kami hanya memohon] pastikan saja tidak [akan] ada perang!'". Tak terasa, air mata meleleh membasahi wajahnya. “Saya tercengang. [Ternyata] sampai begitunya penderitaan mereka dalam Perang [Dingin] terakhir", ungkapnya sambil terbata.
Sisi humanisnya sempat melandasi kebijakannya. Orang heran mengapa Gorbachev membiarkan Eropa Timur bebas menentukan nasib dirinya. Bahkan, mereka telah menanggalkan ideologi sosialisme-nya. Muncul spekulasi bahwa sikapnya itu menunjukan keraguannya melakukan represi karena penurunan relatif kekuatan Uni Soviet. Sekali lagi, argumennya, mengecoh banyak orang. Dalam salah satu wawancara, ia berkata bahwa dia mengambil sikap untuk tidak turut campur dalam perkembangan di Eropa Timur guna mencegah pertumpahan darah. “Selama saya berkuasa pertumpahan darah tidak boleh terjadi lagi”, tegasnya. Sikapnya ini mengakhiri doktrin geopolitik Brezhnev yang menggarisbawahi bahwa “setiap ancaman terhadap pemerintahan sosialis di bagian negara mana pun di dalam blok Soviet, [termasuk] di Eropa Tengah dan Timur adalah ancaman terhadap blok sosialis secara keseluruhan”. Langkah ini merupakan ekspresi penegasan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan represif ala Stalin, sekaligus menunjukkan konsistensi kekagumannya terhadap pemikiran Lenin.
Tahun 2000, ekspresi sisi humanis Gorbachev mencapai titik kulminasi. Setahun setelah ditinggal istrinya tercinta-Raisa Gorbacheva-yang wafat karena leukemia, ia berkata: “Hidup saya telah kehilangan makna utamanya … dan saya tidak pernah memiliki perasaan kesepian yang begitu akut [seperti kali ini]”. Meninggalnya Raisa memang meredupkan keceriaan hidupnya. Namun, kematian Gorbachev minggu lalu tidaklah melanjutkan kesepian dalam kehidupan pribadinya. Terlepas dari kontroversi yang melingkupi dirinya, keberaniannya selama memegang tampuk kepemimpinan negara adidaya bukan hanya meninggalkan kenangan bagi dunia, tetapi juga memberi inspirasi kemanusiaan dalam khazanah hubungan internasional (HI). Apakah inspirasi ini akan ikut berkontribusi mengisi ruang teorisasi HI? Waktu yang akan menjadi saksi …
Advertisement

























