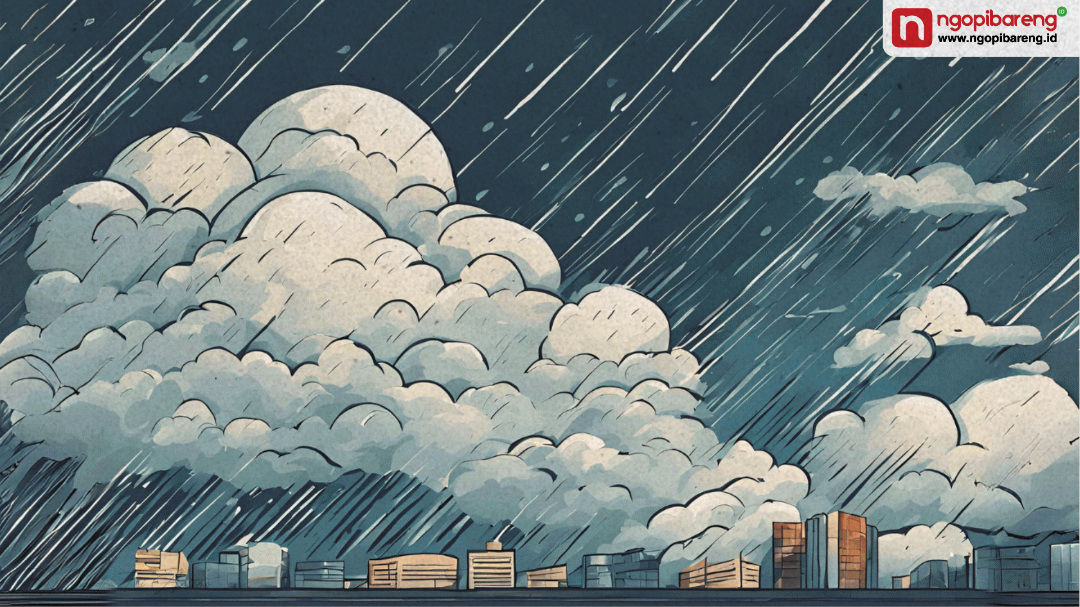Fikih Muhammadiyah Awalnya Tak Beda dengan NU Kini

Kitab Fiqih Muhammadiyah 1924 yang dikarang dan diterbitkan oleh Bagian Taman Pustaka Muhammadiyah Yogyakarta pada 1924 sebenarnya bukan hanya warisan berharga bagi kaum Muhammadiyah, melainkan juga bagi NU. Kitab itu juga bak kitabnya orang NU. Isinya sama dengan kitab-kitab pesantren yang banyak diajarkan dalam dunia NU.
Masalahnya hanyalah satu hal bahwa pada tahun 1924 itu NU belum lahir!
NU lahir pada 1926. Dua tahun setelah kitab itu terbit. Dan hingga hari ini, isi ajaran fiqih yang diajarkan kitab itu masih terpelihara sebagai amalan orang NU. Amalan itu pula yang telah turun-temurun sejak ratusan hingga ribuan tahun lalu di Nusantara ini, yaitu fiqih mazhab Syafi’i.
Jadi, walaupun NU belum lahir, namun ulama-ulama pesantren yang kemudian mendirikan NU itu tiap harinya mengamalkan ajaran fiqih sebagaimana yang ada di dalam kitab Fiqih Muhammadiyah 1924 itu.
“Artinya, di masa awal berdirinya, Muhammadiyah itu adalah NU, fiqihnya menggunakan mazhab Syafi’i yang sama dengan NU,” tulis Ali Shodiqin dalam bukunya Muhammadiyah itu Nahdlatul Ulama – Dokumen Fiqih yang Terlupakan.
Pertanyaannya, mengapa demikian?
Sebab, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam yang sudah ada kala itu di Kesultanan Yogyakarta yang menganut mazhab Syafi’i. Bukan berdakwah dengan mengarang ajarannya sendiri dari nol. Dakwah Muhammadiyah itu, menurut Ali Shodiqin, untuk menghalau kristenisasi yang didukung penjajah Belanda, sekaligus untuk memurnikan tauhid umat.
Kiai Ahmad Dahlan sendiri mendapatkan ilmunya dari ulama-ulama yang sama tempat kiai-kiai NU menimba ilmu. Satu guru, satu ilmu, bahkan satu keluarga. Kiai Dahlan Muhammadiyah dan Kiai Hasyim NU adalah sama-sama keturunan Sunan Giri. Sunan Giri adalah anak Maulana Ishaq yang nasabnya sampai ke Siti Fatimah ra binti Rasulullah saw. Maulana Ishaq kemudian mengajar di Pasai Aceh, pusatnya pengembangan Islam Nusantara ketika itu, yang pengaruhnya sampai ke Sumatera Barat, di mana kaum Padri kelak bermukim. Jadi, sesungguhnya ulama Nusantara ini memiliki jaringan yang sangat kuat, satu guru, satu ilmu, dan satu nasab. Mereka bermazhab Syafi’i. Mereka juga berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah (dalam komunitas NU lebih populer dengan akronim Ahlussunnah Waljamaah/Aswaja-An-Nahdliyah), sebagaimana yang dianut oleh negara adidaya muslim kala itu, yaitu Kesultanan Turki Usmani, yang dinastinya telah berjaya lebih dari 600 tahun.
Kiai Dahlan dan warga Muhammadiyah ketika itu mengamalkan qunut, dan tarawih 20 rakaat. Mereka azan Jumat dua kali, dan takbiran tiga kali. Mereka salat ’id di masjid, bukan di lapangan.
Pendek kata, Kiai Dahlan dan warga Muhammadiyah adalah bagian umat yang sama dengan umat Islam yang sekarang diklaim sebagai umat NU. Sebab, amalan beliau-beliau adalah amalan NU. Amalan itu bukanlah sesuatu yang baru, melainkan telah dikaji dan dijalankan selama seribu tahun lebih hingga masa kenabian.
Lalu pertanyaannya, kapan Muhammadiyah berubah? Kenapa berubah?
Jawabannya adalah bertahap. Ketika Kiai Ahmad Dahlan membuka Muhammadiyah untuk pengembangan paham global, dengan cara mengajarkan huruf Latin dan bahasa Belanda, sehingga generasi berikutnya makin akrab dengan ”Pandora” yang tengah disiapkan penjajah Belanda maka bibit-bibit perubahan masuk.
“Akibat dari sikap membuka diri itu maka benteng tradisi Muhammadiyah otomatis lemah. Ibarat perang dengan sepenuh tawakal, menyerang dengan tanpa menyusun pertahanan. Adat-istiadat pun akhirnya dapat dihilangkan, dan setelah kulit luar itu terkelupas maka bagian isi pun bisa dicampuri dan kemudian bisa diubah. Fiqih mazhab Syafi’i pun lama-lama tanggal,” tutur Ali Shodiqin. (bersambung)
Advertisement