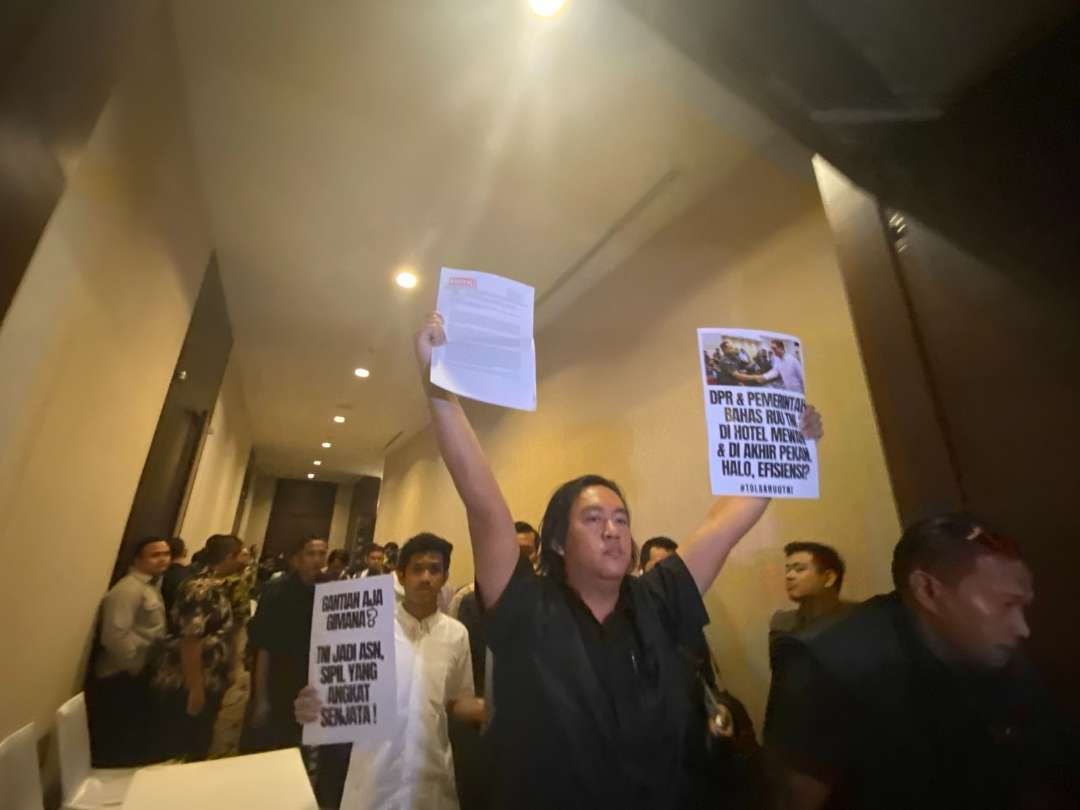Emak Klenger di Lumbung Sawit

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia layak disebut paradok. Kok bisa? Sebab, saat ini, Indonesia menjadi penghasil Crued Palm Oil (CPO) terbesar di dunia. Inilah bahan baku minyak goreng paling murah di jagat.
Karena itu, wajar bila Presiden Joko Widodo gregetan. Sampai mengambil kebijakan ekstrem melarang ekspor CPO dan minyak goreng mulai 28 April 2022 ini. Kebijakan gregetan setelah berbagai kebijakan tak berhasil mengendalikan harga di masyarakat.
Kebijakan presiden terakhir ini pasti mengguncang para pengusaha sawit di Indonesia. Yang sejak perang Rusia-Ukraina menikmati cuan besar karena harga CPO dunia melambung tinggi. Yang juga sempat dirasakan para pengusaha tambang batubara.
Sebetulnya tidak hanya para pengusaha itu yang menikmati cuan besar akibat lonjakan harga CPO dunia. Negara pun tersenyum karena ikut beruntung akibat devisa yang berhasil masuk juga makin besar. Menyumbang surplus neraca perdagangan.
Tapi apalah artinya devisa besar jika emak-emak menjerit akibat harga minyak goreng melambung tinggi. Yang bisa menggerus kepercayaan rakyat kepada pemerintah sekarang. Yang membuat presiden seakan tak mampu mengendalikan harga di dalam negeri.
Sebenarnya sudah dua kebijakan dicoba ketika harga minyak goreng terkerek tinggi. Dengan cara subsidi dan penerapan DMO (Domestic Market Obligation) dan DPO (Domestic Price Obligation). Namun kebijakan itu tak berumur lama. Karena minyak goreng tetap langka di lapangan.
Kelangkaan minyak goreng sempat menjadi laporan media asing. Dengan foto ibu-ibu dan anak antre panjang untuk membeli minyak goreng. Disebutkan antrean minyak goreng di negeri penghasil minyak goreng terbesar di dunia. Memalukan kan? Ironis kan?
Ini ibarat pepatah yang dihafal anak-anak di desa. Tikus mati di lumbung padi. Bayangkan, dalam setahun kita memproduksi 50 juta ton. Kebutuhan untuk minyak goreng domestik hanya 5 juta ton. Hanya sepersepuluh dari total produksi nasional.
Kalau sawit padinya, maka emak-emak tikusnya. Tentu emak-emak tidak sampai mati di ladang sawit. Tapi klenger. Hanya terasa tak elok, ironis, paradoks. Sehingga menjadi meme yang bikin nggrantes ati. Ini barangkali yang membuat gregeten Pak Presiden.
Kasus minyak goreng ini mengingatkan saya kepada Karl Polanyi. Ilmuwan sosial yang mempunyai konsep embeded economy atau ketertanaman ekonomi. Bahwa ekonomi seharusnya tak tercerabut dari lingkungan sosialnya.
Ketika ekonomi kita menghasilkan tikus mati dalam lumbung, berarti ada yang kurang pas dalam sistem kita. Berarti ada kesalahan ekonomi (economic fallacy) di negeri kita. Alam menyediakan sawit berlebihan, tapi emak-emak kelabakan mendapatkan minyak gorengnya. Manusia dan alam menjadi terpisah.
Embeded economy merupakan ekonomi yang terkait dengan relasi sosial di dalam masyarakat. Yang tak memisahkan manusia dengan alam. Liberalisme yang mencerabut ekonomi dari relasi sosial. Komoditas dan penguasaan atas komoditas sama sekali terpisah dengan masyarakatnya.
Masak punya barang melimpah kok nggak bisa mengatur harga. Ini karena harga CPO ditentukan secara global. Bukan semata berdasarkan pasokan dan permintaan di dalam negeri. Begitu harga dunia melonjak, kita yang memasok CPO terbesar dunia pun ikut melonjak.
Pasar swatata --menurut istilahnya Polanyi-- biang keladinya. Hukum pasar yang jadi panglima. Cuan adalah segala-galanya. Kenapa harus memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri kalau diekspor jauh lebih menjanjikan? Gak peduli kita jadi lumbungnya.
Sejak krisis ekonomi 1998, kita memang tidak punya banyak pilihan menata sistem kita. Gara-gara krisis itu, IMF dan Bank Dunia memaksa bangsa ini mengikuti serangkaian paket ekonomi. Berbagai paket restrukturisasi dan privatisasi. Menuju pasar swatata murni: neoliberal.
Intervensionisme negara menjadi barang tabu. Bahkan harus dihilangkan. Padahal, jati diri asli kita bukan seperti itu. Masih ada gotong royong. Masih ada kehidupan sosial dengan komunalitas yang kuat. Tapi ekonomi kita makin mencerabutnya.
Kembali ke minyak goreng, kita sebetulnya punya instrumen negara untuk menstabilkan harga. BUMN. Ini lembaga ekonomi jelmaan aktivisme negara. Yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan pasokan dan permintaan. Sekaligus bisa menjadi penyelaras harga.
Namun, untuk bisa menjalankan akitivisme negara, BUMN memang harus sehat. BUMN harus kuat. Ia perlu dalam tata kelola yang bagus sehingga bisa menjadi pengendali komoditas. Bukan menjadi bagian kartel atau apa saja yang membuat emak-emak klenger.
BUMN karya telah sangat efektif menjalankan fungsi sebagai instrumen negara. Sehingga, pembangunan jalan tol maupun jalan arteri bisa sangat cepat. Trans Jawa dan Trans Sumatra bisa mendekati tuntas. Mudik pun jadi makin mengalir.
Pertamina juga bisa menjalankan peran itu ketika harga BBM (bahan bakar minyak) menggila. Harga BBM kita memang naik. Tapi tidak sampai melonjak tinggi seperti minyak goreng ketika mengikuti harga keekonomian.
Rupanya perlu memperkuat BUMN pangan biar bisa efektif menjadi instrumen negara. Menjadi penyebang ketika terjadi gejolak harga komoditas. Apalagi komoditas yang menjadi favorit emak-emak. Yang kalau teriak bisa membuat siapa pun mengkeret menghadapinya.
Penyehatan BUMN pangan tentu berbeda dengan BUMN lainnya. Dia tidak diarahkan untuk mengikuti arus pasar swatata murni. Tapi lebih mengarah sebagai aktivisme negara dalam menjaga agar ekonomi kita tidak sepenuhnya diserahkan pasar.
Penguatan BUMN pangan penting agar emak-emak tak klenger di lumbung apa saja. Ketimbang pemerintah klenger "dihajar" emak-emak.
Advertisement