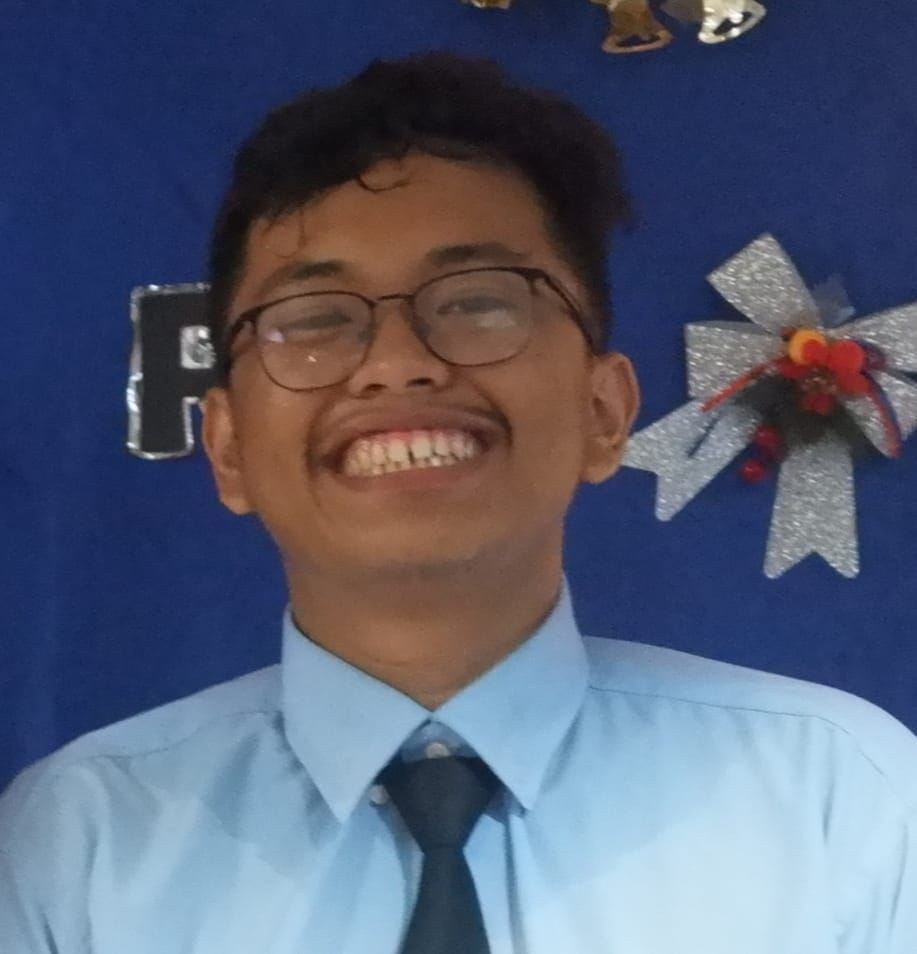Dokter Satrio dan Moerrachman, Walikota Surabaya 'Kiri' yang Kisahnya Termarjinalkan

Sebentar lagi, warga Kota Surabaya akan memilih kembali para pemimpin yang akan menahkodai mereka selama lima tahun mendatang pada Rabu 27 November 2024. Pemilihan itu akan dilakukan secara serentak bersama kabupaten atau kota lain di tanah air.
Mungkin masyarakat hanya mengenal beberapa dari sosok yang pernah menjabat sebagai Walikota Surabaya. Sosok mantan birokrat muda sekaligus kader PDI Perjuangan, Eri Cahyadi, yang maju kembali untuk periode kedua bersama politikus kawakan Armuji yang akan bertarung melawan 'kotak kosong'.
Lalu ada sosok 'srikandi' mantan Menteri Sosial dan sekarang sedang berjuang meraih kursi orang nomor satu di Jawa Timur, Tri Rismaharini. Juga Bambang Dwi Hartono atau yang kerap disapa Bambang DH, Walikota Surabaya pertama yang berlatarbelakang masyarakat sipil pada era reformasi.
Sejarawan Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya Pradipto Niwandhono menjelaskan, ada dua tokoh yang dipinggirkan padahal mereka pernah duduk sebagai orang nomor satu di Kota Pahlawan. Mereka adalah dr. Satrio dan Moerrachman.
Pradipto menjelaskan, terpinggirkanya sosok dr. Satrio dan Moerrachman dari sejarah lokal Kota Surabaya ditengarai karena keterkaitan mereka yang erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), momok menakutkan sekaligus menyeramkan pemerintahan Orde Baru yang dibangun oleh Presiden Soeharto.
Pradipto menjelaskan, Jawa Timur dan Surabaya khususnya telah menjadi basis massa ideologi kiri yang radikal sejak tahun 1920-an silam. Layaknya Semarang dan wilayah pesisir utara lainnya di Pulau Jawa, Surabaya juga telah berwarna 'merah' sejak ideologi komunisme disebarkan oleh Henk Sneevliet dan anak-anak didiknya, seperti Semaun, Darsono, dan Musso.
"Yang pasti di daerah pesisir memang banyak tinggal para buruh dan kelas pekerja lainnya yang basisnya kuat dan kondusif untuk tumbuhnya pergerakan kiri. Ini yang kemudian dianggap bahwa mereka adalah representasi dari kelompok kiri," ungkapnya saat ditemui Ngopibareng.id di Ruang Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNAIR, Selasa 26 November 2024.
Keberlanjutan goresan tinta 'merah' tersebut lalu terukir hingga masa sesudah Proklamasi Kemerdekaan RI. Pradipto menerangkan, pada gelaran Pemilu 1955, PKI berhasil memperoleh kemenangan yang nyaris mutlak di seluruh tempat pemungutan suara di Surabaya.

Menurut Pradipto, kemenangan mutlak PKI tersebut terjadi karena keberadaan buruh-buruh industri yang tinggal dan bekerja di Kota Surabaya yang merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur.
"Suara PKI yang sangat mutlak di Kota Surabaya pada Pemilu 1955. Hanya kalah di wilayah atau lingkungan dengan komunitas Islam yang lebih modernis, misalnya di daerah Ampel, di mana Masyumi berhasil menang mutlak di sana," katanya.
Persoalan-persoalan lainnya yang juga berhasil membawa PKI semakin perkasa di Kota Pahlawan adalah kepekaan mereka dengan isu-isu yang erat kaitannya dengan masyarakat miskin kota. Seperti insiden yang terjadi di Kampung Pakis pada tahun 1956 di mana pemerintah Kota Besar Surabaya saat itu hendak menggusur dan membongkar paksa pemukiman liar masyarakat.
"PKI berhasil memanfaatkan peristiwa tersebut dan menarik simpati dari masyarakat dengan memperjuangkan hak-hak mereka yang notabene terpinggirkan. Masyarakat 'akar rumput' Surabaya lalu melihat bahwa hanya PKI yang aware terhadap nasib dan masalah yang mereka hadapi," ucapnya.
Akhirnya pada pelaksanaan pemilihan umum lokal untuk memilih anggota DPRDS Kota Surabaya pada Juli 1957, PKI berhasil meraih 155 ribu suara. Pradipto menjelaskan, banyak partai politik yang kemudian menuding PKI curang dan melakukan aksi yang intimidatif untuk memilih mereka.
"Pemilihan ulang lalu dilaksanakan pada Februari 1958 oleh pemerintah kota. PKI jadi pemenangnya dan berhasil meraih 150.457 suara dan meraih 17 kursi di DPRD. Unggul jauh dari NU, Masyumi, dan PNI," paparnya.
Doktor Sejarah dari University of Sydney tersebut menjelaskan, kemenangan PKI dalam Pileg 1958 di Surabaya tersebut lalu menjadi senjata utama mereka dalam usaha untuk menempatkan kadernya sebagai orang nomor satu di Surabaya.
Apalagi, posisi Ketua DPRD Kota Surabaya telah dipegang oleh Sudarmadji dari PKI dengan wakil ketuanya adalah Hirman Kusumowardojo (PNI) dan R. Damanhuri (NU). Tidak lama berselang, PKI segera mencalonkan dr. Satrio sebagai calon Walikota Surabaya berikutnya mengingat jabatan walikota yang diemban Istidjab Tjokrokusumo saat itu akan segera berakhir.
"Satrio adalah salah seorang kader PKI yang cukup menonjol secara karier. Pada tahun 1942, Satrio lulus dari pendidikan dokter di NIAS (Nederlandsch-Indische Artsen School) dan pernah menjabat sebagai Menteri Muda Kesehatan pada masa Kabinet Amir Sjarifuddin," ungkapnya.
Dokter Satrio pun lalu terpilih yang dilakukan secara voting oleh anggota DPRD Kota Surabaya dan menjadi Walikota Surabaya sejak tahun 1958 sampai 1963. Pradipto menjelaskan, Satrio lalu disodorkan PKI untuk dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dan terpilih.

Kekosongan posisi walikota sempat dirasakan masyarakat Surabaya hingga pada bulan November 1963, Presiden Sukarno menunjuk seorang mantan tentara pelajar dan aktivis dari organisasi Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), yakni Moerrachman sebagai Walikota Surabaya.
"Proses pemilihan Moerrachman tersebut tidak melalui parlemen melainkan ditunjuk sendiri oleh Presiden Sukarno atas usulan dari pihak PKI. Moerachman adalah seorang politikus muda alumni Universitas Airlangga dan pernah memimpin delegasi mahasiswa Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955," terangnya.

Selama keduanya menjabat sebagai walikota, Pradipto menjelaskan, baik dr. Satrio maupun Moerrachman sama-sama mengusung program yang berkaitan erat dengan ideologi yang mereka anut. Program reformasi agraria (landreform) menjadi isu yang selalu hangat saat berbicara mengenai kepemimpinan mereka di Kota Surabaya.
"Dalam memegang perannya sebagai pejabat eksekutif, mereka kemudian mencoba menengahi dan sedikit memberi angin terhadap aksi reforma agraria. Kalau dibilang mereka sangat agitatif, sebenarnya tidak juga. Malah saat menjadi pejabat mereka jadi penengah," ucapnya.
Peristiwa berdarah pada malam hingga subuh 1 Oktober 1965 mengubah segalanya. Baik dr. Satrio yang duduk sebagai Wakil Gubernur Jatim dan Moerrachman yang menjabat sebagai Walikota Surabaya dipaksa turun dan mengakhiri masa jabatannya secara dini.
Keduanya lalu dikabarkan hilang tanpa jejak. Berdasarkan sumber-sumber, Pradipto menjelaskan, keduanya sempat dijebloskan di Penjara Kalisosok hingga ajal menjemput mereka. Nisan dan makam dr. Satrio maupun Moerrachman pun tidak pernah ditemukan hingga hari ini.
Seiring berjalannya waktu, propaganda Orde Baru mengenai seram dan tabunya PKI, seluruh organisasi sayap, dan kadernya mulai runtuh. Potret dr. Satrio dan Moerrachman kini sudah terpasang dalam bentuk karikatur, berjejer bersama seluruh walikota sejak masa Hindia-Belanda, di Museum Surabaya yang terletak di Gedung Siola.
"Itu langkah yang bagus bahwa artinya sejarah lokal di Surabaya bisa kembali utuh dari yang sebelumnya pernah dipenggal. Rehabilitasi terhadap keberadaan dr. Satrio dan Moerrachman sebagai walikota adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan. Itu positif dan semoga berkelanjutan dan tidak dianulir oleh pemangku kebijakan setelahnya," pungkasnya.
Advertisement