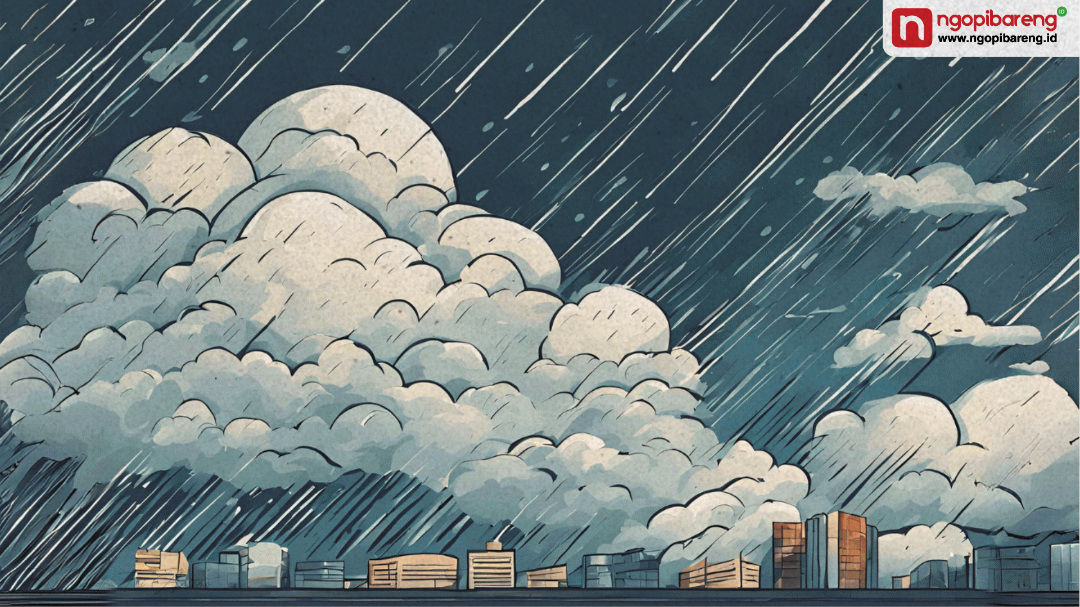Dilema Sosial

Urusan memutus pacar si anu tak mungkin menjadi haru biru 15 tahun lalu. Saat media sosial belum menjadi sesuatu. Yang bisa menggerakkan apa saja.
Presiden Trump sempat dibikin kewirangan, malu, karenanya. Saat menggelar kampanye jelang pilpres. Ada jutaan mendaftar hadir. Ternyata hanya seperempatnya yang datang.
Pasukan netizen sebuah boyband yang lagi ngetop yang bikin ulah. Mereka menggerakkan pasukannya untuk mendaftar hadir di kampanye. Tapi mereka tak mendatanginya. Sekadar ngerjain Trump.
Mereka yang jumlahnya jutaan ini bisa membuat orang malu. Tapi juga bisa menggerakkan hal-hal yang membanggakan. Menggalang dana untuk membuat sesuatu yang berguna. Melalui jejaring sosial. Lintas benua.
Dunia memang telah berubah. Era telah bergeser. Sebuah era yang saling terhubung di seluruh dunia. Yang dikenal dengan sebutan Era Informasi. Era digital.
Pandemi Covid-19 mempercepat tuntasnya era informasi. Kegiatan manusia tak lagi terbatas ruang dan waktu. Komunikasi antar mereka bisa berlaku kapan dan di mana saja.
Memaksa semua orang berkomunikasi tanpa pertemuan fisik. Mereka tersambung dengan berbagai media berbasis teknologi informasi. Kapan pun dan di mana pun.
Inilah yang pernah diperkirakan futurolog yang juga ahli komunikasi Alvin Toffler. Yang membagi perjalanan sejarah manusia ke dalam tiga gelombang: The Third Wafe.
Ketiga gelombang peradaban itu adalah: Era Agraris, Era Industri, dan Era Komunikasi alias Era Informasi. Setiap gelombang itu selalu dipicu oleh revolusi tehnologi.
Teori ini sangat populer di tahun 1980-an. Tidak hanya di kalangan para ilmuwan komunikasi. Tapi juga secara publik. Tidak jarang pejabat mengutipnya dengan bangga.
Padahal, belum terbayangkan seperti apa masyarakat era informasi itu. Televisi masih analog. Platform media cetak masih dominan. Belum ada facebook, twiter, instagram, tiktok, dan sebagainya.
Komunikasi publik masih melalui gate keeper untuk bisa massal. Kalau pun terjadi disinformasi bisa langsung dilacak ke gate keeper penyebar informasi. Apakah itu wartawan, editor maupun editor gambar.
Gate keeper lainnya adalah pemerintah. Melalui berbagai saluran resmi maupun non resmi. Menyebarkan informasi-informasi baik tentang dirinya. Meski informasi itu terkadang berbeda dengan fakta di lapangan.
Setelah hadirnya media sosial, peran gate keeper sebagai penentu kebenaran informasi menjadi tergerus. Tidak lagi menjadi pemegang hegemoni tunggal penyebar informasi.
Informasi menjadi barang bebas yang bisa disebarkan oleh siapa saja. Siapa pun bisa menjadi sumber maupun pengolah informasi. Bukan lagi previledge atau hak istimewa para wartawan yang berprofesi penyebar informasi.
Ada demokratisasi penyebaran informasi. Ada liberalisasi narasumber. Tak lagi hanya orang yang bekompeten yang bisa melakukan. Siapa pun bisa membikinnya.
Ketika terjadi demokratisasi informasi, bukan hanya yang baik yang tersebar. Bukan hanya informasi benar yang beredar cepat. Tapi juga disinformasi. Yang bisa menyebabkan kekacauan.
Disinilah yang kemudian melahirkan dilema era informasi. Dilema yang kemudian melanda para pencipta teknologi informasi. Yang telah mengubah peradaban dalam waktu singkat.
Di satu sisi, Facebook, twitter dan instagram bisa menghubungkan banyak orang. Juga bisa menemukan suadara, teman, dan handai taulan yang telah lama hilang.
Tapi selalu ada sisi gelap dari sebuah teknologi. Ia telah menjadi mesin raksasa yang membuat orang kecanduan. Menggaruk data pribadi dari seluruh dunia yang dijualnya kepada pemasang iklan.
Membuat para penggunanya menyerahkan diri secara sukarela menjadi prduk yang dijual ke pengiklan. Perilaku pengguna direkam, dikategorikan, dan menjadi alat pengeruk uang.
Netflix membuat film dokumenter yang menarik soal ini. Tentang dilema media sosial. Yang mengambil narasumber para kreator dari Google, Facebook, Twitter, Pinterest, dan seterusnya.
Film ini menggambarkan bagaimana tindakan pengguna di platform online ditonton, dilacak, diukur, dipantau, dan direkam. Semuanya jadi tambang uang untuk meningkatkan keterlibatan, pertumbuhan, dan pendapatan iklan.
Bagaimana miliaran penduduk dunia menyerahkan diri dengan sukarela data pribadinya menjadi produk baru yang bernilai miliaran dollar. Yang menjadikan sejumlah orang kaya mendadak dari industri platform media sosial.
Disinilah dilema itu terasa. Di satu sisi, kehadiran mereka mempermudah ummat manusia. Setiap orang bisa belajar, saling berjejaring, bisa berbagi bersama, dan bisa kembali menyambung relasi sosial antar mereka.
Di sisi lain, disinformasi bisa diciptakan dan menyebar dengan cepat. Yang bisa menciptakan saling benci tanpa nalar. Bisa menciptakan polarisasi masyarakat makin mengkristal. Apalagi jika digunakan oleh para maniak kekuasaan.
Film yang dalam 28 hari pertama setelah diluncurkan ditonton 38 juta orang ini bisa menjadi pengingat. Bahwa selalu ada dua sisi mata uang setiap perubahan besar akita teknologi. Termasuk perubahan besar dalam sistem informasi dunia.
Tapi saya selalu yakin, setiap perubahan selalu membawa dampak positif dan negatif. Selalu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Selalu ada yang memanfaatkan dan dimanfaatkan.
Tapi alam akan selalu menciptakan keseimbangan baru. Seperti digambarkan dalam film The Social Dillema karya Jeff Orlowski ini.
Saat disadari ada yang melenceng, muncul kesadaran etik baru dari para penciptanya. Seperti dialami para kreator medsos yang telah mundur dan mencipta penawarnya.
Tidak perlu takut dengan perubahan. Tapi juga jangan terlalu larut dengannya. Saya lebih suka melihat manfaat dari semua yang baru dengan suka cita.
Advertisement