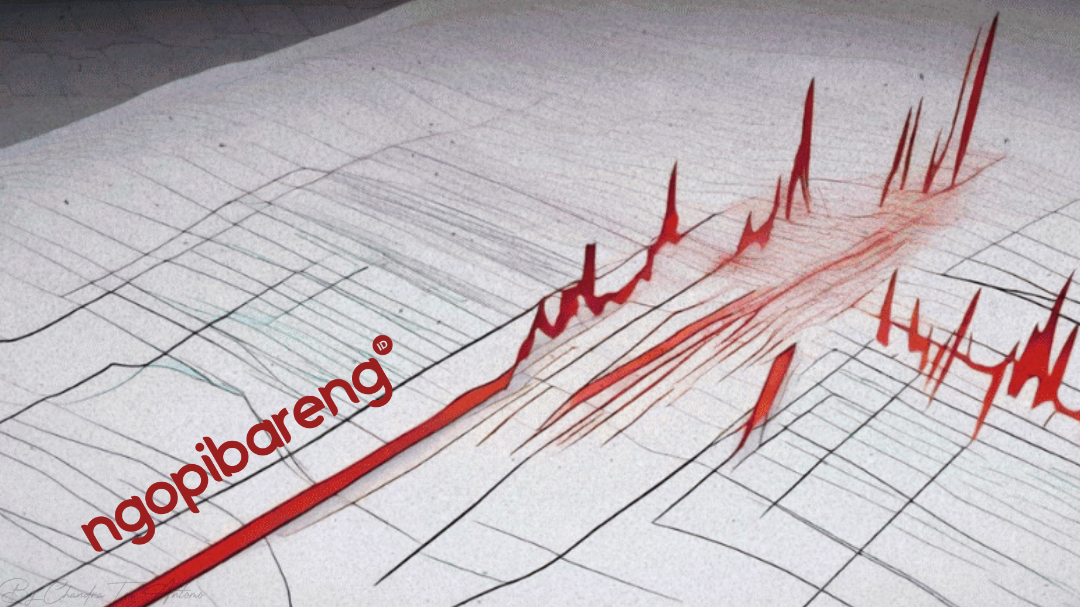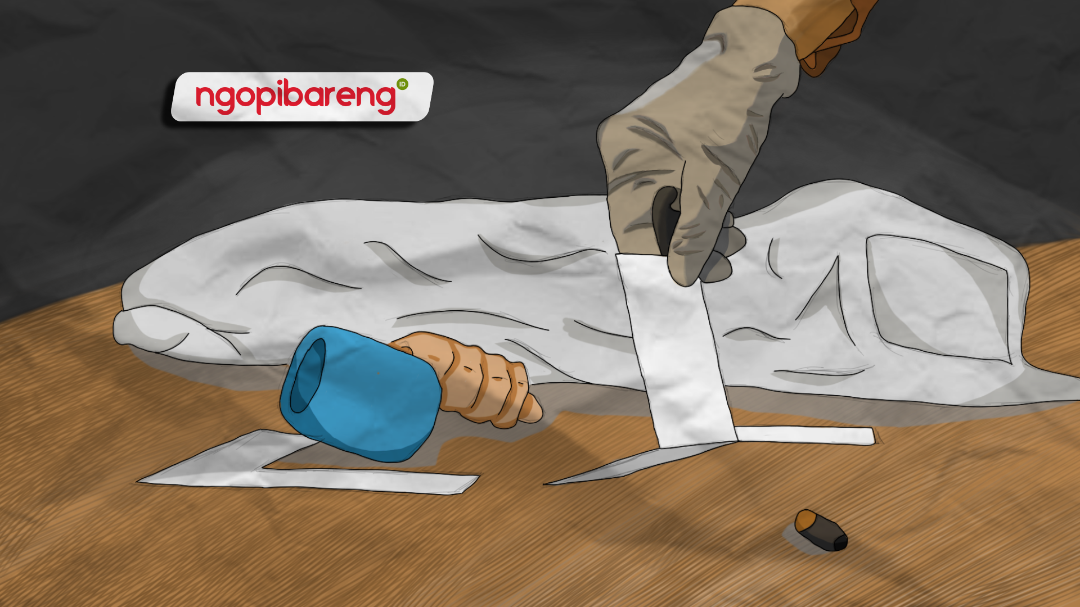Dicari politik Kebudayaan-Kesenian Jawa Timur

Oleh: Halim HD
Satu-satunya propinsi di nusantara, selain Jakarta, yakni Jawa Timur yang memiliki lembaga kesenian “swasta”, Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT) yangoleh pemdanya diberi dana miliaran untuk anggaran operasional dan kegiatan kesenian.
Dana miliaran itu tentu saja bukan sekedar angka yang begitu besar bagi sejumlah dewan kesenian di berbagai daerah yang senin kamis dalam menyelenggarakan kesenian. Angka dalam wujud miliaran itu merupakan praktek dari politik kebudayaan yag diterapkan oleh pemda Jawa Timur, sejak periode Pakde Karwo menjadi gubernur.
Coba anda bayangkan daerah lain, misalnya JawaTengah, yang ngos-ngosan menepuk diri sebagai daerah yang memiliki potensi senibudaya yang kaya, tapi dewan keseniannya melata dalam kegiatan karena, menurut para pengurusnya, hanya diberi anggaran yang jauh dari jumlah proposal yang diajukan.
Demikian juga dengan Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan bahkan Sulawesi Selatan sejak bertahun-tahun dewan keseniannya tak mendapatkan kucuran dana. Oyaa, saya lupa, Bali juga dengan senang hati para pengurusnya selalu mendapatkan perhatian dan kucuran dana dari pemdanya dengan jumlah yang lumayan besar, menyaingi DKJT.
Antara gembira dan sedih, selalu terselip sejumlah pertanyaan, kenapa ada pemda yang bias memberikan dana besar, dan ada pemda yang pelit, bahkan tak peduli dengan dewan kesenian propinsinya, maupun dewan kesenian kota? Tapi, soal “besar” dan “kecil” mungkin saja, apologinya relatif, seperti yang pernah saya dengar dari sejumlah elite pengelola daerah di berbagai wilayah. Juga, ada yang bahkan mempertanyakan, apakah dana itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik?
Pertanyaan yang terakhir ini menarik. Pada beberapa daerah ada elite yang meminta pertanggungjawaban soal dana, walaupun menurut senimannya dana itu tak seberapa besar. Saya pikir, sangat menarik, meminta pertanggungan jawab adalah suatu politik etis yang perlu dan penting diterapkan, apalagi kita kaitkan dengan kehidupan kesenian yang selalu mendengungkan suara-suara yang luhur penuh makna berkaitan dengan posisi dan fungsi kesenian.
Misalnya kasus di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sejak bertahun-tahun tak pernah ada laporan keuangan. Itu pula yang digugat oleh bukan hanya elite pengelola daerah, tapi juga kaum seniman. Sebab, bagi mereka yang ikut merasa prihatin dengan administrasi yang kurang beres dari dewan kesenian adalah wujud dari manajemen yang kurang beres pula. Itulah makanya sudah bertahun-tahun dewan kesenian di Sulawesi Selatan di stop bantuan dananya. Mati surilah lembaga itu.
Lain daerah lain pula prakteknya. Di Jawa Timur dengan pemda yang bermurah hati memberikan miliaran, rasanya tak meminta pertanggungan jawab kepada DKJT. Yang terpenting ada laporan kegiatan tanpa mencatumkan angka-angka yang dikeluarkan. Hal ini menarik. Praktek politik kebudayaan dalam wujud anggaran kesenian yang nampaknya dampak dari periode Pakde Karwo yang memang dengan sengaja memberikan dana miliaran itu sebagai bagian dari political will berkaitan dengan dukungan politis elite kesenian kepada Pakde Karwo. Bagi pemda Jawa Timur, tak ada artinya uang miliaran di antara ratusan triliun anggaran daerah itu. Maka konsekuensi logisnya, pembiaran tanpa laporan keuangan adalah tindakan politis kepada kaum seniman agar terus mendukung rezim yang ada. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan masa sesudah Pakde Karwo? Adakah political will dalam laporan juga dibiarkan, dan adakah lembaga ini hanya menjadi alat legitimassi demi anggaran tanpa praktek manajemen dan administrasi yang rapijali?
Dari hasil pengamatan saya sejak lama, dalam kasus di berbagai daerah, banyak dewan kesenian di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, memang kelemahannya pada manajemen administrasi keuangan, yang bukan hanya secara teknikal lemah, tapi juga kelemahan komitmen etis. Disinilah titik lemah terpenting sehingga posisi lembaga ini tak memiliki kekuatan gugatan moral berkaitan dengan kondisi sosial-budaya ekonomi dan lainnya. Ditambah lagi dengan patronase seperti pada periode Pakde Karwo, maka lembaga kesenian hanya menjadi onderbouw rezim. Kasus ini terjadi pada hampir semua daerah.
Dengan kondisi seperti itu, maka dewan kesenian hanya sekedar menjadi EO (event organizer). Bukan partner di dalam praktek politik kebudayaan yang memiliki dasar dan visi tentang kehidupan kemasyarakatan.
Zaman memang berubah dan berbeda. DKJ di Jakarta periode Ali Sadikin punya reputasi kultural dan fenomenal, seperti juga dewan kesenian di kota-kota lain pada periode tahun 1970-an. Itulah periode posisi-fungsi seniman memiliki makna bagi masyarakat sebagai penyuara hati nurani, yang menggunakan karya kesenian sebagai wujud dari cita-cita. Dari hal itu pula, bukan hanya karena nilai kuratorial yang bagus tapi, karena kaitan antara manajemen dan visi kesenian bertemu, lahirlah karya bermutu. Dalam kondisi dewan kesenian hanya menjadi EO, sejenis sub kontraktor kesenian, tanpa memiliki visi politik kebudayaan, karya kesenian hanya menjadi rutin dan hanya menyajikan reproduksi tanpa ada nilai eksplorasi dari gagasan brilian tentang kesenian.
Jadi, ketika kita bicara dan selalu menggugat politik kebudayaan di daerah, mungkin paling baik adalah melacak ke dalam kondisi internal lembaga kesenian, dan bagaimana berusaha merumuskan sikap dan visi, dan bukan hanya sekedar menjadi onderbouw, dan bukan hanya mengais ais praktek politik elite dan lembaga kesenian melegitimasikannya. Jika kaum seniman masih percaya kepada adagium klasik yang menyatakan bahwa kekuatan moral kesenian hanya bias dibuktikan oleh praktek berkesenian yang didasarkan kepada lembaga yang juga bersih secara moral dan etis, sebaiknya kaum seniman pengelola dewan kesenian menarapkan prinsip itu. Sebab, di antara kondisi politik yang sengkarut dan tak ada batas-batas di mana nilai baik dan buruk tak lagi ada pembatas, maka kaum seniman justeru dituntut untuk mensiagakan dirinya dan membentuk front, sebagai benteng moral. Masih adakah dorongan kehendak seperti itu?
Praktek politik kebudayaan di daerah dengan gampang ditelikung oleh elite pengelola derah dan politisi partai, salah satunya karena posisi-fungsi lembaga kesenian secara moral memang mengalami degradasi. Kemerosotan ini bukan hanya karena secara sistemik mengarah kepada penggusuran nilai-nilai karya kesenian yang diawali dengan praktek komersialisasi, kesenian sebagai komoditas oleh gelombang arus kapital secara global yang memasuki ruang-ruang kaum seniman. Tapi juga oleh kerentanan daya hidup kaum seniman yang masuk ke dalam pola konsumerisme dan hedonism banal atas nama gaya hidup. Disinilah keterpurukan secara sistemik posisi-fungsi kaum seniman dan karya seninya, dan hanya diselingi, sejenis intermezo oleh sejumlah “event” yang dianggap menjadi “peristiwa politis” oleh seniman orang per orang.
Otokritik kepada kaum seniman dan lembaga yang dikelolanya sangat perlu agar kaum seniman mengetahui posisi-fungsi dirinya, agar otokritik itu pula bias memilah suatu nilai ideal dengan pragmatisme yang merajalela. Dalam konteks itulah kita memperbincangkan politik kebudayaan dalam praktek internal kaum seniman, sebelum kita memasuki ruang “pertarungan politik” dengan rezim, politisi serta partai politik.
Selamat bercermin dan merenungkan diri.
* Halim HD, Networker Kebudayaan
Advertisement