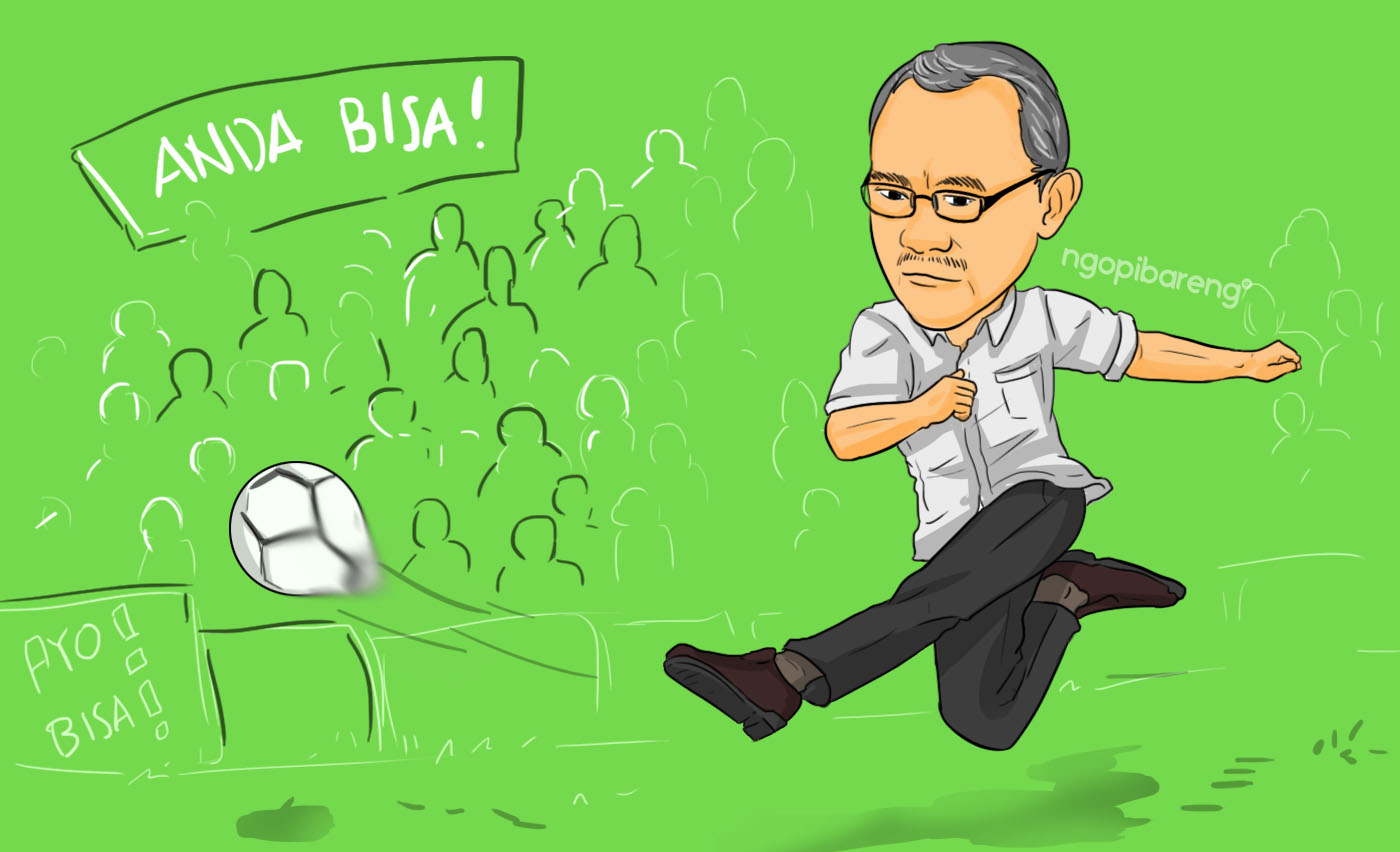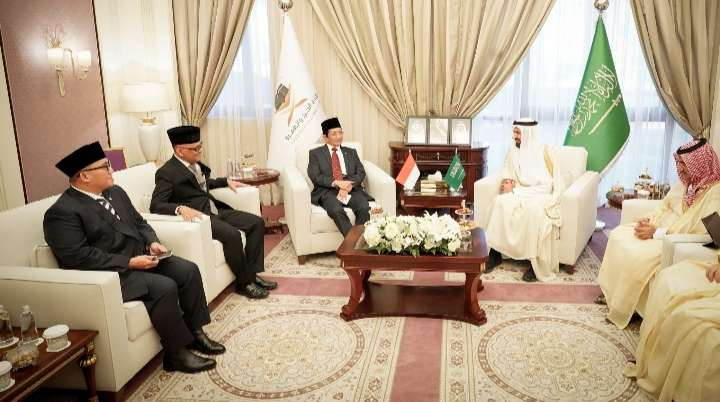Beri Daku Dusta, Emha!!!

KETIKA membaca sejumlah hasil survei yang muncul berkaitan dengan posisi politik warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta, saya tiba-tiba ingat puisi Taufik Ismail yang berjudul “Beri Daku Sumba”. Puisi ini memang paling disenangi oleh anak-anak remaja seusia saya, tentu kala aktif dalam kegiatan Pramuka dan Pecinta Alam pada masa Sekolah Menengah Atas. Puisi itupun tak luntur kala saya aktif dalam Kelompok Studi Mahasiswa Universitas Indonesia, Teater Sastra Universitas Indonesia, maupun Madah Bahana Universitas Indonesia. Kegiatan-kegiatan alam itu – terutama penelitian di daerah-daerah gersang dan jauh, memintal ingatan kepada area-area yang jauh.
Padahal, puisi itu ditulis pada tahun 1970, sebelum saya lahir!
“Beri daku sepotong daging bakar, lenguh kerbau dan sapi malam hari \\ Beri daku sepucuk gitar, bossa nova dan tiga ekor kuda \\ Beri daku cuaca tropika, kering tanpa hujan ratusan hari \\ Beri daku ranah tanpa pagar, luas tak terkata, namanya Sumba”
Begitu kutipan puisi Taufik Ismail. Taufik menulis puisi itu kala berada di Uzbekistan. Senakal-nakalnya saya terhadap Taufik – terutama berdebat secara terbuka dengan beliau, kala buku Prahara Budaya dilarung ke arena kampus --, tetap saja tak hilang rasa kagum pada kemampuan dokter hewan ini menulis puisi. Saya termasuk pengkritisi buku yang ditulis bersama Des Moeljanto itu. Saking bapernya, Om Taufik “menuduh” saya pernah bertemu dengannya dalam serangkaian kegiatan seni di sejumlah negara. Padahal, mana pernah saya ke luar negeri kala mahasiswa. Sahabat saya – intelektual muda kampus yang rajin mengawal pamannya ini – Fadli Zon justru yang sering mewakili Universitas Indonesia keliling dunia. Saya? Kebagian keliling Indonesia saja.
Mengapa puisi itu? Mengingat survei dan hasil-hasilnya yang disampaikan kepada publik sama sekali tak setelanjang aslinya. Survei bukanlah \\ ranah tanpa pagar \\ luas tak terkata. Survei justru adalah benteng kawat berduri yang sudah diisi dengan mesiu yang siap meledak, kala dihembus cuaca tropika, apalagi dihela tiga ekor kuda. Makanya, saya lebih suka membaca buku “Berbohong dengan Statistik” karya Darrel Huff, ketimbang mengikuti mata kuliah Statistik Sosial yang diasuh oleh almarhum Dedy Nur Hidayat PhD dalam program magister Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Walau lulus mata kuliah wajib itu, saya lebih menyenangi perdebatan dengan Pak Dedy yang baik hati itu, ketimbang percaya sama sekali pada data-data kuantitatif yang tersedia.
Contoh yang paling “pahit” adalah bagaimana saya bisa percaya dengan hasil survei Charta Politika periode 7 – 12 April 2017 yang menyebutkan angka 22,6 % responden menyatakan memilih Anies Rasyid Baswedan adalah karena satu agama (Islam)? Padahal, hampir tak ada lembaga survei yang mencoret fakta yang menyebutkan betapa pemilih-pemilih beragama Kristen dan Katoliklah yang sangat solid mendukung Basuki Tjahaja Purnama. Sementara, pemilih Muslim justru berbagi angka, yakni mayoritas terbatas memilih Anies Rasyid Baswedan dan mayoritas yang lain dalam angka yang tak jauh memilih Basuki Tjahaja Purnama.
Sehari setelah survei Charta Politika diumumkan, saya bertemu dengan sejumlah warga utama Provinsi Bangka Belitung, termasuk Gubernur Terpilih Erzaldi Rosman Djohan. Ada beberapa warga Tionghoa juga yang sangat kritis terhadap Ahok. Kebetulan, saya sejak tahun 2000 melakukan penelitian di kawasan Bangka Belitung bersama Farid Gaban, Hardy Hermawan dan Andrinof Chaniago. Kesimpulan kami sama, betapa hubungan antara suku Tionghoa dengan suku Melayu sangatlah akrab dan mesra di Bangka Belitung. Dengan mata kepala sendiri, kami melihat bagaimana pelajar-pelajar sekolah menengah yang usai menerima rapor berboncengan menuju pantai dalam pakaian yang coret-moret. Apa yang luar biasa? Tak ada jarak antara siswa atau siswi Tionghoa dan Melayu untuk saling berbonceng dan bersenda-gurau.
Fakta yang juga sangat penting adalah bagaimana Ahok dan adiknya Basuri bisa terpilih menjadi Bupati Belitung Timur, dengan populasi kaum muslim yang mencapai sekitar 90 persen? Apabila faktor kesamaan agama (Kristen) menjadi pilihan, sampai hutan bakau tumbuh di pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakartapun tak bakal ada yang bisa menjadi Bupati di Belitung Timur itu. Tetapi mengapa justru orang Muslim memilih orang Kristen sebagai Bupati?
Contoh yang sebetulnya teramat sederhana ini menyingkap kain kelambu yang menutupi betapa berbahayanya statistik yang dipakai dan diperagakan. Secara kasat mata, mestinya situasi berjalan berkebalikan, yakni karena kesamaan agama (Kristen dan Katolik, bahkan mungkin Kong Hu Chu) yang membuat Anies-Sandi sama sekali hampir tak mendapatkan suara. Perbedaan agamalah yang menjauhkan pemilih Kristen, Katolik dan Kong Hu Chu tak menjatuhkan pilihan kepada Anies-Sandi yang menggunakan peci sejak putaran pertama.
Lalu, kenapa justru pemilih Anies-Sandi yang justru disebut memilih karena kesatuan agama? Semakin diurai angka-angkanya, justru tak ada sama sekali 100% kaum muslim memilih kaum muslim juga. Jika itu yang terjadi, alias kesimpulan survei itu diperturutkan oleh warga, maka dalam putaran pertama justru yang bersaing adalah Agus Harimukti Yudhoyono dan Anies Rasyid Baswedan. Ahok? Barangkali sudah tercampak terlebih dahulu akibat muncul dalam agama minoritas.
Tapi, survei tetaplah survei. Statistik yang dihasilkan adalah rekaman dari persepsi yang diurai menjadi angka dari jawaban responden atas pertanyaan (terbuka dan tertutup) yang muncul dalam quisioner. Saya tidak tahu, apakah klausa \\ karena satu agama (Islam) \\ adalah jawaban spontan di halaman titik-titik dalam quisioner ataukah sudah dituliskan oleh yang empunya survei untuk dimintakan persetujuan dari responden. Lalu, mengapa pula isu \\ Jakarta bersyariah \\ menjadi isu negatif bagi pasangan Anies-Sandi, sementara isu \\ beda agama \\ pun juga menjadi isu negatif pasangan Ahok-Djarot? Bagi saya, terlalu rumit dan sentimentil konsepsi yang muncul, kala \\ Jakarta bersyariah \\ dijelaskan secara ketata-negaraan.
Saya menduga – tapi bukan curiga – betapa jawaban \\ karena satu agama \\ sudah terangkai rapi, dalam narasi yang terlalu rumit dan sentimentil tadi: \\ latar belakang suku yang tidak penting dan latar belakang agama yang juga mayoritas dipilih sebagai hampir tidak penting. Tatkala diurai dalam isu-isu negatif, malahan menjadi penting dibandingkan dengan isu \\ reklamasi \\ korupsi \\ liberal ataupun \\ dipecat jadi menteri \\ yang merupakan hak prerogatif Presiden RI – beberapa yang dipecat dipilih kembali, misalnya. Interviewer tinggal mencoreng pilihan itu. Kalau pilihan itu dihitung, muncul angka fantastik, yakni sekitar 400.000 pemilih Anies-Sandi (dalam putaran pertama, misalnya) diiikat jemarinya untuk menyoblos faktor itu.
Sebaliknya, kala jawaban-jawaban rasional tertuang dalam tabel Ahok-Djarot, benarkah juga jawaban spontan atau sudah ditulis bersamaan dengan jawaban lain untuk tinggal dipilih? Pun yang rasional dalam tabel Anies-Sandi, tapi malah dalam kalimat yang negatif? Artinya, baik rasional ataupun emosional, justru jawaban yang sudah disediakan oleh sang pembuat survei guna dipilih oleh responden dalam proses wawancara yang bisa saja tak lama.
Tentu, saya tak ingin menggali lebih jauh lagi. Pun saya tidak perlu mengulas terus-menerus tentang bagaimana anomali demi anomali muncul dalam setiap kali survei di DKI Jakarta (dan sejumlah daerah lainnya yang dihuni kaum super kaya hingga super miskin seperti Tangerang Selatan) diumumkan, lalu hasil didapatkan pada hari penyoblosan. Saya juga tak akan berkampanye untuk tak percaya lagi kepada hasil-hasil survei, selama pertanyaan demi pertanyaan disusun demi kepentingan client dari konsultan yang merangkap menjadi surveyor, pun sebagai spin doktornya di media massa dan media sosial. Saya tentu tak ingin kehilangan banyak kawan, sahabat, kolega dan junior kalau meneruskan tulisan ini dengan detil yang panjang berhela-hela.
Belakangan, saya menganggap lembaga-lembaga survei makin acak-adut membuat narasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan dalam lembar quisioner. Keacak-adutan itu adalah pertanyaan-pertanyaan dalam lembaran itu justru berasal dari materi (serangan) berupa kampanye negatif atau bahkan kampanye hitam yang disebarkan dengan kekuatan finansial dan jaringan relawan berupah mahal di seantero Jakarta. Seolah – atau memang begitu tugasnya – lembaga survei yang notabene adalah akademik dan saintik dalam batas-batas ilmu yang bebas nilai, justru dipakai sebagai alat cecap statistik guna menakar kerja Tim Siluman, Tim Kelewang, Tim Angin Ribut, Tim Hoax, hingga Tim Media Online yang bekerja masif dan bisa dipantai jejak digitalnya itu.
Hampir tak ada dan sama sekali tak penting untuk mengukur apakah pajak akan naik atau turun, sebagaimana pertanyaan kampanye yang paling klasik dalam standar quisioner lembaga survei di Amerika Serikat, misalnya. Dengan pertanyaan-pertanyaan survei yang sebangun, seragi dan sesugih kerja tim-tim kampanye resmi dan tak resmi itu; terbaca sekali betapa surveyor bukanlah lembaga akademik yang dibual-bualkan berbusa-busa oleh pelakunya. Surveyor malah menjadi teror keilmuan yang dipaparkan dan dipampangkan sebagain reklame mahal, bahkan tanpa ada satupun buku sebagai hasil utamanya guna dijadikan sebagai bahan studi di kampus atau lembaga riset.
Apapun, tulisan ini tentu perlu ditutup. Dalam pikiran saya, kembali muncul puisi sebagai cara untuk mengakhiri. Yang tiba-tiba saja hadir adalah puisi “Seribu Masjid Satu Jumlahnya” karya Emha Ainun Nadjib yang ditulis pada tahun 1987 – kala sentimen keislaman belum lagi menaik, akibat “ditikam” oleh sekularisasi negara.
“Seribu masjid tumbuh dalam sejarah \\ Bergetar menyatu sejumlah Allah \\ Digenggamnya dunia tidak dengan kekuasaan \\ Melainkan dengan hikmah kepemimpinan \\.
Allah itu mustahil kalah \\ Sebab kehidupan senantiasa lapar nubuwwah \\ Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah \\ Muadzin kita selalu mengumandangkan Hayya ‘Alal Falah!”
Ya, lebih dari tujuh juta warga DKI Jakarta memberikan hak pilihnya pada tanggal 19 April 2017 nanti. Dari yang tujuh juta itu, berapa yang Muslim? Sebanyak itu kaum Muslim, tentulah juga menggunakan ratusan atau ribuan masjid yang sebetulnya satu itu. Saya tak ingin membuat tafsir atas puisi Emha itu. Sama seperti saya tak ingin juga mengingat bagaimana Emha justru bersatu sebagai keluarga dengan Novia Kolopaking, mahasiswi Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang sedang naik daun sebagai kembang mekar di Taman Sastra. Emha diundang bersusah payah oleh mahasiswa-mahasiswa yang nyeni atau sok jadi seniman – termasuk saya – dengan harapan ada mahasiswi tertarik juga membaca puisi.
Lah? Ternyata Emha datang bagai seorang pangeran tanpa tanding, sekali dua berdeklamasi, setelah itu membawa Sang Putri. Entah berapa puluh puisi ikut disobek, kala pernikahan Emha – Novia diumumkan angin yang berbisik tanpa berisik.
Seribu mahasiswa, tumbang oleh satu Emha...
Emha, tentu tak berdusta. Tapi surveyor? Beri daku dusta!
Jakarta, 16 April 2017
(Dewan Pendiri Sang Gerilya Institute)
Advertisement