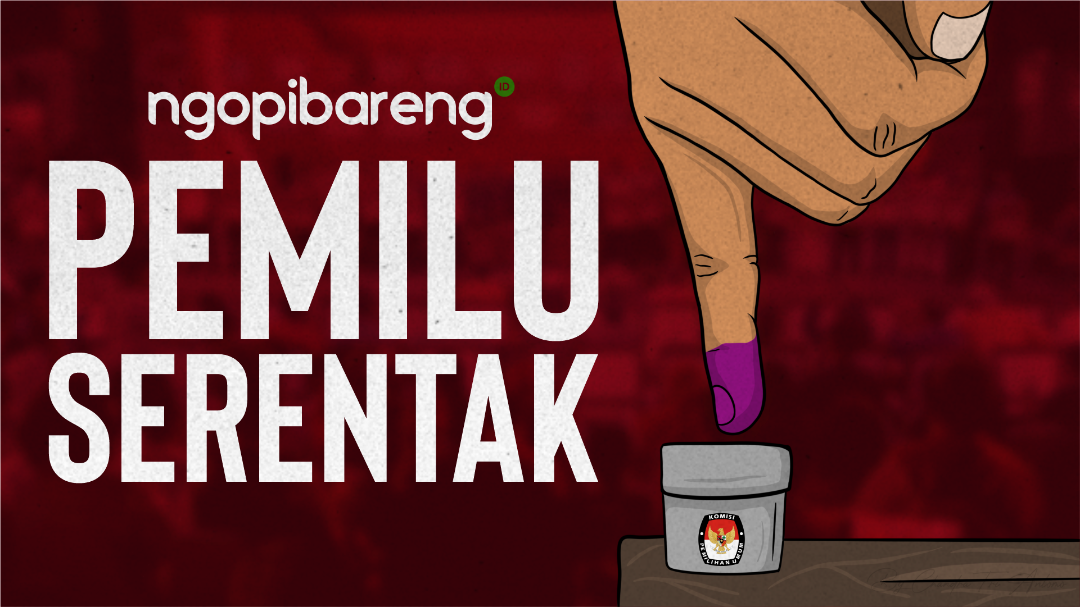Bangkitkan Hantu PKI, Mampukah Jadi Alat Konsolidasi Politik?

PKI hidup lagi. Ini sudah kesekian kali. Seakan menjadi rutinitas lima tahunan. Ketika secara nasional ada hajatan politik.
Ya. Partai yang sudah menjadi "bangkai" sejak 1966 itu selalu hidup lagi. Atau lebih tepatnya dihidupkan lagi.
Ketua DPP Partai Gerindra Fadli Zon termasuk yang aktif membongkar kuburan PKI. Dia jadikan lirik nyanyian bertitel Bebek Angsa. Dia kelilingkan ke daerah dengan berbagai cara.
Sebuah poster besar beredar di mana-mana. Juga berseliweran di berbagai lini masa. Beredar di media sosial. Melalui broadcast grup-grup whattapps.
Misalnya yang mulai terjadi minggu lalu: Poster Deklarasi Jatim Menolak Kebangkitan PKI. Disebutkan, kegiatan itu akan digelar hari ini, 1 Oktober 2018, di Tugu Pahlawan Surabaya.
Sejumlah selebriti politik nasional dijadwalkan jadi pembicara. Tepatnya oratornya. Mereka semua adalah tokoh #2019GantiPresiden.
Mulai dari Fadli Zon, Ahmad Dani, Fahri Hamzah, Haikal Hasan dan Gus Nur. Juga ada selebriti politik perempuan seperti Ratna Sarumpaet dan Neno Warisman.
Terakhir beredar kegiatan itu akan digelar di Lapangan Kodam V/Brawijaya. Ternyata hoax. Pihak Kodam membantah lapangannya dipakai kegiatan tersebut. Apalagi menjadi penyelenggaranya.
Pertanyaannya, mengapa isu PKI diangkat kembali? Apakah isu ini masih bisa menjadi alat konsolidasi politik? Mengapa mereka tidak berusaha memproduksi isu lain yang lebih kekinian?
Kampanye Politik
Sebetulnya, isu hantu PKI sudah mengemukan sejak pilpres 2014. Malah Capres Jokowi yang saat itu langsung menjadi korbannya. Ia difitnah sebagai anak PKI. Sadis.
Ternyata isu itu tak mampu meredam pilihan rakyat. Buktinya, ia tetap melenggang menjadi Presiden RI ke-7. Ia mengalahkan Prabowo Subianto yang dalam pilpres kali ini juga menjadi lawannya.
Isu ancaman PKI selalu menjadi alat mempertegas politik identitas. Ia menjadi "hantu" yang terus dihidupkan untuk mengkonsolidasikan kekuatan.
Tapi, masihkah efektif untuk mendulang suara?
Secara teori, ada dua target dalam setiap kontestasi politik. Pertama, setiap kampanye bertujuan untuk mengdongkrak citra dan keterpilihan kandidat. Kedua, memerosotkan alias men-down grade citra dan keterpilihan lawan.
Hantu PKI bisa dipakai sebagai upaya memerosotkan citra lawan. Karena itu selalu disebutkan sebagai ancaman. Selalu dinarasikan sebagai bahaya laten yang akan terus mengancam bangsa ini.
PKI adalah Partai Komunis Indonesia yang telah dibubarkan Soeharto, 12 Maret 1966. Setelah ia mendapat kuasa melalui Surat Perintah 1 Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno.
Partai ini juga dianggap sebagai musuh besar kelompok Islam di Indonesia sejak pemberontakan PKI di Madiun 1948. Karena itu, ia selalu direproduksi untuk menyatukan emosionalitas pemilih Islam.
Dalam pemerintahan Soeharto, isu PKI terus dikapitalisasi menjadi sebuah ancaman bangsa meski telah dihabisi secara fisik, sosial dan politik. Kebangkitannya tidak hanya dianggap sebagai ancaman bagi kelompok Islam, tetapi juga bagi ideologi Pancasila dan dan NKRI.
Ideologi komunisme yang menjadi dasar PKI melahirkan pertarungan sengit politik identitas. Politik yang didasarkan pada keyakinan agama, etnis, dan ras. Politik yang mengaduk-aduk emosionalitas ketimbang rasionalitas program.
Masa itu, PKI bisa menjadi kuat karena dunia juga dalam pertarungan politik ideologi. Antara kapitalisme Barat dan Komunisme yang berbasis di Uni Soviet dan China. Poros ideologis ini yang melahirkan perang dingin berkelanjutan.
Sejak runtuhnya Uni Soviet dan kapitalisasi ekonomi China, isu ideologis komunisme tidak lagi menjadi isu politik internasional. Bersamaan dengan runtuhnya komunisme, para pengamat menyebutnya sebagai The End of Ideology, akhir sebuah ideologi. Isu yang dominan beralih ke isu ekonomi dan kesejahteraan.
Perang yang berkembang pun bukan lagi perang fisik. Tetapi perang dagang. Perang untuk menguasai sumber-sumber ekonomi melalui mekanisme perdagangan antar negara. Perang yang kemudian disulut dengan tegas oleh pemerintahan Donald J Trump sekarang.
Generasi Baru
Zaman telah berubah. Generasi baru telah datang. Jika isu komunisme bisa menjadi alat konsolidasi kuat di masa lalu, belum tentu bisa menjadi instrumen kuat di zaman sekarang.
Mengapa demikian? Antara lain karena 40 persen pemilih di pilpres 2019 ini adalah generasi milineal yang tidak akrab dengan isu tersebut. Mereka lahir paska era pemerintahan Orde Baru yang menjadikan ancaman komunisme sebagai alat konsolidasi politik.
Mengungkit isu ancaman PKI hanya mungkin efektif untuk mengkonsolidasikan sebagian generasi tua yang pernah mengalami era perang ideologi dan mereka yang masih percaya akan kekuatan ideologis tersebut. Generasi yang lahir tahun 1960-pun makin kritis terhadap kekuatan PKI hidup lagi.
Warga Nahdliyin yang menjadi korban politik PKI sekaligus korban rekayasa melawan kekuatan PKI-malah memelopori upaya rekonsiliasi nasional soal ini. Mereka yang memiliki konstituen terbesar kelompok muslim tak menganggap PKI sebagai ancaman. Justru radikalisme atas nama agama yang dianggap lebih membahayakan.
Singkatnya, sebagai narasi politik, isu ancaman PKI sudah tidak lagi mendapatkan momentum sebagai instrumen untuk mengkosolidasi dukungan politik. Karena itu, efektifitasnya untuk mendulang dukungan perlu ditinjau ulang. Secara global, isu tersebut juga sudah kehilangan momentumnya.
Tampaknya, untuk memenangkan kontestasi politik kepemimpinan nasional, masing-masing kandidat perlu lebih kreatif mempeoduksi isu. Merumuskan narasi sesuai dengan kebutuhan pemilih sekarang. Bukan dengan cara membongkar-bongkar "bangkai ideologi" melalui isu ancaman PKI.
Memilih narasi kekinian dalam kontestasi politik rasanya lebih bermakna untuk membangun budaya politik masa depan yang lebih baik. Menjadikan kontestasi politik sebagai agenda lima tahunan dengan ceria dan menyenangkan.
Memproduksi narasi ancaman justru akan melahirkan kecemasan dan ketakutan. Sebaiknya politik lebih memberikan harapan ketimbang ketakutan. Harapan baru yang lebih mensejahterakan dan menyenangkan. (arif afandi)
Advertisement