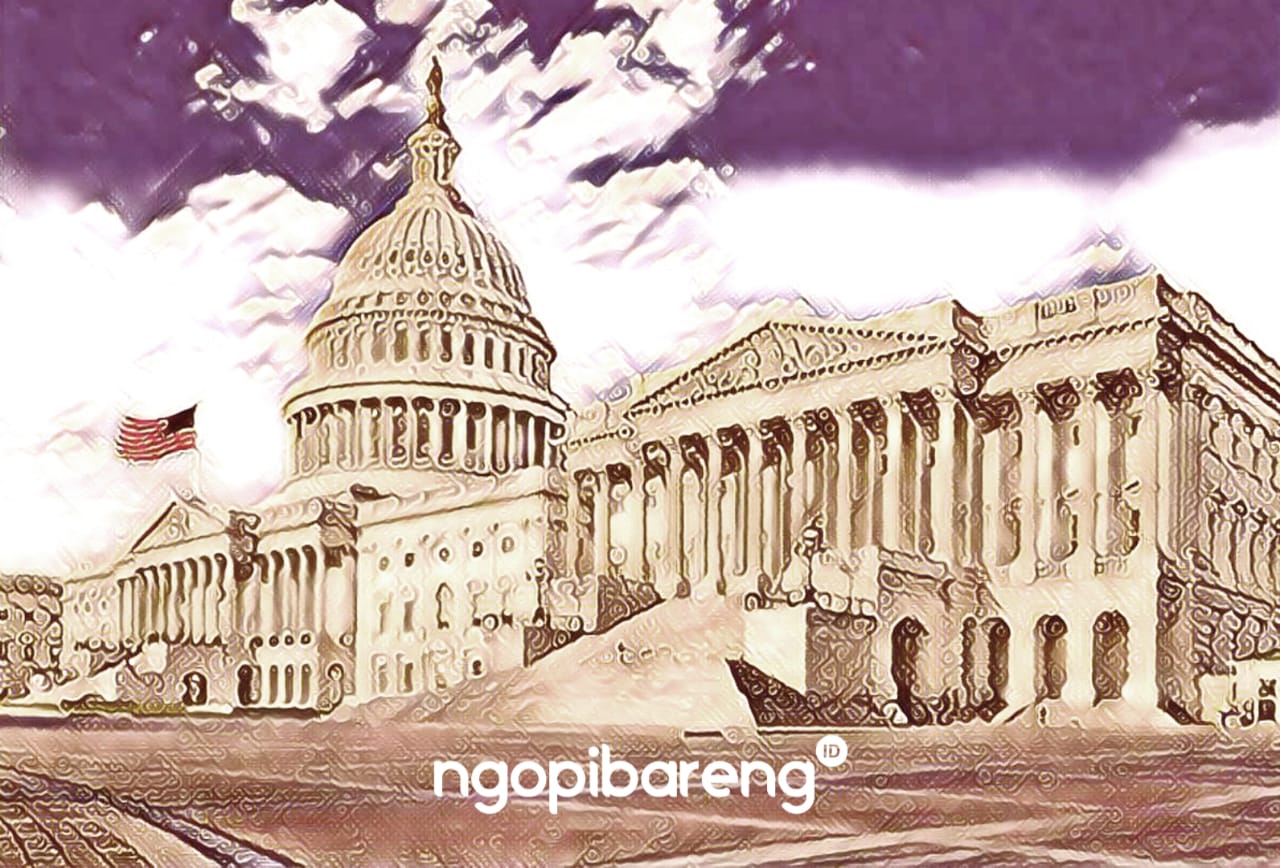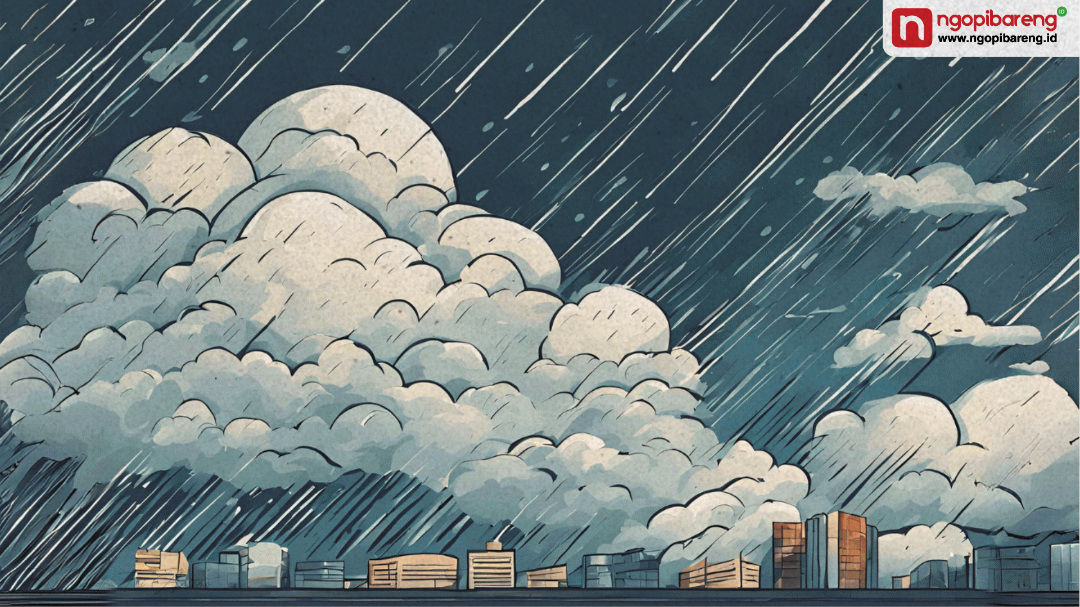Asa Budaya Arief Santosa

“Kamu masih punya uang,” tanyanya pelan. Saya tak menjawab. Hanya membalasnya dengan senyum dan mata berbinar.
Segera dia masuk ke kotak ATM yang AC-nya selalu dingin itu. Tak berapa lama dia keluar. Menyerahkan beberapa lembar uang kepada saya.
“Buat tambah bekal pulang ke Jogja,” pesannya sebelum kami berpisah. Sebelumnya, dia mentraktir saya makan malam. Di kantin Graha Pena, kantor koran Jawa Pos di Surabaya, yang megah itu.
Kami makan sambil diskusi panjang lebar. Tentang pekerjaanya juga romantisme saat aktif jadi wartawan kampus. Dia juga mengenalkan saya kepada beberapa wartawan yang tengah mengaso.
Pertemuan malam itu, adalah pertemuan pertama kami. Sekitar awal tahun 2000. Saya mendapatkan nomor telepon genggamnya dari teman lainnya.
Lantas nekat mengirim pesan pendek. Meminta waktunya untuk ngobrol. Dia rela turun dari kantornya, di sela-sela pekerjaannya mengedit naskah.
Meluangkan waktu. Bertemu mahasiswa yang belum dikenalnya. Mentraktir makan. Memberi pesan. Dan terakhir memberi bekal uang pulang.
Namanya Arief Santosa Legowo. Senior saya di pers mahasiswa Balairung di UGM, Yogyakarta. Kegiatan ekstra kulikuler tingkat universitas. Dia kuliah di Fakultas Sastra, sedangkan saya di Fakultas Filsafat.
Malam itu, dia panjang lebar bercerita tentang liputan yang paling berkesan. Mewartakan proses pemakaman Sri Sultan Hamengkubuwono IX. “Saya satu-satunya wartawan pers mahasiswa,” ungkapnya sambil menerawang.
Saat itu, pria asli Jogja ini menempel wartawan Majalah Tempo yang menurunkan tim untuk membuat liputan khusus. “Saya memakai surjan. Jalan kaki dari Keraton sampai Imogiri,” tambahnya. Bahkan, saking ramainya peziarah, sandalnya pun hilang.
Alhasil, sepanjang perjalanan itu, dilakukan tanpa alas kali, nyeker. Rasa letih, kaki pegal, juga panas terkena aspal tak dirasa. “Saya bahagia sekali saat liputan itu terbit,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Pertemuan itu, jadi awal persahabatan kami. Walau berjarak 12 tahun, dia menganggap saya sebagai teman. Dia banyak sekali menolong saya. Terutama saat dia didapuk jadi redaktur budaya.
Yang bertanggung jawab atas artikel budaya populer, cerpen, resensi buku, opini, atau puisi. Biasanya hanya terbit tiap hari Minggu. Posisi ini, membuat dirinya terikat komitmen untuk terus berkontribusi atas kelangsungan budaya atau kerja kebudayaan di Jawa Timur.
Termasuk mencari para penulis muda. Menyemangati mereka. Terpenting, memberi kesempatan karya mereka dibaca banyak orang.
Salah satu korbannya, adalah saya. Walau sebenarnya, saya juga sangat membutuhkannya. Sebab, saat kuliah, saya harus berjibaku mencari tambahan uang kuliah.
Karena hanya punya modal menulis, saya pun menyebar banyak artikel. Ada yang dimuat, ada yang tidak. Namun, Mas Arief ini lebih banyak memuat.
Apalagi kalau setelah saya kirim artikel, saya mengiriminya pesan pendek. “Buat makan Mas,” tulis saya. Biasanya dia hanya membalas dengan tertawa saja.
Tentu saja, saya harus tetap memenuhi standar kelayakan artikel. Honornya lumayan. Jadi setelah mengirim artikel, kerjaan saya tiap minggu pagi, mampir ke kios koran di dekat Alun-alun Kidul itu.
Membolak-balik halaman budaya. Mencari apakah ada nama saya di sana. Kalau ada, siangnya saya merayakannya dengan makan agak enak. Gule sapi di dekat Taman Sari.
Pernah suatu hari, dia menelepon saya. “Jar, ada perempuan yang telepon ke redaksi. Menanyakan kamu,” katanya. Saya yang bingung, hanya menjawab dengan nada tak percaya.
“Wuih, sudah punya penggemar. Beneran iki,” godanya dalam bahasa Jawa. Mungkin, waktu itu, karena agak sering menulis, ada yang mengikuti tulisan-tulisan saya.
Sesekali, saat dia melawat ke Jakarta, kami bertemu. Ngobrol ke sana-kemari. Saya sempat mengikuti jejaknya jadi wartawan. Tapi hanya bertahan kurang dari 24 purnama.
Saya pindah haluan. Jadi karyawan. Hebatnya, dia masih menyemangati saya untuk menulis. Meminta saya mengirim artikel ke koran yang dia asuh.
Di masa itu, dia sering bercerita atas proyek kebudayaannya. Terus mencari bibit penulis muda. Menyemai harapan mereka.
“Kadang, saya harus menghubungi mereka. Saya sodori tema, dan minta menulis,” paparnya. Saat Mas Arief menyebut seorang nama penulis mudanya itu, saya mengenalnya. Kini, dia menjadi salah satu kurator seni papan atas negeri ini.
Memang urusan halaman budaya Jawa Pos itu, masih dipantau Pak Dahlan Iskan, bos besar. Walau dia sudah aktif jadi Dirut PLN. Pernah, dia dikomentari Pak Dahlan yang datang ke kantor pada dini hari.
“Wah, urusan budaya banyak juga. Sampai jam segini belum pulang,” gurau Pak Dahlan seperti ditirukannya. Entahlan, mungkin saat itu dia baru memeriksa artikel budaya. Pasalnya, ada penulis yang hobi kirim artikel melewati tenggat.
Percakapan dengannya tak melulu urusan kerja jurnalistik atau budaya populer. Pernah, seusai dia naik haji, ceritanya tentang pengalaman spiritualnya. “Nikmat sekali. Ayo cepat daftar untuk berhaji,” katanya menyemangati saya.
Dia orang baik, masih mau memuji orang lain. Juga mengingat kebaikan yang walau kecil. “Oh ya, tas pemberianmu sangat berguna saat haji itu,” tambahnya. Mendengar ucapannya, hati saya ikut bahagia.
Saat tahu dia mulai olah raga, saya gantian terus menyemangatinya. Kami bertukar pengalaman nikmatnya saat keringat membasahi badan. “Habis lari terus posisi plank semenit saja, wuih keringatnya enak sekali,” katanya di ujung telepon.
Beberapa kali ke Surabaya, saya memaksa mampir ke kantornya. Saat dia jadi Koordinator Liputan Jawa Pos. Dia tunjukan meja dan kursinya. Lantas mengajak saya duduk di meja bundar tempat rapat redaksi Jawa Pos.
Oktober 2018 dia jatuh sakit. Kabarnya, sempat tak sadarkan diri saat bekerja. Dibawa ke RS Dr Soetomo, untuk perawatan. Saat mulai membaik dia menjalani perawatan jalan.
Saya mengikuti postingan istrinya di media sosial, atas aktifitas Mas Arief seusai sakit. Saya gembira dengan perkembangannya. Tentu saja, turut berdoa, agar bisa beraktifitas lagi.
Namun, hari Rabu, 13 November 2019, pukul 12.55 WIB, Allah SWT berkehendak lain. Mas Arief Santosa meninggal dunia. Meninggalkan istri dan dua putera.
Saat membaca pesan di Whatsapp Group alumni Balairung UGM, saya duduk termenung. Agak lama. Sedih.
Akhirnya, dengan gontai saya memilih berwudlu. Masih terbayang kebaikannya. Tak berapa lama, saya mengucap takbir. Memulai rakaat pertama salat ghaib untuknya.
Ajar Edi, kolomnis “Ujar Ajar” di ngopibareng.id
Advertisement