Antara Khofifah, Jokowi dan Megawati
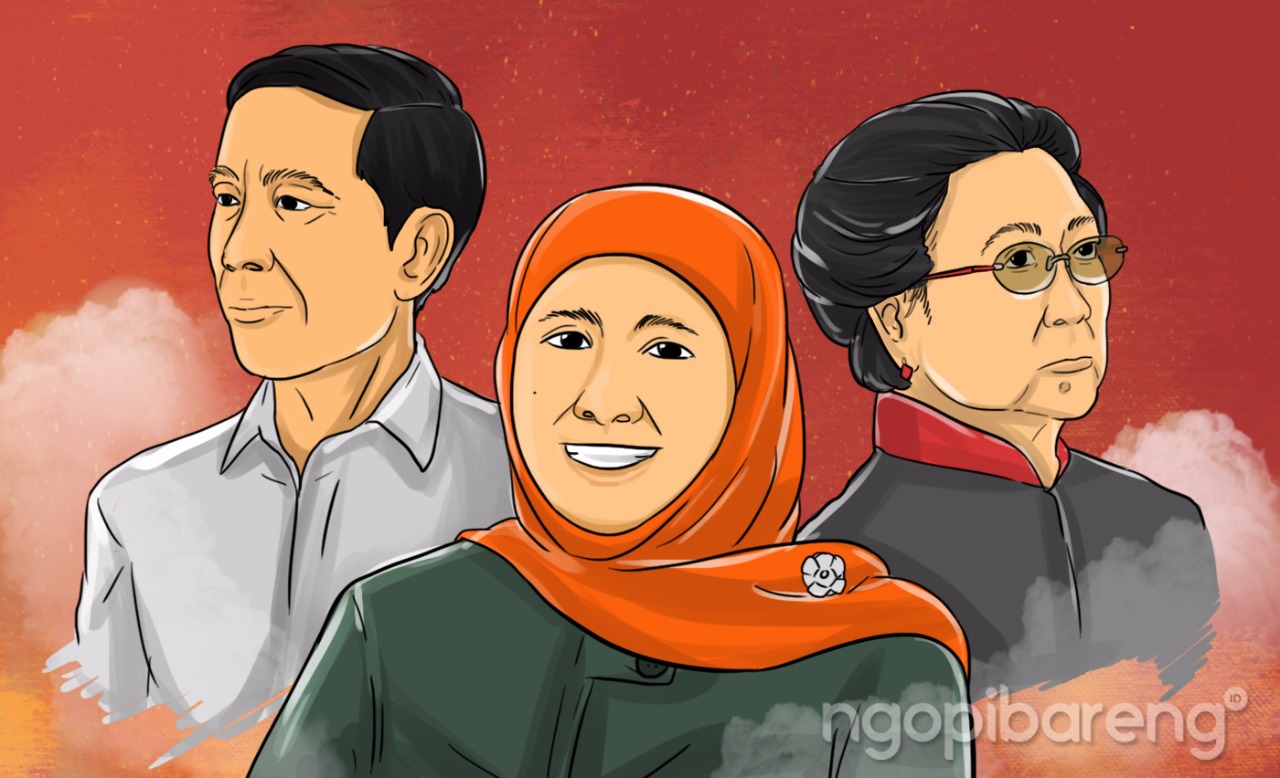
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa hatinya sedang berbunga-bunga. Rekomendasi dari Partai Demokrat dan Golkar, memastikan dirinya mendapat tiket untuk kembali bertarung di Pilkada Jawa Timur 2019.
Bagi Khofifah, Jatim adalah “cinta mati.” Sudah dua kali kalah bertarung dan memiliki posisi yang lebih tinggi di Kabinet Jokowi, namun dia tetap mengejar posisi sebagai orang nomor satu di ujung timur pulau Jawa itu.
Coba apa namanya kalau bukan cinta mati? Jangan-jangan malah lebih tepat disebut sebagai cinta buta.
Sebagai tokoh yang sangat matang di dunia politik, bahkan sudah menjadi aktivis sejak mahasiswa, pasti Khofifah punya pertimbangan sendiri mengapa dia tetap bersikeras berlaga dalam pilkada.
Apakah murni pertimbangan romantisme politik, atau sebagai menteri, Khofifah sedang mendapat penugasan yang sangat penting dari Jokowi?
Pertama, dari perspektif pribadi wajar bila Khofifah masih penasaran dengan Jatim. Dari dua kali berlaga, boleh dibilang Khofifah tidak sepenuhnya kalah. Nasib baik saja yang belum berpihak kepadanya. Pada pilkada 2008 bahkan sampai harus dilakukan pemilihan ulang di Madura.
Ibarat pertandingan bola, ini adalah el clasico antara Real Madrid Vs Barcelona. Dua laga sebelumnya Khofifah melawan Soekarwo yang berpasangan dengan Saifullah Yusuf. Sementara pada laga ketiga dia akan bertemu dengan Saifullah Yusuf. Timnya sama, hanya pemain bintangnya yang berbeda.
Sebagai kader Demokrat, Soekarwo sekarang berada di belakang Khofifah. Jadi posisi Soekarwo mirip-mirip Jose Mourinho yang pernah menjadi asisten pelatih di Barcelona, kemudian harus berhadapan dengan klub lamanya setelah menjadi pelatih Madrid. Posisi ini pasti membuat Khofifah bakal lebih pede.
Khofifah pasti bekerja keras, all out, at all costs agar kali ini tidak kalah lagi. Publik, terutama yang tidak menyaksikan langsung pertandingan, hanya akan mengingat siapa pemenangnya. Tidak peduli seberapa bagus maupun jeleknya sebuah permainan.
Tidak ada seorang pun yang ingin dikenang sebagai pecundang. Ini menyangkut reputasi. Harga diri, atau orang Bugis –daerah asal almarhum suami Khofifah—menyebutnya sebagai siri.
Kedua, dengan pertaruhan reputasi pribadi yang sangat mahal dan jabatan tinggi, kemungkinan besar Khofifah mendapat penugasan dari Jokowi untuk mengamankan Jatim. Dia menjadi proxy. Itu kalkulasi yang paling masuk akal.
Urusannya tidak jauh-jauh dari Pilpres 2019. Jatim merupakan kantong suara terbesar kedua setelah Jabar . Dua provinsi itu harus diamankan bila Jokowi ingin kembali melenggang mulus sebagai presiden untuk periode kedua.
Indikasi bahwa ini merupakan penugasan dari Jokowi sangat kuat ketika Khofifah menyatakan hanya akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden, bukan pengunduran diri.
Peraturan perundang-undangan memang tidak ada kewajiban bagi seorang menteri untuk mengundurkan diri ketika berlaga dalam pilkada. Namun melihat beban menteri yang begitu berat, dan medan pertempuran pilkada Jatim yang berdarah-darah, keputusan Khofifah menimbulkan pertanyaan besar.
Keputusan Khofifah untuk mempertahankan posisinya sebagai menteri, atau seperti yang dia nyatakan, tidak akan “tinggal glanggang, colong playu,” alias tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai menteri, sangat sulit dipahami.
Akan lebih sulit dipahami lagi bila Jokowi ternyata juga mengabulkan keinginan Khofifah dan tetap mempertahankannya di dalam kabinet. Bila itu terjadi, maka majunya Khofifah di pilkada Jatim adalah bertemunya dua kepentingan Khofifah dan Jokowi.
Khofifah bisa menuntaskan rasa penasaran dan romantisme politiknya di Jatim. Jokowi bisa mengamankan suaranya di Jatim dengan menempatkan orang kepercayaannya.
Publik tentu belum lupa ketika Jokowi menuntut para menterinya tidak rangkap jabatan. Ketua Umum Hanura Wiranto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dipaksa memilih menjadi menteri atau tetap aktif di partai. Korban lainnya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang terpaksa tidak masuk kabinet, karena memilih tetap menjadi ketua partai.
Kepentingan Jokowi Vs Megawati
Penugasan Khofifah oleh Jokowi --sekali lagi jika ini benar-- bisa menjadi indikasi kian menguatnya Jokowi akan bersimpang jalan dengan Megawati pada Pilpres 2019.
Indikasi itu juga terlihat dalam pilihan politik di Jabar, maupun keputusan PDIP yang hingga kini belum memutuskan untuk mencalonkan kembali Jokowi.
Di Jabar melalui partai-partai pendukungnya –Nasdem, PKB, PPP dan Golkar-- Jokowi mengusung Ridwan Kamil yang telah teken kontrak untuk mengamankannya pada Pilpres 2019. Sementara PDIP masih berkutat mencari kandidat kuat untuk menandingi Ridwan Kamil.
Salah satu kandidat incarannya adalah kader PKS Netty Heryawan, istri Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. PDIP bahkan membuka peluang koalisi dengan PKS. Namun peluang tersebut menjadi tertutup karena PKS sudah memutuskan berkoalisi dengan PAN, dan Demokrat mengusung Deddy Mizwar-Achmad Syaichu. Akan jadi sangat menarik bila kemudian PDIP ternyata memutuskan bergabung dengan PKS-Demokrat, dan PAN .
Sampai sekarang PDIP juga belum memutuskan apakah akan kembali mengusung Jokowi pada Pilpres 2019 atau tidak. Mereka baru akan memutuskan pada Rapimnas Januari 2018. Padahal Golkar, Nasdem dan PPP malah sudah lebih dahulu menyatakan akan mencalonkan kembali Jokowi.
Dengan menugaskan Khofifah, Jokowi menegaskan pilihannya berbeda dengan PDIP. Bersama PKB, PDIP telah lebih dulu mengajukan paket Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas sebagai pasangan cagub-cawagub.
Yang menarik Khofifah menggandeng Bupati Trenggalek Emil Dardak. Sebagai kader PDIP Emil sudah diyakinkan berkali-kali untuk tidak maju bersama Khofifah dan berhadapan dengan PDIP. Emil bahkan sudah dipanggil Megawati. Tapi Emil tetap bersikeras maju.
Saifullah-Azwar Anas Vs Khofifah-Emil sesungguhya adalah pertarungan internal PKB (NU) dan PDIP. Kalau dalam pewayangan bisa disebut sebagai perang campuh. Perang jarak dekat, yang saling menikam. Tidak begitu jelas siapa kawan dan siapa lawan. Sebuah pertarungan antara Kurawa dan Pandawa yang sesungguhnya masih terikat dalam kekerabatan.
Saifullah seorang nahdliyin berdarah biru yang pernah menjadi kader PDIP dan kemudian balik kandang ke PKB. Azwar Anas juga nahdliyin yang menjadi kader PKB dan kemudian berganti baju merah dengan menjadi calon PDIP.
Khofifah bahkan Ketua Umum Muslimat organisasi sayap perempuan NU dan menjadi kader PKB. Emil Dardak adalah bupati yang diusung oleh PDIP. Sementara Soekarwo yang kini mendukung Khofifah, adalah aktivis GMNI yang secara tradisional berafiliasi dengan PDIP (PNI).
Pertempuran antara kubu hijau Vs merah yang bertukar pasangan ini dipastikan akan membuat dukungan di kedua kubu terbelah. Perpecahan yang sangat nyata terjadi di kubu NU. Membuat musuh yang jeli, bisa memanfaatkan situasi.
Sebelum Khofifah memutuskan maju, para kyai sepuh NU sudah sepakat bulat mendukung Saifullah. Ketika mengetahui gelagat Khofifah akan maju, mereka mencoba mencegahnya. Posisinya sebagai Ketua Muslimat membuat Khofifah juga punya pendukung kuat di kalangan nahdliyin dan juga para kyai dan nyai (tokoh perempuan).
Dengan mendukung Khofifah, Jokowi bisa dianggap memecah belah suara NU. Mereka pasti sangat kecewa, dan akan punya perhitungan sendiri terhadap Jokowi. Padahal selama ini Jokowi sudah mati-matian merangkul kelompok nahdliyin, terutama para kyai, untuk mengimbangi perlawanan kelompok-kelompok Islam, pasca Pilkada DKI 2017.
Dengan begitu pilkada Jatim bisa dilihat bukan hanya sebagai pertaruhan Khofifah pribadi, tapi juga pertaruhan politik Jokowi. Ajang berbagai pilkada tampaknya digunakan oleh Jokowi maupun Megawati untuk memperkuat posisi tawarnya.
Seberapa kuat posisi tawar mereka masing-masing, akan sangat menentukan apakah mereka akan tetap bersama menjadi sekutu? Atau keduanya akan berubah dari sekutu menjadi seteru?
Dengan mendukung Khofifah, Jokowi tampaknya memberi isyarat keras, dia tidak ingin terus menerus menjadi petugas partai dan dalam bayang-bayang kekuasaan Megawati. End
*) Hersubeno Arief adalah wartawan senior yang kini menjadi konsultan media dan politik
Advertisement



















