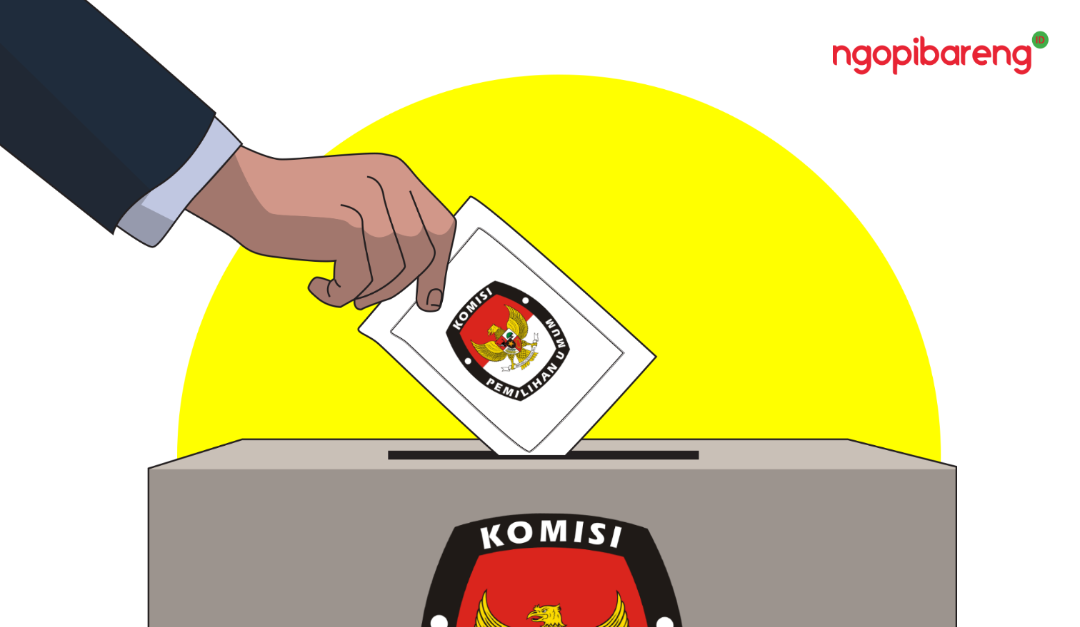Amplop di Balik Tirai: Siapa yang Memilih?

Pilkada menjadi panggung bayangan. Rakyat memilih, tapi uang yang menentukan. Kita harus bicara soal ini.
Pemilu adalah panggung besar untuk demokrasi. Sebuah ruang yang harusnya dihiasi gagasan dan visi masa depan. Tapi di balik tirai kotak suara, ada amplop yang berbisik lebih keras dari janji dan program kerja. Amplop itu menyelinap malam sebelum pencoblosan, mendatangi rumah-rumah dengan pesan singkat: pilih saya.
Di balik tirai TPS, suara kita mestinya bicara lantang. Tapi siapa yang sesungguhnya memilih? Hati kita? Logika kita? Atau amplop yang mampir malam sebelumnya dan kemudian membentuk barisan panjang angka kemenangan?
Amplop itu tidak bergerak sendiri. Ia datang dengan senyum basa-basi. Dengan pesan singkat: “Tolong pilih ya.” Bukan sekali-dua kali ini terjadi. Dari Pilkada ke Pilkada. Dari nama ke nama. Drama yang sudah terlalu lama kita saksikan. Amplop kecil itu berjalan sunyi, tapi menghancurkan banyak hal. Termasuk masa depan kita.
Bawaslu punya angka yang bikin kita sama-sama geleng kepala. Pilkada 2020, 52% pelanggaran yang dilaporkan adalah soal politik uang. Amplop. Barang. Janji. Semua berputar di luar logika demokrasi. Belum cukup? Lembaga Survei Indonesia (LSI) menambah data. Sebanyak 33% pemilih mengaku menerima uang atau barang dari kandidat. Bayangkan, satu dari tiga orang kita sudah terbiasa dengan praktik seperti ini. Angka-angka ini bukan lagi tanda tanya, tetapi bukti nyata bahwa demokrasi kita telah dirampas dalam sunyi.
Amplop itu tidak hanya menyasar rakyat kecil. Ia masuk ke setiap sudut. Memengaruhi sistem. Membeli kepercayaan. Menukar suara dengan kekuasaan. Ia menjawab pertanyaan dengan materi, bukan visi. Ia menukar gagasan besar dengan transaksi kecil. Demokrasi yang mestinya memuliakan rakyat malah memanfaatkan kemiskinan mereka. Kandidat yang membawa amplop tahu betul bahwa di tengah ketimpangan ekonomi, uang adalah senjata paling ampuh. Siapa yang dirugikan? Kita semua. Pemilih, rakyat, dan demokrasi itu sendiri.
Mengapa amplop bisa sebesar ini dampaknya? Pertama, kemiskinan masih jadi tembok besar demokrasi kita. Bagi sebagian orang, amplop itu seperti rezeki nomplok. “Daripada tidak dapat apa-apa.” Logika sederhana ini berjalan di banyak tempat. Kedua, biaya politik yang luar biasa besar. Kampanye di era baliho raksasa, iklan media, dan penggalangan massa adalah permainan mahal. Kandidat yang tidak punya gagasan akan memilih jalan pintas: uang. Ketiga, budaya politik yang terlalu pragmatis. Banyak pemilih memilih bukan karena program, tapi karena uang siapa yang lebih cepat sampai ke kantong mereka.
Tapi, siapa yang benar-benar menang dalam permainan ini? Pemilih yang menerima amplop hanya mendapatkan keuntungan sesaat. Uang itu habis dalam hitungan hari, sementara pemimpin yang mereka pilih akan memutuskan masa depan mereka selama bertahun-tahun. Di sisi lain, kandidat yang membeli suara juga kehilangan arah. Mereka tidak lagi menjadi pelayan rakyat, tetapi pelayan modal yang telah mengangkat mereka ke tampuk kekuasaan.
Lalu apa akibatnya? Jangan kira amplop berhenti di TPS. Ia merembet ke semua dimensi kehidupan kita. Dalam urusan Ideologi, amplop itu menghancurkan nilai Pancasila. Musyawarah dan hikmat kebijaksanaan digantikan oleh transaksi.
Dalam urusan Ekonomi, politik uang membuka jalan bagi korupsi. Amplop itu seperti investasi awal. Setelah terpilih, pemimpin yang sudah “berutang” akan mencari cara untuk mengembalikannya. Kita tahu bagaimana caranya: penggelembungan proyek, penyalahgunaan anggaran, dan permainan tender. Dan di urusan Sosial Budaya, amplop itu menciptakan budaya baru. Budaya pragmatis. Budaya jual-beli suara. Pemilih tidak lagi melihat pemilu sebagai tanggung jawab. “Yang penting dapat bagian.” Ini bukan demokrasi. Ini pasar gelap suara.
Tapi kita tidak bisa terus-terusan diam. Amplop ini harus dilawan. Caranya? Dimulai dari diri sendiri, dari hati kita. Suara kita terlalu mahal untuk ditukar amplop. Kalau hari ini kita menerima uang, besok kita yang akan membayar mahal. Dalam bentuk jalan rusak. Sekolah yang ambruk. Kesehatan yang diabaikan.
Regulasi harus lebih tegas. Jangan hanya ada di kertas. Bawaslu perlu diberi kekuatan lebih. Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016 sebenarnya sudah mengatur pidana bagi pelaku dan penerima politik uang, tetapi pelaksanaannya masih lemah. Bawaslu dan KPK harus diberi wewenang lebih besar untuk menindak tegas pelaku, tanpa pandang bulu.
Tapi regulasi saja tidak cukup. Pendidikan politik adalah kuncinya. Pemilih harus tahu: amplop itu seperti racun. Sekali diterima, ia akan membunuh kepercayaan kita pada demokrasi. Rakyat perlu tahu bahwa pemilu bukan soal siapa yang membayar, tetapi siapa yang membawa solusi.
Dan di zaman teknologi seperti ini, digitalisasi pemilu harus menjadi senjata baru. Dengan transparansi yang lebih luas, ruang untuk amplop bisa semakin sempit. Tinggal mau atau tidak menggunakannya sebagai alat transparansi. Atau memang sengaja tidak transparan karena ada yang disembunyikan?
Pertanyaannya sekarang: maukah kita berubah? Amplop di balik tirai itu tidak akan pergi jika kita terus membiarkan. Amplop di balik tirai itu memang sunyi, tapi efeknya keras sekali. Kalau kita membiarkan ini terus, demokrasi hanya tinggal nama. Siapa yang sebenarnya memilih pemimpin kita? Kalau jawabannya amplop, maka kita tahu: kita sedang berjalan mundur.
Suara kita adalah masa depan kita. Jangan biarkan amplop mencurinya. Setidaknya kita selamatkan masa depan anak-anak kita dari derita akibat kesalahan kita saat memilih pemimpin. Amplop tidak akan pernah memilih pemimpin yang baik. Hanya rakyat yang bisa. Dan untuk itu, kita harus memutus siklus ini, sebelum demokrasi benar-benar hanya tinggal nama.
(Diana AV Sasa, Mahasiswa Pasca Sarjana Program Pendidikan Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada)
Advertisement